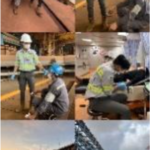Perempuan di Pusaran Pangan: Meneguhkan Resiliensi, Menegosiasi Ulang Relasi Kuasa
Oleh: Elis Nurhayati, S.Ag., M.Hum., MPP. Master kebijakan publik dan direktur eksekutif Daya Data Komunitas
Di Indonesia, tak ada yang lebih politis daripada urusan perut. Presiden datang dan pergi, tetapi pangan tetap menjadi agenda besar negeri ini. Soekarno pernah mengingatkan dengan lantang: “Stomach cannot wait!”. Kalimat yang sederhana namun mengandung pesan kuat: lapar dapat mengguncang negara, dan pangan adalah urusan hidup-mati.
Namun siapa yang sebenarnya menjaga dapur bangsa ini tetap mengepul? Siapa yang mengolah tanah, menyimpan benih, melestarikan ilmu pangan dalam tradisi tutur yang tak selalu tercatat? Di balik sejarah besar pembangunan pangan, ada perempuan—yang perannya sering tersembunyi dalam narasi besar negara dan korporasi.
Dalam Sesi Ketiga Short Course Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch 5, Dr. Noorhidayah, S.H., M.A. mengajak kita membongkar sejarah panjang kebijakan pangan yang tampak megah dari kejauhan, tetapi sesungguhnya menyisakan luka pada perempuan, alam, dan keberagaman pangan lokal. Materi berjudul “Women, Gender Relations, and the Food Regime” menjadi kacamata untuk membaca ulang perjalanan bangsa dalam mengelola pangan—dari kisah sagu yang dipinggirkan hingga food estate yang menjanjikan modernitas, namun menghadirkan ancaman baru.
Rezim Pangan: Beras Sebagai Ideologi Negara
Sejak Indonesia merdeka, pemerintah selalu gugup dan gagap menghadapi kenyataan bahwa memberi makan rakyat adalah tugas berat. Di masa Soekarno, kelaparan masih menghantui. Ketergantungan pada beras sulit dilepaskan.
Soekarno sesungguhnya telah mencoba merambah jalan lain. Lewat buku Mustikarasa Indonesia: Resep Masakan Indonesia (1967), ia ingin mengisahkan bahwa Nusantara adalah mozaik kuliner yang kaya; beras, jagung, umbi-umbian, dan sagu adalah saudara sekandung yang setara. Sayangnya, buku itu bagai secercah cahaya yang tenggelam dalam gelombang revolusi hijau dan politik pangan Orde Baru. Rezim Soeharto kemudian dengan cermat membangun monumen bernama “Beras”. Ia, yang mengaku sebagai “anak desa”, menjadikan beras sebagai tulang punggung politik ekonomi kerakyatan sekaligus pengukuhan kekuasaannya.
Leon A. Mears, seorang profesor yang menghabiskan lebih dari dua puluh lima tahun meneliti ekonomi perberasan, menaruh perhatian besar pada dinamika beras di Indonesia. Ia pertama kali datang pada tahun 1956 sebagai pengajar dari Universitas Berkeley yang ditugaskan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Karyanya telah menjadi rujukan klasik dalam bidang ini, Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia, diterbitkan tahun 1982 oleh Universitas Gadjah Mada dan diterjemahkan dari aslinya The New Rice Economy of Indonesia. Selama tiga periode “Repelita”, atau Rencana Pembangunan Lima Tahun, sebagian besar anggaran pembangunan negara terus mengalir ke sektor pertanian. Indonesia memang mulai melangkah menuju industrialisasi dan bahkan tidak lagi tergolong negara berpendapatan rendah menurut Bank Dunia. Namun, tantangan untuk memastikan pasokan pangan bagi 147 juta penduduk tetap jadi prioritas. Dalam konteks ini, beras adalah komoditas yang memiliki posisi sangat istimewa.
Bergulirlah gagasan Food Estate. Ia berakar dari Era I pada masa Presiden Soeharto melalui Keppres No. 82/1995 dengan Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah. Namun proyek ini dinyatakan gagal pada 1998 lewat Keppres No. 33/1998 di masa BJ Habibie. Gagalnya PLG dipicu ketiadaan kajian sosio-ekologi untuk bertanam padi di ekosistem gambut yang unsur haranya tidak sesuai. Ketika lahan gambut dibuka, ia rentan memicu kebakaran hutan dan lahan. Proyek ini akhirnya membebani anggaran negara ketika berubah menjadi bencana karhutla. Alih-alih menghadirkan lumbung pangan, sebagian wilayah PLG justru berubah menjadi perkebunan sawit. Proyek ini menelan Rp1,7 triliun Dana Reboisasi, disertai tambahan biaya hingga Rp3,9 triliun untuk rehabilitasi lahan yang juga tidak jelas hasilnya.
Upaya membangun ketahanan pangan berlanjut dalam Era II di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 yang membuka 1,2 juta hektar lahan hutan di Merauke untuk pangan dan bioenergi. Implementasinya menyingkirkan hutan sagu dan mengganggu akses pangan masyarakat adat setempat. Proyek serupa diluncurkan di Bulungan, Kalimantan Utara tahun 2011 dengan target 30.000 hektar dan di Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2013 dengan target 100.000 hektar, namun hanya 0,11% lahan yang benar-benar termanfaatkan akibat hambatan sosial-budaya dan buruknya infrastruktur.
Pada Era III, Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali Food Estate tahun 2020 dengan 30.000 hektar lahan di Kalimantan—termasuk 20.000 hektar bekas PLG—melalui intensifikasi pengairan dan dukungan sarana seperti bibit, pupuk, serta pelibatan TNI sebagai tenaga tani. Tahun 2021, pemerintah memperluas program ke komoditas karbohidrat alternatif seperti singkong seluas 31.000 hektar di Gunung Mas, berkolaborasi dengan Korea Selatan. Namun pembukaan lahan turut mengonversi 600 hektar hutan alam, melepas 61.000 ton karbon, serta memicu banjir di area yang sebelumnya aman dari bencana.
Namun bukannya dihentikan, Food Estate kemudian malah diperluas ke Sumatera Utara yaitu Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara & Selatan, dan Pakpak Bharat—dengan skema 3 hektar per petani plus kontrak produksi berbasis bibit pemerintah dan harga jual melalui koperasi. Namun realisasinya, pengadaan sarana produksi dikuasai korporasi, bibit diarahkan ke industri, dan petani menjual panen ke pasar demi harga yang lebih baik. Di tengah kritik publik, mencuat isu kepentingan politik dalam proyek ini melalui PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang berada di bawah Yayasan Pertahanan dan disebut memiliki kedekatan dengan tokoh penting pemerintahan saat itu, memperkuat sorotan bahwa Food Estate bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal kuasa dan kepentingan. Berdasarkan penelusuran Tempo pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, “Tim Kajian Krida Karya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.”
Dalam akta pendirian perseroan pada 3 April 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Pengurus Yayasan tersebut di antaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi terbaru, menurut analisis Kompas, luasan 20 juta hektar hutan akan dibuka sebagai cadangan energi dan pangan, diperkirakan didapatkan dari 15,53 juta hektar lahan yang belum berizin dan 5,07 juta hektar lahan yang berizin, tetapi tidak aktif. Lahan yang belum berizin tersebut terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi.
Fakta ini mengukuhkan betapa nasib rezim bergantung pada stabilitas harga pangan dan ketersediaan beras. Swasembada beras 1984 dirayakan sebagai puncak kejayaan politik pangan Presiden Soeharto, yang ingin diulang oleh menantunya, Presiden Prabowo.
Politik pangan semakin mengerucut: Indonesia sama dengan beras dan beras sama dengan legitimasi kekuasaan.
Dari satu rezim ke rezim berikutnya, agenda pangan bertajuk food estate atau lumbung pangan nasional, dikerjakan dengan gegap-gempita oleh kementerian dan korporasi, seolah menjadi jawaban mutakhir atas ancaman krisis pangan global. Ironisnya, proyek mercusuar ini kembali mengulang kesalahan yang sama: memaksakan padi di tanah yang tak mengenal padi—seperti yang terjadi di Kalimantan dan Papua. Adapun keberagaman pangan lokal—jagung, singkong, ubi, sagu—perlahan tersingkir. Tradisi pangan lokal hanya menjadi catatan kaki dalam buku sejarah pembangunan.
Padahal sejarah pangan Nusantara menawarkan pelajaran penting: Pangan bukan sekadar produksi. Pangan adalah budaya, identitas, dan relasi manusia dengan alam.
Sagu, Perempuan, dan Pengetahuan yang Terpinggirkan
Dalam bukunya yang memukau, Sagu Papua untuk Dunia, Ahmad Arif bukan sekadar menulis tentang tanaman, melainkan tentang peradaban. Ia menggambarkan bagaimana sagu, sang pangan purba Nusantara, secara sistematis didesak ke pinggiran oleh narasi besar “cetak sawah” dan “budi daya padi”. Politik pangan yang berpusat di Jakarta, dengan logika industrial dan birokratis teknokratisnya, telah meminggirkan kekayaan pangan lokal yang justru lebih adaptif secara ekologis.
“Bagi masyarakat Papua, sagu tidak hanya sumber makanan pokok, tetapi juga memberikan seperangkat emic, sumber pengetahuan, dan sistem religi,” tulis Arif. Pengambilan sagu bukanlah aktivitas produksi semata, melainkan sebuah ritus yang penuh makna. Di sinilah titik awal kita memahami persimpangan antara rezim pangan, perempuan, dan alam.
Dr. Noorhidayah dalam pemaparannya mengaitkan langsung konsep Food Regime—pola global sistem pangan yang didukung relasi kekuasaan, teknologi, dan kepentingan korporasi—dengan nasib perempuan. Food Estate, yang digadang-gadang sebagai lumbung pangan modern, sering kali hanya menjadi perpanjangan tangan dari rezim ini: meminggirkan pengetahuan perempuan dan menjadikan mereka kelompok yang semakin rentan secara ekonomi. Yang paling terdampak dari logika industrial itu adalah: perempuan dan lingkungan.
Food Estate yang menjanjikan modernisasi dan komersialisasi pertanian ternyata lebih banyak menyisakan ketimpangan. Ia mengubah pola-pola produksi pangan tradisional yang telah dijaga perempuan selama berabad-abad, perempuan sebagai penjaga benih lokal, penopang ketahanan pangan keluarga dan komunitas, dan aktor pengetahuan ekologis tradisional.
Namun di atas kertas kebijakan, posisi mereka—kalaupun disebut—sering hanya ditempatkan sebagai “kelompok rentan”.
Lima Wajah Penindasan dalam Cengkeraman Food Regime
Melalui lensa ekofeminisme, Dr. Noorhidayah membeberkan bagaimana rezim pangan yang patriarkal melahirkan lima bentuk penindasan terhadap perempuan:
- Eksploitasi (Exploitation): Tenaga dan sumber daya perempuan diambil untuk keuntungan sistem yang lebih besar, tanpa imbalan yang setara. Mereka bekerja di lahan, tetapi hasilnya dikuasai oleh mekanisme pasar dan kebijakan yang tidak memihak mereka.
- Marjinalisasi (Marginalization): Perempuan didorong ke pinggiran. Dalam program Food Estate yang sarat teknologi dan alat berat, peran mereka sebagai pengelola pengetahuan lokal dianggap tidak relevan. Mereka dipaksa kembali ke ruang domestik, sementara keputusan strategis dipegang oleh laki-laki.
- Ketidakberdayaan (Powerlessness): Perempuan kehilangan kendali atas kondisi hidup mereka. Mulai dari jenis tanaman yang boleh ditanam, cara bertani, hingga pemasaran hasil, semua telah diatur oleh logika food estate yang seragam. Mereka menjadi objek, bukan subjek pembangunan.
- Imperialisme Kultural (Cultural Imperialism): Standar kesuksesan pertanian adalah produktivitas beras dan komoditas ekspor. Logika ini dianggap universal, sehingga menghancurkan keanekaragaman pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan tentang sagu, umbi-umbian, dan tanaman pangan lain yang lebih berkelanjutan. Pengetahuan mereka distigmatisasi sebagai kuno dan tidak efisien.
- Kekerasan (Violence): Penindasan ini bukan hanya metafora. Perempuan di daerah-daerah proyek food estate rentan mengalami kekerasan sistematis berbasis gender, baik secara ekonomi, sosial, maupun fisik, sebagai konsekuensi dari struktur yang timpang.
Pembagian Kerja yang Timpang dan Agen Perempuan di Balik Layar
Dalam gendered division of labor yang diurai Dr. Noorhidayah, terlihat dengan jelas bagaimana nilai kerja dinilai secara tidak adil. Laki-laki mengerjakan tugas yang dianggap “bernilai tinggi”: mengolah tanah dengan traktor, mengoperasikan alat berat, dan berhubungan dengan pasar. Sementara perempuan terjebak dalam pekerjaan yang dianggap “rendah”: merawat benih, menanam, memanen, mengolah hasil pascapanen, plus menyelesaikan seluruh pekerjaan domestik. Pekerjaan perawatan yang dilakukan perempuan ini, meski menjadi penopang utama sistem, kerap tak dihargai secara ekonomi dan sosial.
Namun, di balik narasi ketertindasan ini, terselip sebuah kekuatan: agensi perempuan. Mereka tidak pasif. Respon mereka terhadap hegemoni Food Estate berlapis dan kompleks. Ada yang menerima dengan terpaksa demi bertahan hidup. Ada yang melakukan adaptasi ekonomi dengan mencari sumber pendapatan sampingan. Dan yang paling digdaya, ada juga yang melakukan resistensi senyap—dengan tetap memelihara benih-benih lokal di pekarangan rumah, meneruskan ritual adat panen sagu, dan mengajarkan pengetahuan tentang umbi-umbian kepada anak-anak mereka. Inilah bentuk pemulihan identitas sosial-ekologis yang dilakukan dari akar rumput.
Membaca Ulang Pangan dan Memusatkan Aksi dari Pinggiran
Kisah pangan Indonesia tak bisa dipisahkan dari sejarah kolonialisme dan pembangunan sentralistik. Politik Jakarta—yang jauh dari tanah sagu di Papua atau hutan makanan di Mentawai—terlalu lama memaksakan identitas pangan tunggal. Padahal, sagu bagi komunitas adat bukan sekadar makanan—ia adalah pengetahuan, ritual, dan relasi spiritual dengan leluhur.
Ketika sagu dipaksa mundur oleh “revolusi hijau” bernama padi, yang hilang bukan hanya bahan pangan, melainkan pengetahuan ekologis yang diwariskan sejak lama.
Dr. Noorhidayah mengingatkan bahwa narasi pembangunan sering menutup mata pada keberagaman pangan lokal karena ia tak terlihat di statistik, tak tercatat dalam indikator pertumbuhan ekonomi, dan tak menghasilkan profit besar dalam logika pasar global.
Ekofeminisme: Cara Baru Membaca Pangan dan Peradaban
Kebijakan pangan tak lagi bisa dipandang netral. Ia sarat kekuasaan dan sistem nilai. Ekofeminisme menawarkan cara pandang baru: bahwa penindasan terhadap perempuan memiliki akar yang sama dengan eksploitasi alam.
Ketika perempuan dipinggirkan, lingkungan pun rusak. Sebaliknya, ketika perempuan diberi ruang, ekologi turut hidup.
Saat ekofeminisme membentuk cara kita memaknai relasi perempuan dan alam, di situlah ia menjadi ideologi yang membumi—menghidupkan solidaritas, menghormati keberagaman pengetahuan, dan mengembalikan hak perempuan atas tanah dan pangan.
Kesimpulan: Pangan Adalah Kedaulatan Perempuan
Fast forward ke hari ini, di bawah bayang-bayang kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menekankan ketahanan pangan, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan kuat menghadapi krisis pangan global. Pertanyaannya yang lebih mendasar adalah: ketahanan pangan untuk siapa, dan dengan cara apa?
Jika jawabannya masih berkisar pada food estate yang mengeksploitasi lahan, meminggirkan pengetahuan lokal, dan mengabaikan relasi gender, maka kita hanya sedang mengulangi siklus rezim pangan lama yang represif.
Pelajaran berharga dari sesi Dr. Noorhidayah ini adalah bahwa ketahanan pangan sejati tidak bisa dilepaskan dari keadilan gender dan ekologi. Ketahanan pangan yang hakiki hanya akan terwujud ketika suara perempuan—sebagai penjaga benih, ahli ekologi praktis, dan arsitek ketahanan keluarga—tidak hanya didengar, tetapi dijadikan fondasi utama dalam merancang kebijakan.
Di banyak desa Indonesia, perempuan adalah “arsip hidup” pengetahuan ekologis. Mereka tahu kapan musim tiba, jenis bibit yang cocok, bagaimana memulihkan tanah, dan cara bertahan ketika krisis melanda.
Jika negara ingin benar-benar tangguh menghadapi krisis pangan dunia, jawabannya sudah ada di depan mata.
Ketahanan pangan sejati hanya mungkin Ketika suara perempuan didengar, pengalaman perempuan diakui, kerja perempuan dihargai, tanah perempuan dilindungi, pengetahuan perempuan menjadi dasar kebijakan. Perempuan bukan sekadar peserta pembangunan.
Mereka adalah penjaga kehidupan.
Dan mungkin sudah saatnya, kita benar-benar mengamalkan kalimat Soekarno—
bahwa urusan perut tak bisa ditunda—tetapi kita tak berhenti di situ. Mari menambahkan frasa baru: Urusan perut adalah urusan perempuan. Jika perempuan tak merdeka, kedaulatan pangan hanyalah ilusi belaka.
Perjuangan untuk mengembalikan resiliensi dan otonomi perempuan atas tubuh, tanah, dan masa depannya, sedang berlangsung melalui negosiasi ulang relasi kuasa yang ada. Dan itu adalah perjuangan kita semua.

Food Estate Dadahup Perspektif Women, Gender Relations, and the Food Regime Catatan Kritis dari Praktisi Pangan Indonesia
Oleh: Muhammad Adri Waskito Praktisi Food Supply Chain Indonesia dan UK, Studi Kasus: Food Estate Dadahup & Perkembangannya di Era Pemerintahan Prabowo Subianto
Pendahuluan
Sebagai seseorang yang pernah bekerja dalam ekosistem BUMN Holding Pangan di Indonesia dan kemudian berkecimpung dalam Food Supply Chain di London, saya melihat langsung bagaimana pembangunan pangan modern sering mengadopsi logika food regime, sebuah sistem global yang menempatkan produksi massal, komoditas tunggal, dan kontrol negara/korporasi sebagai pusat kekuasaan pangan (McMichael, 2009).
Dalam kerangka ini, perempuan dan relasi gender sering kali menjadi lapisan yang tidak terlihat (invisible layer), padahal mereka merupakan aktor paling penting dalam menjaga keragaman pangan, ketahanan pangan rumah tangga, dan ekologi lokal.
Konteks ini sangat jelas terlihat dalam implementasi Food Estate di Dadahup, Kalimantan Tengah, sebuah proyek yang pernah ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo namun kemudian menuai evaluasi publik.
Food Regime dan Ketimpangan Gender: Kerangka Analisis
Menurut penelitian Agarwal (2018) dan FAO (2020), relasi gender dalam sistem pangan membentuk:
- Siapa yang memiliki akses terhadap lahan
- Siapa yang mengontrol keputusan penanaman
- Siapa yang mengambil manfaat ekonomi
- Siapa yang menanggung beban kegagalan atau krisis pangan
Dalam food regime, keputusan pangan cenderung tersentralisasi dan maskulin yang didorong oleh negara, pasar, dan teknologi mekanisasi, sementara peran perempuan dalam produksi kecil, benih lokal, dan diversifikasi pangan sering diabaikan.
Studi Kasus: Food Estate Dadahup dan Relasi Gender
Food Estate Dadahup dikembangkan di atas lahan gambut/eks-PLG (Proyek Lahan Gambut), dan sejak awal menghadapi masalah ekologi: drainase buruk, kesuburan rendah, dan risiko gagal panen.
Riset dari Greenpeace (2023) dan peneliti agraria seperti Eko Cahyono (2021) menemukan bahwa:
- Sebagian besar petani mengalami kegagalan
- Infrastruktur irigasi tidak berfungsi
- Lahan gambut terancam rusak dan tidak sesuai untuk monokultur
Tetapi efek paling tersembunyi adalah terhadap perempuan.
1. Hilangnya Ruang Produktif Perempuan
Penelitian Sunderland et al., 2014 menunjukkan bahwa perempuan berperan besar dalam agroforestri, tanaman pekarangan, dan pangan rumah tangga. Ketika lahan dialihkan menjadi proyek komoditas massal, perempuan kehilangan:
- Ruang tanam pekarangan
- Keragaman pangan lokal
- Penghasilan kecil dari penjualan hasil kebun
2. Marginalisasi dalam Pengambilan Keputusan
Studi IFAD (2019) menunjukkan perempuan pedesaan sering dikeluarkan dari rapat desa terkait proyek besar. Hal yang sama terjadi di beberapa desa sekitar Dadahup, di mana partisipasi formal perempuan hampir tidak ada.
3. Beban Ketahanan Pangan Keluarga
Ketika Food Estate gagal atau tidak stabil, perempuan memikul beban menyediakan pangan keluarga melalui:
- membeli bahan yang lebih mahal
- mengatur ulang pola konsumsi
- menghidupkan kembali pekerjaan informal
Situasi ini selaras dengan temuan Nitya Rao (2017) bahwa perempuan adalah “buffer terakhir” dalam
krisis pangan.
Perkembangan Food Estate di Era Presiden Prabowo Subianto
Pemerintahan Prabowo melanjutkan program Food Estate dengan narasi:
- Perluasan sawah baru,
- Optimalisasi lahan,
- Mekanisasi pertanian,
- Penguatan produksi beras nasional.
Namun berbagai analisis kebijakan (Tirto, 2025; Antara, 2025; Betahita, 2025) memperlihatkan bahwa:
- Pendekatan tetap top-down.
- Fokus masih pada komoditas tunggal.
- Minim pembahasan tentang gender impact assessment.
- Minim transparansi dalam evaluasi proyek Dadahup, Humbang Hasundutan, dan
Jika tidak ada intervensi berbasis gender, maka food regime baru di era Prabowo berisiko mengulang pola lama: industrialisasi pangan yang mengorbankan pengetahuan lokal dan tenaga kerja perempuan.
Mengapa Analisis Gender Penting dalam Food Estate
Tiga simpulan penting dari literatur akademik:
1. Perempuan Adalah Penjaga Biodiversitas Pangan Lokal
Howard (2013) menyebut perempuan sebagai “keepers of seed diversity.” Jika proyek food estate menghapus varietas lokal, dampaknya sangat besar bagi perempuan.
2. Produktivitas Naik Jika Perempuan Diberi Akses Lahan & Teknologi
FAO (2011) menunjukkan bahwa gap produktivitas dapat berkurang 20–30% jika perempuan diberi akses setara.
3. Ketahanan Pangan Tidak Akan Maju Tanpa Keadilan Gender
Penelitian Quisumbing (2014) & World Bank (2022) menyimpulkan bahwa household food security meningkat signifikan jika perempuan dilibatkan dalam keputusan tanah dan produksi.
Rekomendasi Kebijakan: Membangun Food Regime Baru yang Inklusif Gender
- Lakukan Gender Impact Assessment pada Semua Lokasi Food Estate
Termasuk Dadahup, Humbang Hasundutan, Merauke, dan lokasi baru.
2. Libatkan Perempuan dalam Perencanaan Desa & Pengelolaan Lahan
Bukan hanya “diundang”, tetapi diberi kuasa untuk memutuskan.
3. Perkuat Model Agroekologi & Diversifikasi Pangan
Literatur Francis et al. (2019) menunjukkan agroekologi lebih ramah gender dan lingkungan.
4. Pastikan Infrastruktur Disesuaikan dengan Ekologi Lokal
Lahan gambut seperti Dadahup tidak cocok untuk monokultur padi riset Page et al. (2015)
membuktikannya.
5. Transparansi Publik dalam Evaluasi Food Estate
Laporan kinerja harus dibuka, termasuk keberhasilan, kegagalan, serta dampak sosial gender.
Kesimpulan
Food Estate baik di era Jokowi maupun Prabowo merupakan proyek besar dalam kerangka food regime Indonesia. Namun seperti banyak proyek pangan skala besar di dunia, ia berisiko memperkuat ketimpangan gender jika tidak disertai analisis kritis.
Perempuan adalah aktor kunci dalam ketahanan pangan. Jika mereka diabaikan, maka kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan tanpa nyawa.
Sebagai praktisi yang pernah berada di jantung industri pangan, saya melihat bahwa keberhasilan Food Estate tidak dapat diukur hanya dari tonase gabah atau luas sawah, tetapi dari sejauh mana proyek ini memanusiakan komunitas lokal, memulihkan ekologi, dan memuliakan peran perempuan dalam sistem pangan nasional.

Refleksi Ekofeminisme: Menjalin Kembali Harmoni Perempuan dan Alam dalam Tantangan Global dan Aksi Lokal
Oleh: Elis Nurhayati, S.Ag., M.Hum., MPP. Master kebijakan publik dan direktur eksekutif Daya Data Komunitas
“Kalau Tidak Ada Air, Tidak Ada Tanah, Tidak Ada Hutan, Tidak Ada Batu, Kami Tidak Bisa Bertahan Hidup.”- Aleta Baun
Di jantung Nusa Tenggara Timur, seorang perempuan berbalut tenun tradisional memimpin perlawanan yang menggetarkan kekuasaan perusahaan tambang. Aleta Baun, atau yang akrab disapa Mama Aleta, bukan hanya sekadar aktivis lingkungan, melainkan representasi hidup dari perjuangan ekofeminisme di Indonesia. Ia lahir dari gunung, dari batu, dari air, dari hutan Mutis yang menjadi ibu bagi seluruh aliran sungai di Timor Barat. Mutis adalah jantung ekologi yang memompa air minum, air irigasi, obat-obatan, pangan, warna tenun, dan spiritualitas ke tubuh masyarakat. Bagi orang Molo, alam bukan latar belakang kehidupan—ia adalah bagian inti keluarga batih.
Mungkin karena itulah, ketika perusahaan tambang datang dengan buldoser dan izin-izin yang mengkhianati nurani, orang Molo tidak sekadar merasa tanah mereka dirampas; mereka merasa keluarganya dilukai. Dan dari luka itu, bangkitlah seorang perempuan dengan selendang tenun di bahu dan bayi yang digendongnya ke hutan, sembari terus membisikkan pada dirinya bahwa hidup tidak boleh tunduk pada ketakutan.
Sejak 1996, Mama Aleta berjuang. Ia diburu, diancam dibunuh, dihargai kepalanya oleh mereka yang takut pada suaranya. Ia bersembunyi di hutan selama berbulan-bulan sambil menggendong anaknya, sementara warga lain dipukuli dan ditangkap. Ia mengorganisir ratusan perempuan untuk melakukan aksi protes damai—bukan dengan teriakan, tetapi dengan menenun di tengah-tengah lokasi penambangan marmer. Seolah mereka ingin berkata: kami akan merawat bumi dengan tangan yang sama yang merawat keluarga kami, dan dengan tekad kuat sekuat batu.
Dan keajaiban itu terjadi. Pada 2007, perusahaan-perusahaan tambang hengkang. Mutis selamat. Hari ini, Mama Aleta dan komunitas Timor Barat melanjutkan perjuangan dengan memetakan hutan adat, memperkuat pertanian ekologis, dan menemukan warna-warna tenun baru dari tumbuh-tumbuhan liar. Ia seakan menunjukkan pada dunia bahwa ketika perempuan mengambil peran sebagai penjaga alam, bumi menemukan kembali bahasa penyembuhannya.
Dalam sesi kedua Short Course Certified of Environmental Management Leadership, Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. mengajak kita melihat kisah Mama Aleta bukan hanya sebagai cerita perjuangan, tetapi sebagai pintu masuk memahami apa yang disebut sebagai ekofeminisme—sebuah cara berpikir yang menolak melihat perempuan dan alam sebagai dua objek yang bisa dieksploitasi oleh kekuasaan patriarki dan modal.
Ibu Lena sendiri bukan akademisi yang berbicara dari menara gading. Riset-risetnya berpusat di persoalan gender, tanah, kekerasan, hingga agama. Sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat sekaligus relawan bantuan hukum bagi perempuan dan keluarga, sekretaris di lembaga perlindungan anak, dan peneliti dengan gelar doktor dari University of New South Wales tentang Hukum Waris Islam dan pengalaman perempuan Banjar, ia membawa perspektif empirik, hukum, sekaligus humanis. Sejak S1 ia sudah meneliti kesetaraan gender dalam pemilikan dan penguasaan lahan, dan saat S2 meneliti kekerasan terhadap perempuan dalam konflik etnis Sampit. Seluruh perjalanan akademiknya membentuk cara pandang bahwa perempuan dan alam seringkali luka oleh struktur yang sama.
Apa Itu Ekofeminisme? Sebuah Jendela untuk Melihat dan Merawat Luka Bersama
Ekofeminisme menggabungkan analisis feminis dengan pemikiran ekologis, menawarkan lensa kritis untuk memahami keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan kerusakan lingkungan. Aliran pemikiran ini menolak dualisme tradisional seperti manusia/alam, rasio/emosi, dan budaya/alam, sebaliknya menekankan etika perawatan (ethics of care), keadilan sosial, dan pluralitas pengetahuan ekologis. Dualisme ini secara halus menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek pelengkap penderita, mirip seperti bagaimana kapitalisme menempatkan alam sebagai sumber daya yang bebas dieksploitasi.
Premis utama ekofeminisme berdiri di atas beberapa fondasi penting. Pertama, penindasan perempuan dan degradasi lingkungan memiliki akar yang sama dalam sistem patriarki. Kedua, struktur dominasi yang menindas perempuan juga menindas alam. Ketiga, pembebasan perempuan dan pelestarian lingkungan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keempat, perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman unik dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelima, solusi ekologis harus inklusif gender dan menghormati pengetahuan lokal.
Ekofeminisme tidak sekadar mengatakan “perempuan lebih dekat dengan alam”, karena itu risiko esensialis. Yang ingin ditegaskan adalah: struktur sosial menempatkan perempuan lebih sering pada posisi yang harus menghadapi dampak kerusakan lingkungan, sehingga mereka menjadi aktor penting yang memahami krisis secara langsung.
Dalam kelas, Ibu Lena merekomendasikan film Salt of the Earth (1954), sebuah karya yang dianggap terlalu progresif pada zamannya hingga sempat diblokir di Amerika. Film ini menceritakan kisah para penambang zinc yang melakukan mogok kerja, namun ketika laki-laki dihadapkan pada tembok hukum yang membungkam gerakan mereka, para perempuan mengambil alih garis depan.
When the men were silenced, the women roared.
Esperanza, tokoh perempuan dalam film itu, mengorganisir para ibu, istri, dan anak-anak untuk memimpin aksi. Sementara para laki-laki tak lagi bisa berdiri di garis piket, perempuan maju dengan strategi yang lebih halus namun lebih tajam, menghadapi intimidasi aparat dan tekanan perusahaan. Mereka bukan sekadar pengganti, tetapi inovator taktis yang akhirnya memenangkan perjuangan komunitas.
Kisah dalam film ini membuat kita seakan melihat refleksi dari Mutis—perempuan yang turun masuk ke lokasi tambang dengan tenun di tangan. Bedanya hanya ruang dan waktu; semangatnya sama. Seolah sejarah ingin mengingatkan bahwa ketika bumi terluka, perempuan sering kali pertama yang mendengarnya dan pertama yang berdiri membelanya.
Akar, Varian, Tokoh, dan Evolusi Ekofeminisme
Ekofeminisme muncul dari perpaduan antara gerakan feminis dan gerakan lingkungan tahun 1970-an. Françoise d’Eaubonne, tokoh Prancis yang memperkenalkan istilah ecofeminism pada 1974, melihat betapa struktur patriarki menghasilkan eksploitasi alam yang brutal. Karyanya, Le Féminisme ou la Mort, menjadi penanda penting bahwa krisis ekologis bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah ideologis.
Ekofeminisme berkembang menjadi beragam aliran:
- Liberal/Reformis: fokus pada inklusi perempuan dalam kebijakan lingkungan.
- Materialis/Sosialis: mengkritik kapitalisme ekstraktif yang menempatkan tubuh perempuan dan alam sebagai komoditas produksi.
- Radikal: menggali akar dalam dominasi patriarki dan budaya maskulin.
- Spiritual/Religius: melihat hubungan kosmologis manusia-alam sebagai dasar etika ekologis.
- Postkolonial/Adat: menyoroti pengalaman perempuan adat dan kolonialisasi pengetahuan.
Ibu Lena secara menarik mengaitkan ini dengan konteks Indonesia, terutama dari pengalaman perempuan Banjar dalam hukum waris dan tanah. Baginya, persoalan patriarki bukan entitas tunggal; ia berkelindan dengan agama, adat, kolonialitas, dan kapitalisme. Dan ini pula yang membuat ekofeminisme di Indonesia harus disesuaikan secara kontekstual.
Perkembangan ekofeminisme modern bergerak dari klaim afinitas biologis perempuan-alam menuju analisis sosial yang menekankan struktur ekonomi-politik, pembagian kerja, kolonialisasi, serta pengetahuan lokal. Perspektif yang lebih kritis ini penting agar ekofeminisme tidak terjebak romantisisme.
Ekofeminisme lahir dalam konteks aktivisme feminis dan lingkungan tahun 1970-an. Françoise d’Eaubonne memperkenalkan istilah ‘ekofeminisme’ pada 1974 melalui bukunya Le Féminisme ou la Mort (Feminism or Death), yang mengaitkan dominasi laki-laki dengan krisis ekologis. Ia bukan penemu namun bisa disebut sebagai peramu karena sebagai praktik kearifan lokal, berbagai nilai dan bentuk ekofeminisme sudah ada jauh sebelumnya di banyak komunitas adat di seluruh dunia.
Evolusi pemikiran ekofeminisme menunjukkan pergeseran signifikan—dari klaim afinitas alami perempuan-alam menuju analisis struktural sosial, tenaga kerja, dan kolonialitas yang menjelaskan keterkaitan penindasan gender dan degradasi lingkungan secara lebih komprehensif.
Selain Françoise d’Eaubonne, si perintis istilah ekofeminisme, Ibu Lena selanjutnya mengajak kita mengenal beberapa tokoh penting lainnya, seperti:
- Vandana Shiva, aktivis India yang menunjukkan bahwa perempuan petani merupakan benteng terakhir dalam mempertahankan keanekaragaman hayati. Melalui karya monumentalnya Staying Alive: Women, Ecology and Development, Shiva mengkritik Revolusi Hijau dan pertanian industri sambil memperjuangkan kedaulatan benih dan pengetahuan tradisional.
- Carolyn Merchant, sejarawan lingkungan Amerika yang mengkaji sejarah pemisahan manusia/alam dalam pemikiran Barat melalui karya klasik The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution. Ia menganalisis bagaimana wacana ilmiah membenarkan eksploitasi lingkungan dan menjelaskan bagaimana revolusi ilmiah mengubah alam dari “ibu” menjadi “mesin” yang bisa dikontrol.
- Ariel Salleh, Greta Gaard, Ivone Gebara yang mengembangkan ekofeminisme materialis dan ekofeminisme queer yang memperkaya khazanah pemikiran ekofeminisme dengan perspektif yang lebih inklusif.
Menarik bahwa banyak tokoh kunci adalah perempuan Global South. Ini penting karena krisis lingkungan paling brutal dialami di dunia Selatan—dari sawit di Indonesia, tambang di Amerika Latin, hingga monokultur beras di India. Di sinilah pengalaman perempuan adat, petani, dan masyarakat lokal memperkaya ekofeminisme secara nyata.
Mengapa Ekofeminisme Penting untuk Indonesia?
Indonesia berada pada persimpangan sejarah lingkungan yang genting: deforestasi cepat, ekspansi tambang, perkebunan sawit, pencemaran sungai, dan krisis air. Di garis depan persoalan ini berada perempuan, terutama perempuan adat.
Pemateri kemudian mengurai dampak berlapis yang dialami perempuan: hilangnya tanah dan wilayah adat menghancurkan kedaulatan pangan keluarga, meningkatnya beban kerja karena harus mencari air lebih jauh, tekanan kesehatan reproduksi akibat pencemaran, marginalisasi dalam pengambilan keputusan, kekerasan dalam konflik agraria, serta terhapusnya pengetahuan lokal yang selama ini diwariskan melalui tubuh perempuan.
AMAN mendokumentasikan ratusan konflik perampasan wilayah adat, di mana perempuan mengambil peran kunci dalam mediasi dan mobilisasi. Seperti yang Ibu Lena tekankan, perempuan adat tidak hanya menjadi korban—mereka adalah pencipta solusi, pembawa spiritualitas, penenun budaya, sekaligus negosiator ulung.
Namun ada catatan penting: minimnya riset empiris tentang dampak gender dalam kerusakan lingkungan. Karena itu, Ibu Lena mendorong perlunya penelitian lapangan, etnografi gender, pemetaan klaim perempuan, hingga dokumentasi praktik perlawanan.
Kritik Ekofeminisme: Menghindari Jerat Esensialisme
Ekofeminisme bukan tanpa kritik. Kritik utama ialah esensialisme, yaitu afinitas ‘alami’ antara perempuan dan alam, yang menganggap bahwa perempuan secara alami dan kodrati dekat dengan alam. Ini bisa berbahaya karena menyederhanakan pengalaman gender, menormalkan beban kerja perempuan, mengabaikan perbedaan kelas, etnis, agama, dan orientasi seksual, serta berpotensi memperkuat stereotip gender.
Sebagai respons, gelombang pemikiran ekofeminisme selanjutnya mengembangkan pendekatan materialis dan postkolonial yang menekankan struktur sosial ketimbang determinisme biologis. Konsensus kontemporer dalam ekofeminisme lebih memfokuskan pada struktur sosial dan pembagian kerja, sambil mengakui keragaman pengalaman perempuan dan menghindari generalisasi universal.
Gelombang baru ekofeminisme menghindari romantisasi ini dengan fokus pada struktur sosial, pembagian kerja, dan pengalaman material. Perspektif postkolonial mengkritik ekofeminisme Barat karena melakukan apropriasi terhadap pengetahuan dan praktik indigenous, mengabaikan konteks lokal dan sejarah kolonial, serta menerapkan solusi top-down yang tidak sensitif budaya. Kebutuhan mendesak adalah membangun aliansi yang peka konteks, mendekolonisasi pengetahuan, dan memusatkan suara perempuan adat dalam wacana ekofeminisme global.
Dalam konteks Indonesia, ini penting—karena tanah, adat, agama, dan gender selalu saling bertaut. Kajian ekofeminisme di Indonesia perlu menggunakan pendekatan dekolonisasi yang membangun kembali narasi, pengalaman, dan praktik lokal yang selama ini tersisihkan oleh wacana dominan global. Pendekatan ini melibatkan kita untuk menggeser basis epistemologis dari teori Barat sebagai satu-satunya pijakan menuju kearifan lokal, sejarah kolonial, dan pengalaman perempuan Indonesia. Kita juga perlu mengkritik kapitalisme ekstraktif yang mewarisi kolonialisme, seperti industri tambang dan proyek pembangunan besar dan menghidupkan praksis kolektif yang menolak individualisme dalam feminisme liberal Barat dengan mengedepankan gotong royong, solidaritas komunitas, dan aksi bersama.
Indonesia memiliki konteks historis dan budaya yang kaya untuk mendukung kajian ekofeminisme, termasuk membongkar warisan kolonialisme Belanda yang menghancurkan ekosistem sekaligus menggeser peran perempuan, tradisi kosmologi lokal yang menempatkan manusia, alam, dan perempuan dalam relasi setara.
Ekofeminisme dalam Praktik: Dari India, Kenya, Amerika, ke Indonesia
Gerakan ekofeminisme bukan hanya ide dan bukan sekadar aktivisme, tetapi bentuk ethics of care—etika merawat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ia hidup dalam jaringan perlawanan di seluruh dunia. Pada 1973, perempuan India memeluk pohon untuk mencegah penebangan, menyatukan tubuh mereka dengan alam dalam perlawanan tanpa kekerasan. Lalu di Kenya, dipelopori oleh Wangari Maathai, gerakan perempuan pedesaan menanam jutaan pohon untuk mencegah desertifikasi, menciptakan ‘sabuk hijau’ yang menyatukan lingkungan dan pemberdayaan Perempuan. Pada 1978, Lois Gibbs memimpin komunitas di Amerika untuk memprotes lingkungan beracun yang menyebabkan penyakit pada anak-anak dan masalah reproduksi perempuan, hingga berhasil mengamankan relokasi hampir 800 keluarga oleh pemerintah federal.
Kisah ekofeminisme yang lebih dekat adalah Mama Yosepha Alomang melawan perusahaan tambang emas asal Amerika di Papua. Yosepha Alomang, atau Mama Yosepha, adalah perempuan Suku Amungme, memimpin perlawanan terhadap PT Freeport Indonesia yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan masif dan pelanggaran HAM. Perjuangannya penuh pengorbanan—anak sulungnya, Johanna, meninggal karena kelaparan saat keluarganya bersembunyi di hutan menghindari operasi militer pada 1977.
Pada 1991, Mama Yosepha menggelar aksi pendudukan bandara Timika selama tiga hari dengan menyalakan api di landasan udara untuk memprotes penolakan Freeport dan pemerintah Indonesia mendengarkan keprihatinan masyarakat lokal. Akibat aktivitasnya, ia dituduh memihak organisasi Papua Merdeka dan pada 1994 ia ditangkap dan disiksa oleh pasukan keamanan negara. Bersama Mama Yuliana, tokoh perempuan Papua lainnya, Mama Yosepha diperam dalam kontainer pengangkut kotoran dan urine manusia selama berhari-hari dalam panas tinggi dengan sedikit makanan atau air untuk bertahan hidup.
Tidak patah arang, pada 1996 Mama Yosepha meluncurkan gugatan perdata terhadap Freeport McMoRan di Amerika Serikat, menuntut ganti rugi untuk cedera pribadi dan kerusakan lingkungan. Dana ganti rugi ini kemudian digunakan untuk membangun Kompleks Yosepha Alomang yang terdiri dari monumen pelanggaran HAM, klinik, panti asuhan, dan gedung pertemuan. Pada 1999, Mama Yosepha mendapat penghargaan Yap Thiam Hien dan mendirikan YAHAMAK (Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan). Tahun 2001, ia dianugerahi Goldman Environmental Prize—semacam Hadiah Nobel Lingkungan—untuk usahanya mengorganisir komunitasnya melawan praktik Freeport yang telah menghancurkan hutan, mengubah gunung, mencemari Sungai dengan tailing, dan menggusur komunitas lokal.
Penutup: Ekofeminisme sebagai Jalan Pulang
Dari Mutis ke Timika, dari rumah tenun ke landasan udara, dari film Salt of the Earth hingga kelas bersama Ibu Lena, kita belajar bahwa perempuan selalu berada di garis depan perjuangan merawat bumi. Bukan karena mereka “lebih dekat” dengan alam, tetapi karena struktur kehidupan menempatkan mereka pada posisi yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan—dan karena mereka lah yang paling sering mengambil inisiatif untuk menjaga kehidupan tetap berjalan.
Ekofeminisme bukan sekadar teori; ia adalah cermin untuk memandang tubuh bumi sebagai tubuh kita sendiri. Ia adalah panggilan kembali kepada etika perawatan, keadilan sosial, dan pengakuan bahwa pengetahuan ekologis perempuan merupakan warisan yang harus diperjuangkan.
Seperti kata Mama Aleta, bila tanah, air, hutan, dan batu hilang, maka hilanglah kehidupan. Maka tugas kita adalah memastikan bahwa suara perempuan seperti Aleta Baun dan Yosepha Alomang tidak hanya dikenang sebagai cerita heroik, tetapi dijadikan fondasi dalam merancang kebijakan lingkungan, riset, pendidikan, dan gerakan sosial.
Karena mungkin, pada akhirnya, ekofeminisme adalah cara bumi mengingatkan kita bahwa untuk bertahan hidup, manusia harus kembali belajar merawat—seperti seorang ibu merawat anaknya, seperti perempuan Molo menenun tanahnya, seperti perempuan Amungme menyalakan api perlawanan.
Pada akhirnya, ekofeminisme mengingatkan kita bahwa pembebasan perempuan dan pelestarian lingkungan adalah dua sisi dari mata uang yang sama—kita tidak dapat mencapai keadilan gender tanpa keadilan lingkungan, dan sebaliknya. Perjuangan Mama Aleta, Mama Yosepha, dan ribuan perempuan lain di garis depan pertahanan lingkungan adalah testament hidup atas kebenaran ini.

“Ekofeminisme dan Pembangunan”
Oleh: AMINUDDIN, S.Pd., M.M., Ph.D. Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar
Short course Certified of Enviromental Management Leadership (C.EML) batch 5 yang dilaksanakan oleh Assosiasi Peneliti Studi Kalimantan, dimulai pada hari Sabtu tanggal 1 November 2025 memberi pengalaman berarti buat saya yang baru pertama kali mengenali apa itu ekofeminisme. Pemateri pertama Ibu Irene Natalia Lambung dari Universitas Palangkaraya yang juga Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM), menyampaikan materi yang diberi judul Ekofeminisme dan Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan.
Dalam paparannya yang dimulai dengan mejelaskan ekofeminisme serta berbagai Komunitas yang peduli dengan lingkungan, termasuk diantarannya di Kota Makassar yaitu Solidaritas Perempuan Angin Mamiri Makassar. Selanjutnya membincangkan tentang krisis pangan yang dihadapi komunitas lokal saat ini, yang juga menjadi permasalahan dengan krisis keadilan gender. Dari paparan yang disampaikan saya memahami betapa saat ini telah terjadi penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi sumber daya alam sering kali berasal dari sistem patriarki yang sama. Untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan, kedua isu ini harus ditangani secara bersamaan. Sebagaimana diketahui bahwa, dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran air dan udara, perubahan iklim serta kerugian ekonomi jangka panjang. Sementara sitem patriarki pun menjadi tantangan bagi kaum perempuan karena rentan terhadap kekerasan fisik, emosional, bahkan kekerasan seksual sehingga mengakibatkan kesetaraan perempuan tidak dimiliki dalam berbagai aspek kehidupan.
Dalam kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengenali apa yang menjadi permasalahan di Kota Makassar, sepanjang pengetahuan dan riset yang dilakukan oleh komunitas. Setidaknya ada dua contoh yang disampaikan yaitu pertama reklamasi Pantai Losari dan kedua pembangunan kawasanan Makassar New Port (MNP). Menurut sejarah bahwa Pantai Losari pernah menjadi lokasi berdasandarnya kapal-kapal dari daerah disekitar abad ke-20. Hal ini menjadi pemandangan menarik, karena pantainya pun berpasir putih. Seperti lasimnya sebuah bibir pantai ditumbuhi pohon bakau, nipah dan beberapa jenis tanaman lainnya. Namun beberapa tahun kemudian, keindahan Pantai Losari menjadikan ikon utama bagi Kota Makassar karena memiliki cerita yang panjang. Pantai Losari menjadi objek wisata domestik maupun mancanegara, meski telah mengalami beberapa kali perubahan. Pantai Losari ini sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pantai ini menjadi tempat bagi warga Makassar untuk menghabiskan waktu pada pagi, sore, dan malam hari menikmati pemandangan matahari tenggelam yang sangat indah.
Sejak era tahun 2010-an yang lalu, didepan anjungan Pantai Losari telah dilakukan reklamasi pantai sehingga yang dulu air laut yang mengarah kebibir Pantai Losari tidak lagi sederas dulu, karena terhalang dengan hasil reklamasi dan Pulau Lae-Lae yang ada di depan anjungan. Disisi lain yang disampaikan adalah pembangunan Makassar New Port (MNP) yang terletak di bahagian utara kota Makasar. MNP adalah Proyek Strategis Nasional yang telah dimulai sejak tahun 2015. PSN ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan logistik di Kawasan Timur Indonesia dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari pelabuhan lama, dengan dilengkapi jalan tol yang terintegrasi. Selain peningkatan kapasitas logistik, NMP juga melakukan efisiensi logistik dimana waktu sandar kapal meningkat menjadi maksimal dari sebelumnya 48 jam menjadi 24 jam. Karena hal ini, MNP dirancang untuk menjadi hub logistik kawasan timur Indonesia yang dapat mendukung kegiatan eksport dan memperkuat konektifitas.
Jika melihat aspek yang disampaikan pada dasarnya reklamasi Pantai Losari adalah sebuah langkah pemerintah dalam menambah wilayah daratan kota Makassar yang hanya berkisar 175,77 km persegi. Sementara MNP mejadi hub logistic di kawasan Timur Indonesia. Mungkin yang menjadi pertanyaan kemudian apakah pengembangan tersebut dilakukan setelah mengadvokasi keadilan sosial masyarakat yang memang tidak terpisahkan dari keadilan lingkungan. Ini karena kepemimpinan berkelanjutan, mengadopsi prinsip yang berusaha untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi semua pihak, termasuk generasi mendatang. Sekedar mengingatkan bahwa kepemimpinan berkelanjutan mendorong inklusi suara perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan dapat membawa perspektif baru yang lebih mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Perempuan sering kali menjadi penjaga tradisi dan sumber daya di komunitas. Dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, mereka memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam mempromosikan praktik yang ramah lingkungan. Ekofeminisme yang dipaparkan di sesi I adalah bahagian untuk mendorong perubahan paradigma yang melihat keterhubungan antara manusia dan alam. Kepemimpinan berkelanjutan yang diinspirasi oleh perspektif yang berfokus pada solusi holistik yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Perempuan di Garda Depan Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan
Oleh: Rina Sahfitri, S.E. UIN Antasari Banjarmasin
Dalam wacana pembangunan berkelanjutan, sering kali perempuan hanya ditempatkan sebagai “korban” perubahan iklim bukan sebagai pemimpin yang berdaya. Padahal, pengalaman dan kearifan perempuan dalam mengelola sumber daya alam justru menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Karena dalam kedekatan ini, perempuan lebih peka terhadap perubahan lingkungan sekitar, menjadikan perempuan sebagai aktor penting dalam merumuskan solusi yang realistis dan berakar pada kebutuhan masyarakat. Perlu disadari bahwa keadilan gender adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan ekologis. Ketika perempuan diberdayakan dan memiliki ruang dalam pengambilan keputusan. Sudah saatnya kita melihat kepemimpinan perempuan bukan sekadar pelengkap dalam isu lingkungan, melainkan sebagai pusat dari transformasi menuju keadilan ekologis yang berakar pada empati, keberanian, dan tanggungjawab.
Perempuan memiliki kedekatan historis dan emosional dengan alam. Dalam banyak komunitas lokal, mereka berperan menjaga, mengatur, mengelola, dan memastikan ketahanan pangan keluarga. Hubungan ini bukan sekadar “kodrat”, melainkan hasil dari pengalaman sosial yang panjang. Konsep ekofeminisme menjelaskan keterkaitan antara eksploitasi alam dan penindasan terhadap perempuan. Ketika tanah, air, dan hutan dirampas oleh kekuasaan ekonomi dan politik, perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya kehilangan sumber penghidupan, ruang hidup, bahkan suara dalam pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan mereka, setidaknya perempuan-perempuan lain yang sudah berada dalam sebuah lingkaran marginalisasi bisa melihat tapak-tapak yang mereka lalui sehingga mereka tidak harus terjerat dengan permasalahan yang sama.
Salah satu contoh nyata datang dari gerakan Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM) di Kalimantan Tengah. Gerakan yang lahir dari pengalaman pahit perempuan desa menunjukkan bagaimana kerusakan lingkungan berdampak paling besar terhadap perempuan di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan proyek food estate bangkit memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan. Mereka membentuk kebun kolektif, mengelola benih lokal, dan menolak praktik pembangunan yang merusak ekosistem gambut. Kepemimpinan perempuan di sini lahir dari penderitaan, tetapi tumbuh menjadi kekuatan transformasi sosial.
Kepemimpinan perempuan dalam isu lingkungan tidak bersandar pada hierarki, melainkan pada empati, kerja kolektif, dan kesadaran moral. Hal ini tumbuh dari pengalaman kehidupan sehari-hari yang berhadapan langsung dengan realitas kehidupan itu sendiri, dikarenakan struktur atau pola kepimimpinan yang lahir pada rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kehidupan lingkungan sekitar. Berbeda dari model kepemimpinan yang sering berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, kepemimpinan perempuan lebih menekankan keberlanjutan hidup bukan sekadar kelangsungan produksi. Disinilah perspektif perempuan menjadi penting karena perempuan menilai keberhasilan bukan dari seberapa besar atau banyaknya yang dihasilkan, melainkan seberapa lama kehidupan bisa dipertahankan dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata terlihat dari bagaimana para perempuan di komunitas pedesaan Indonesia memimpin pengelolaan hutan sosial, menjaga sungai, hingga menginisiasi bank sampah. Mereka tidak menunggu keputusan dari atas, tetapi membangun perubahan dari bawah. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan rasa tanggung jawab antargenerasi menjadi inti kepemimpinan ekologis versi perempuan. Gerakan ini membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya tentang representasi, tetapi sebuah transformasi.
Meski peran perempuan semakin diakui, masih ada hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan lingkungan. Budaya patriarki, bias gender, dan minimnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap inisiatif akan komunitas perempuan. Namun, ada harapan. Undang-undang yang menunjukkan kebolehan kepemimpinan perempuan di Indonesia ada pada UU No. 7 tahun 2017 yang menjadi dasar hukum untuk mendorong kepemimpinan perempuan, Kebijakan nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan terhadap lingkungan serta UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memberi ruang bagi partisipasi perempuan yang menjadi tolak ukur penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan menegakkan hak-hak perempuan. Tantangannya kini adalah bagaimana implementasi kebijakan itu benar-benar berpihak, bukan sekadar formalitas sehingga dapat mendorong perempuan dalam kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dari Pengendalian ke Pemanfaatan: Paradigma Baru Pengelolaan Gulma di Indonesia
Oleh: Andi Ashari, S.Kom. MTA, C.EML, CCSME. Praktisi Lapangan – Program Desa Devisa (UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR)
Sebagai mahasiswa Magister Agroteknologi di Universitas Islam Makassar sekaligus praktisi dalam Program Desa Devisa LPPM IAIN Bone, saya berupaya menjembatani ruang antara teori akademik dan praktik lapangan dalam membangun sistem pertanian yang berkelanjutan. Pengalaman terlibat langsung dengan masyarakat desa di Sulawesi selatan dan Sulawesi Tenggara memperlihatkan kepada saya bahwa pengelolaan sumber daya pertanian tidak bisa lagi bersifat tunggal dan eksploitatif, melainkan harus bertransformasi menuju pendekatan yang adaptif dan ekologis.
Dalam sistem pertanian konvensional, gulma sering di anggap sebagai musuh utama tanaman dikarenakan dapat mengaggu pertumbuhan dan bersaing dalam memperebutkan unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Pandangan ini melahirkan pendekatan untuk memberantasnya dengan sebutan “pengendalian gulma”, baik secara kimiawi, mekanis, maupun manual. Namun, pandangan tersebut melahirkan sebuah pertanyaan seiring berkembangnya konsep pertanian berkelanjutan yang menekankan keseimbangan ekosistem dan efisiensi sumber daya dan temuan baru bahwa tidak semua yang dianggap gulma tidak memiliki manfaat kerna pada hakekatnya setiap ciptaan Allah SWT pasti memiliki manfaat. Sehingga dari sinilah saya mencoba membuat gagasan baru untuk mengubah sudut pandang dari pengendalian menuju pemanfaatan gulma.
Istilah pemanfaatan gulma yang saya maksudkan untuk memperluas persepsi petani bahwa keberadaan gulma tidak selalu bersifat merugikan, melainkan dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Beberapa Gulma dapat berfungsi sebagai bahan organik potensial, penutup tanah alami untuk mencegah erosi, indikator kesuburan tanah, bahkan sebagai sumber pakan ternak atau bahan baku kompos dan biochar. Sehingga pendekatan ini tidak lagi menekankan pemusnahan total, tetapi pengelolaan cerdas berbasis nilai guna ekologis dan ekonomis.
Pemanfaatan gulma secara manual menjadi titik awal transformasi ini. Metode manual yang melibatkan tenaga manusia, seperti mencabut, mencangkul, atau memotong gulma, memungkinkan petani berinteraksi langsung dengan kondisi lahannya sehingga lebih memahami jenis gulma yang tumbuh, karakteristik tanah, serta dinamika ekosistem mikro di sekitarnya. Pendekatan manual juga lebih ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu kimia dan dapat dikombinasikan dengan strategi konservasi lahan.
Perubahan istilah dari “pengendalian” menjadi “pemanfaatan” memiliki makna sosial dan psikologis yang penting. Kata pengendalian berkonotasi negative seolah gulma adalah ancaman yang harus dilawan. Sementara kata pemanfaatan mengandung semangat kolaboratif, inovatif, dan solutif. Dengan pergeseran istilah ini saya harapkan dapat mengubah cara pandang petani terhadap gulma yang bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian serta terbitnya sebuah regulasi baru yang lebih baik.
Landasan Ekologi Gulma dalam Perspektif Pemanfaatan
Gulma secara ekologis memiliki daya adaptasi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Kemampuan untuk tumbuh pada tanah miskin hara, kondisi kering, atau lahan tergenang menunjukkan peran ekologis gulma sebagai indikator kesuburan dan dinamika lingkungan pertanian. Dalam pandangan Masyarakat kehadiran gulma dianggap akan menurunkan produktivitas tanaman utama karena persaingan terhadap air, unsur hara, cahaya, dan ruang tumbuh itu tidak salah, namun keberadaannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.
Diketahui bahwa beberapa jenis gulma memiliki kandungan biomassa tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kompos, pupuk hijau, atau biochar. Misalnya, gulma dari genus Cyperus dan Echinochloa memiliki kandungan lignoselulosa yang baik untuk fermentasi organik. Ada juga spesies seperti Ageratum conyzoides dan Chromolaena odorata mengandung senyawa alelopatik yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati alami (UIR Repository, 2023). Dengan memahami ekologi gulma tidak semata bertujuan untuk mengendalikannya, tetapi juga untuk menemukan potensi pemanfaatannya dalam sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan.
Gulma juga dapat berfungsi sebagai penutup tanah alami yang melindungi permukaan lahan dari erosi, terutama pada lahan miring atau terbuka. Gulma juga menyediakan habitat bagi mikroorganisme tanah dan serangga berguna yang membantu siklus nutrisi alami. Sehingga pendekatan ekologis terhadap gulma menempatkannya sebagai bagian dari sistem agroekologi yang memiliki nilai guna ekologis, bukan sekadar hama yang perlu diberantas.
Teknik Manual yang Efektif dalam Kerangka Pemanfaatan
Teknik manual selama ini dikenal sebagai metode pengendalian yang paling sederhana namun efektif, biasanya untuk lahan skala kecil hingga menengah dengan mencabut, mencangkul, atau memotong gulma secara langsung memungkinkan petani melakukan identifikasi jenis gulma yang tumbuh dan mengelola keberadaannya secara selektif (IPB Journal, 2024). Dalam konteks pemanfaatan, teknik manual tidak hanya diarahkan untuk membasmi gulma, tetapi juga untuk memanen gulma secara terkendali sebagai sumber bahan organic, pakan ternak atau bahan baku produk.
Salah satu contoh pemnafaat gulma adalah dengan dikumpulkan, dicacah, lalu dikomposkan untuk memperkaya bahan organik tanah. Bisa juga digunakan sebagai mulsa alami untuk menekan pertumbuhan gulma baru dan menjaga kelembapan tanah. Sehingga Teknik manual berperan ganda yaitu mengurangi kompetisi tanaman utama sekaligus menyediakan input alami bagi kesuburan tanah.
Metode manual juga memiliki keunggulan sosial-ekonomi. Karena ramah lingkungan juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja lokal dan memperkuat kemandirian petani tanpa ketergantungan pada input kimia seperti herbisida. teknik ini memang memerlukan waktu dan tenaga yang relatif besar tapi memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan tanah, kualitas produk, dan keselamatan lingkungan. Keterpaduan antara teknik manual dan pemanfaatan biomassa gulma menjadikannya strategi yang relevan untuk sistem pertanian regeneratif.
Integrasi Pemanfaatan Gulma dalam Sistem Lahan Adaptif dan Produktif
Dalam sistem pertanian modern yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika lingkungan, pengelolaan gulma tidak dapat dilakukan hanya dengan satu metode saja, melainkan dibutuhkan pendekatan integratif yang bertujuan untuk menyeimbangkan produktivitas lahan, kesehatan ekosistem, dan efisiensi tenaga kerja. Sistem pemanfaatan gulma terpadu menggabungkan berbagai Teknik manual, mekanis, biologis, dan Budaya dengan tujuan bukan hanya menekan pertumbuhan gulma, tetapi juga mengelola fungsi ekologisnya agar memberi manfaat bagi lahan (Sciencedirect, 2024).
Integrasi ini dapat diwujudkan melalui:
- Rotasi Tanaman dan Penutup Tanah (Cover Cropping) : Penggunaan tanaman penutup seperti Mucuna bracteata atau Calopogonium mucunoides menekan pertumbuhan gulma sambil memperbaiki struktur tanah. Gulma sisa yang muncul dapat dimanfaatkan sebagai mulsa organik.
- Pemanfaatan Hewan Merumput dan Mikroorganisme : Hewan seperti kambing dan domba mampu mengendalikan gulma sambil menghasilkan pupuk kandang alami. Beberapa mikroorganisme juga dapat mempercepat dekomposisi biomassa gulma menjadi bahan organik tanah.
- Penggunaan Herbisida Nabati atau Herbisida Kimia Terbatas : Jika diperlukan, penggunaan herbisida dilakukan secara selektif dengan bahan alami dari ekstrak tanaman tertentu (misalnya tagetes atau tithonia), dan hanya digunakan pada area dengan populasi gulma tinggi untuk mencegah resistensi.
- Sirkulasi Biomassa Gulma dalam Sistem Lahan : Semua hasil penyiangan, baik dari teknik manual maupun mekanis, dikembalikan ke lahan sebagai kompos atau bahan biochar untuk menutup siklus nutrisi.
Pendekatan adaptif dalam pemanfaatan gulma berfungsi sebagai strategi pengelolaan sumber daya yang mendukung ketahanan dan keseimbangan agroekosistem terhadap gangguan lingkungan, dengan strategi ini dapat berkontribusi terhadap efisiensi biaya produksi, peningkatan kesuburan tanah alami, dan pengurangan ketergantungan terhadap input kimia.
Pemanfaatan Gulma Lokal Indonesia Berdasarkan Potensi Ekologis dan Ekonomis
Sebagai negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki ribuan jenis gulma yang tumbuh pada berbagai ekosistem pertanian mulai dari sawah, ladang, kebun, hingga lahan rawa dan pesisir. keberadaan gulma sering dipandang negatif karena dianggap menurunkan hasil pertanian. Namun, penelitian dan pengalaman lapangan menunjukkan bahwa banyak gulma yang memiliki nilai guna tinggi bagi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi masyarakat (Biodiversity Warriors, 2023; Rumah Rempah Solo, 2024).
Pendekatan pemanfaatan gulma bukan hanya sebatas mengubah terminologi, akan tetapi juga mencerminkan paradigma baru yang menempatkan gulma sebagai sumber daya terbarukan. Gulma dapat menjadi bahan obat, pangan alternatif, pupuk organik, bioenergi, maupun material konstruksi alami. Prinsipnya adalah memanfaatkan biomassa gulma tanpa mengabaikan pengelolaan keseimbangan ekosistem.
Berikut 10 Gulma yang ada di Indonesia dan rekomendasi pemanfaatannya :
- Ilalang (Imperata cylindrica)
Ilalang termasuk gulma perenial dengan akar rimpang menjalar dan daya regenerasi tinggi. Umumnya tumbuh di lahan kering, padang alang-alang, dan bekas tebangan hutan.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pengobatan: Rimpang ilalang berkhasiat sebagai diuretik dan antipiretik alami, berguna dalam pengobatan gangguan ginjal, hipertensi, hepatitis, dan infeksi saluran kemih (Rumah Rempah Solo, 2024; Alodokter, 2024).
- Konstruksi: Daunnya kering digunakan sebagai atap rumah tradisional yang tahan lama hingga 3–5 tahun, ramah lingkungan dan mudah diperbaharui (Wikipedia, 2024).
- Pertanian dan Ekologi: Dapat dijadikan penutup tanah untuk mencegah erosi, bahan biochar, atau mulsa kering untuk menekan gulma lain.
- Bioindustri: Potensi serat daun untuk bahan pengisi bantal atau isolator alami (Biodiversity Warriors, 2023).
- Bandotan (Ageratum conyzoides)
Gulma berbatang lembut, berbau khas, sering tumbuh di lahan terbuka dan pinggiran sawah.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pengobatan: Mengandung flavonoid dan tanin, digunakan untuk mengobati luka, demam, dan peradangan kulit.
- Pestisida Nabati: Ekstrak daun bandotan memiliki sifat insektisida dan antijamur terhadap OPT tanaman padi dan hortikultura (TaniLink, 2024).
- Ekologi: Menarik serangga penyerbuk dan menjaga keragaman mikrofauna tanah.
- Krokot (Portulaca oleracea)
Gulma menjalar dengan daun sukulen, tumbuh subur pada lahan lembab dan terpapar sinar matahari penuh.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pangan dan Gizi: Dapat dikonsumsi sebagai sayuran segar atau lalapan. Kaya omega-3, vitamin A dan C, serta mineral penting (IDN Times, 2024).
- Pengobatan: Memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan antihipertensi.
- Pertanian: Krokot dapat dimanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah alami di kebun sayuran organik.
- Anting-Anting (Acalypha indica)
Sering ditemukan di kebun, tegalan, dan sekitar pemukiman.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pengobatan Tradisional: Akar dan daun digunakan sebagai obat batuk, pencahar ringan, dan pengobatan cacingan (LindungiHutan, 2023).
- Pupuk Hijau: Biomassa anting-anting dapat dikomposkan untuk memperkaya unsur nitrogen di tanah.
- Ekologi: Menarik serangga predator alami seperti laba-laba dan kumbang tanah.
- Sambiloto (Andrographis paniculata)
Gulma tahunan dengan rasa sangat pahit, tumbuh liar di pekarangan dan tepi ladang.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Obat Herbal Modern: Mengandung andrographolide yang berfungsi sebagai antivirus, antidiabetes, dan imunostimulan (ResearchGate, 2024).
- Pengelolaan Hayati: Ekstrak sambiloto efektif sebagai pestisida nabati untuk hama ulat dan wereng.
- Bioindustri: Potensial sebagai bahan baku jamu dan fitofarmaka.
- Bayam Duri (Amaranthus spinosus)
Tumbuh liar di lahan terbuka, memiliki batang berduri dan daun menyerupai bayam.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pangan: Daun muda dapat dimasak seperti bayam biasa, kaya zat besi dan protein nabati.
- Pakan Ternak: Digunakan sebagai hijauan untuk kambing dan domba.
- Pertanian: Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pupuk hijau organik melalui fermentasi sederhana.
- Meniran (Phyllanthus niruri)
Gulma kecil dengan batang halus dan daun kecil majemuk, sering tumbuh di area lembab.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pengobatan Herbal: Meniran dikenal sebagai imunomodulator dan hepatoprotektor, membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga fungsi hati (Alodokter, 2024).
- Biofarmasi: Potensi dikembangkan menjadi bahan dasar obat herbal modern berbasis fitokimia.
- Konservasi Tanah: Akar meniran memperkuat struktur tanah dan menekan pertumbuhan gulma lain.
- Maman Ungu (Cleome rutidosperma)
Gulma tahunan dengan bunga ungu kecil, sering tumbuh di area lembab atau tanah gembur.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pengobatan: Daun dan akar digunakan secara tradisional untuk demam dan sakit kepala.
- Pangan: Di beberapa daerah Afrika dan Asia, maman dimasak sebagai sayuran kaya protein.
- Ekologi: Menjadi habitat bagi serangga penyerbuk seperti lebah kecil.
- Putri Malu (Mimosa pudica)
Gulma dengan daun majemuk yang menutup saat disentuh; banyak ditemukan di lahan kering dan padang rumput.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pengobatan: Mengandung mimosin, alkaloid, dan tanin yang bermanfaat untuk gangguan saraf dan tidur.
- Konservasi Tanah: Akar kuat membantu menahan erosi, sementara tajuknya menutup tanah dengan baik.
- Bioenergi: Biomassa putri malu dapat dijadikan bahan dasar produksi biochar.
- Teki (Cyperus rotundus)
Gulma berumbi kecil, sangat adaptif, dan sulit dikendalikan.
Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai :
- Pengobatan: Umbi teki digunakan sebagai obat gangguan pencernaan dan penenang alami.
- Bioenergi: Biomassa teki dapat diolah menjadi briket organik.
- Pertanian: Umbinya berpotensi sebagai bahan inokulan untuk mikroba tanah tertentu setelah fermentasi anaerob.
Model Bisnis Lokal Berbasis Pemanfaatan Gulma
Pemanfaatan gulma sebagai bahan baku produk bernilai tambah merupakan langkah strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau di tingkat lokal yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat secara langsung.
- Konsep Model Bisnis Berbasis Pengolahan Gulma
Model bisnis ini berfokus pada pengolahan gulma, seperti eceng gondok, ilalang, dan jenis gulma lainnya, menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga gulma tidak lagi dianggap sebagai limbah atau gangguan ekosistem, melainkan sebagai sumber daya lokal yang dapat diolah menjadi berbagai produk bermanfaat.
Berikut model Bisnis yang dimaksud adalah sebagai berikut :
- Mulai dari bahan Baku: Gulma dikumpulkan dari lingkungan sekitar secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Contohnya, eceng gondok dari perairan, rumput liar dari lahan pertanian, atau gulma rawa yang melimpah.
- Pengolahan: Gulma diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti media tanam (baglog) untuk budidaya jamur, pakan ternak, pupuk organik, kompos, hingga kerajinan tangan berbasis serat alami. Proses pengolahan dapat dilakukan dengan teknologi sederhana yang mudah diterapkan oleh masyarakat.
- Pemberdayaan Masyarakat: Kelompok masyarakat lokal seperti ibu rumah tangga, pemuda desa, dan kelompok rentan dapat menjadi pelaku utama dalam kegiatan produksi. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.
- Pelatihan dan Pendampingan: Program pelatihan diberikan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam pengolahan gulma, manajemen usaha kecil, dan strategi pemasaran. Pendampingan berkelanjutan memastikan bahwa setiap kelompok produksi mampu menjaga kualitas produk dan keberlanjutan usaha.
- Penguatan Jaringan Pemasaran: Hasil produksi dipasarkan melalui jejaring lokal seperti koperasi, kios pertanian, BUMDes, serta platform daring. Strategi ini membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai jual produk ramah lingkungan.
- Dukungan Kelembagaan: Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), BUMDes, dan dunia usaha berperan penting dalam memberikan pendanaan, fasilitas, serta dukungan regulasi untuk keberlangsungan dan ekspansi bisnis pemanfaatan gulma.
Pendekatan ini menghasilkan manfaat ganda disapmping sebagai pengendalian gulma yang lebih ramah lingkungan juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya peluang ekonomi baru dan juga menjadi inisiatif yang turut mendukung transisi menuju ekonomi hijau dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien dan berkelanjutan.
- Contoh Implementasi Nyata
Salah satu contoh penerapan model bisnis pemanfaatan gulma dapat ditemukan pada Program SIMAGMUR di Waduk Cirata. Program ini berhasil mengubah gulma eceng gondok yang sebelumnya dianggap sebagai perusak ekosistem perairan menjadi media tanam jamur tiram yang bernilai ekonomi. Melalui konsep Creating Shared Value (CSV), program ini tidak hanya mengendalikan pertumbuhan gulma, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar melalui pelatihan, pendampingan, dan pembentukan jejaring pemasaran yang berkelanjutan.
Model tersebut menunjukkan bahwa dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, gulma dapat menjadi bahan baku ekonomi produktif yang memperkuat keterkaitan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.
- Rekomendasi Pengembangan Model Bisnis
Untuk memperluas dampak positif dari pemanfaatan gulma, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, antara lain:
- Diversifikasi Produk: Mengembangkan berbagai produk berbasis gulma untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam, seperti produk kesehatan herbal, bahan bangunan ramah lingkungan, kerajinan berbasis serat, serta bahan untuk pertanian organik.
- Inovasi Teknologi: Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi sederhana namun efektif guna meningkatkan efisiensi pengolahan dan kualitas produk yang dihasilkan.
- Manajemen Usaha Partisipatif: Menerapkan sistem manajemen usaha yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota masyarakat yang terlibat.
- Integrasi dengan Pembangunan Lokal: Mengintegrasikan model bisnis ini dalam perencanaan pembangunan desa atau wilayah sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan lingkungan berkelanjutan.
Melalui Langkah dan model bisnis pemanfaatan gulma dapat berkembang menjadi sistem ekonomi lokal yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Sehingga gulma yang sebelumnya dianggap sebagai permasalahan lingkungan kini dapat dikonversi menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi, mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekologi lokal
Strategi Kebijakan Lokal untuk Pemanfaatan Gulma Secara Berkelanjutan
Pemanfaatan gulma secara berkelanjutan memerlukan kebijakan yang dirancang melalui pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. perubahan paradigma menuju pemanfaatan gulma dapat dipandang sebagai sumber daya potensial yang memiliki nilai guna ekonomi dan ekologis. Sehingga pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian populasi gulma, tetapi juga pada upaya optimalisasi manfaatnya bagi sistem pertanian dan masyarakat sekitar.
- Landasan Kebijakan Berkelanjutan
Kebijakan lokal perlu mengedepankan pentingnya pengelolaan gulma yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan yaitu dengan mengubah paradigma dari sekadar “mengendalikan” menjadi “memanfaatkan” gulma. Pengelolaan gulma terpadu (integrated weed management) menjadi strategi utama yang mengsinergikan berbagai metode untuk mencapai efektivitas dan keberlanjutan jangka panjang dan juga dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap herbisida kimia dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.
- Teknik dan Program Pendukung
Keberhasilan strategi pemanfaatan gulma memerlukan dukungan teknis dan program pemberdayaan Masyarakat berupa program pelatihan dan penyuluhan kepada petani yang mencakup identifikasi jenis gulma yang berguna atau memiliki nilai ekonomis, seperti pengolahan menjadi obat herbal, pakan ternak, bahan kompos, produksi bioherbisida alami atau bahan serat alami untuk kerajinan tangan. Kelompok tani juga dapat diberdayakan untuk mengembangkan unit usaha kecil berbasis pemanfaatan gulma.
- Regulasi
Diperlukan dukungan regulasi yang jelas dan progresif dalam mengatur praktik pemanfaatan gulma secara berkelanjutan. Regulasi ini dapat mencakup larangan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pengendalian gulma, serta memberikan panduan tentang praktik ramah lingkungan yang mendukung produktivitas lahan. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan yang mendorong pemanfaatan gulma secara optimal dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem.
- Penguatan Jejaring dan Kolaborasi
Peguatan jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci. Pemerintah, lembaga akademik, organisasi masyarakat, dan sektor swasta perlu berkolaborasi untuk saling berbagi informasi, teknologi, serta praktik terbaik dalam pengelolaan dan pemanfaatan gulma. Kolaborasi lintas sektor antara bidang pertanian, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi akan memperluas dampak positif dari strategi ini, baik dalam peningkatan kesejahteraan petani maupun dalam menjaga fungsi ekosistem.
Kesimpulan
Pemanfaatan gulma secara manual merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa gulma hanya musuh tanaman, dan sebaliknya menempatkan gulma sebagai bagian penting dari siklus ekologi pertanian. Dengan memahami landasan ekologinya, petani dapat memanfaatkan keberadaan gulma untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan bahan organik, serta menjaga keanekaragaman hayati.
Teknik manual menjadi media utama dalam implementasi strategi ini karena memungkinkan interaksi langsung antara petani dan lahan, sekaligus menyediakan bahan organik bernilai guna. Integrasi antara teknik manual dan metode lain seperti rotasi tanaman, pemanfaatan hewan merumput, serta pengelolaan residu gulma sebagai kompos, memperkuat sistem lahan yang adaptif dan produktif.
Melalui perubahan istilah dari “pengendalian” menjadi “pemanfaatan,” diharapkan muncul pergeseran mindset petani: dari sekadar menyingkirkan gulma menuju mengelola potensi gulma secara cerdas dan ekologis. Dengan begitu, strategi pemanfaatan gulma secara manual dapat menjadi bagian dari gerakan pertanian regeneratif, yang bukan hanya menanam untuk hasil panen, tetapi juga merawat kehidupan tanah dan ekosistem secara menyeluruh.
strategi kebijakan lokal yang efektif untuk pemanfaatan gulma secara berkelanjutan harus didasarkan pada pendekatan integratif yang mencakup aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Perubahan paradigma dari “pengendalian” menjadi “pemanfaatan” membuka peluang baru bagi petani untuk mengubah masalah menjadi potensi ekonomi. Gulma bukan lagi dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara kreatif dan produktif.
Keterlibatan masyarakat, dukungan penelitian, serta regulasi dan insentif yang berpihak pada praktik berkelanjutan menjadi fondasi keberhasilan program ini. Dengan demikian, pemanfaatan gulma dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian, pelestarian lingkungan, serta pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan

Ekofeminisme dan Peran Strategis Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan
Oleh: Trimanto, S.I.Kom, C.ICD. - Yayasan Hidayatul Muchsinin Alfatih
Asosiasi Pusat Studi Kalimantan (APSK) kembali mengadakan Short Course in
Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch 5 dengan tema
“Ekofeminisme dan Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan” yang pada Sabtu, 1
November 2025 diisi oleh Ev. Irene Natalia Lambung, SE, seorang aktivis Ekofeminisme,
Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM), Universitas Palangkaraya.
Pada kesempatan tersebut Irene Lambung mengemukakan latar belakang berdirinya
SPMM. Bermula dari adanya konflik dan ketidakadilan yang terjadi pada perempuan akan rumput di tiga desa di Kabupaten Kapuas. Konflik timbul karena adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menghabiskan wilayah hutan dan desa. Hal ini mengakibatkan perempuan di tiga desa tersebut kehilangan sebagian besar wilayah dan akses terhadap hutan dan lahan yang menjadi sumber penghidupannya.
Selain itu, pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar yang melanda wilayah gambut
khususnya di daerah Kapuas bagian hilir yang wilayahnya didominasi oleh lahan gambut. Masyarakat menjadi korban bencana kabut asap. Perempuan-perempuan di desa tersebut adalah kelompok rentan yang terkena dampak bencana paling besar.Solidaritas Perempuan hadir melakukan advokasi dan memberikan pengetahuan serta penguatan kepada perempuan agar mampu bersuara atas ketidakadilan yang dialami.
Kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 perempuan dari berbagai latar belakang memutuskan membentuk komunitas yang bergerak dan berjuang bersama-sama melawan ketidakadilan yang mereka namakan Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM). Nama Mamut Menteng sendiri diambil dari Bahasa Dayak yang artinya Pantang Mundur, sejalan dengan perlawanan dan perjuangan perempuan dalam bersuara.
Dalam uraiannya, Irene Lambung mengungkapkan adanya ketidakadilan gender dalam
persoalan lingkungan hidup, di antaranya:
1. Marginalisasi
Yaitu proses peminggiran, penyingkiran, atau penyisihan kaum perempuan dalam
pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan. Misalnya, rapat-rapat
pengambilan keputusan seringnya dilakukan pada jam-jam sibuk perempuan dengan
kegiatan domestik rumah tangga.
2. Diskriminasi
Yaitu perbedaan perlakuan dalam partisipasi perempuan di ruang publik, seperti
pendidikan, politik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup. Contoh, masih
minimnya elibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Perempuan belum
dianggap memiliki kapasitas pengetahuan, sehingga pendapatnya kurang mendapat apresiasi. Juga adanya pembatasan akses terhadap lahan, karena perempuan dianggap tidak mampu atau memiliki fisik yang lemah.
3. Pelabelan (Stereotip)
Cap atau hal yang dilekatkan pada perempuan. Misalnya, perempuan sebagai pengurus
rumah tangga, pengasuh anak, pengumpul kayu bakar, dan lain-lain. Pelabelan ini
membatasi peran dan kesempatan perempuan dalam aktivitas produktif dan kerja-kerja
pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan inisiatif dan kontribusi perempuan jarang diakui.
4. Subordinasi
Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam ranah domestik saja, sedangkan laki-laki lebih bertanggung jawab dalam ranah publik, sehingga kesempatan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik sangat terbatas.
5. Beban Ganda
Perempuan sering melakukan pekerjaan produktif dan reproduktif. Setelah pulang bekerja bertani/berladang, perempuan masih dibebani kerja lain seperti memasak, mencuci, mengurus anak, membersihkan dan merapikan rumah, dan lain-lain. Padahal kerja-kerja tersebut adalah kerja yang bisa dikerjasamakan atau dipertukarkan (kolaborasi dan substitusi).
Sementara itu, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh SPMM bersama komunitas
lainnya, yaitu peningkatan dan penguatan kapasitas perempuan, membentuk kelompok sel, melakukan riset partisipatif, menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan, termasuk
berpartisipasi dalam kegiatan advokasi kebijakan. SPMM juga menyoroti perihal kedaulatan pangan perempuan yang terabaikan, meliputi:
a. Pengabaian partisipasi bermakna dan keadilan rekognisi dalam seluruh tahapan
kebijakan dan program pangan nasional;
b. Tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan produsen pangan;
c. Penghilangan identitas perempuan dan pemiskinan sistemik terjadi akibat kebijakan
patriarki dan kekuasaan otokrasi egalisme;
Sedangkan, ada beberapa inisiatif kolektif yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan
dalam hal ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup, di antaranya melakukan
praktik pertanian tradisional dan kebun bersama, solidaritas ekonomi kaum perempuan
(feminism economic solidarity), serta membangun gerakan politik feminis untuk menjaga
sumber daya alam dan ruang penghidupan bagi perempuan.
Penutup
Bagi saya, paparan yang disampaikan oleh Irene Lambung menyadarkan kita akan pentingnya peran perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup maupun program ketahanan pangan. Setelah mengikuti kursus ini, kita diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengampanyekan perihal ekofeminisme ini kepada masyarakat luas, terutama kaum perempuan. Harapannya, ekofeminisme dapat menjadi kesadaran kolektif sekaligus gerakan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan.
*) Peserta Sekolah Lintas Iman (SLI) Certification in Interfaith Communication and Dialogue (C.ICD) – Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius dalam Pembangunan SDGs APSK

Ekofeminisme & Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan
Oleh: H. Muhammad Syarwani S.Pd, M.H. UNISKA Banjarmasin –Kalimantan Selatan
Krisis lingkungan global adalah kenyataan yang semakin mendesak. Perubahan iklim,
kerusakan ekosistem, polusi plastik, hingga ketidakadilan akses terhadap sumber daya
menjadi tantangan serius bagi peradaban modern. Di tengah dinamika tersebut, muncul
perspektif ekofeminisme yang menyoroti hubungan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Gerakan ini menghadirkan pendekatan etis dan sosial untuk membangun kepemimpinan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
A. Pengertian Ekofeminisme
Ekofeminisme adalah sebuah pendekatan yang menghubungkan isu feminisme dan
lingkungan, dengan keyakinan bahwa ketidakadilan terhadap perempuan dan kerusakan alam memiliki akar yang sama yaitu dominasi, patriarki, dan sistem eksploitasi.
Menurut konsep ekofeminisme, perempuan seringkali lebih dekat dengan lingkungan
karena peran sosial budaya mereka dalam mengelola sumber daya rumah tangga, pertanian, air, dan pangan. Karenanya, perempuan dianggap sebagai katalis penting dalam upaya perlindungan dan keberlanjutan ekosistem.
B. Prinsip-Prinsip Ekofeminisme
1. Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Perempuan memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan.
2. Keadilan Sosial & Ekologi Kerusakan lingkungan sering memperburuk ketidakadilan sosial, terutama bagi perempuan di pedesaan.
3. Pengakuan terhadap Pengetahuan Perempuan Perempuan memiliki kearifan lokal, dalam pengelolaan pangan, herbal, air, dan pertanian tradisional.
4. Penolakan terhadap Eksploitasi Baik tubuh perempuan maupun bumi tidak boleh
dijadikan objek eksploitasi ekonomi.
C. Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan
1. Penggerak Komunitas
Perempuan banyak memimpin gerakan lingkungan berbasis masyarakat, seperti:
a. perempuan petani organik
b. aktivis anti deforestasi
c. gerakan bank sampah & daur ulang
Mereka sering melakukan pendekatan persuasif, kolaboratif, dan emosional yang kuat.
2. Penjaga Nilai Keberlanjutan
Nilai-nilai seperti kepedulian, kelembutan, ketekunan, dan kesabaran menjadi modal
sosial untuk menumbuhkan budaya ramah lingkungan.
3. Pionir Ekonomi Hijau
Perempuan banyak terlibat dalam:
a. produk ramah lingkungan
b. pertanian berkelanjutan
c. usaha mikro berbasis alam
Model ekonomi hijau berbasis perempuan mendorong kesejahteraan sekaligus kelestarian
alam.
4. Kepemimpinan di Ruang Kebijakan
Perempuan kini semakin hadir dalam diplomasi hijau, komunitas akademik, dan
pemerintahan. Dari level lokal hingga global, mereka mendorong kebijakan iklim yang inklusif dan berkeadilan.
D. Tantangan dalam Ekofeminisme
Meskipun potensinya besar, ekofeminisme masih menghadapi hambatan:
1. budaya patriarki yang membatasi ruang perempuan
2. minimnya akses modal dan pendidikan
3. ketidakadilan ekonomi
4. kurangnya representasi perempuan pada pengambilan keputusan tinggi
Oleh sebab itu, dukungan institusi, pendidikan, dan kebijakan menjadi langkah
penting.
E. Ekofeminisme sebagai Solusi Masa Depan
Ekofeminisme memberikan perspektif baru dalam membangun dunia yang lebih adil
dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengutamakan:
1. kesetaraan dan keberpihakan pada kelompok rentan
2. pelestarian alam sebagai nilai utama
3. partisipasi aktif perempuan dalam kepemimpinan
4. pembangunan yang menghargai kearifan lokal
Dengan memberi ruang lebih besar bagi perempuan dalam gerakan lingkungan,
masyarakat dapat menciptakan perubahan yang lebih humanis, inklusif, dan berjangka
panjang. Ekofeminisme bukan hanya kritik sosial, tetapi juga strategi transformasi lingkungan. Melalui pendekatan ini, perempuan ditempatkan sebagai agen penting dalam mengatasi krisis ekologis. Kepemimpinan perempuan yang berbasis empati, keadilan, dan kerja sama menghadirkan harapan baru bagi dunia yang lebih hijau dan setara. Masa depan bumi memerlukan kolaborasi, kesadaran, dan keberanian—dan
perempuan memainkan peran sentral dalam perjalanan tersebut. Dengan menggabungkan kesadaran gender dan lingkungan, kita membangun pondasi kuat menuju keberlanjutan bumi untuk semua generasi.
“Bumi adalah rumah bagi semua, dan perempuan adalah pelindung cahaya kehidupan.
Saat perempuan memimpin menjaga alam, masa depan tumbuh lebih hijau, lebih adil, dan lebih manusiawi.”

Ekofeminisme dan Kepemimpinan Lingkungan
Oleh: Elis Nurhayati, S.Ag., M.Hum., MPP. Pendiri Daya Data Komunitas & Peneliti Riset Estungkara Kemitraan
Sesi perdana Short Course Certified of Environmental Management Leadership (C.EML)
Batch 5, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSKAL) pada 1
November 2025, menghadirkan Irene Natalia Lambung, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM) dari Universitas Palangka Raya. Dengan tema “Ekofeminisme dan Kepemimpinan Lingkungan Berkelanjutan,” sesi ini menyoroti bagaimana krisis pangan yang kini dihadapi banyak komunitas lokal di Indonesia juga merupakan krisis keadilan gender. Melalui pengalaman SPMM, Irene menunjukkan bahwa di balik kerentanan akibat tekanan struktural dan eksploitasi sumber daya, yang diperparah dengan dampak perubahan iklim, perempuan justru menumbuhkan kapasitas adaptif dan daya kepemimpinan yang penting bagi keberlanjutan lingkungan.
Solidaritas Perempuan Mamut Menteng lahir dari realitas ketidakadilan ekologis di tiga desa di Kabupaten Kapuas — Mantangai Hulu, Kalumpang, dan Sei Ahas. Konflik bermula ketika ekspansi perkebunan kelapa sawit menyerobot wilayah hutan dan desa, menyebabkan perempuan kehilangan lahan dan sumber penghidupan. Perubahan tutupan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber pangan dan air, yang selama ini menopang kehidupan
warga.
Krisis tersebut mencapai puncaknya pada kebakaran besar tahun 2015, yang melanda
kawasan gambut dan menimbulkan bencana asap parah. Perempuan, bersama kelompok lanjut usia dan anak-anak, menjadi kelompok paling rentan: mereka harus tetap memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan pangan, kesehatan yang memburuk, dan hilangnya sumber penghidupan. Namun, dari krisis itu pula muncul kesadaran baru. Pada 21 Juli 2019, para perempuan di tiga desa tersebut membentuk Solidaritas Perempuan Mamut Menteng. Frasa “Mamut Menteng” berasal dari bahasa Dayak yang berarti pantang mundur — sebuah wujud perlawanan tak gentar terhadap ketidakadilan dan ruang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kerja kolektif SPMM berfokus pada lima ranah utama: peningkatan kapasitas perempuan, riset partisipatif, pembentukan kelompok sel, penciptaan pemimpin perempuan, dan advokasi kebijakan di tingkat lokal. Melalui kegiatan ini, perempuan bukan hanya memperoleh pengetahuan dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mengembangkan model ekonomi alternatif berbasis solidaritas.
Mereka membangun kebun kolektif, menghidupkan praktik pertanian tradisional, dan
memperkuat jaringan dukungan lintas komunitas. Kisah SPMM mencerminkan gagasan utama dalam konsep ekofeminisme yang pertama kali dirumuskan oleh feminis dan ekolog Perancis Francoise d’Eaubonne pada 1974 yang mengaitkan eksploitasi terhadap alam dengan dominasi atas Perempuan. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Maria Mies dan Vandana Shiva dalam Ecofeminism (1993/2014). Mies dan Shiva berargumen bahwa kezaliman terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan berakar pada sistem patriarki dan kapitalisme global, yang keduanya mengobjektifikasi tubuh perempuan dan alam sebagai sumber daya untuk dieksploitasi tanpa batas. Mereka menawarkan “perspektif subsisten” (subsistence perspective)—cara pandang yang berfokus pada praktik-praktik perawatan, kerja kolektif, dan reproduksi kehidupan sehari-hari sebagai dasar bagi sistem ekonomi dan ekologis yang berkeadilan (Mies & Shiva, 2014 [1993]). Dalam konteks SPMM, perspektif ini diwujudkan melalui kebun kolektif, pertanian tradisional, dan solidaritas ekonomi feminis yang berbasis pada kerja sama, bukan kompetisi pasar.
Pendekatan SPMM juga sejalan dengan pemikiran Vandana Shiva dalam Ecology and the Politics of Survival (1991), yang menegaskan bahwa perempuan di Selatan Global, terutama di pedesaan dan komunitas adat, memiliki kedekatan material dan spiritual dengan alam karena keterlibatan langsung mereka dalam mempertahankan kehidupan. Seperti perempuan di India Utara yang memelopori gerakan Chipko untuk melindungi hutan dari penebangan, perempuan di Kapuas juga menolak kehilangan sumber kehidupannya dengan cara yang damai dan berdaya: mengorganisir diri, menanam kembali lahan terbakar, dan menghidupkan kearifan lokal dalam pengelolaan pangan.
Dalam kerangka teoretis yang lebih luas, pengalaman SPMM mengilustrasikan apa yang
disebut oleh Ariel Salleh (1984) sebagai embodied materialism, yakni pemahaman bahwa
tubuh perempuan—melalui pengalaman reproduksi, perawatan, dan hubungan sehari-hari dengan alam—menjadi locus kesadaran ekologis. Salleh berargumen bahwa perempuan, sebagai “penjaga oikos” atau rumah tangga ekologis, memiliki posisi strategis untuk mempraktikkan etika ekologis setiap hari. Hal ini tampak nyata pada perempuan SPMM yang memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk memulihkan ekosistem gambut dan membangun kembali sistem pangan lokal berbasis gotong royong.
Di sisi lain, Carolyn Merchant dalam The Death of Nature (1980/1990) menelusuri akar
historis dari paradigma patriarkis modern terhadap alam, yang bermula pada revolusi ilmiah abad ke-17. Merchant menunjukkan bagaimana filsafat mekanistik yang diusung Francis Bacon dan ilmuwan Eropa lainnya membenarkan dominasi manusia (terutama laki-laki) atas alam melalui bahasa kekuasaan dan penaklukan. Dalam logika ini, alam direduksi menjadi “mesin” dan perempuan disubordinasikan ke ranah domestik. Jejak historis ini masih terasa dalam kebijakan pembangunan modern yang menyingkirkan perempuan dari pengelolaan sumber daya alam. SPMM, dengan strategi advokasi dan pendidikan publiknya, sedang menantang warisan epistemologis itu melalui praktik kepemimpinan ekologis yang berakar pada relasi timbal balik antara manusia dan alam.
Pandangan etis ekofeminisme sebagaimana dirumuskan oleh Karen J. Warren (1997) juga relevan dalam konteks ini. Warren menegaskan adanya keterkaitan mendasar—baik historis maupun simbolis—antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam. Ia menyebutnya sebagai “the logic of domination,” yaitu cara berpikir dualistik yang memisahkan budaya dari alam, akal dari emosi, dan laki-laki dari perempuan. Menurut Warren, etika lingkungan yang memadai harus memutus logika dominasi tersebut dan membangun etika relasional yang menghargai keberagaman, kerja sama, dan kepedulian. Gagasan ini hidup dalam praktik SPMM, di mana perempuan menjadi pengambil keputusan dalam pengelolaan pangan komunitas dan mengubah relasi kuasa di tingkat rumah tangga maupun desa.
Krisis pangan yang dialami perempuan di Kapuas, sebagaimana dicatat oleh Catatan
Tahunan Solidaritas Perempuan (2025), bukan sekadar akibat degradasi lingkungan, tetapi hasil dari struktur kebijakan yang mengabaikan partisipasi perempuan. Sebanyak 3.624 perempuan di 57 desa di Indonesia mengalami pemiskinan dan kehilangan sumber
penghidupan akibat ekspansi industri ekstraktif. Fenomena ini memperlihatkan bentuk-
bentuk ketidakadilan gender dalam lingkungan hidup: diskriminasi dalam pengambilan
keputusan, marginalisasi ekonomi, pelabelan peran domestik, subordinasi sosial, dan beban ganda. Banyak penelitian di Asia, termasuk salah satunya Riset Estungkara Kemitraan (2025) menunjukkan bahwa bentuk-bentuk ketimpangan ini merupakan konsekuensi langsung dari komodifikasi sumber daya yang menyingkirkan peran perempuan dalam ekonomi lokal. Namun, dari situ pula muncul daya lenting sosial-ekologis. SPMM membuktikan bahwa resiliensi bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi proses membangun sistem pengetahuan dan ekonomi alternatif yang lebih adil. Melalui riset partisipatif, kelompok sel perempuan, dan pendidikan kepemimpinan, mereka mengartikulasikan ulang kedaulatan pangan sebagai hak politik dan ekologis. Pendekatan ini selaras dengan gagasan feminist political ecology (Harcourt & Nelson, 2015) yang menekankan pentingnya mengaitkan isu lingkungan dengan relasi kekuasaan gender dan keadilan sosial.
Sesi perdana C.EML ini menunjukkan bahwa krisis pangan dan krisis iklim tidak dapat
dipisahkan dari krisis representasi dan rekognisi terhadap perempuan. Kepemimpinan
lingkungan yang berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan Irene Natalia Lambung dan
SPMM, tumbuh dari etika perawatan, solidaritas, dan penghargaan terhadap
kehidupan—nilai-nilai yang selama ini diabaikan dalam model pembangunan arus utama. Program C.EML Batch 5 terdiri dari empat sesi. Setelah Irene, tiga narasumber lainnya adalah Dr. Lena Hanifah dari University of New South Wales, Dr. Aurora Hanggarani Ponda dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Universitas Gadjah Mada, dan Dr. Noorhidayah dari Goethe University. Keempat sesi ini diharapkan tidak hanya memperkaya pemahaman akademik, tetapi juga memperkuat gerakan kepemimpinan lingkungan yang berpihak pada keadilan ekologis dan kesetaraan gender di Indonesia. Keseluruhan rangkaian ini
menegaskan bahwa masa depan kepemimpinan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari
perjuangan perempuan yang membangun dunia lebih adil bagi manusia dan bumi.
Sesi perdana C.EML juga menunjukkan bahwa mengatasi krisis pangan dan iklim tidak cukup dengan inovasi teknologi atau kebijakan ekonomi hijau, tetapi memerlukan transformasi sosial yang mengakui hak dan kapasitas perempuan. Ketika perempuan diakui sebagai pemilik pengetahuan unik dan menjadi bagian aktif dalam pengambilan keputusan, sistem pangan menjadi lebih tangguh, beragam, dan adil. Inilah makna substantif dari ekofeminisme di Indonesia — bukan sekadar teori, melainkan praktik sosial yang tumbuh dari pengalaman komunitas perempuan dalam menjaga kehidupan.

Krisis Pangan dan Keadilan Gender
Oleh: Muhammad Adri Waskito, S. Psi Praktisi Food Supply Chain Indonesia dan UK
Sebagai seseorang yang pernah bekerja di lingkungan BUMN Holding Pangan, saya sering menyaksikan secara langsung betapa kompleksnya persoalan pangan di Indonesia. Di ataskertas, konsep food estate seperti yang dikembangkan di Dadahup, Kalimantan Tengah tampak menjanjikan: lahan ribuan hektar yang dikelola secara modern, terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan dukungan teknologi dan investasi besar-besaran. Namun di balik ambisi kedaulatan pangan yang diagung-agungkan, ada satu aspek yang sering terabaikan: perempuan dan peran mereka dalam ekosistem pangan lokal.
Food Estate Dadahup: Antara Harapan dan Realita
Saat Presiden Jokowi meninjau proyek food estate di Dadahup, harapan masyarakat begitu besar. Lahan-lahan rawa yang selama ini dianggap sulit diolah diubah menjadi sentra produksi padi nasional. Namun, di lapangan, banyak hambatan muncul: kondisi tanah gambut yang rapuh, sistem irigasi yang tidak berfungsi optimal, hingga lemahnya pemberdayaan masyarakat lokal. Yang paling ironis, food estate yang seharusnya memberdayakan petani justru kerap menggeser peran mereka terutama perempuan.
Perempuan dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga
Dalam banyak komunitas pedesaan di Indonesia, perempuan bukan sekadar “pendamping petani”. Mereka adalah penentu strategi pangan keluarga: mengatur apa yang ditanam di pekarangan, bagaimana bahan pangan diolah, disimpan, hingga dijual di pasar. Dalam konteks seperti Dadahup, di mana proyek besar mengambil alih lahan-lahan warga, perempuan sering kehilangan ruang produktifnya. Mereka tidak lagi memiliki akses ke lahan kecil yang dulu bisa ditanami sayur atau rempah; bahkan kadang kehilangan sumber penghasilan kecil dari hasil kebun. Ketika proyek besar datang dengan orientasi komoditas tunggal (padi, singkong, atau jagung), keragaman pangan yang dijaga oleh perempuan justru lenyap.
Perspektif dari Dalam Sistem
Sebagai praktisi yang dulu terlibat di BUMN Holding Pangan, saya melihat bagaimana
kebijakan pangan sering dibuat dari meja rapat di Jakarta, dengan asumsi efisiensi,
produktivitas, dan skala ekonomi besar. Namun, dalam banyak rapat strategis, isu gender dan peran sosial masyarakat lokal jarang sekali menjadi pertimbangan. Padahal, jika berbicara tentang kedaulatan pangan, bukan hanya soal ketersediaan beras atau jagung dalam volume besar. Kedaulatan pangan berarti hak masyarakat termasuk perempuan untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri: dari benih, pola tanam, hingga distribusi. Belajar dari Lapangan. Dalam kunjungan lapangan saya ke daerah sentra pangan di Kalimantan dan Sulawesi, saya sering melihat perempuan yang tetap menjaga ketahanan pangan keluarga dengan cara-cara sederhana: menanam di lahan sempit, mengelola hasil panen rumah tangga, bahkan membuat produk olahan seperti keripik singkong atau abon ikan. Sayangnya, inisiatif seperti ini jarang mendapat dukungan formal dari proyek besar yang lebih sibuk menghitung tonase produksi.
Menuju Kedaulatan yang Inklusif
Kedaulatan pangan seharusnya tidak hanya tentang “beras cukup”, tetapi juga tentang keadilan sosial dalam produksi dan distribusi pangan. Perempuan harus diakui bukan sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama. Setiap perencanaan food estate atau proyek pangan nasional seharusnya melibatkan perempuan lokal dalam tahap perencanaan, pelatihan, dan pengambilan keputusan. Tanpa mereka, kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan yang kehilangan makna karena ia berdiri di atas ketimpangan yang sama: pembangunan yang maskulin, birokratis, dan tidak berpihak pada akar rumput.
Penutup
Kita perlu mengingat bahwa kedaulatan pangan sejati bukan sekadar swasembada, melainkan kemandirian dan keberlanjutan yang tumbuh dari bawah. Jika perempuan terus dikesampingkan, maka proyek pangan apa pun sebesar dan secanggih apa pun akan kehilanganja ntungnya. Karena pada akhirnya, yang menjaga kehidupan pangan bangsa ini bukan mesin traktor, melainkan tangan-tangan perempuan yang menanam, mengolah, dan memberi makan keluarga mereka setiap hari.

Perempuan Bangkit [Tanpa] Mengabaikan Laki-Laki
Oleh: Dr. Muhammad Said, S.Sos.M.Si. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Pengetahuan yang berbasis aktivisme selalu menarik. Ia tidak berjarak antara narasi dan praktik. Ia langsung berdampak. Ia mampu menghubungkan pengetahuan dengan tindakan dan perubahan sosial. Setidaknya pelajaran pertama ini adalah refleksi kritis dari materi ekofeminis dan kepemimpinan lingkungan berkelanjutan di Short Course Batch 5 APSK pada hari Sabtu 1 Nopember 2025 (01/11/2025). Pematerinya adalah seorang perempuan luar biasa, Irene Natalia Lambung, seorang akademisi sekaligus aktivis perempuan. Dia adalah Ketua BEK Solidaritas Perempuan Mamut Menteng (SPMM) Kalimantan Tengah. Tema materinya menggambarkan paradigma gerakan “ekofeminis” yang diangkat dari masalah-masalah sehari-hari perempuan di akar rumput yang ingin langsung menembus jantung masalah “memampukan perempuan” menuju kepemimpinan lingkungan berkelanjutan. Paradigma ini yang ingin diadaptasi oleh Kemendiktisaintek dan kampus-kampus di negeri ini yang meluncurkan logo dan slogan “berdampak” di pertengahan tahun 2025.
Irene Natalia Lambung, mantan penyiar radio rohani gema oikumene dan radio swasta ozon, bersama perempuan-perempuan hebat yang lain terlibat aktif dalam mendirikan, memobilisasi dan mengorganisir SPMM. Mereka memberikan nama organisasinya sebagai organisasi perjuangan, filosofis, dan menggunakan bahasa lokal sebagai bukti “mereka tidak berjarak dengan perempuan yang dibela dan diperjuangkan. Nama Mamut Menteng diambil dari Bahasa Dayak yang artinya Pantang Mundur, sejalan dengan perlawanan dan perjuangan perempuan dalam bersuara.
Ini pelajaran kedua dari materi ini, bahwa setiap kerja-kerja pendampingan, pembelaan dan advokasi dari “orang luar” hendaknya memposisikan diri sebagai “orang dalam”, kalau tidak ingin mengatakan sama-sama menjadi “pihak korban” yang turut serta merasakan atau “live in” dengan masyarakat yang didampingi, dibela dan diadvokasi. Pendekatan ini dianggap sukses dalam meng-engagement masyarakat dampingan untuk terlibat, berpartisipasi dan berkomitmen terhadap suatu isu dan gerakan.
Gerakan SPMM yang dicertikan oleh Irene Natalia Lambung: “berawal atau berangkat dari adanya konflik dan ketidakadilan yang terjadi pada perempuan akar rumput di 3 desa di Kabupaten Kapuas, yaitu yaitu Desa Mantangai Hulu, Desa Kalumpang dan Desa Sei Ahas. Konflik timbul karena adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menghabiskan wilayah hutan dan desa akibtnya perempuan di desa kehilangan sebagian besar wilayah dan akses terhadap hutan dan lahan yang menjadi sumber penghidupannya. Kemudian, Pada tahun 2015 terjadi kebakaran besar yang melanda wilayah gambut khususnya di daerah Kapuas bagian hilir yang wilayahnya didominasi oleh lahan gambut. Masyarakat di Desa Mantangai, Desa Kalumpang dan Desa Sei Ahas menjadi korban bencana kabut asap. Perempuan perempuan di desa tersebut adalah kelompok rentan yang terkena dampak bencana sangat besar”. Harus diakui bahwa setiap terjadi suatu krisis, maka perempuanlah yang paling merasakan dampaknya.
Ini pelajaran ketiga, dimana sejatinya setiap gerakan yang diniatkan untuk berhasil dan berkelanjutan setidaknya menemukan “momentum” sebagai trigger perjuangan. Gerakan ini dimulai dari telaah dan pemetaan fenomena dan masalah yang tengah berlangsung di lapangan kemudian mengundang teori, paradigma dan pendekatan yang sesuai konten dan konteks sosialnya. Seperti kata Spradley (2006): “Sebelum Anda menerapkan teori Anda pada orang yang Anda pelajari, terlebih dahulu temukanlah bagaimana orang-orang itu mendefinisikan dunia”. Tentu saja, pengetahuan awal tetap penting untuk menelaah fenomena dan masalah yang sedang berlangsung. Dalam konteks gerakan sosial, kira-kira ini disebut dengan aktivisme yang berpengetahuan.
Terjebak Romantisasi Gerakan Feminisme
Di penghujung materi, Irene Natalia Lambung menyarikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender (dalam konteks ini ketidakadilan terhadap perempuan) dalam Lingkungan Hidup sebagai basis gerakan ekofeminis: (1) Diskriminasi: perbedaan perlakuan dalam partisipasi perempuan di ruang public, pendidikan, pekerjaan, politik, sosial dan lingkungan hidup; (2) Marginalisasi : proses peminggiran, penyingkiran atau penyisihan perempuan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan; (3) Pelabelan/sterotype: cap atau hal yang dilekatkan pada perempuan contoh perempuan sebagai pengumpul kayu bakar, perempuan sebagai penjaga rumah,keluarga; (4)Subordinasi: Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam ranah domestic saja, sedangkan laki-laki lebih bertanggung jawab dalam ranah produksi dan public; (5) Beban Ganda:Perempuan sering melakukan pekerjaan produktif dan reproduktif. Setelah pulang bekerja mencari uang/berladang, perempuan juga dibebani kerja lain yaitu kerja-kerja domestic seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan lain-lain.
Salah satu praktik baik dari gerakan ini adalah kemandirian perempun dalam mengorganisir pratek pertanian tradisional dan kebun kolektif sebagai bagian dari inisatif kolektif perempuan dalam memastikan keberlanjutan pangan
dan kelestarian lingkungan tanpa keterlibatan laki-laki, mulai dari proses pengurusan ijin, pengolahan tanah, produksi dan distribusi hasil panen.
Menurut penulis, gerakan ekofeminis ini masih terjebak pada romantisasi gerakan femenisme awal (Feminisme Radikal) yang lahir pada abad ke-18, dimana gerakan feminisme muncul sebagai sebuah respons terhadap posisi sebagai sebuah pola relasi yang menempatkan laki-laki sebagai subyek, yaitu kaum superior yang mendominasi kaum perempuan. Semacam gugatan terhadap hegemoni laki-laki terhadap perempuan, bahwa apa yang menjadi tuntutan dan persoalan dari gerakan ini adalah kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Gunawan (2016) mengkritik bahwa sekalipun kesetaraan jenis kelamin merupakan sesuatu yang dapat diterima secara umum, namun secara substansi, apa yang dituntut oleh kaum feminis, dapat menimbulkan persoalan baru di dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan.
Gunawan (2016) mengutip karya Friedan, The Second Stage. Friedan berpendapat bahwa feminisme yang baru akan menuntut perempuan berkolaborasi dengan laki-laki untuk melepaskan diri dari akibat yang ditimbulkan oleh Feminist Mystique, yaitu bahwa perempuan mengabaikan cinta, kasih sayang dan rumah. Ia mendapati bahwa perempuan tidak dapat dilepaskan dari kemanusiaannya di dalam kerangka hubungannya dengan laki-laki sebagai seorang istri, ibu dan perawat rumah. Dengan cara inilah, ia memperbaharui pemikirannya: bersama-sama dengan laki-laki, perempuan dapat mengembangkan nilai-nilai sosial, kepemimpinan dan struktur institusional sehingga memungkinkan kedua jenis kelamin ini mencapai pemenuhannya, baik di dunia publik ataupun di dunia privat. Dalam karyanya The Second Stage, Friedan mulai menyadari bahwa: “pekerjaan tanpa keluarga justru akan membuat perempuan kesepian”.

Tri Hita Karana: Menjaga Harmoni, Merawat Alam
Oleh: Adnan Iman Nurtjahjo Amir, S.M., C.EML. FKUB Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta
Di tengah gempuran krisis lingkungan global, masyarakat Bali menyimpan warisan kearifan lokal yang menjadi penuntun dalam menjaga keseimbangan hidup. Konsep itu adalah Tri Hita Karana, falsafah hidup yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan). Ketiganya tak bisa dipisahkan, membentuk satu kesatuan untuk menciptakan kehidupan yang selaras dan berkelanjutan.
Tri Hita Karana bukan sekadar semboyan, melainkan prinsip hidup yang mewujud dalam praktik keseharian masyarakat. Dalam setiap aktivitas, baik bersifat religius, sosial, maupun ekologis, masyarakat Bali berupaya menjaga keseimbangan agar tidak terjadi ketimpangan yang berujung pada kerusakan. Ketika salah satu hubungan terganggu, maka keharmonisan semesta pun ikut tercabik.
Dasar Spiritual Menjaga Alam
Hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan) menjadi dasar spiritual dalam menjaga alam. Setiap upacara keagamaan seperti tumpek uduh yang khusus dipersembahkan untuk menghormati pohon dan tumbuhan, menjadi bentuk penghormatan terhadap sumber kehidupan. Doa-doa dipanjatkan agar alam tetap subur, seimbang, dan memberi berkah bagi manusia.
Kesadaran spiritual ini membentuk pola pikir bahwa alam bukan objek eksploitasi, melainkan entitas suci yang layak dihormati. Sungai tidak sekadar aliran air, tetapi bagian dari kehidupan yang memiliki roh. Gunung dianggap sebagai tempat tinggal para dewa, dan laut dipandang sebagai sumber berkah sekaligus wilayah yang harus dijaga dari pencemaran.
Hubungan manusia dengan sesama (pawongan) mencerminkan pentingnya solidaritas dalam menjaga lingkungan. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan bersama komunitas yang saling bergantung. Dalam urusan lingkungan, gotong royong menjadi alat penting untuk membersihkan desa, mengelola sampah, hingga menghidupkan pertanian berkelanjutan.
Nilai pawongan juga tercermin dalam sistem adat yang mengatur tata ruang desa. Setiap pembangunan harus melalui musyawarah dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Hal ini mencegah terjadinya eksploitasi yang bisa merugikan generasi mendatang. Peran kolektif dalam merawat alam menjadi wujud nyata dari hubungan harmonis antarwarga.
Dimensi palemahan, atau hubungan manusia dengan alam, menjadi aspek paling konkret dalam konteks kelestarian lingkungan. Dalam falsafah ini, alam adalah bagian dari kehidupan, bukan hanya sarana penopang hidup. Oleh karena itu, tindakan yang merusak hutan, mencemari sungai, atau mengeksploitasi tanah dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan semesta.
Subak Warisan Budaya Dunia
Salah satu implementasi dari Tri Hita Karana adalah sistem pertanian subak, yakni sistem irigasi tradisional yang mengatur pembagian air secara adil untuk para petani. Subak bukan sekadar soal teknis pertanian, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang menyatu. Di tengah sistem itu terdapat pura subak yang menjadi pusat doa dan pengikat moral. Melalui sistem subak, para petani belajar bahwa menjaga sumber air, tanah, dan ekosistem pertanian adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab bersama. Keseimbangan ini membuat pertanian di Bali tetap lestari meskipun tekanan modernisasi terus datang menghampiri. Subak bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa perkembangan zaman membawa tantangan baru. Alih fungsi lahan untuk pembangunan pariwisata, meningkatnya sampah plastik, dan menurunnya kualitas air menjadi isu yang mulai menggerus nilai-nilai Tri Hita Karana. Banyak komunitas adat kini berjuang mempertahankan warisan kearifan lokal di tengah arus globalisasi.
Di sinilah pentingnya revitalisasi nilai Tri Hita Karana melalui pendidikan dan kebijakan publik. Sekolah-sekolah, komunitas, dan pemerintah lokal perlu mengintegrasikan konsep ini dalam program pembangunan. Dengan begitu, kelestarian lingkungan tidak lagi sekadar jargon, melainkan menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup masyarakat.
Kearifan Lokal Menjadi Inspirasi Global
Beberapa desa di Bali bahkan sudah mulai mengembangkan ekowisata berbasis Tri Hita Karana. Wisatawan diajak tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar tentang harmoni hidup masyarakat Bali. Mereka melihat langsung praktik subak, ikut serta dalam ritual adat, dan memahami filosofi yang menjaga keharmonisan alam.
Ketika dunia tengah mencari solusi atas krisis iklim dan kerusakan lingkungan, Tri Hita Karana menawarkan perspektif alternatif yang bersifat holistik. Ia tidak hanya menjawab masalah ekologi, tetapi juga memperkuat fondasi spiritual dan sosial dalam menghadapi tantangan zaman. Inilah bentuk kearifan lokal yang mampu menjadi inspirasi global.
Dengan menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam, manusia tidak hanya menjaga lingkungannya, tetapi juga menjaga jati dirinya sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Konsep ini mengajarkan bahwa kesejahteraan tidak bisa dicapai dengan mengorbankan alam, melainkan dengan hidup berdampingan dalam keseimbangan.
Tri Hita Karana memberi pesan sederhana namun dalam: ketika manusia hidup selaras dengan alam, maka alam pun akan melindungi manusia. Dalam harmoni itu, ada ruang untuk tumbuh bersama, sehat bersama, dan lestari bersama—bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang.

Generasi Muda :Pewaris Masa Lalu dan Penentu Masa Depan Dalam Spirit Dharma, Ekoteologi, dan Kearifan Nusantara
Oleh : I Putu Dicky Merta Pratama, S.H., M.H. (PRADITAMA - Prakarsa Dharma Insan Pratama Nuswantara)
“Tat Twam Asi – Engkau adalah aku, aku adalah engkau.”
Ungkapan suci ini tidak hanya menyatukan makhluk hidup dalam kesadaran spiritual, tetapi juga mengandung pesan mendalam: bahwa penderitaan dan kehancuran yang dialami bumi serta sesama makhluk adalah juga penderitaan kita sendiri.
Kita hidup di zaman yang penuh paradoks.
Kemajuan teknologi melesat, tetapi krisis iklim memburuk.
Jaringan global terbuka luas, tetapi intoleransi dan polarisasi identitas justru mengeras.
Kemudahan informasi tak terbendung, tetapi kebijaksanaan lokal dan nilai-nilai luhur terpinggirkan.
Kita membangun gedung-gedung pencakar langit, namun akar spiritual dan ekologis kita tercabut dari tanah.
Kita menciptakan ruang digital yang menghubungkan dunia, tapi hubungan antarmanusia menjadi kering dan dangkal.
Kita memuja efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, namun melupakan harmoni dan keberlanjutan hidup bersama.
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan, alam dikorbankan, budaya disederhanakan, dan spiritualitas tercerabut dari akarnya.
Bali yang disebut sebagai pulau dewata hari ini pun menghadapi tekanan berat:
- Apakah pembangunan yang terus melaju itu masih setia pada Tri Hita Karana, atau justru melanggengkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan?
- Apakah nilai-nilai seperti Sad Kertih dan Dharma-Shanti masih menjadi nafas hidup masyarakat, atau hanya menjadi simbol dalam upacara?
Di titik ini, generasi muda tidak bisa sekadar berdiri di pinggir jalan sejarah.
Mereka adalah pewaris peradaban yang juga bertanggung jawab menulis arah baru masa depan.
Sudahkah kita benar-benar memahami warisan yang kita terima? Atau justru sedang membiarkan warisan itu memudar dalam ketidakpedulian?
Apakah kita cukup berani mempertanyakan: kemajuan seperti apa yang sedang kita kejar? Dan atas nama siapa pembangunan ini dilaksanakan?
Dunia tidak menanti pemuda yang hanya cerdas secara akademik atau lincah di media sosial.
Dunia membutuhkan pemuda yang berani berdiri atas nilai, yang menyatukan iman dan aksi, dan yang menghidupkan kembali dharma dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagaimana tertulis dalam Lontar Tutur Bhuwana:
“Bumi bukanlah milik kita untuk diambil sekehendak hati, tetapi kita yang menjadi bagian darinya.
Jagalah Bhuwana Agung seperti menjaga ibu kandungmu sendiri.”
Refleksi ini membawa kita pada kesadaran mendalam: bahwa ekoteologi bukanlah konsep asing bagi peradaban Nusantara, melainkan denyut nadi hidup yang diwariskan para leluhur.
Kepemimpinan berbasis dharma, spiritualitas, dan kasih terhadap semua makhluk telah hadir dalam sistem Subak, semangat Nyegara Gunung, dan prinsip Desa Kala Patra yang menjaga harmoni antara ruang, waktu, dan tindakan manusia.
Maka pertanyaannya bukan lagi: “apa yang harus dilakukan pemerintah?” tetapi: “apa yang bisa saya mulai, hari ini, untuk menjaga keseimbangan jagat ini?”
Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu nanti—peradaban yang tercerai, atau bumi yang lestari?
Dari sinilah generasi muda perlu bergerak.
Bukan sekadar menatap masa depan dengan harapan kosong, tetapi melangkah dengan kesadaran dan keberanian.
Bergerak untuk menghidupkan kembali nilai-nilai spiritual dalam tindakan nyata—agar iman tak berhenti di altar dan upacara, tetapi hadir dalam kepedulian sosial, keberpihakan pada yang terpinggirkan, dan penghormatan pada kehidupan.
Bergerak untuk membangun solidaritas lintas iman dan lintas budaya, bukan sebagai slogan damai semu, tetapi sebagai jalinan kemanusiaan yang saling menguatkan di tengah krisis yang memecah.
Bergerak untuk merawat warisan alam dan budaya, bukan sebagai komoditas yang dikemas dan dijual, tetapi sebagai pusaka jiwa yang diwariskan oleh leluhur dan harus disucikan dengan cinta dan tanggung jawab.
Dan yang terpenting, bergerak untuk menghadirkan kepemimpinan baru—yang tidak lahir dari ambisi kekuasaan, tetapi dari kedalaman welas asih, dari keberanian menjaga yang rapuh, dan dari tekad merawat keseimbangan jagat raya.
Generasi muda tidak hanya pewaris bhisama para leluhur, mereka adalah penulis bab baru peradaban.
Peradaban yang dibangun atas dasar dharma, yang berjalan seiring dengan alam, dan yang menjadikan spiritualitas sebagai suluh jalan.
Apakah kita siap menjadi cahaya kecil yang menyalakan obor perubahan?
Atau justru kita memilih menjadi bayangan yang ikut larut dalam gelapnya zaman?
Menyalakan Dharma, Menjaga Bhuwana
Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita—generasi muda—dihadapkan pada pilihan: menjadi saksi bisu dari keruntuhan peradaban, atau menjadi cahaya kecil yang menyalakan kembali api dharma.
Pilihan ini bukan perkara besar atau kecilnya peran, tetapi tentang kesadaran untuk bertindak, sekecil apa pun langkah itu.
Sebagaimana diajarkan dalam Bhagavad Gītā:
“Svadharme nidhanam śreyah, paradharmo bhayāvahah”
(Lebih mulia mati dalam dharmamu sendiri, daripada hidup dengan dharma orang lain.)
Kini saatnya kita kembali ke dharma kita sendiri: menjaga bumi, memuliakan keberagaman, dan menyatukan langkah lintas iman, lintas generasi, dan lintas batas identitas demi masa depan yang berkeadilan dan berkeberlanjutan.
Mari kita menjadi penjaga warisan, perawat harmoni, dan penentu arah baru peradaban.
Karena menjaga bumi bukan sekadar tugas ekologis, tetapi tindakan spiritual paling mulia dalam zaman ini.
Jagadhita bukan hanya cita-cita, Tapi tugas kita bersama.
Dan sekaranglah waktunya untuk menjawab panggilan zaman itu, dengan terang di hati dan keberanian melangkah.

Merawat Kendeng, Menyelamatkan Semesta: Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius dalam Spirit Laudato Si’
Oleh: Adnan Iman Nurtjahjo Amir, S.M., C.EML. FKUB Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta
Pegunungan Kendeng Utara di Jawa Tengah telah menjadi simbol perjuangan rakyat kecil melawan eksploitasi sumber daya alam yang tak berkeadilan. Di tengah gemuruh kepentingan ekonomi yang kerap abai pada kelestarian lingkungan, muncul satu tawaran jalan baru: model kepemimpinan ekoteologis interreligius seperti yang diajarkan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’. Model ini menggabungkan iman, kepedulian ekologis, dan keterbukaan antariman demi masa depan bumi yang lestari dan adil bagi semua.
Laudato Si’, yang diterbitkan tahun 2015, bukan sekadar dokumen gerejawi, Dalam konteks Pegunungan Kendeng, jeritan itu nyata: suara para petani yang menggantungkan hidup pada tanah dan air yang kini terancam tambang, serta rusaknya lanskap ekologis yang berdampak pada generasi mendatang. Kepemimpinan yang lahir dari semangat Laudato Si’ tidak hanya berbicara soal iman, tetapi tentang keberanian membela kehidupan.
Ensiklik Laudato Si’, yang berarti “Terpujilah Engkau”, bukan hanya seruan iman Katolik, tapi juga dokumen lingkungan hidup yang menembus batas agama. Dalam surat tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan bumi sebagai “rumah kita bersama” yang terluka karena keserakahan manusia. Ia mengajak seluruh umat manusia, bukan hanya umat Katolik, untuk mendengar “jeritan bumi dan jeritan kaum miskin”—dua hal yang nyata di Pegunungan Kendeng. Kepemimpinan yang tumbuh dari semangat ini tidak sekadar birokratis atau politis, tetapi berbasis kasih, kesadaran ekologis, dan keterlibatan lintas iman.
Model kepemimpinan ekoteologis mengedepankan relasi yang harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ia tidak mengenal sekat agama. Justru dalam keberagaman keyakinan, umat beriman dapat bersatu dalam kepedulian ekologis yang sama. Inilah kekuatan dari pendekatan interreligius.
Manusia Bukan Penguasa
Dalam pandangan ini, manusia bukan penguasa, tetapi penjaga ciptaan. Tokoh-tokoh lintas agama yang terlibat dalam perjuangan Kendeng membawa serta nilai-nilai spiritual mereka, menyatukan semangat Islam, Kristen, Katolik, dan kearifan lokal untuk satu tujuan: melindungi bumi. Mereka tidak hanya berorasi, tetapi berjalan bersama masyarakat, menanam pohon, menggelar doa bersama, dan menjadi penuntun moral di tengah krisis ekologis demi menyatukan suara, dan memimpin komunitas dalam gerakan menjaga bumi.
Interreligiusitas menjadi kekuatan utama dalam gerakan ini. Ketika masyarakat kerap dibelah oleh identitas agama, perjuangan menyelamatkan Kendeng justru mempersatukan. Doa lintas iman digelar di ladang, di tepi sungai, dan di halaman rumah. Para kiai bersanding dengan pastor dan pemuka agama lokal, menyuarakan nilai-nilai universal: kesederhanaan, tanggung jawab, dan penghormatan pada kehidupan. Dalam kesatuan itu, tumbuh solidaritas ekologis yang lebih kuat daripada perbedaan teologis.
Menjaga Bumi Adalah Bentuk Ibadah
Ketika korporasi dan elite kekuasaan kerap mengaburkan nilai moral demi keuntungan jangka pendek, model ini justru mengembalikan kepemimpinan kepada pangkuan nurani. Tokoh-tokoh lokal yang membimbing masyarakat bukan hanya berbicara soal data dan kajian lingkungan, tetapi juga menyentuh sisi spiritual perjuangan. Mereka mengajarkan bahwa menjaga bumi adalah bentuk ibadah, dan tanah bukanlah komoditas semata, melainkan ibu yang memberi kehidupan.
Pegunungan Kendeng menyimpan cadangan air yang vital dan tanah yang subur. Kehadirannya bukan hanya penting untuk warga lokal, tetapi juga untuk ketahanan pangan nasional. Dalam semangat Laudato Si’, perjuangan melindungi Kendeng bukan soal “menolak pembangunan,” melainkan memperjuangkan pembangunan yang manusiawi, berkelanjutan, dan menyeluruh. Pembangunan yang tidak mengorbankan segelintir demi kepentingan segelintir.
Di balik cadas kapurnya, mengalir mata air yang menjadi sumber hidup ribuan keluarga. Jika eksploitasi tambang terus berlanjut, bukan hanya ekosistem yang terancam, tetapi juga ketahanan pangan dan keberlanjutan kehidupan warga. Dalam semangat Laudato Si’, melindungi Kendeng adalah tindakan adil bagi bumi dan manusia, terutama mereka yang selama ini tersingkir dari percakapan pembangunan.
Kepemimpinan ekoteologis tidak hadir di ruang-ruang kekuasaan, melainkan tumbuh dari akar rumput. Ibu-ibu petani, pemuda desa, tokoh adat, dan rohaniwan lokal menjadi pelaku utama perubahan. Mereka menyampaikan suara moral, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian spiritual. Di sana, kita belajar bahwa perjuangan merawat bumi bukan semata urusan teknis, tetapi juga tindakan iman dan cinta kasih terhadap ciptaan. Dengan pendekatan spiritual dan kultural, masyarakat tidak merasa sendirian. Mereka menemukan harapan dalam kebersamaan, kekuatan dalam doa lintas agama, dan makna dalam perjuangan yang melampaui batas-batas politik dan ekonomi. Ini bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi tentang membangun narasi hidup yang utuh dan berdaya.
Kendeng Medan Pembelajaran Moral dan Spiritual
Gerakan ini memberikan pelajaran penting bahwa perubahan tidak harus datang dari pusat kekuasaan. Ia bisa tumbuh dari akar rumput, dari komunitas yang terhubung dengan tanah dan langit. Dalam semangat interreligius, Pegunungan Kendeng menjadi medan pembelajaran moral dan spiritual, bukan hanya medan konflik. Di sana, kita melihat bahwa iman yang hidup harus bersuara bagi bumi yang menderita.
Dalam setiap aksi dan doa, terkandung narasi perlawanan terhadap sistem yang menjadikan alam hanya sebagai objek eksploitasi. Model kepemimpinan ini mendorong transformasi struktural: mendorong negara dan korporasi untuk bertanggung jawab, menuntut keadilan ekologis, dan menawarkan alternatif pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah kegersangan arah kebijakan, suara-suara Kendeng menjadi oase nilai.
Melalui kepemimpinan ekoteologis interreligius, Pegunungan Kendeng menjadi contoh bagaimana keberagaman iman dapat menjadi kekuatan penyembuh bumi. Semangat ini menginspirasi banyak pihak, dari akademisi hingga aktivis, dari pelajar hingga rohaniwan, untuk membayangkan masa depan yang lebih adil, di mana kesejahteraan tidak dibeli dengan kerusakan, dan kemajuan tidak menyingkirkan kearifan lokal.
Absennya Pengakuan Negara
Spirit Laudato Si’ juga mengajarkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. Penderitaan petani Kendeng bukan hanya akibat tambang, tapi juga karena absennya pengakuan negara terhadap hak-hak mereka. Maka, kepemimpinan ekoteologis menjadi jembatan antara spiritualitas dan advokasi. Ia tidak hanya mengutuk kerusakan, tetapi menawarkan visi baru dunia yang hidup berdampingan secara adil.
Lebih dari sekadar aksi penyelamatan, perjuangan Kendeng menjadi ruang pendidikan masyarakat. Anak-anak belajar mencintai tanah air bukan dari buku teks, tapi dari cerita dan pengalaman orang tua mereka yang berani melawan ketidakadilan demi bumi. Generasi muda diajak untuk tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga bijak secara ekologis. Mereka tumbuh dengan kesadaran bahwa kehidupan yang baik bukanlah yang mewah, tapi yang selaras dengan alam.
Model ini juga menantang cara kita memandang pembangunan. Apakah pembangunan selalu identik dengan pabrik, beton, dan penggalian tanah? Atau mungkinkah pembangunan adalah ketika masyarakat punya akses air bersih, tanah subur, dan udara segar? Dalam kerangka ekoteologis, pembangunan tidak boleh bertentangan dengan kelestarian. Ia harus memulihkan, bukan merusak; memberdayakan, bukan menyingkirkan.
Perlunya Pertobatan Ekologis
Di saat banyak pemimpin dunia gamang menghadapi bencana ekologis, para penjaga Kendeng justru menunjukkan jalan keluar melalui kesederhanaan, solidaritas, dan spiritualitas. Mereka menjadi saksi hidup dari apa yang dimaksud Paus Fransiskus: bahwa pertobatan ekologis dimulai dari hati dan tindakan nyata di komunitas. Dari Kendeng, kita belajar bahwa mempertahankan bumi bukan sekadar perjuangan fisik, tetapi juga perjuangan nilai. Kepemimpinan ekoteologis interreligius menjadi wajah baru kepemimpinan yang dibutuhkan zaman: membumi, melibatkan iman, dan berpihak pada kehidupan. Ia menghidupkan harapan bahwa masa depan bisa dibentuk melalui cinta, bukan kerakusan.
Jika bumi adalah rumah bersama, maka Kendeng adalah ruang tamu yang perlu dijaga bersama. Dalam doa lintas iman, dalam peluh petani, dan dalam semangat Laudato Si’, kita menemukan alasan untuk terus merawat bumi. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita bertanggung jawab. Untuk anak cucu, untuk keadilan, untuk semesta.

Membaca Ulang Local Wisdom Nusantara (Bhisama : Titah Ekoteologi Nusantara dan Kearifan Lokal yang Terlupakan)
Oleh : I Putu Dicky Merta Pratama, S.H., M.H. (PRADITAMA - Prakarsa Dharma Insan Pratama Nuswantara)
Di tengah dunia yang terus bergerak maju dengan jargon “pembangunan berkelanjutan” dan “transisi hijau”, kita justru dihadapkan pada sebuah ironi: kita sering kali lupa bahwa warisan kearifan ekologis sudah tertanam lama dalam tubuh kebudayaan Nusantara. Local wisdom atau kearifan lokal, yang kini kerap direduksi menjadi simbol budaya atau objek pariwisata, sesungguhnya merupakan fondasi filosofis dan praksis yang mengandung nilai ekoteologis mendalam.
Dalam khazanah peradaban Nusantara, hubungan antara manusia dan alam bukan sekadar relasi fungsional, melainkan relasi spiritual yang berakar dalam pandangan hidup kosmologis. Di berbagai pelosok Nusantara, dari Bali hingga Kalimantan, dari Maluku hingga Nusa Tenggara, kita menemukan satu benang merah: bahwa alam adalah bagian dari kehidupan yang suci, tak terpisahkan dari manusia maupun Sang Pencipta. Di sinilah konsep ekoteologi lokal tumbuh dan mengakar jauh sebelum istilah “sustainable development” dikenal dunia modern.
Salah satu warisan agung yang merekam etika ekoteologi lokal ini adalah Bhisama, titah sakral atau wejangan luhur para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dalam tradisi masyarakat Bali sebagai pedoman hidup. Di Bali, Bhisama bukan sekadar amanat, tapi sangkan paraning dharma—arah suci yang harus dijaga.
Sebut saja Bhisama Batur Kalawasan, dalam teks lontarnya yang menegaskan:
“Ingat pesanku kepada masyarakat sekalian : Di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan pantai/laut, Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat membersihkan diri,Di daratan kita bekerja untuk hidup, jangan hidup nyaman dari merusak alam. Jika melanggar, kamu akan terkena kutuk :Tidak menemukan keselamatan, Kekurangan sandang dan pangan, Menderita penyakit dan mengalami pertengkaran sosial.”
Pesan Bhisama ini bukan sekadar petuah moral, ini juga bukan sekadar larangan atau ancaman, tetapi ini adalah peringatan kosmologis sekaligus konstitusi ekologis spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Tegas, mendalam dan terasa sangat relevan dengan situasi hari ini. Ia mewakili pandangan dunia di mana alam bukan sekadar sumber daya, tetapi entitas sakral yang memiliki nilai intrinsik dan spiritual, bahwa jika manusia melupakan yadnya terhadap alam, maka kehancuran tidak hanya terjadi di luar—tetapi juga dalam kehidupan rohani dan sosialnya, sebagaimana ekoteologi lokal merupakan pandangan bahwa keseimbangan ekologis adalah tanggung jawab spiritual manusia. Kearifan tersebut lahir dari pengalaman panjang hidup berdampingan dengan alam dan disahkan oleh sistem nilai komunitas.
Mengapa Terlupakan?
Hari ini, Bhisama dan berbagai kearifan lokal itu justru semakin dijauhkan dari pusat pengambilan kebijakan. Ia dianggap terlalu lokal, terlalu tradisional, bahkan tidak relevan. Padahal, justru karena sifatnya lokal dan kontekstual, ia mampu menjawab tantangan ekologis secara tepat sasaran.
Terlupakannya kearifan ini juga mencerminkan krisis epistemik dalam pembangunan: kita terlalu terobsesi pada narasi barat-modern, dan lupa bahwa Nusantara memiliki kosmologi sendiri—yakni kosmologi dharma, di mana kehidupan harus berjalan dalam orbit harmoni.
Menghidupkan Kembali Titah Leluhur sebagai Pedoman Masa Depan
Dalam perjalanannya, Nusantara tidak pernah kekurangan sumber hikmah. Ajaran-ajaran luhur yang diwariskan para leluhur, dari Bhisama Bali hingga Tri Hita Karana, sesungguhnya telah memetakan jalan pembangunan yang selaras dengan hukum alam, spiritualitas, dan keadilan sosial. Warisan ini bukan sekadar memori budaya, tetapi pedoman praksis untuk menavigasi tantangan zaman modern.
Kini, di tengah krisis ekologis global dan erosi nilai spiritual akibat modernitas yang serba materialistik, Nusantara memiliki tanggung jawab ganda: pertama, menjaga warisan ekoteologis sebagai identitas diri; kedua, mengaktualisasikannya sebagai kontribusi etik global dalam upaya membangun peradaban yang lebih beradab terhadap alam dan sesama manusia.
Kepemimpinan ekoteologis Nusantara sejatinya adalah panggilan dharma bukan sekadar mengelola, tetapi menuntun arah peradaban. Ini adalah kepemimpinan yang berakar pada kesadaran kosmis bahwa kesejahteraan manusia tidak pernah terpisah dari keselamatan bumi dan keharmonisan spiritual. Sebagaimana roda dharma berputar menjaga keseimbangan semesta.
Membaca ulang Bhisama dan local wisdom Nusantara bukan sekadar romantisme terhadap masa lalu. Ini adalah tindakan restoratif dan strategis untuk masa depan. Dengan menghidupkan kembali peran Bhisama dan kearifan lokal lainnya:
- Kita membangun pembangunan yang berakar, bukan yang melayang.
- Kita menguatkan hukum adat dan spiritualitas lokal sebagai bagian dari sistem perlindungan lingkungan.
- Kita meneguhkan kembali bahwa pembangunan harus berbasis etika keberlanjutan dan dharma(Kebajikan), bukan hanya data dan target ekonomi.
Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan UU Lingkungan Hidup, negara seharusnya menjadikan kearifan lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan ekologis. Dan dalam Agenda SDGs, prinsip “Leave no one behind” juga berarti tidak meninggalkan kearifan masyarakat adat di belakang.
Akhirnya, masa depan Nusantara bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang keberanian meneguhkan kembali siapa kita sejatinya: anak-anak Ibu Pertiwi yang diamanahkan menjaga keseimbangan bumi, bukan sekadar penghuninya. Di sinilah letak sumbangsih terbesar ekoteologi Nusantara bagi dunia: membangun peradaban yang tidak tercerabut dari akar spiritualnya, namun tetap relevan menjawab tantangan zaman, inilah saatnya Nusantara kembali bersuara, bukan dalam jargon politik, melainkan melalui kearifan ekoteologis lintas iman yang diwariskan para leluhur.
Kembali ke Akar, Menatap Masa Depan
Di tengah dunia yang kelelahan karena eksploitasi dan ketimpangan ekologis, Nusantara sebenarnya memiliki warisan etis dan spiritual yang bisa menjadi kontribusi global: ekoteologi lokal berbasis local wisdom.
Membaca ulang Bhisama adalah menghidupkan kembali suara bumi, suara leluhur, dan suara masa depan. Karena sesungguhnya, masa depan yang berkelanjutan tidak bisa dibangun tanpa fondasi kearifan yang mengakar.
Kini saatnya kita menyadari bahwa dalam dunia yang kehilangan arah, Nusantara memiliki petunjuknya sendiri.
Di tengah krisis lingkungan global hari ini, dunia butuh model baru. Nusantara memiliki warisan besar yang dapat menjadi kontribusi etik global: ekoteologi lintas iman berbasis warisan lokal. Kini, tantangan terbesar kita sebagai generasi hari ini adalah:
- Mau dan mampukah kita membaca ulang warisan leluhur sebagai pedoman hidup, bukan sekadar pusaka/cagar warisan budaya?
Bhisama (Local Wisdom) bukan sekadar teks tua. Ia adalah suara yang menunggu untuk kita dengar kembali. Dan mungkin, justru dari suara lama itulah kita bisa menemukan arah masa depan. Local Wisdom/warisan leluhur bukan hanya kebudayaan yang layak dilestarikan, tetapi model masa depan yang menginspirasi dunia.
Kini saatnya kita membangun kembali visi pembangunan Nusantara yang sejati yang tidak melulu berorientasi pada eksploitasi sumber daya, tetapi berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial. Ekoteologi Nusantara bukanlah masa lalu yang usang, melainkan masa depan yang mesti kita rawat dan aktualisasikan bersama.

Peran Serta Pemuka Agama Dalam Pelestarian Alam
Oleh: Maudy Sandra S. S. (Nasionalis Cyber Indonesia (NCI)
Sungguh suatu peran yang sangat penting, para pemuka agama dalam menyampaikan betapa krusial upaya pelestarian sumber daya alam, yang harus disampaikan melalui mimbar khotbah.
Belakangan ini, banyak kita ketahui dari berita mainstream dan media sosial, betapa banyak luka mendalam, di berbagai daerah yang memiliki kawasan pertambangan.
Kebijakan yang dibuat dalam sekejap mata demi memberikan keleluasaan kepada segelintir orang dan pejabat negara.
Mengorbankan masyarakat luas yang bertanya-tanya, akankah kemakmuran hidup mereka membaik, dengan ditambangnya sekian banyak sumber daya di daerah mereka?
Ternyata tidak. Semua hanya angan-angan yang nampak di fatamorgana. Sepertinya ada, namun tiada. Menyedihkan memang.
Tapi itulah realitas yang harus kita hadapi sebagai warna negara biasa tanpa kekuasaan apapun.
Disinilah peran pemuka agama sangat dibutuhkan, untuk memberi kesadaran penuh dan membuka mata para pemangku kepentingan di negeri ini, bahwa masih banyak yang harus dibenahi, bukan hanya diri sendiri, namun harkat hidup orang banyak dan keseimbangan alam yang perlu dijaga.
Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan untuk menjaga sumber daya alam sebaik mungkin agar lestari dan dapat tetap dinikmati anak cucu kita.
Semoga, para pemuka agama kita dapat secara penuh memberi kesadaran kepada kita semua, terutama kepada para pemangku kepentingan di negeri ini, untuk selalu menjaga keseimbangan alam dengan baik dan menyeluruh.

Dunia Butuh Aksi, Bukan Sekedar Janji: Menanggapi Ajaran Ensiklik Laudato Si dalam Perspektif Interreligius
Oleh: Nuraeni M.Pd (Guru SMA Negeri 1 Sumber
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama di kesempatan yang berbahagia ini dalam kegiatan Sekolah Lintas Iman dengan suasana penuh kebersamaan dan kedamaian.
Peduli terhadap lingkungan tidak cukup hanya diungkapkan melalui perkataan. Tindakan nyata sangat dibutuhkan. Dan tindakan itu harus digerakkan oleh siapa? Oleh para pemimpin yang peduli dan mampu memotivasi. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan petunjuk, tetapi juga menjadi teladan. Ia mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi bumi seperti menanam pohon, mengelola limbah, hingga menjaga kebersihan lingkungan. Namun, perubahan tidak dapat terjadi tanpa usaha bersama. Masyarakat juga harus menyadari dan bergerak secara kolektif. Ketika pemimpin dan rakyat bersatu, lingkungan akan lebih terjaga. Jangan menunggu kerusakan terjadi baru peduli. Saatnya untuk bertindak, mulai dari sekarang.
Aksi Nyata tersebut ada disuatu Komunitas Pegunungan Kendeng Utara dengan menghadirkan para tokoh interreligious khususnya Islam dan Katolik dalam kegiatan Sekolah Lintas Iman (SLI) certification in Interfaith Communication and Dialogue (C.ICD) sesi III – Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius dalam Pembangunan SDGs pada hari Sabtu, 21 Juni 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK) dengan narasumber Romo Dr. Aloys Budi Purnomo Pr, M.Hum., Lic.Th. Penggerak mereka biasanya dikenal dengan komunitas Sedulur Sikep. Istilah ini diambil dari bahasa Jawa. Secara bahasa kalau kita artikan terpisah Sedulur yang artinya Saudara dan Sikep artinya memegang teguh. Jadi dapat diartikan saudara-saudara yang memegang teguh keyakinan dan prinsip.
Sedulur Sikep merupakan kelompok adat yang menganut ajaran Saminisme yang disampaikan oleh Samin Surosentiko, seorang pemimpin perjuangan melawan kolonialisasi Belanda pada akhir abad ke-19. Komunitas ini menetap di daerah Jawa Tengah, termasuk Blora, Pati, dan Grobogan. Komunitas mereka telah bersatu. Bukan untuk tujuan politik atau kekuasaan, melainkan demi satu tujuan yang lebih penting yaitu melindungi bumi. Mereka mengungkapkan kritik kepada pemerintah serta orang-orang serakah yang merusak lingkungan tanpa rasa malu. Mereka merasa marah, kecewa, dan jemu menyaksikan kerakusan, keserakahan, serta egoisme yang disamarkan dengan indah dalam nama pembangunan dan kepentingan pribadi. Sungguh mengherankan bagaimana kekuasaan sering kali dibentuk di atas reruntuhan kerusakan alam.
Kita sedang berada di zaman di mana hutan ditebang untuk proyek pertambangan dan industri, sungai-sungai terkontaminasi oleh limbah, udara semakin tercemar, dan tanah kehilangan kesuburan. Semua itu dilakukan atas nama sebuah “kemajuan”. Namun, kemajuan jenis apa yang bersedia mengorbankan masa depan generasi mendatang kita?
Ironisnya, bisikan suara-suara yang menolak kerusakan ini sering kali dianggap sebagai gangguan. Aktivis lingkungan dianggap ekstrem, masyarakat setempat diabaikan, dan pengetahuan tradisional dipandang ketinggalan zaman. Namun, mereka tetap tidak putus asa. Mereka terus berdiri, menyatakan kebenaran, dan menyatukan kekuatan dari berbagai usia dan latar belakang untuk satu tujuan adalah melestarikan bumi. Ini bukan hanya masalah lokal ini adalah krisis yang berskala global. Apabila kita tetap diam dan hanya menjadi pengamat yang acuh tak acuh, maka kita pun berkontribusi pada proses kehancuran tersebut. Saatnya kita menghentikan pandangan terhadap alam sebagai benda yang dapat dieksploitasi, dan mulai memperlakukannya sebagai tempat tinggal yang perlu kita jaga bersama.
Kita tidak dapat terus menerus menimpakan kesalahan kepada pemerintah, sektor industri, atau pihak lainnya. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri dari sikap kita dalam membuang sampah, memilih produk yang kita gunakan, hingga keberanian untuk berbicara saat menyaksikan ketidakadilan lingkungan yang terjadi di sekeliling kita. Alam telah memberikan banyak hal, tanpa pernah mengharapkan imbalan. Namun sekarang, ia berteriak. Apakah kita masih memilih untuk tetap tenang?
Aksi nyata ini juga dilakukan dalam bidang pendidikan, terutama pada ekstrakurikuler Pramuka dan berbagai kegiatan di dalam sekolah yang bertujuan menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam semesta bagi para peserta didik. Melalui kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga kampanye hemat energi, siswa tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga dilatih untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan lingkungan di sekolah menjadi pondasi penting agar generasi muda di era sekarang untuk tumbuh dengan kesadaran bahwa bumi bukanlah warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Dalam kegiatan Pramuka, misalnya, nilai-nilai cinta alam dan kepedulian sosial ditanamkan sejak usia dini. Anggota diundang untuk mengenali kondisi lingkungan, memahami ekosistem, dan secara aktif pindah ke upaya konservasi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu akademis, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup. Jika lembaga pendidikan berani memainkan peran dalam pelestarian alami, kami sedang mempersiapkan generasi mendatang yang tidak hanya cerdas secara cerdas, tetapi juga bertanggung jawab secara lingkungan. Saya tidak sabar lagi. Pendidikan harus berada di garis depan saat menyelamatkan planet ini. Karena ketika anak-anak kita belajar mencintai alam, mereka belajar mencintai hidup mereka sendiri.
Lalu bagaimana model kepemimpinan ekoteologis sesuai Ensiklik Laudato Si dalam perspektif interreligious terutama dalam agama Katolik? Berdasarkan sumber yang saya ikutin dalam Webinar dan referensi Disertasi yang berjudul “Model Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius Sesuai Ensiklik Laudato Si’ dalam Konteks Komunitas Pegunungan Kendeng Utara” yang ditulis oleh Romo Dr Aloys Budi Purnomo.
Berdasarkan ajaran Paus Fransiskus mengutip tokoh Ortodoks mengakui bahwa semua agama memiliki nilai-nilai yang mendukung pelestarian lingkungan. Dalam Islam, ada konsep khalifah dan amar ma’ruf nahi mungkar yang bisa diterapkan untuk membela keadilan ekologis. Dalam Hindu, bumi adalah ibu pertiwi yang suci. Dalam Buddha, kehidupan selaras dengan alam adalah bentuk pembebasan dari penderitaan. Perspektif ajaran Gereja Katolik, kepemimpinan yang sejati terhadap lingkungan bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga tindakan spiritual dan moral yang mendalam. Di instansi sekolah Katolik, misalnya, nilai-nilai Laudato Si’ dapat ditanamkan melalui kegiatan ekologi lintas iman seperti gerakan bebas plastik, kebun sekolah bersama, dan proyek pemulihan lingkungan di sekitar komunitas. Semua nilai ini dapat menjadi titik temu untuk kerja sama lintas agama terhadap penderitaan bumi.
Merekalah menjadi aksi nyata pemimpin lingkungan yang bekerja di ruang kelas, aula pemerintahan, dan diberbagai bisnis di seluruh dunia. Seseorang pemimpin ekoteologis tidak hanya memikirkan hari ini, namun juga menghidupi tanggung jawab antargenerasi. Sekarang ini, ketika ketidakpastian perubahan iklim dan dampaknya menyelimuti alam semesta, suara dan tindakan mereka menjadi cahaya harapan di tengah kabut. Mereka mendorong transformasi spiritual dan sosial, membangkitkan kesadaran bahwa bumi bukan sekadar sumber daya, melainkan rumah bersama yang suci. Keberanian dan kasih yang berakar pada iman, mereka membangun jembatan antara keadilan ekologis dan nilai-nilai luhur kemanusiaan, mengajak kita semua untuk hidup selaras dengan ciptaan.
Membayangkan sebuah masa depan para tokoh agama, komunitas dan yang lainnya apabila mereka bersatu menyuarakan keadilan ekologis dengan aksi nyatanya melindungi alam semesta, sepertinya akan seru serta kekayaan Indonesia akan tetap terjaga untuk generasi selanjutnya. Bumi tidak lagi menjerit dan meluapkan emosinya karena ulah manusia. Mari kita lakukan langkah sekecil apapun secara konsisten dan terbuka terhadap kolaborasi bisa menjadi jalan bagi pertobatan ekologis. Dan semoga kita, bersama saudara-saudari lintas agama, bisa berjalan bersama menuju bumi yang lebih sehat, adil, dan penuh damai. Jadi, slogan kita adalah Bumi tidak butuh lebih banyak janji, bumi butuh aksi nyata. Ajaran ini mengajak kita untuk melihat kembali bumi bukan sebagai objek eksploitasi sebagai karunia Tuhan yang dipercayakan kepada manusia. Namun saya sendiri menurut kacamata Islam menganalisa isu-isu wahabi lingkungan ala Gus Ulil semakin membingungkan “bagaimana kita sebagai manusia agar bijak terhadap alam semesta? Apakah bersikap bijak terhadap alam berarti hidup dengan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab kepada Tuhan, sesama, dan seluruh ciptaan. Disisi lain semua kitab suci melarang untuk membuat kerusakan alam semesta, disisi lain juga dalam pandangan yang sudah canggih teknologi, meningkatnya penduduk kelahiran butuh untuk tempat tinggal setiap harinya itu hasil dari Sumber Daya Alam juga seperti batu, semen, pasir dan lain-lain.

Harmonisasi Alam sebagai Ibu Bumi (Mother Earth)
Oleh: Maudy Sandra S. S. (Nasionalis Cyber Indonesia (NCI)
Berkaca dari kondisi menyedihkan bagaimana pemerintah kita memperlakukan sumber daya alam nya, sangat disayangkan tidak adanya kehati-hatian dan perhatian mendalam terhadap kelestarian alam sekitar.
Sepatutnya teladan yang diberikan filosofi agama Hindu bisa diteladani dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata, bagaimana umat Hindu selalu berusaha menjaga keseimbangan manusia dan alam dengan baik, memberi ruang bernafas dan berbuah secara cukup, tanpa lupa “mengembalikan” kepada alam semesta dan Tuhan dalam bentuk persembahan sesajen dan buah-buahan sebagai perwujudan rasa terima kasih yang nyata dan mendalam.
Tidak hanya mengambil dan mengeruk, tapi juga ingat untuk memberi kepada Ibu Bumi (Mother Earth) yang kita pijak dan tinggali.
Penambangan secara masif dan sembarangan diberbagai daerah di Indonesia adalah contoh memprihatinkan yang sangat tidak layak untuk dipraktekkan, namun selalu dilakukan secara berulang, bahkan dengan kasar dan tidak bertenggang rasa dengan flora dan fauna sekitar.
Mempermainkan alam dengan licik dan rakus, mengambil tanpa mau memberi, dan merampas hak-hak warga sekitar lokasi penambangan.
Didalam agama Hindu, ada yang namanya hukum karma. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen.
Tidak ada yang dapat membebaskan kita dari lingkaran karma perbuatan kita, kecuali diri kita sendiri, dengan cara menjaga keseimbangan alam dan selalu melakukan kebaikan baik terhadap orang lain, maupun alam semesta.
Sangat berharap pemerintah berkenan koreksi diri dan mengubah kebijakan penambangan sumber daya alam yang sangat masif digalakkan belakangan ini, dengan lebih memperhatikan keselarasan alam berikut floda dan fauna, serta masyarakat sekitar.
Harmonisasi yang Indah, akan membawa keselamatan dan kebahagiaan untuk semua pihak, terutama untuk alam semesta, sebagai ibu yang melahirkan kita.

TRI HITA KARANA, MENDORONG HIDUP DALAM KEHARMONISAN
Oleh: Trimanto B. Ngaderi, S.I.Kom (Yayasan Hidayatul Muchsinin Alfatih ).
Akhir-akhir ini bencana alam sering sekali terjadi. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hama tikus yang menyerang tanaman padi, perubahan iklim, hingga meningkatnya pemanasan global. Alam seolah-olah begitu murka dengan nafsu serakah manusia. Bencana alam seakan memberikan “alarm” bahwa perilaku manusia telah jauh melampaui batas.
Betapa tidak. Manusia begitu rakus mengeksploitasi alam. Mulai dari penebangan pohon, penggundulan hutan, kegiatan pertambangan, perburuan satwa liar, alih fungsi lahan, dan sebagainya. Mereka tidak sekedar mengambil dari alam sesuai yang dibutuhkannya. Namun, mereka mengambil sebanyak mungkin demi memupuk pundi-pundi kekayaan.
Mereka tak peduli lagi terhadap dampak negatif akibat ulah keserakahan mereka. Mereka sengaja menutup mata atas kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, musnahnya satwa langka, dan hancurnya tatanan ekosistem. Paham kapitalisme yang mereka usung hanya berorientasi kepada akumulasi modal. Mereka rela mengorbankan orang banyak demi kekayaan bagi segelintir orang.
Parahnya lagi, mereka memisahkan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan.
Tri Hita Karana
Setiap agama dan kepercayaan memiliki konsep yang mengatur hubungan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Demikian halnya dengan agama Hindu, ada yang disebut dengan “Tri Hita Karana”, yaitu konsep hidup yang tangguh. Hidup yang tangguh (sejahtera) akan tercapai apabila terjadi hubungan yang harmonis antara Tuhan (pharayangan), manusia (pawongan), dan alam semesta (palemahan). Ini merupakan yadnya bagi setiap orang agar tercapai pelestarian dan keberlangsungan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Dr. Ni Nyoman Rahmawati, S.Ag., M.Si pada Sesi II Sekolah Lintas Iman (SLI) Certification in Interfaith Communication and Dialogue (C.ICD) – Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius dalam Pembangunan SDGs yang diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK).
Beliau juga menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, umat Hindu mempraktikkan ritual-ritual yang bertujuan membangun keselarasan dengan alam, di antaranya:
- Kain Poleng, kain berwarna hitam-putih yang disematkan di pohon-pohon sebagai simbol magis, kekuatan, dan pelestarian alam;
- Tawur Kesanga dalam upacara Bhuta Yadnya, bertujuan untuk menyucikan alam semesta, menjaga keseimbangan alam, dan menciptakan harmoni antara manusia dan lingkungan;
- Tumpek Wariga adalah hari di mana umat Hindu memberikan penghormatan kepada Desa Sangkara sebagai Dewa Tumbuh-Tumbuhan;
- Subak, sistem kuno di Bali yang menyatukan harmoni antara alam, komunitas, dan spiritualitas;
- Tumpek Kandang, pemujaan kepada Dewa Rare Anggon agar para hewan diberkati dengan kesehatan dan keselamatan.
Demikian halnya dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, Nyepi hadir sebagai momen istimewa untuk refleksi diri dan menjaga keseimbangan alam. Ia tidak hanya memiliki makna spiritual yang mendalam, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan kualitas udara, penghematan energi dan air, serta mendorong kesadarandan kepedulian terhadap lingkungan.
Ditambahkan pula bahwa dalam Suku Dayak Salako, terdapat ritual adat Ngabayotn. Bertujuan untuk menyampaikan rasa syukur, terutama atas hasil panen padi di kalangan masyarakat Dayak. Ada pula Mamapas Lewu yang dijalankan masyarakat Dayak pemeluk agama Kaharingan sebagai sarana membersihkan wilayah dari berbagai sengketa, marabahaya, sial, dan wabah penyakit. Ada lagi Manyanggar, sebuah upacara adat suku Dayak di Kalimantan Tengah untuk membuka lahan baru.
Membangun Sebuah Kesadaran
Konsep Tri Hita Karana selain membentuk hidup yang tangguh (sejahtera), juga membangun sebuah kesadaran (awarness), baik kesadaran personal maupun kesadaran kolektif untuk senantiasa menyatu dengan alam dan Tuhan. Satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
Kesadaran inilah yang akan menjadi ruh setiap pemeluk agama Hindu dalam menjalani kehidupan di jagad raya ini. Kesadaran akan mewujud dalam bentuk sikap dan perbuatan dalam memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. Mereka dituntun untuk menempuh dharma (jalan kebenaran) untuk menuju jagathita (kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan). Itulah intisari dari apa yang disebut sebagai “Moksartam Jagathita Ya Ca Iti Dharma”, yang merupakan tujuan tertinggi dalam agama Hindu.
*) Peserta Sekolah Lintas Iman (SLI)

MIZAN: PERAN PENTING MENJAGA KESEIMBANGAN
Oleh: Nuraeni, S.Pd., M.Pd. (Guru SMA NEGERI 1 SUMBER ).
Istilah mizan sebenarnya dari agama Islam yang berarti keseimbangan mencakup berbagai aspek kehidupan dimulai dari beribadah, berperilaku, dan berinteraksi dengan alam. Alam sekarang kondisinya tidak menentu seperti ibarat seorang ibu pertiwi yang sedang marah akibat keluarganya. Alampun sama, mereka dirusak, digunduli dan lain-lain akibat keserakahan manusia yang tidak pernah kenyang mengekploitasi kekayaan alam.
Alam pun menangis dan menjerit kesakitan sehingga mereka memberi sinyal emosi dari mulai banjir akibat membuang sampah sembarangan, tanah longsor, kebakaran hutan, hama tikus yang menyerang padi, saling berubah-rubah iklimnya, pencemaran laut dan udara, musnahnya satwa langka sampai meningkatnya pemanasan global. Oleh karena itu, mari kita semua sebagai manusia menjaga keseimbangan dari aspek kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari kita agar kelak nanti cucu-cucu kita bisa menikmati keindahan alam semesta. Kalau bukan dari kita sebagai manusia dewasa yang memiliki ilmu, pengetahuan dan agama. Siapa lagi! Mari kita lawan yang ingin merusak lingkungan.
Agama Hindu menekankan pentingnya keadilan lingkungan dan memastikan bahwa tindakan manusia tidak merusak alam semesta. Seperti yang disampaikan oleh narasumber Dr. Ni Nyoman Rahmati, S.Ag., M.Si pada sesi II Sekolah Lintas Iman (SLI) certification in Interfaith Communication and Dialogue (C.ICD)-Kepemimpinan Ekoteologis Interreligius dalam Pembangunan SDGs pada hari Sabtu, 14 Juni 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK). Beliau juga menyampaikan untuk menciptakan stabilitas dan harmoni alam semesta dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:
Dalam agama hindu, menjaga keseimbangan lingkungan dianggap sebagai cara untuk menjaga koneksi dengan Tuhan dan mencapai kesadaran spiritual. Lingkungan dianggap sebagai ciptaan Tuhan, sehingga menjaga keseimbangan lingkungan adalah cara untuk menghormati dan mensyukuri ciptaan-Nya. Selain itu, menjaga keseimbangan lingkungan juga merupakan bagian dari prinsip Ahimsa (non-kekerasan) dan keadilan lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh penulis Trimanto B.Ngaderi ada konsep Tri Hita Karana yang mengatur hubungan antara manusia, alam semesta dan Tuhan. Dimana konsep tersebut hidup yang Tangguh (sejahtera) akan tercapai apabila terjadi hubungan yang harmonis antara Tuhan, manusia dan Alam semesta, agar tercapai pelestarian dan keberlangsungan lingkungan. Dr. Nyoman menjelaskan bahwa umat Hindu dalam keseharian menjalankan berbagai ritual yang bertujuan menjaga keharmonisan dengan alam. Beberapa di antaranya adalah:
- Kain Poleng, kain bermotif hitam-putih yang biasanya dililitkan pada batang pohon, melambangkan kekuatan spiritual, keseimbangan, dan upaya pelestarian alam.
- Tawur Kesanga, bagian dari upacara Bhuta Yadnya, dilaksanakan untuk mensucikan alam semesta dan menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungannya.
- Tumpek Wariga, hari penghormatan kepada Dewa Tumbuh-tumbuhan, Desa Sangkara, sebagai bentuk syukur dan perawatan terhadap alam.
- Subak, sistem irigasi tradisional di Bali yang mencerminkan integrasi antara lingkungan, kehidupan sosial, dan nilai-nilai spiritual.
- Tumpek Kandang, sebuah hari persembahan kepada Dewa Rare Anggon, ditujukan untuk memohon perlindungan dan kesehatan bagi hewan ternak.
Selain itu, peringatan Hari Raya Nyepi menjadi momen penting dalam kehidupan umat Hindu untuk merenung dan menyeimbangkan diri dengan alam. Perayaan ini bukan hanya bermakna spiritual, tetapi juga membawa dampak positif terhadap lingkungan, seperti berkurangnya polusi udara, hemat energi dan air, serta meningkatnya kesadaran ekologis masyarakat.
Sementara itu, dalam masyarakat Suku Dayak Salako, dikenal ritual Ngabayotn sebagai ungkapan rasa syukur atas panen padi. Adapula Mamapas Lewu, dijalankan oleh masyarakat pemeluk agama Kaharingan, yang bertujuan menyucikan kampung dari konflik, bencana, kesialan, dan wabah. Sedangkan Manyanggar merupakan upacara adat masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang dilakukan sebelum membuka lahan baru.
Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, individu dapat menciptakan stabilitas dan harmoni alam semesta, serta mencapai kesadaran spiritual dan keseimbangan hidup. Dalam pandangan Hindu, menciptakan stabilitas dan harmoni alam semesta adalah bagian dari tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mencapai Moksha, atau kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Atau bisa dikenal dengan istilah sebagai “Moksartam Jagathita Ya Ca Iti Dharma”, yang merupakan tujuan tertinggi dalam agama Hindu.

Iman Membumi, Bumi Terjaga: Jadikan Agama Sebagai Suluh Merawat Alam
Oleh: Adnan Iman Nurtjahjo Amir, S.M., C.EML. (FKUB Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta ).
Saat ini, dunia tengah bergulat dengan krisis iklim yang tak lagi bisa diabaikan. Perubahan suhu global, bencana alam yang kian sering, pencemaran yang merajalela semua menjadi tanda bahwa hubungan manusia dan alam sedang tidak baik-baik saja. Namun di balik semua itu, tersimpan satu potensi besar yang kerap terabaikan dalam gerakan lingkungan yaitu agama.
Dalam hampir semua ajaran agama, terdapat pesan moral yang menggarisbawahi pentingnya menjaga ciptaan Tuhan. Islam, misalnya, menekankan konsep khalifah fil ardh atau pemimpin di bumi, yang artinya manusia memiliki amanah untuk memelihara dan tidak merusak bumi. Dalam tradisi Kristen, terdapat ajaran stewardship bahwa manusia adalah pengelola yang bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Begitu pula dalam Hindu dan Buddha, keseimbangan alam merupakan bagian dari dharma dan jalan hidup yang suci.
Agama Membentuk Kesadaran Ekologis
Di tengah ancaman krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang kian nyata, manusia dituntut tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memperkuat dimensi spiritual dalam menjaga alam. Agama, yang selama ini menjadi pedoman hidup, sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran ekologis. Nilai-nilai agama yang luhur sesungguhnya telah mengajarkan manusia untuk tidak serakah, mencintai makhluk hidup lain, serta menjaga harmoni dengan semesta.
Namun, realitasnya kini berbanding terbalik. Eksploitasi alam terus terjadi atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sungai dicemari, hutan digunduli, dan udara dikotori, seolah-olah bumi hanya diciptakan untuk ditaklukkan tanpa batas. Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sebagai suluh atau pelita yang menuntun perilaku manusia agar tidak gelap mata oleh keserakahan dan kepentingan sesaat.
Gerakan keagamaan hijau mulai bermunculan dalam beberapa dekade terakhir sebagai respons atas krisis lingkungan. Masjid ramah lingkungan, gereja hijau, hingga komunitas lintas iman yang menanam pohon bersama adalah contoh konkret bagaimana agama bisa menjadi kekuatan sosial yang mendorong perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Tindakan-tindakan kecil seperti hemat energi, memilah sampah, hingga menghindari konsumsi berlebihan bisa menjadi wujud ibadah yang membumi.
Di berbagai daerah, para tokoh agama mulai menyisipkan pesan-pesan ekologis dalam khutbah, ceramah, maupun liturgi. Mereka menyadari bahwa umat cenderung lebih mudah tersentuh jika isu lingkungan disampaikan dalam bingkai nilai-nilai spiritual. Ini menjadi langkah penting untuk mengembalikan agama pada fungsinya sebagai cahaya penuntun hidup, termasuk dalam menghadapi tantangan ekologi global.
Pendidikan agama pun seharusnya mulai dirancang tidak hanya membahas ritual dan akidah semata, tetapi juga mengaitkannya dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. Anak-anak perlu ditanamkan sejak dini bahwa membuang sampah sembarangan atau merusak tanaman bukan hanya kesalahan etis, tetapi juga pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Agama harus mengakar, tidak hanya di tempat ibadah, tetapi juga di laku harian yang mencerminkan cinta pada bumi.
Manusia Bukan pemilik Bumi
Tak dapat dipungkiri, krisis lingkungan sesungguhnya adalah krisis moral dan spiritual. Ketika manusia merasa paling unggul dan berkuasa, maka ia lupa bahwa alam pun memiliki hak hidup. Di sinilah agama memainkan perannya untuk mengingatkan manusia bahwa ia bukan pemilik bumi, tetapi hanya menumpang hidup di atasnya. Semua yang ada di alam ini adalah titipan, yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Setiap pohon yang ditebang, setiap sungai yang dicemari, dan setiap makhluk yang punah semua ada catatannya di hadapan Tuhan.
Agama juga bisa menjadi dasar moral dalam kebijakan publik. Pemimpin daerah yang agamis semestinya memegang prinsip rahmatan lil ‘alamin alias rahmat bagi semesta, bukan hanya manusia. Perizinan tambang, industri, dan pembangunan infrastruktur harus berlandaskan etika lingkungan yang kuat. Sebab, merusak alam sama artinya dengan mengkhianati amanah Tuhan.
Agama dan Alam Tidak Pernah Bertentangan
Agama dan alam sejatinya berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran agama mengandung nilai-nilai luhur yang menuntun manusia untuk hidup selaras dengan ciptaan Tuhan lainnya, termasuk alam semesta. Dalam berbagai kitab suci, alam bukan hanya latar tempat hidup manusia, tetapi juga tanda-tanda kebesaran Tuhan (ayat kauniyah) yang patut direnungkan. Oleh karena itu, memelihara alam adalah bagian dari ketaatan spiritual, bukan sesuatu yang terpisah dari ajaran agama. Alam sendiri berjalan menurut hukum-hukum Tuhan yang penuh keteraturan. Ketika manusia mengikuti nilai-nilai agama secara utuh seperti hidup sederhana, tidak rakus, berlaku adil, dan mencintai sesama makhluk maka otomatis ia juga akan menjaga harmoni dengan alam. Tidak ada ajaran agama yang membenarkan perusakan lingkungan atau eksploitasi tanpa batas. Justru, agama mengajarkan batas dan etika dalam memperlakukan sumber daya alam.
Pertentangan antara agama dan alam hanya terjadi ketika manusia salah menafsirkan atau mengabaikan nilai-nilai dasar agama itu sendiri. Ketika agama dijadikan formalitas belaka dan tidak membentuk perilaku ekologis, di situlah konflik muncul. Padahal jika dipahami dengan benar, agama dan alam saling menguatkan: agama memberikan makna, dan alam menjadi ladang pengabdian. Keduanya bersatu dalam menuntun manusia menuju kehidupan yang seimbang, damai, dan berkelanjutan.
Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai spiritual dalam relasi manusia dan lingkungan, kita membuka harapan bagi bumi yang lebih lestari. Karena pada akhirnya, agama dan alam tidak pernah bertentangan. Keduanya sama-sama mengajarkan kebaikan, keseimbangan, dan kasih sayang bagi seluruh makhluk.
Agama Sebagai Suluh Menjaga Bumi
Menjadikan agama sebagai suluh dalam menjaga alam adalah panggilan zaman. Ini bukan sekadar gerakan moral, tetapi juga bentuk nyata dari ibadah dan kepatuhan terhadap Sang Pencipta. Sebab menjaga alam berarti menjaga kehidupan, menjaga masa depan, dan menjaga amanah yang telah dititipkan kepada umat manusia.
Pada akhirnya, menjadikan agama sebagai suluh menjaga bumi adalah ikhtiar suci. Iman tidak boleh berhenti di langit, ia harus menyentuh tanah. Karena bumi yang kita pijak hari ini bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan titipan bagi anak cucu. Dan menjaga titipan adalah bagian dari iman.
Kesadaran ini harus menjadi gerakan kolektif. Para pemuka agama, tokoh masyarakat, pendidik, hingga pemimpin daerah perlu bersinergi menjadikan nilai-nilai agama sebagai fondasi dalam merancang kebijakan publik yang berkelanjutan. Ritual keagamaan bisa diperkaya dengan kampanye cinta lingkungan. Perayaan hari besar agama bisa dibingkai dengan aksi bersih-bersih atau pembagian bibit pohon. Setiap ibadah menjadi momen refleksi dan penguatan komitmen untuk menjaga bumi.

ARSIP YANG TERLUPAKAN, TAK LEKANG OLEH WAKTU
Oleh: Nuraeni, S.Pd., M.Pd. (Guru SMA NEGERI 1 SUMBER ).
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan. Rahayu
Setelah mengikuti kegiatan APSK pada hari Sabtu, 7 Juni 2025 dengan narasumber dari Pdt. Yoto, S.Th, MA, M.Pd.K dengan materi Kepemimpinan Ekoteologis, Interreligius dalam Pembangunan SDGs. Saya sangat senang bisa menambah ilmu dan pengetahuan yang baru melalui kegiatan webinar ini. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Ada beberapa alasan pertama, menyesuaikan dengan tema pemateri. Kedua, konsep lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan memiliki warisan nilai-nilai yang sangat kaya, dimulai dari etika, moral, dan prinsip-prinsip universal yang sudah lama diajarkan dalam berbagai tradisi agama. Hal ini, kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang bisa merasakan, membaca dan memahami untuk melindung alam semesta disekitar kita yang semakin hari semakin dikeruk oleh para manusia yang tidak memiliki hati terhadap alam semesta yang Tuhan kasih untuk bumi.
Isu-isu lingkungan bukan menjadi masalah baru. Sejak dahulu, manusia telah meninggalkan jejak hubungan sakral dengan alam dalam berbagai macam jenis baik melalui naskah kuno, tradisi lisan, ritual keagamaan maupun aturan adat. Tetapi, dokumen-dokumen tersebut terabaikan, terkubur dalam “arsip yang terlupakan” oleh arus modernisasi. Padahal, warisan ekoteologis dan kearifan lokal dari berbagai peradaban memiliki nilai luhur dalam menjaga keseimbangan ekologis. Artikel ini menelusuri rekaman-rekaman sejarah tentang kepedulian lingkungan lintas zaman dan lintas iman, yang ternyata menyimpan benih awal dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) masa kini. Merekalah bukti bahwa meski terlupakan, jejak-jejak itu tak pernah lekang oleh waktu. Apabila ditelusuri dengan cermat, arsip-arsip itu menyimpan nilai-nilai luhur tentang tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi. Apa yang kini dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sejatinya telah hadir dalam bentuk-bentuk lokal yang kontekstual, dari larangan menebang pohon sembarangan di daerah adat, membuang sampah sembarangan, merusak laut dan gunung hingga penghormatan terhadap air dan tanah dalam tradisi keagamaan. Artikel ini bertujuan mengangkat kembali suara-suara sunyi dari masa lalu suara yang tidak lekang oleh waktu untuk menjadi inspirasi dan dasar moral dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, adil, dan manusiawi. Sehingga menjadi permasalahan disini yaitu Bagaimana manusia akan bisa sadar terhadap lingkungan yang diberi oleh Allah SWT kalau manusianya saja bisa merusak perut bumi. Akan tetapi, bagaimana manusia bisa bekerja mencari nafkah jika tidak seperti itu?. Bagaimana manusia bisa membangun rumah permanen jika tidak dari perut bumi? Manusia yang memakai emas ini juga hasil dari perut bumi. Apakah mereka yang mengumpulkan emas juga tidak memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Sebenarnya saling symbiosis mutualisme. Bukan membela merusak lingkungan bukan pula menyalahkan manusia yang memakai emas. Ini semua antara teori dan ilmu yang tidak diaplikasikan oleh mereka karena rendahnya pendidikan di Indonesia. Yang bekerja mencari emas, pasir, batu dan lain-lain mereka hanya lulusan SD dan SMP. Yang punya ilmu dan teori tentang ekoteologis apakah ada mengedukasi Teknik-tekniknya untuk mengeksplore kekayaan alam.
Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Kesaksian
Dalam pandangan Kristen, arsip bukan hanya sekumpulan catatan atau dokumen lama, melainkan jejak kesetiaan Allah dan kesaksian umat-Nya di sepanjang sejarah. Alkitab itu sendiri adalah bentuk arsip ilahi—Firman Tuhan yang hidup, yang mencatat perjalanan manusia bersama Allah sejak penciptaan hingga pengharapan akan kehidupan kekal.
“Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.”
— 2 Timotius 3:16
Firman Tuhan adalah arsip yang tidak lekang oleh waktu, bukan karena dicetak dalam tinta dan kertas, tapi karena roh yang menghidupinya. Setiap kisah dalam Alkitab—dari penciptaan, kejatuhan, penebusan oleh Kristus, hingga pengharapan akhir—adalah bukti nyata bahwa Allah bekerja dalam sejarah.
Dalam era modern, isu lingkungan sering kali dibahas dalam bentuk laporan ilmiah, data statistik, atau dokumen kebijakan. Namun, bagi orang percaya, lingkungan bukan sekadar objek studi atau data teknis. Ia adalah ciptaan Allah yang menyuarakan kesaksian tentang kemuliaan-Nya. Dalam terang iman Kristen, lingkungan hidup bukan hanya persoalan ekologis, tapi juga dimensi spiritual dan moral—suatu panggilan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan ciptaan.
Lingkungan: Ciptaan yang Bersaksi tentang Penciptanya
Kitab Suci membuka dengan sebuah kesaksian agung: bahwa langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah hasil karya tangan Tuhan. Alam semesta bukan hadir secara kebetulan, melainkan diciptakan dengan maksud dan tujuan yang dalam.
“Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya.”
— Mazmur 19:2
Ayat ini menegaskan bahwa alam adalah pewarta sunyi tentang keberadaan, kuasa, dan kebijaksanaan Allah. Setiap gunung, hutan, sungai, dan makhluk hidup menyimpan jejak Sang Pencipta. Mereka menjadi arsip hidup yang tidak hanya bisa dilihat, tetapi juga direnungkan.
Melupakan Arsip, Melupakan Jati Diri
Di zaman ini, banyak orang Kristen melupakan warisan rohani dan sejarah iman mereka. Mereka hidup dalam kekristenan yang dangkal, tidak berakar, dan cenderung kehilangan arah. Padahal, dengan memahami “arsip-arsip” iman—baik melalui pembacaan Alkitab, pengakuan iman para bapa gereja, maupun pengalaman spiritual para pendahulu—kita dibentuk untuk tetap setia, tangguh, dan bijak.
“Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka.”
— Ibrani 13:7
Ayat ini mengingatkan kita agar tidak mencabut diri dari akar sejarah rohani, karena dari sanalah kita belajar berjalan dalam terang Tuhan.
Jejak yang Harus Dihidupi Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk membaca atau mengingat arsip iman, tapi menghidupinya. Arsip bukan untuk dikenang saja, tapi untuk ditindaklanjuti.
“Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.”
— Yakobus 1:22
Ketika kita menjaga dan menghidupi warisan rohani baik dalam bentuk nilai-nilai Injil, kesaksian hidup, maupun pengajaran yang sehat kita sedang memperpanjang kehidupan dari “arsip” itu sendiri. Dalam tindakan kasih, keadilan, dan kesetiaan kepada Tuhan, kita menjadikan sejarah sebagai hidup yang nyata saat ini.
Kesimpulan: Menjadi Penjaga dan Pelaku Arsip Kekal
Di hadapan dunia yang terus berubah, orang Kristen dipanggil untuk menjadi penjaga dan pelaku dari arsip yang kekal. Bukan untuk nostalgia atau romantisasi masa lalu, tapi untuk membawa terang itu ke dalam dunia yang sedang kehilangan arah. Firman Tuhan, kesaksian iman, dan nilai-nilai Injil adalah arsip yang akan tetap berdiri, bahkan ketika langit dan bumi berlalu.
“Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.”
— Matius 24:35
Mari kita gali kembali, rawat, dan hidup dalam kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Sebab di dalamnya, ada kekuatan untuk menghadapi hari ini dan pengharapan untuk hari esok.

“Antara Ajaran, Kekuasaan, dan Kesadaran”
Oleh: I Putu Dicky Merta Pratama, S.H.,M.H. (PRADITAMA - Prakarsa Dharma Insan Pratama Nuswantara)).
Di tengah banyaknya ajaran yang diwariskan, baik dari agama, filsafat, maupun sastra suci, kita hidup dalam zaman yang semakin sarat paradoks. Kita diajarkan tentang dharma, tentang kebenaran, tentang jalan tengah yang adil, namun kenyataannya, perintah-perintah suci itu sering kali tidak dijalankan secara utuh. Bukan karena manusia tidak tahu, tetapi karena manusia memilih.
Manusia lebih suka melaksanakan yang menguntungkan dirinya. Ia mencari dalil untuk yang mudah, dan meninggalkan yang rumit. Ajaran tidak lagi dijalankan sebagai jalan keselamatan, melainkan dibaca sebagai legitimasi kekuasaan. Bahkan, dalam banyak kasus, justru oknum tokoh-tokoh yang seharusnya menjaga nilai—agamawan, cendekia, akademisi berubah menjadi tameng oknum kekuasaan. Mereka bukan berdiri sebagai penegak moral, tetapi menjadi juru tafsir yang membenarkan apa yang sebelumnya salah.
Sebagaimana dalam Sarasamuscaya, dikatakan:
“Akaśa dharmaḥ kālaḥ śāstraṁ guruvākyaṁ ca bhinnatvena vartante”
“Ajaran yang luhur bisa dipersepsi berbeda tergantung pada waktu, tempat, dan siapa yang menyampaikannya.”
Namun perbedaan persepsi bukanlah pembenaran untuk pengkhianatan nilai. Perbedaan bukanlah alasan untuk manipulasi.
Apa yang terjadi hari ini, di sekitar kita, adalah suatu bentuk ironi kolektif. Kita sering kali menyebut diri spiritual, tetapi menolak kebijaksanaan ketika ia menyusahkan. Kita sering kali menuntut toleransi, namun komunikasi kita masih kerap kali bersifat satu arah. Dalam forum lintas iman seperti Sekolah Lintas Iman (SLI), kita bicara tentang kepemimpinan ekoteologis dan pembangunan berkelanjutan, namun di balik panggung/disekitar kita, struktur tetap timpang: yang berkuasa menentukan narasi, yang lain mengikuti atau mengalah.
Sungguh miris, ketika hukum, etika, dan nilai suci tak lebih dari alat retorika. Mereka yang membuat aturan, kerap menjadi yang pertama melanggarnya. Dan ketika pelanggaran itu terkuak, mereka cukup mengubah aturannya, agar tampak tak melanggar. Itulah wajah nyata dari paradoks sistemik yang kita hadapi hari ini.
Dan ketika ada yang berkata, “Masuklah ke dalam sistem agar kau bisa mengubahnya,” maka kita patut bertanya:
Apakah benar sistem itu akan berubah oleh kehadiran kita, atau justru kitalah yang akan diubah, dibentuk ulang, dan dilemahkan agar menyerupai sistem itu sendiri?
Dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, Arjuna tidak masuk ke istana untuk mengubahnya dari dalam. Ia bertapa. Ia menepi. Ia menaklukkan godaan duniawi. Ia tidak menjadi bagian dari sistem, tetapi memurnikan dirinya untuk kemudian menjadi cahaya dalam kegelapan zaman.
“Tan hana dharma mangrwa” — Tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran tidak bisa dipermainkan, tidak bisa dipilah-pilah. Ia harus utuh dijalankan.
Dalam konteks ini, karya ilmiah, sastra hingga seniapapun yang kita ciptakan untuk mengingatkan juga berisiko menjadi sia-sia. Ia hanya dipajang. Ditonton sepintas. Diapresiasi secara estetika, tapi tidak dibaca dengan hati, tidak didengar dengan jiwa, apalagi dijadikan laku hidup.
Padahal sastra kita yang terdalam, seperti Nitisastra, mengingatkan:
“Darma tan wruh lamun tan hana laku.”
“Kebijaksanaan tidak berarti apa-apa jika tidak diwujudkan dalam perbuatan.”
Jadi pertanyaannya kini:
Beranikah kita hidup dalam nilai yang kita serukan?
Ataukah kita hanya akan terus membuat karya, tanpa nyawa?
Antara Gerak Besar dan Langkah Nyata
Di akhir segala renungan, kita pun harus menimbang:
Apakah satu karya, satu langkah, satu suara kecil—masih berarti?
Ketika dunia bergerak terlalu cepat, dan sistem seolah terlalu kuat untuk digoyang?
Di sinilah kita perlu kembali pada hikmah sastra kuno.
Dalam Kakawin Sutasoma, karya Mpu Tantular, terdapat ajaran halus:
“Ruruh sarpin ning aji, sakeng saking iwang pratiti.”
“Seutas benang yang terputus, tetap bermakna, jika berasal dari pemahaman sejati.”
Artinya, bahkan satu tindakan kecil, satu gerak yang lahir dari kesadaran, memiliki nilai abadi—lebih daripada gerak besar yang hampa dari makna.
Kita tidak harus selalu menciptakan gerakan besar yang viral atau disorot dunia.
Yang penting adalah:
Apakah karya itu tulus? Apakah langkah itu jujur? Apakah ia lahir dari dharma?
Sebab dalam Bhagavadgītā , Krishna tidak meminta Arjuna untuk mengubah dunia,
tetapi untuk bertindak sesuai swadharma-nya.
“Swadharme nidhanam shreyaḥ, paradharmo bhayāvahaḥ.”
“Lebih baik mati dalam jalan kebenaranmu sendiri, daripada hidup dalam jalan orang lain yang tampak mulia.”
Maka, jangan remehkan satu langkah kecilmu; Jangan meragukan satu karya yang kau ciptakan dengan kesadaran; Sebab dari situlah benih perubahan ditanam perlahan, sunyi, namun pasti.
“Dharma hanya dapat dipahami melalui laku nyata yang berakar pada tekad, diteguhkan oleh pengorbanan, dilandasi pengetahuan yang diwujudkan dalam tindakan, karena satu langkah kecil yang setia menapaki jalan kehidupan jauh lebih bermakna daripada angan-angan tanpa arah yang tak pernah menjadi karya.”

Satukan Iman, Gapai Tujuan : Strategi Lintas Agama Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Oleh: Adnan Iman Nurtjahjo Amir, S.M., C.EML. (FKUB Kabupaten Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta).
Di tengah dunia yang penuh tantangan seperti krisis iklim, kesenjangan ekonomi, konflik sosial, hingga kerusakan lingkungan, manusia tidak hanya membutuhkan teknologi atau kebijakan publik. Dunia juga memerlukan kekuatan moral, spiritual, dan sosial yang mampu menggerakkan perubahan dari akar hingga ke pucuk. Di sinilah agama memainkan peran strategis. Agama, dalam seluruh ragam bentuknya, adalah institusi sosial dan spiritual yang hidup dalam keseharian miliaran manusia. Agama menyentuh nurani, menumbuhkan kepedulian, serta membentuk cara manusia memperlakukan sesamanya dan alam. Membangun kerjasama lintas agama dan kepercayaan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) bukanlah pilihan tambahan, melainkan elemen kunci bagi keberhasilan pembangunan global yang adil, damai, dan lestari.
Mengapa Agama dan Kepercayaan Penting Dalam SDGs?
SDGs, dengan 17 tujuan globalnya, adalah peta jalan menuju masa depan dunia yang lebih baik: bebas dari kemiskinan, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Agenda ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil, termasuk komunitas keagamaan. Agama memiliki kekuatan transformatif. Pemimpin agama dihormati, dipercaya, dan punya akses langsung ke komunitas akar rumput. Setiap minggu, jutaan orang menghadiri ibadah dan menerima pesan-pesan moral yang dapat diselaraskan dengan nilai-nilai SDGs. Namun tantangannya besar: bagaimana menyatukan berbagai keyakinan dalam tindakan bersama yang konkret?
- Membangun Ruang Dialog Jujur Berbasis Ekologis
Kerjasama lintas agama dimulai dari membangun ruang dialog. Forum-forum lintas iman seperti United Nations Interfaith Harmony Week, Religions for Peace, dan Interfaith Dialogue on Climate Action telah membuka ruang perjumpaan antara tokoh-tokoh agama untuk membicarakan solusi konkret atas masalah bersama.
Di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi wadah penting untuk meredam gesekan sosial dan membangun konsensus dalam isu-isu strategis. Dari Aceh hingga Papua, berbagai bentuk dialog lokal berbasis kearifan budaya juga telah tumbuh, menjadi modal sosial yang sangat penting.
- Kolaborasi Nyata Dalam Aksi Sosial dan Lingkungan
Langkah berikutnya adalah aksi bersama. Banyak organisasi keagamaan memiliki jaringan yang kuat dari masjid, gereja, pura, vihara, hingga komunitas spiritual lokal. Jaringan ini bisa menjadi kekuatan sosial untuk melaksanakan program-program berbasis SDGs, seperti pelestarian lingkungan.
Contoh kolaboratif bisa dilihat dalam program Religious Response to Climate Change di Afrika dan Asia, di mana kelompok Muslim, Kristen, Hindu, dan Budha bahu-membahu menanam pohon, memperbaiki sistem irigasi, dan mendampingi petani kecil. Di Indonesia, kerjasama antara komunitas Gereja Katolik dan pesantren dalam program ketahanan pangan berbasis pertanian organik di NTT dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa semangat gotong royong lintas iman bukan hanya mungkin, tapi juga efektif.
- Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai SDGs di Institusi Keagamaan
Pengarusutamaan nilai-nilai SDGs dalam pendidikan keagamaan. Pesantren, seminari, sekolah Minggu, sekolah keagamaan Hindu dan Budha, semuanya bisa menjadi tempat untuk menanamkan kesadaran lingkungan, keadilan ekonomi, dan nilai-nilai perdamaian. Kurikulum yang mengajarkan bahwa “merusak alam adalah dosa” akan memperkuat motivasi spiritual untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. Misalnya, konsep Rahmatan lil Alamin dalam Islam, Ahimsa dalam Hindu dan Budha, serta Tanggung Jawab Sosial dalam kekristenan bisa menjadi landasan moral untuk mendorong perilaku yang pro-lingkungan.
- Pemimpin Agama sebagai Agen Perubahan dan Advokat Kebijakan
Para tokoh agama tidak hanya berbicara kepada umat, tetapi juga bisa memengaruhi arah kebijakan publik. Ketika mereka bersuara dalam isu-isu seperti krisis air, keadilan ekonomi, dan kerusakan alam, dampaknya jauh melampaui pidato akademik atau teknokratik. Inisiatif seperti Laudato Si’ dari Paus Fransiskus, yang menyerukan aksi global untuk melawan perubahan iklim, adalah contoh kuat bagaimana suara spiritual dapat mengguncang dunia. Di sisi lain, gerakan Eco-Pesantren di Indonesia juga menunjukkan bahwa pesantren dapat menjadi motor penggerak aksi lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.
Karenanya, tokoh-tokoh agama bisa dan harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah dan nasional. Mereka dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat dalam isu-isu sensitif seperti redistribusi lahan, pembangunan energi bersih, atau mitigasi bencana alam.
- Inklusivitas: Merangkul Kepercayaan Lokal dan Minoritas
Kerjasama lintas agama yang sukses juga harus bersifat inklusif. Tidak hanya menyertakan agama-agama besar, tapi juga kepercayaan lokal, komunitas adat, dan kelompok minoritas spiritual lainnya. Mereka sering kali memiliki kearifan ekologis yang tinggi dan hubungan mendalam dengan alam. Di Kalimantan, komunitas Dayak merawat hutan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai warisan spiritual. Di Sumba, kepercayaan Marapu mengajarkan harmoni antara manusia, leluhur, dan alam. Ketika kearifan ini dihargai dan dilibatkan dalam strategi pembangunan, hasilnya bisa lebih lestari dan berkeadilan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Tentu saja, kerjasama lintas agama tidak selalu mudah. Hambatan bisa datang dari eksklusivisme, konflik sejarah, atau kecurigaan politik. Namun jika ada niat baik, keterbukaan, dan komitmen pada nilai-nilai universal, maka perbedaan tidak lagi menjadi penghalang, melainkan kekayaan untuk diperjuangkan bersama. Karena sesungguhnya, bumi ini adalah rumah ibadah terbesar kita semua. Menjaganya adalah ibadah yang tidak mengenal sekat agama.
Pemerintah dan lembaga internasional perlu menyediakan ruang dan dukungan bagi inisiatif lintas iman ini. Termasuk dengan mengintegrasikan peran tokoh agama dalam strategi nasional pembangunan berkelanjutan. Di tengah dunia yang terus berubah, kerjasama lintas agama adalah cahaya harapan. Ketika para pemimpin agama, tokoh adat, komunitas spiritual, dan warga dunia bersatu untuk menjaga bumi, memperjuangkan keadilan, dan menegakkan martabat manusia, maka SDGs bukan lagi sekadar target, melainkan amanah moral bersama.

Jiwa Hutan: Ketika Ilmu Bertemu Kesadaran
Penulis: Hj. Mariza SS., MM. (Lions Club Jakarta, Monas Heritage).
Dalam hidup yang penuh kepentingan dan keramaian modern, saya merasa seperti pohon di pinggir jalan kota—tumbuh, tapi tak sepenuhnya hidup. Namun pada tanggal 24 Mei 2025, dalam Short Course Batch 4 APSK, saya diingatkan kembali akan akar terdalam eksistensi manusia: relasi kita dengan alam, khususnya dengan hutan—paru-paru bumi dan penyeimbang kehidupan.
Melalui materi yang padat, filosofis, dan teknis, saya merasa tidak hanya sedang belajar, tapi sedang “diingatkan”. Disapa oleh kejujuran ilmu dan dikembalikan pada simpul-simpul kesadaran ekologis. Dan penyambung makna itu adalah sosok Bapak Januminro, seorang pejuang lingkungan hidup yang bukan hanya membawa gelar dan pengalaman, tetapi juga membawa jiwa besar dalam menyampaikan ilmu.
Bapak Januminro: Api Pengetahuan yang Menyala untuk Bumi
Beliau bukan sekadar pemateri. Dalam setiap kalimat yang disampaikan, saya menangkap denyut cinta akan hutan, bukan sebagai objek studi semata, tetapi sebagai sahabat kehidupan. Suaranya tenang namun membakar semangat, seperti embun pagi membisikkan harapan pada daun yang layu.
Bapak Januminro dikenal luas sebagai praktisi lingkungan hidup, khususnya atas dedikasinya dalam rehabilitasi lahan gambut yang terbakar dan pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun kontribusinya melampaui angka dan alat. Ia adalah pemilik sekaligus pengelola Jumpun Pambelom—sebuah hutan hak milik di Kalimantan Tengah yang dulunya adalah lahan gambut terbakar, lalu ia hidupkan kembali menjadi pusat konservasi dan relawan.
Melalui Jumpun Pambelom, beliau tak hanya menanam kembali pohon-pohon tahan api, tetapi juga menanamkan kesadaran kepada masyarakat. Di hutan yang ia rawat, ia menggerakkan program adopsi pohon, menjadikan pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sosial, bukan hanya agenda para pakar. Ia merangkul warga untuk turut merasa memiliki hutan, menyentuh akar-akar perubahan dari bawah.
Tidak mengherankan jika pada tahun 2015, ia menerima Penghargaan Kalpataru, penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup di Indonesia. Tapi bagi saya dan para peserta short course, penghargaan sejatinya adalah kehadirannya sendiri—utuh sebagai pelaku, pemikir, dan penggerak.
Teknologi, Kearifan, dan Komitmen
Saat memaparkan alat-alat penting seperti Kestrel 5500FW untuk membaca kondisi mikroklimat dan potensi kebakaran, serta perlengkapan pemadam punggung yang wajib dimiliki relawan di lapangan, beliau tidak hanya memberi instruksi. Ia menautkan antara teknis dan etika, antara logika dan cinta pada bumi. Ilmu yang ia bagikan bukan hanya berbasis pada teori, melainkan pada pengalaman nyata di tengah bara, asap, dan keringat perjuangan.
Ia menunjukkan bahwa pencegahan lebih utama daripada pemadaman, dan keterlibatan masyarakat lebih kokoh daripada intervensi sesaat. Baginya, pelatihan karhutla bukan sekadar aktivitas tahunan, melainkan proses berkelanjutan menanamkan disiplin ekologis.
Hutan Sebagai Cermin Diri
Bapak Januminro mengatakan dengan tegas: “Ketika hutan terbakar, bukan hanya pohon yang mati. Ada masa depan yang turut musnah.” Kalimat itu menghantam kesadaran saya. Betapa seringnya kita mengabaikan suara hutan, menganggapnya sebagai latar, bukan aktor utama dalam keberlanjutan hidup manusia.
Refleksi ini membuat saya merenung bahwa hutan adalah cermin jiwa kita. Ketika ia rusak, sesungguhnya kita sedang menyaksikan kerusakan batin manusia itu sendiri — serakah, abai, dan lupa akan batas. Tapi dalam tangan sosok seperti Bapak Januminro, saya melihat bagaimana ilmu bisa menjadi alat penyembuh, dan bagaimana kesadaran bisa menjadi kekuatan yang menyelamatkan dunia.
Ketika Ilmu Menyentuh Jiwa
Sebagai peserta, saya tidak hanya mendapatkan materi pelatihan, tapi mendapatkan pengalaman batin yang mengubah cara pandang saya terhadap lingkungan. Sosok beliau membuktikan bahwa seorang pelopor hutan gambut hak milik tidak hanya bekerja dengan cangkul dan bibit, tetapi juga dengan hati yang teguh dan visi yang jernih.
Saya kagum pada bagaimana ia menggabungkan pendekatan ilmiah dengan kearifan lokal, bagaimana ia menyusun sistem pengelolaan berbasis komunitas, dan bagaimana ia menciptakan model pelestarian hutan yang tidak menggantungkan diri pada proyek, tapi pada partisipasi.
Belajar Menjadi Api Menyala untuk Kehidupan
Dari short course ini, saya tidak hanya belajar bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana menjadi api yang menghidupkan: api pengetahuan, api kepedulian, api kesadaran. Sosok Bapak Januminro telah mengajarkan bahwa dalam menghadapi kebakaran hutan, kita tidak cukup dengan air—kita butuh jiwa yang menyala, hati yang ikhlas, dan ilmu yang berpihak pada kehidupan.
Terima kasih Bapak Januminro, atas ilmu, teladan, dan ketulusan Anda. Semoga semangat Jumpun Pambelom menjalar ke setiap relung bumi yang kering dan terluka, dan semoga kami bisa menjadi bagian dari pohon-pohon harapan yang Anda tanam.

Apakah Kita Penonton di Panggung Kematian Bumi?
Penulis: Hj. Mariza SS., MM. (Lions Club Jakarta, Monas Heritage).
Langit tak lagi biru seperti dulu. Awan-awan tampak lebih berat menanggung duka yang tidak pernah diucapkan oleh manusia. Ranting-ranting pohon yang dulu riang bergoyang kini seperti menggigil, entah oleh angin atau oleh rasa takut akan hilangnya rumah mereka. Bumi, yang sejak jutaan tahun menjadi ibu bagi seluruh kehidupan, kini memandang kita dengan tatapan sayu—memohon, bukan marah. Mengharap, bukan mengutuk. Namun, sampai kapan ia akan bertahan?
Sebuah video yang dibagikan oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK) di kanal YouTube dan Instagram menjadi percikan kecil di lautan informasi yang kadang terlalu ramai dan membingungkan. Tapi percikan itu bisa menjadi nyala, bila kita sudi memandangnya dengan hati terbuka. Diskusi itu adalah cermin: menampilkan wajah kita yang tak selalu bersih, memperlihatkan betapa rakus dan acuhnya manusia terhadap bumi tempatnya berpijak.
Bagi saya—seorang awam yang baru memijakkan kaki di dunia kesadaran ekologis—tayangan ini seperti embun di padang yang kering. Menyegarkan sekaligus menyadarkan. Bahwa mencintai bumi tidak cukup hanya dengan tahu, tetapi harus sampai tahap bertindak. Bahwa menjaga lingkungan bukan gaya hidup kekinian, tapi wujud keimanan dan tanggung jawab spiritual.
Apakah iman kita cukup dalam, jika kita tega membiarkan sungai penuh limbah?
Apakah sembahyang kita sampai ke langit, jika kita menutup mata terhadap hutan yang dibakar?
Dalam berbagai ajaran, menjaga alam bukan perkara teknis, tapi etis. Dalam Islam, manusia adalah khalifah—pemelihara bumi, bukan penguasa serakah. Dalam kearifan lokal Nusantara, bumi disebut sebagai “Ibu Pertiwi”—sosok yang harus dihormati, bukan dijarah. Dan dalam budaya Bali, ada prinsip “Tri Hita Karana”, tiga harmoni suci antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.
Mengabaikan bumi berarti merusak harmoni ini. Maka tidak heran, kerusakan alam seringkali dibarengi krisis spiritual, krisis sosial, dan krisis jati diri.
Satu kutipan menggema kuat di tengah tayangan tersebut:
“Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak-anak kita.”
Itu adalah ucapan dari Chief Seattle, seorang kepala suku Duwamish dan suku Suquamish, penduduk asli Amerika, yang hidup pada abad ke-19. Beliau adalah simbol kebijaksanaan ekologis. Dalam suratnya yang terkenal kepada Presiden Amerika, ia menggambarkan bumi bukan sebagai benda mati, tetapi makhluk hidup yang memiliki roh—dan roh itu akan membalas jika dilukai. Ia adalah filsuf dari alam, suaranya adalah bisikan pepohonan dan hembusan sungai.
Pertanyaannya: apakah kita mendengar suara itu, atau sibuk dengan deru mesin dan bising ego kita sendiri?
Generasi kini dan yang akan datang harus memahami bahwa bumi tidak bisa diperbaiki dengan sekali demo atau satu kali aksi tanam pohon. Dibutuhkan kesadaran yang konsisten, seperti mata air yang tak pernah lelah mengalir. Kita harus mengingatkan mereka—anak-anak kita, murid-murid di sekolah, teman-teman kita sendiri—bahwa:
- Sampah yang dibuang sembarangan hari ini adalah racun yang akan mematangkan luka bumi esok hari.
- Air yang tercemar hari ini adalah air mata anak-anak di masa depan yang kehilangan sumber hidup.
- Udara yang kita kotori adalah nafas yang akan sesak ditanggung oleh generasi sesudah kita.
Pendidikan lingkungan bukan hanya soal teori dalam ruang kelas. Ia harus ditanamkan sejak kecil, melalui keteladanan, melalui kisah-kisah yang menyentuh. Kita butuh dongeng baru, bukan tentang pangeran dan naga, tapi tentang anak manusia yang menyelamatkan gunung, sungai, dan hutan. Kita butuh tokoh-tokoh yang diteladani bukan karena popularitas, tapi karena kepekaannya terhadap bumi.
Kita harus ajarkan bahwa bumi ini bukan milik siapa-siapa, tapi tanggung jawab semua. Tak ada kata “nanti” dalam menjaga lingkungan. Sebab setiap detik yang kita tunda, adalah satu pohon yang mungkin tumbang, satu spesies yang punah, satu air mata bumi yang jatuh ke tanah.
Dan ketika anak-anak kita bertanya nanti:
“Apa yang kalian lakukan saat dunia mulai rusak?”
Maka semoga kita bisa menjawab dengan jujur,
“Kami bangkit. Kami sadar. Kami bertindak.”
Bumi bukan hanya ruang fisik tempat kita berjalan. Ia adalah bagian dari jiwa kita. Jika kita merusaknya, kita merusak diri sendiri. Maka dari itu, hormatilah bumi sebagaimana kita menghormati ibu kandung kita. Peliharalah tanah ini sebagaimana kita menjaga tempat ibadah kita.
Bumi semesta bukan hanya perlu disayangi—ia perlu dilindungi, dihargai, dan dipeluk dengan sepenuh rasa. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita sadar bahwa hidup kita hanya sejenak, dan bumi ini akan tetap ada setelah kita pergi.
Dan semoga, ketika saat itu tiba, bumi bisa tersenyum, bukan menangis.

Belajar dari Jejak Perjuangan Heroes
Penulis: Hj. Mariza SS., MM. (Lions Club Jakarta, Monas Heritage).
Alam semesta bukan sekadar gugusan bintang dan planet yang berputar dalam keteraturan. Ia adalah puisi agung yang ditulis oleh Sang Pencipta dalam bahasa angin, air, tanah, dan cahaya. Dan dalam puisi itulah, manusia diberi satu peran sakral: menjadi penjaga harmoni. Namun, di tengah hiruk-pikuk zaman, tak banyak yang benar-benar memahami peran itu. Di tengah derap industri dan ambisi, suara-suara bumi kerap terabaikan.
Lalu, dalam ruang virtual sebuah short course tentang manajemen lingkungan, saya bersua—melalui layar dan kata—dengan seorang perempuan luar biasa: Ibu Siti Maimunah. Seperti angin yang lembut tapi pasti mengubah musim, beliau hadir dengan cerita yang bukan sekadar informasi, melainkan perenungan dan kesadaran baru bagi saya, seorang awam dalam ilmu lingkungan.
Saya menyimak semua rekaman dan materi dengan saksama. Dari video profil, presentasi singkat, hingga situs resmi IUCN tempat beliau berkiprah dalam konservasi spesies terancam. Setiap penjelasan Ibu Siti bukan hanya berbicara tentang data dan kebijakan, tapi tentang jiwa. Tentang tanah yang dilukai, tentang sungai yang merintih, dan tentang spesies yang perlahan-lahan kehilangan rumahnya. Ia menyampaikan semua itu bukan dengan nada menggugat, melainkan dengan empati dan keteguhan.
Bagi saya, Ibu Siti adalah perwujudan dari filosofi bumi itu sendiri: sabar, kokoh, dan penuh kasih. Dalam perjalanannya, ia mengorbankan kenyamanan demi keberlanjutan. Ia meninggalkan pilihan hidup yang lebih ringan demi berjalan di jalur yang sunyi—jalur yang hanya sedikit orang berani tempuh, karena penuh birokrasi dan badai politik lingkungan.
Dari materi yang ia sampaikan, saya belajar bahwa menjaga bumi bukan hanya tugas akademisi, aktivis, atau pemerintah. Ia adalah tanggung jawab setiap manusia yang masih bernapas, yang masih berharap melihat pelangi setelah hujan. Dalam konteks itu, pengetahuan tentang manajemen lingkungan dan emisi karbon membuka cakrawala baru dalam benak saya.
Saya baru benar-benar memahami bahwa jejak karbon bukan hanya berasal dari pabrik besar atau kendaraan bermotor. Bahkan dalam kebiasaan kecil—seperti membuang sampah sembarangan, menyalakan listrik tanpa keperluan, atau tidak bijak dalam konsumsi—kita sedang menorehkan jejak yang tak kasatmata, tapi membebani bumi. Dan sistem manajemen emisi bukan sekadar soal teknis pengukuran, tapi tentang etika hidup.
Refleksi saya sederhana tapi mendalam: selama ini saya hidup dalam lingkaran konsumsi yang tidak disadari. Saya mengambil dari bumi tanpa berpikir bagaimana mengganti. Saya menikmati oksigen tanpa menyapa pepohonan. Saya berjalan di atas tanah tanpa bertanya, apakah tanah itu masih bisa menumbuhkan harapan? Pertemuan ini menyentil, lalu menggerakkan.
Ibu Siti menyampaikan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian kecil. Dan keberanian itu bisa hadir dalam bentuk sederhana—seperti mulai memilah sampah, menanam pohon, mengurangi plastik, hingga menyuarakan pentingnya keadilan ekologis. Bagi saya yang sebelumnya hanya penonton pasif, kini saya ingin mulai berjalan, meski pelan, menuju keterlibatan yang nyata.
Saya juga sangat terkesan dengan pendekatan Ibu Siti yang tidak hanya menyentuh dimensi ekologis, tapi juga sosial dan kultural. Bahwa ekologi bukan sekadar hitungan ilmiah, tetapi erat terikat dengan identitas, kebudayaan, bahkan spiritualitas suatu masyarakat. Ia mengingatkan kita bahwa menjaga hutan berarti menjaga bahasa, menjaga adat, menjaga ingatan kolektif yang tak tergantikan.
Filosofi ini menancap dalam benak saya: alam semesta ini bukan objek untuk ditaklukkan, melainkan subjek untuk diajak berdialog. Seperti guru yang tak pernah marah, bumi terus memberi meski terus dilukai. Tapi bumi juga punya batas sabar. Ketika bencana datang, itu bukan murka, melainkan isyarat bahwa keseimbangan telah miring terlalu jauh.
Dalam short course ini, saya merasa bukan hanya menerima ilmu, tapi menerima panggilan. Panggilan untuk tidak lagi tinggal diam. Karena seperti kata pepatah Indian kuno: “Kita tidak mewarisi bumi dari leluhur kita, kita meminjamnya dari anak cucu.” Dan ketika kita sadar bahwa kita hanya penumpang sementara dalam perahu bernama Bumi, maka kita akan menjaga layar dan dayungnya dengan lebih bijak.
Terima kasih Ibu Siti, atas ilmu dan inspirasinya. Terima kasih panitia dan fasilitator, atas ruang belajar yang membuka mata dan hati. Saya mungkin belum bisa banyak berbuat, tapi satu hal pasti: saya tak akan lagi memandang sepele daun yang gugur, tak akan lagi mengabaikan air yang mengalir. Karena kini saya tahu, dalam setiap unsur alam, ada kehidupan yang saling terkait, dan saya adalah bagian darinya.
Dari kisahmu, Ibu Siti, saya belajar satu hal: mencintai bumi adalah bentuk cinta tertinggi, karena ia mencakup semua makhluk—yang tampak dan tak tampak, yang dekat maupun jauh, yang hidup kini dan nanti.

Jejak Langkah Sang Patriot Hijau
Penulis: Hj. Mariza SS., MM. (Lions Club Jakarta, Monas Heritage)
Di zaman ketika banyak anak muda berlari mengejar cahaya layar, terpikat gemerlap dunia digital dan kemewahan semu, ada satu sosok yang memilih jalan berbeda. Ia tak berdiri di atas panggung popularitas, tapi melangkah di antara rerimbun pepohonan dan jejak tanah yang sunyi. Ia adalah Brian—pemuda dengan jiwa seterang mentari pagi dan hati sedalam samudra yang mengemban satu misi agung: menyelamatkan bumi.
Saya menyimak kisahnya dalam video yang direkomendasikan, memperhatikan tiap detail dalam portofolio, serta menyelami energi dan ketulusan dalam setiap rekaman dokumentasi yang dibagikan. Dan sebagai peserta awam yang belum sepenuhnya memahami ilmu lingkungan, saya tidak hanya tercengang—saya tersentuh. Bukan oleh retorika, tetapi oleh keteladanan. Bukan oleh pencapaian semata, tetapi oleh pengorbanan yang nyata.
Brian bukan sekadar narasumber. Ia adalah mata air yang memancar di tengah gurun keacuhan. Di balik senyumnya yang sederhana, tersembunyi semangat yang meletup seperti gunung api kesadaran. Ia berjalan tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk pohon yang ditebang tanpa ampun, untuk sungai yang dikeruhkan oleh limbah, dan untuk udara yang kian berat oleh polusi. Setiap langkahnya adalah puisi tentang cinta kepada bumi.
Pemuda ini telah mengorbankan banyak hal yang oleh generasi seusianya dianggap sebagai simbol kebebasan dan kesenangan. Ia menukar waktu remaja yang riang dengan kerja lapangan yang melelahkan. Ia mengganti pesta malam dengan diskusi tentang pelestarian hayati. Ia membangun ekosistem, bukan ego. Dan semua itu ia lakukan tanpa mengeluh, karena bagi Brian, mencintai bumi bukanlah pilihan—itu adalah takdir yang ia peluk erat.
Saya teringat pada pandangan filsuf Stoik, Marcus Aurelius, yang pernah berkata bahwa hidup terbaik adalah hidup yang selaras dengan alam. Brian adalah contoh nyata dari pandangan itu. Ia tidak melawan arus demi pujian, tetapi karena jiwanya tahu: kehancuran lingkungan adalah kehancuran kemanusiaan. Bahwa bumi yang luka akan melahirkan generasi yang kehilangan arah.
Dalam video yang saya tonton, saya menyaksikan semangat yang tak dibuat-buat. Brian berbicara seperti akar bicara pada tanah—jujur, mendalam, dan menghidupi. Ia bukan sekadar membawa data dan presentasi; ia membawa pengalaman, keberanian, dan ketulusan. Ia tidak hanya berbicara tentang solusi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi itu sendiri.
Sebagai peserta yang masih belajar, saya merasa tersiram hujan kesadaran. Brian mengingatkan saya bahwa bumi bukanlah sesuatu yang berada di luar diri kita. Ia adalah bagian dari napas kita, dari denyut nadi kita. Ketika kita melukai alam, sejatinya kita sedang melukai diri sendiri.
Tindakan-tindakan yang dilakukan Brian—mulai dari edukasi lingkungan, pelestarian kawasan konservasi, hingga inisiatif berbasis masyarakat—adalah bentuk patriotisme sejati. Ia mungkin tak memanggul senjata, tapi ia berperang melawan ketidakpedulian. Ia mungkin tak berdiri di depan istana, tapi suaranya menggema hingga akar-akar desa dan pelosok hutan. Ia adalah patriot hijau—pahlawan yang tidak menuntut gelar, tapi meninggalkan jejak perubahan.
Saya meyakini bahwa sosok seperti Brian adalah cermin bagi generasi muda. Cermin yang jernih, yang memantulkan bahwa keberanian tak selalu tentang keras kepala, tapi tentang kelembutan hati yang terus bertahan untuk hal yang diyakini benar. Bahwa menjadi muda bukan hanya tentang mengejar mimpi pribadi, tetapi juga menjaga mimpi bumi agar tak pudar dalam kabut krisis iklim dan kerusakan ekologis.
Filsuf Prancis, Pierre Teilhard de Chardin, pernah menulis bahwa kita bukan makhluk bumi yang mengalami pengalaman spiritual, melainkan makhluk spiritual yang mengalami pengalaman bumi. Dan Brian, dalam sikap dan tindakannya, menjelma sebagai jembatan antara langit dan tanah. Ia menjadikan spiritualitasnya sebagai laku nyata: mencintai tanah, merawat air, menyapa angin, dan menghidupi api semangat yang tak padam.
Saya berharap semakin banyak pemuda yang meneladani semangat Brian. Karena bumi ini tidak hanya butuh ilmuwan dan aktivis, tetapi juga butuh keberanian dari setiap anak muda untuk mengambil bagian. Kita mungkin tak bisa menjadi Brian, tapi kita bisa menjadi cahaya kecil yang ikut menyinari jalan perjuangan.
Terima kasih kepada seluruh penyelenggara dan komunitas Penulis Indonesia yang telah membuka ruang ini, memperkenalkan kami pada kisah pemuda luar biasa ini. Terima kasih, Brian, atas ketulusanmu. Engkau bukan hanya menyelamatkan lingkungan—engkau menyelamatkan harapan kami pada generasi ini.
Kini, saya melangkah dengan kesadaran baru. Bahwa menjaga bumi bukan lagi sekadar slogan. Ia adalah jalan hidup. Dan saya, dari titik ini, ingin turut melangkah—meski pelan, asal pasti. Karena bumi ini terlalu indah untuk dibiarkan hancur, dan masa depan terlalu berharga untuk tidak diperjuangkan.

Jejak Sang Penjaga Bumi
Penulis: Hj. Mariza SS., MM. (Lions Club Jakarta, Monas Heritage)
Di tengah riuh dunia yang makin ramai oleh ambisi dan kebisingan pembangunan, saya menemukan seberkas cahaya yang merayap perlahan ke dalam kesadaran saya—melalui rekaman sederhana, melalui suara yang tak digemakan oleh panggung besar, namun mengetuk hati dengan denting paling dalam. Cahaya itu bernama Pak Misman.
Seperti akar pohon yang diam-diam menembus batu demi mencari air kehidupan, demikianlah perjuangan beliau. Tak bersuara lantang, tapi mengguncang fondasi pemikiran saya tentang apa arti menjadi manusia sejati di tengah semesta yang terluka.
Saya, hanyalah peserta awam dalam hal ilmu lingkungan. Sebelumnya, mungkin saya mengira bahwa menjaga bumi hanyalah tugas para ahli, para pemangku kebijakan, atau barisan aktivis yang turun ke jalan dengan spanduk dan pekik perubahan. Namun setelah menyimak kisah Pak Misman, saya sadar: menjaga bumi bukanlah sekadar ilmu, tapi panggilan jiwa. Sebuah bentuk cinta paling murni, tanpa syarat dan tanpa pamrih.
Dari video dan dokumentasi yang saya saksikan, saya melihat bukan hanya seorang pria paruh baya berbaju sederhana. Saya melihat hutan yang menangis di matanya, sungai yang mengalir di urat nadinya, dan langit yang teduh bersemayam di suaranya. Beliau adalah satu dari sedikit manusia yang rela menukar kenyamanan hidupnya demi menjaga denyut kehidupan bumi yang mulai sekarat. Kalpataru yang beliau terima bukan sekadar penghargaan—itu adalah simbol pohon kehidupan yang tumbuh dari tetesan keringat dan air mata.
Pak Misman mengajarkan bahwa mencintai alam tak bisa dibatasi oleh gelar atau jabatan. Ia adalah soal keterhubungan, kesadaran bahwa tanah yang kita injak bukanlah milik kita semata, melainkan warisan bagi anak cucu dan bagian tak terpisahkan dari semesta. Beliau bukan hanya menjaga hutan dan air, tetapi juga menjaga harapan, menjaga keseimbangan, menjaga makna hidup.
Filsuf Yunani kuno, Herakleitos, pernah berkata bahwa alam semesta ini adalah satu kesatuan abadi yang terus berubah, namun dalam perubahan itu ada keharmonisan. Dan saya melihat harmoni itu ada dalam setiap langkah Pak Misman. Ia berjalan melawan arus zaman, saat banyak orang berlomba membangun gedung tinggi, ia memilih menanam pohon. Saat banyak orang membangun peradaban yang menggerus alam, ia membangun cinta yang sunyi dan gigih kepada bumi.
Saya tertegun ketika beliau menceritakan bagaimana ia kehilangan kesempatan pribadi demi menyelamatkan lingkungan. Betapa banyak hal yang beliau korbankan—waktu, harta, bahkan mungkin kasih sayang orang terdekat—demi sebuah perjuangan yang tak semua orang mengerti. Namun dari pengorbanan itulah, lahir jejak-jejak yang kini bisa kita ikuti. Ia adalah tapak kaki di tanah basah, yang menunjukkan bahwa jalan cinta kepada bumi memang tak selalu mudah, namun sangat layak untuk dilalui.
Sebagai peserta kelas ini, saya merasa seolah telah membuka jendela baru dalam cara saya memandang hidup. Alam bukanlah benda mati. Ia hidup, bernapas, merasa. Ia mendengar setiap langkah kita, merasakan setiap luka yang kita goreskan. Dan kini saya menyadari, setiap plastik yang saya buang sembarangan, setiap air yang saya sia-siakan, adalah bisikan duka bagi bumi yang telah begitu sabar memeluk kita.
Saya teringat pada pepatah suku Dayak yang pernah saya baca: “Hutan adalah ibu kami. Jika ia mati, kami pun akan mati.” Kalimat itu kini terasa begitu nyata. Di tengah gempuran perubahan iklim, banjir, polusi, dan bencana yang kian sering menyapa, kisah seperti perjuangan Pak Misman adalah kompas moral yang patut kita genggam erat. Di dunia yang kehilangan arah, beliau adalah penunjuk jalan.
Terima kasih kepada Yayasan Naula Hipatia Averrous dan Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan yang telah menghadirkan sesi luar biasa ini. Kelas ini bukan hanya tempat berbagi ilmu, tapi juga ruang perenungan tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita bukan penguasa atas alam ini. Kita hanyalah bagian kecil dari harmoni agung yang diciptakan semesta.
Kini saya tahu, bahwa mencintai bumi bisa dimulai dari hal paling sederhana—dari menyimak kisah orang-orang yang telah lebih dulu menanam kebaikan, seperti Pak Misman. Dari membuka mata, hati, dan pikiran, lalu perlahan berani menapaki jejak yang sama: menjadi penjaga, bukan perusak. Menjadi pengasuh, bukan penjarah.
Semoga semakin banyak orang yang terinspirasi. Semoga kisah beliau tak hanya berhenti sebagai dokumentasi, tetapi tumbuh menjadi benih kesadaran baru di hati kita semua. Sebab bumi tak butuh banyak kata. Ia butuh aksi nyata. Dan saya, dari titik ini, berjanji akan memulainya—meski dari langkah kecil. Karena seperti kata filsuf Lao Tzu: “Perjalanan seribu mil dimulai dari satu langkah kecil.”
Dan langkah itu, hari ini, dimulai dari menyimak dan mengapresiasi perjuangan seorang lelaki sederhana yang hatinya lebih luas dari hutan mana pun di dunia ini: Pak Misman, sang penjaga bumi.
Bionarasi:
Mariza, perempuan, ibu rumah tangga, 62 tahun. Selama pandemi Covid 19, Agustus 2020-2025 sudah mendaki 34 gunung hingga puncaknya. Gunung dengan ketinggian rata-rata di atas 3000 mdpl, di Sumatera, Selat Sunda, Borneo, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Eropa, New Zealand. Total 40 gunung (ada gunung yang sama via jalur berbeda). Mariza bukan pendaki gunung sejak muda, baru mulai mendaki gunung di usia menjelang 50 tahun. Melihat sampah yang dihasilkan pendaki gunung luar biasa banyaknya. Kerusakan alam telah terjadi di gunung-gunung nusantara. Pendidikan: Sarjana Sastra Universitas Indonesia Prodi Sinologi (lulus 1987). Magister Manajemen Universitas Indonesia Jurusan Manajemen Internasional (lulus 1991). Memiliki beberapa sertifikasi bidang lainnya.

Merawat Bumi, Merawat Peradaban
Penulis : Aprinalistria, S.Psi., S.Fil., M.Pd., CHRP Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan – Universitas Muhammadiyah Bogor Raya
Pada tanggal 17 Mei 2025, dalam rangkaian Short Course Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch #4 yang diadakan oleh Asosiasi Pusat Studi Kalimantan (APSK), saya berkesempatan menyimak kisah perjuangan lapangan Ibu Dr. Ir. Siti Maimunnah, S.Hut., M.P., IPU, ASEAN Eng. Beliau adalah sosok perempuan tangguh di balik berbagai inisiatif konservasi hutan dan lahan gambut Indonesia, sekaligus aktivis lingkungan yang membumikan nilai-nilai keberlanjutan melalui kolaborasi lintas sektor dan nilai spiritualitas.
Menjawab Tantangan: Konservasi dalam Ketegangan Sosial-Budaya
Tidak semua jalan mulus. Ketika mendekati komunitas tertentu yang berlatar agama non-Muslim, istilah “konservasi” justru menjadi pemicu penolakan. Tetapi, alih-alih mundur, Ibu Maimunnah membalikkan pendekatan. Ia mengganti narasi, bukan misinya. Dengan mengamati kebutuhan lokal, beliau menemukan solusi cerdas: pemanfaatan getah damar dari pohon meranti yang hanya diambil saat rontok, tanpa melukai pohonnya. Solusi ini tidak hanya melestarikan hutan, tetapi juga menciptakan ekonomi alternatif yang adil dan berkelanjutan.
Beliau bahkan berperan sebagai tengkulak damar untuk masyarakat—sebuah contoh nyata transformasi sosial melalui empati dan keteladanan.
Hutan sebagai Manifestasi Rahmat: Islam dan Ekologi Spiritual
Menariknya, konservasi yang dijalankan tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Di Universitas Michigan, beliau diminta menandatangani pernyataan bahwa “Islam adalah rahmatan lil alamin dalam membangun hutan.” Pernyataan ini seolah mewakili semangat Ibu Maimunnah bahwa ajaran Islam mendorong perdamaian dengan alam, bukan eksploitasi. Ini menunjukkan bahwa ekologi spiritual adalah jembatan yang kuat untuk gerakan lingkungan lintas budaya.
Dari Bawah ke Atas: Suara Masyarakat sebagai Fondasi Kebijakan
Salah satu kekuatan besar beliau adalah kemampuan menyuarakan aspirasi masyarakat akar rumput ke meja kebijakan. Saat kebakaran besar melanda Kalimantan Tengah tahun 2015, masyarakat dan pemerintah bertanya-tanya mengapa hutan yang dikelola oleh beliau tidak ikut terbakar. Jawabannya sederhana tapi revolusioner: masyarakat dilibatkan sebagai penjaga, bukan dituding sebagai perusak.
Kuncinya adalah pendidikan dan pengakuan akan nilai ekonomi dari menjaga hutan—yang disebut beliau sebagai livelyhood approach. Ketika masyarakat sadar bahwa mereka bisa makan dari hutan tanpa harus merusaknya, maka mereka akan menjadi pelindung terkuat hutan itu sendiri.
Teknologi, Kearifan, dan Semangat Tak Kenal Lelah
Ibu Maimunnah tidak hanya mengandalkan pendekatan sosial. Inovasi teknologi juga menjadi bagian dari restorasi lahan gambut. Melalui metode aerial seeding, benih ditabur dari helikopter ke lahan gambut yang tak bisa diinjak. Bahkan, benih dirakit dalam bentuk bom benih yang akan meledak ringan dan menyebar secara alami. Teknik ini tidak hanya cerdas, tetapi juga adaptif terhadap kondisi ekologis ekstrem.
Namun, teknologi tidak akan bermakna tanpa kegigihan. “Saya menikmati segala kesusahan di lapangan,” ucap beliau. Sebuah pengakuan tulus dari seseorang yang menjadikan tantangan sebagai bentuk syukur dan medan amal.
Integrasi Lintas Sektor: Dari Sawit, Tambang hingga USAID
Pendampingan masyarakat tidak berhenti pada ekosistem alam, tetapi merambah ke sektor industri. Dalam kerja sama dengan perusahaan tambang, beliau memastikan adanya area bernilai konservasi tinggi (HCVF) yang dilindungi. Ia menjadi penghubung antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, agar keberlanjutan bukan sekadar jargon, tetapi praktik nyata.
Dalam konteks keterlanjuran sawit, masyarakat yang sudah terlanjur menanam sawit tidak dimarahi, melainkan diedukasi untuk merestorasi dengan menanam tanaman lokal seperti nangka. Pendekatan non-konfrontatif ini berhasil mengubah pola pikir: dari eksploitasi menjadi konservasi yang produktif.
Pendidikan Karbon dan Pelatihan Hidroponik: Masyarakat sebagai Ilmuwan Lokal
Melalui kerja sama dengan USAID, masyarakat diajarkan menghitung potensi karbon di wilayah hutan yang mereka kelola. Hasilnya mengejutkan: dari 2 miliar ton potensi karbon, masyarakat hanya menghitung 500 juta. Edukasi ini membuktikan bahwa jika diberi ilmu, masyarakat bisa menjadi ilmuwan lokal yang cakap dan mandiri dalam pengelolaan sumber daya.
Tak hanya itu, pelatihan hidroponik juga dilakukan sebagai alternatif penghidupan yang berkelanjutan—membuka peluang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap lahan yang rawan rusak.
Dedikasi yang Tulus: Ilmu, Pengabdian, dan Pahala
“Apakah ada uangnya?” tanya banyak orang. “Tidak ada,” jawab beliau jujur. Tapi justru di situlah letak keberkahan. Dengan melakukan pendampingan masyarakat, beliau tidak hanya mendapat data otentik untuk jurnal ilmiah dan pengabdian masyarakat, tetapi juga kebahagiaan spiritual yang tak tergantikan.
Bagi beliau, penghargaan seperti Kalpataru bukanlah tujuan, melainkan efek samping dari niat tulus. Semua jerih payah di lapangan akan menjadi cerita indah pada waktunya. Sebab, dalam keyakinannya, rezeki bukan sekadar uang—tetapi keberkahan hidup dan manfaat yang ditinggalkan.
Penutup: Mengubah Mindset, Menguatkan Akar
Refleksi dari Ibu Dr. Ir. Siti Maimunnah memberi pelajaran penting: bahwa keberhasilan konservasi bukan hanya soal teknologi atau pendanaan, tetapi kemauan untuk mendengarkan, mendidik, dan memuliakan masyarakat. Bahwa hutan bukan hanya kumpulan pohon, melainkan ruang kehidupan yang menghidupi.
Semakin banyak yang kita lakukan dari hati, semakin besar pula manfaat yang kembali kepada kita. Maka mari kita jaga bumi, karena seperti beliau katakan, “umur bumi bergantung pada apa yang dilakukan manusia.”

Konservasi Vs. Urbanisasi: Konservator Alam Melihat Persimpangan IKN
Penulis : Eman Sukmana, S.H.I., M.Han., M.Par., CHE. (Dosen Politeknik Negeri Samarinda)
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga ujian bagi komitmen negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Bagi para pegiat konservasi seperti Brian Martin dari Yayasan Ulin Samarinda, IKN bukanlah sesuatu yang harus ditolak mentah-mentat, melainkan sebuah proyek yang harus dibangun dengan prinsip berkelanjutan dan berstandar lingkungan. Narasumber menekankan dengan tegas poin-poin penting komitmen pemerintah dalam pembangunan IKN, diantaranya:
- Dukungan dengan Syarat: Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Yayasan dan organisasi komunitas masyarakat tidak menentang kehadiran IKN, asalkan pembangunannya mematuhi prinsip-prinsip ramah lingkungan. Mereka menekankan pentingnya penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap kawasan hutan dan keanekaragaman hayati. Tanpa komitmen kuat terhadap standar lingkungan, IKN justru berisiko menjadi ancaman baru bagi ekosistem Kalimantan yang sudah rentan.
- Koridor Fauna Endemik: Menjaga Jejak Migrasi Satwa Liar
Salah satu poin kritis yang harus diperhatikan dalam pembangunan IKN adalah perlindungan terhadap fauna endemik Kalimantan, seperti orangutan, bekantan, dan beruang madu. Sesuai dengan yang termaktub di dalam dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045, koridor satwa harus menjadi prioritas untuk memastikan hewan-hewan tersebut tetap dapat bermigrasi mencari makanan dan menghindari fragmentasi habitat. Tanpa koridor yang memadai, urbanisasi akan memutus rantai ekologis dan mempercepat kepunahan spesies langka.
- Identifikasi Kawasan Hutan: Mitigasi Dampak Ekologis
Sebelum pembangunan masif dilakukan, perlu upaya serius untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kawasan hutan di sekitar IKN. Pemetaan ini penting untuk menentukan zona-zona yang boleh dikembangkan dan area yang harus dilindungi. Dengan begitu, dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, erosi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, dapat diminimalisir. Pendekatan berbasis sains harus menjadi landasan setiap keputusan pembangunan.
- Gerakan Generasi Muda: Edukasi dan Aksi Nyata
Selain kebijakan struktural, peran generasi muda dalam konservasi lingkungan juga krusial. Gerakan-gerakan kreatif seperti lomba fotografi alam, videografi dokumenter, atau kampanye digital bisa menjadi sarana edukasi yang efektif. Dengan melibatkan anak muda dalam event berwawasan lingkungan, kesadaran akan pentingnya konservasi akan tumbuh, sekaligus menciptakan tekanan sosial agar pembangunan IKN tetap mempertimbangkan aspek ekologi.
Oleh karena itu, pembangunan IKN tidak harus menjadi pertarungan antara konservasi dan urbanisasi. Keduanya bisa berjalan beriringan jika ada komitmen kuat untuk memadukan kemajuan infrastruktur dengan perlindungan lingkungan. Para konservator tidak anti-pembangunan, tetapi mereka ingin memastikan bahwa kemajuan itu tidak mengorbankan masa depan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia.

Isu Ekosistem dan Budaya
Penulis : Aprinalistria, S.Psi, S. Fil, M. Pd, CHRP (Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan) Universitas Muhammadiyah Bogor Raya
Dalam momen istimewa ini, saya merasa bangga dapat berbagi pengalaman serta pandangan mengenai upaya pelestarian alam, khususnya dalam konteks menjaga keberlanjutan lingkungan hidup kita. Melalui kegiatan Shortcourse Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch 4 yang mengangkat tema “Peran Konservator Alam untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”, yang diselenggarakan pada Sabtu, 10 Mei 2025, saya ingin menekankan betapa pentingnya kontribusi kita sebagai penjaga alam dalam menghadapi tantangan serius yang mengancam planet ini.
Salah satu sosok yang memberikan banyak inspirasi dalam bidang konservasi lingkungan adalah Brian Martin, seorang pejuang lingkungan yang telah mendedikasikan dirinya melalui Yayasan Ulin.
Brian Martin, melalui Yayasan Ulin, dikenal mengkritisi bagaimana sains dan teknologi sering kali dimanfaatkan bukan demi kepentingan masyarakat luas, melainkan demi kepentingan industri atau kekuasaan. Ia menyuarakan pentingnya “sains partisipatif”, di mana masyarakat memiliki suara dalam menentukan bagaimana pengetahuan dan teknologi digunakan.
Dari perspektif Brian Martin, fenomena seperti porang bisa dianalisis sebagai berikut:
- Modal industri mengubah persepsi: Sesuatu yang sebelumnya dianggap tak berguna atau bahkan berbahaya bisa jadi “bernilai” jika ada kepentingan industri.
- Siapa yang mendapat manfaat? Apakah petani lokal mendapat keuntungan maksimal dari porang, ataukah justru korporasi besar yang menguasai teknologi dan pasarnya?
- Peran pengetahuan lokal vs pengetahuan ilmiah: Petani lokal sudah lama mengenal porang, tapi baru dianggap “bernilai” setelah masuk ke radar industri dan akademisi.
Refleksi Kritis
Brian Martin akan mendorong kita untuk berpikir:
- Apakah industrialisasi porang benar-benar memberdayakan masyarakat lokal?
- Siapa yang menentukan nilai suatu tanaman—masyarakat, pasar, atau ilmuwan?
- Bagaimana kita bisa memastikan bahwa sains dan industri tidak merampas, melainkan memberdayakan masyarakat akar rumput?
Pemanfaatan Modal Industri: Studi Kasus Porang dan Pendekatan Yayasan Ulin oleh Brian Martin
Porang, tanaman umbi yang dulunya dianggap tidak berguna bahkan beracun, kini berhasil dikembangkan menjadi komoditas industri yang bernilai tinggi. Perubahan ini terjadi berkat pendekatan yang tepat dalam memanfaatkan potensi lokal menjadi produk ekspor dan bahan baku industri pangan serta kosmetik. Menurut Brian Martin dari Yayasan Ulin, potensi industri seperti ini muncul dari pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal dan proses ilmiah yang bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap sumber daya alam.
Contoh porang menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna dapat menjadi aset ekonomi, selama ada upaya pemberdayaan, riset, dan akses pasar. Yayasan Ulin mendukung transformasi seperti ini sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi hijau berbasis komunitas.
Bisnis Berkelanjutan dan Diversifikasi Kredit Ekologis
Dalam konteks bisnis berkelanjutan, pemanfaatan jasa lingkungan menjadi strategi utama. Jasa-jasa ini mencakup wisata alam, pemanfaatan air dan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, serta pengelolaan karbon. Salah satu contohnya adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), di mana misalnya jika ada kegiatan penanaman kembali di lahan seluas 10 hektare, maka bisa dilakukan offset dengan menanam di lahan lain sebagai bentuk kompensasi ekologis.
Menurut Brian Martin dari Yayasan Ulin, pendekatan seperti ini mendukung konsep diversifikasi ekonomi berbasis ekosistem. Melalui skema seperti carbon credit dan jasa lingkungan lainnya, komunitas lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis wilayah mereka.
Respon Budaya terhadap Ekosistem: Studi Kasus Papua dan Flores
Budaya Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan alam sekitarnya. Di Papua, burung cenderawasih bukan hanya fauna endemik yang indah, tetapi juga memiliki peran penting dalam upacara adat dan simbol kehormatan. Aturan adat mengatur siapa yang boleh menggunakan bulu burung tersebut, mencerminkan upaya konservasi berbasis budaya.
Sementara itu di Flores, gading gajah menjadi simbol penting dalam prosesi lamaran. Meskipun tidak ada populasi gajah di wilayah tersebut, masyarakat tetap mempertahankan tradisi dengan mendatangkan gading dari pedagang India sejak masa lalu. Ini menunjukkan bahwa budaya bisa beradaptasi dan membentuk jaringan perdagangan lintas budaya untuk memenuhi nilai simbolik. Fenomena ini membuka peluang untuk mengembangkan inovasi budaya yang berkelanjutan. Misalnya, pembuatan replika gading secara etis atau produksi hiasan kepala adat dari bahan sintetis bisa menjaga nilai budaya tanpa merusak alam. Budaya dapat menjadi media konservasi, sekaligus basis ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
Jasa Lingkungan
Konsep bisnis berkelanjutan yang memanfaatkan jasa lingkungan seperti wisata alam, energi terbarukan (air, matahari, angin, panas bumi), dan diversity credit (kredit keanekaragaman hayati) adalah bentuk ekonomi baru yang muncul dari nilai ekologis suatu wilayah. Salah satu contohnya adalah program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), di mana penanaman kembali pohon di satu lokasi dapat dikompensasikan dengan menanam di lokasi lain (misalnya: menebang 10 hektar, mengganti dengan tanam 10 hektar di tempat lain). Dari perspektif Brian Martin dan pendekatan kritis Yayasan Ulin, ini dapat dianalisis lebih dalam:
- Komodifikasi Alam
Menurut Brian Martin, ketika alam diberi nilai ekonomi—misalnya hutan dihargai karena menyerap karbon, atau air sungai dianggap “layak jual”—maka alam tidak lagi dilihat sebagai warisan bersama, melainkan sebagai aset yang bisa diperdagangkan. Misalnya:
Kredit karbon: Perusahaan besar tetap mencemari, lalu menebus dosa lingkungan dengan membeli kredit dari proyek RHL. Diversity credit: Mengganti keanekaragaman hayati yang rusak di satu tempat dengan ‘melestarikan’ di tempat lain—padahal tiap ekosistem unik.
- Ilusi Penggantian (offset)
Contoh: “Menebang 10 hektar, menanam 10 hektar di tempat lain.” Ini seolah setara, tapi bagi aktivis lingkungan: Pohon tua 100 tahun tidak sama nilainya dengan pohon baru umur 1 tahun. Ekosistem rusak tidak bisa sepenuhnya diganti hanya dengan kuantitas pohon baru.
- Ketimpangan Kuasa
Sering kali bisnis berkelanjutan dijalankan oleh korporasi atau lembaga besar dengan modal besar, bukan oleh komunitas lokal. Brian Martin menyoroti bahwa: Masyarakat adat atau lokal kadang justru disingkirkan demi proyek “hijau”. Ada “greenwashing”—proyek berlabel hijau tapi sebenarnya menguntungkan elite.
Apa yang Diusulkan dari Perspektif Yayasan Ulin?
Yayasan Ulin, dengan semangat sains partisipatif dan keadilan ekologis, akan mendorong:
- Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan proyek RHL, wisata alam, atau energi terbarukan.
- Pengakuan terhadap pengetahuan lokal—tidak hanya sains barat modern yang dijadikan patokan.
- Evaluasi kritis terhadap sistem offset—apakah benar menggantikan kerusakan atau hanya mempermanis kerugian lingkungan?
- Model bisnis kooperatif atau komunitas yang membagi hasil secara adil dan berkelanjutan.
Daftar Satwa Dilindungi di Indonesia: Konteks Konservasi dan Hukum
Indonesia memiliki daftar resmi spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Beberapa contoh satwa yang termasuk dalam daftar tersebut meliputi:
- Mamalia: Orangutan (Pongo spp.), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
- Burung: Cenderawasih (Paradisaea spp.), Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), Jalak Bali (Leucopsar rothschildi).
- Reptil: Komodo (Varanus komodoensis), Penyu Hijau (Chelonia mydas).
- Amfibi: Beberapa spesies katak endemik Indonesia.
- Ikan dan Biota Laut: Coelacanth (Latimeria menadoensis), Kuda Laut (Hippocampus spp.).
Kriteria perlindungan meliputi populasi yang terancam punah, endemisme, serta nilai ekologis dan budaya. Pelanggaran terhadap perlindungan ini dikenai sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta. Masyarakat, terutama yang hidup berdampingan dengan alam, perlu diedukasi mengenai pentingnya konservasi ini, baik melalui kurikulum, pelatihan, maupun regulasi berbasis komunitas.
Terima kasih kepada Asosiasi Pusat Studi Kalimantan (APSK) yang telah mengadakan acara ini dan kepada semua peserta yang telah hadir. Mari bersama-sama kita terus menjaga alam untuk masa depan yang berkelanjutan. Terutama kepada Brian Martin yang telah menginspirasi banyak pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semoga acara ini dapat menambah wawasan dan mendorong lebih banyak orang untuk ikut serta dalam gerakan konservasi demi masa depan yang berkelanjutan.


Kalimantan Tengah- Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK Official) menggelar Podcast Averrous dengan Tema “ From Lokal ke Global: lolos PPAN, wujudkan mimpi”. Selasa, 6 Mei 2025
Dengan Menghadirkan narasumber, yang inspiratif yang merupakan ketua PCMI (Purna Caraka Muda Indonesia), dan narasumber juga alumni PPAN tahun 2019 ke Korea Selatan. Narasumber bernama Destri Ayu Angela merupakan putri daerah Kalimantan Tengah berasal dari Kabupaten Gunung Mas. Podcast dipandu dengan host Muhammad Raihan. (Researcher’s – Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan)
Narasumber menceritakan kegiatannya selama melaksanakan PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) di Korea Selatan selama 1 bulan. Selama di Korea Selatan narasumber belajar tentang teknologi, dan mengetahui kenapa negara Korea Selatan bisa semaju itu padahal negara yg usianya tergolong muda dan lebih kecil dibandigkan negara Indonesia. Di Korea Selatan juga mengunjungi perusahaan handphone samsung untuk melihat cara pembuatannya. Setelah dari perusahan samsung juga menuju ke pabrik mobil yang terkenal dari Korea Selatan yaitu nissan yang pekerjaannya dibuat oleh robot menggantikan manusia dalam pembuatannya.
Narasumber menambahkan selama disana juga memperlajari budaya Korea dengan mendatangi 6 Provinsi, seperti Seoul, Busan dan lain-lain. selama PPAN dibawa ke tempat yg jarang tersorot oleh media, untuk mempelajari kultur dan kebisaan orang lokal serta mempelajari tentang kerasnya pendidikan di korea. Belajar formal dan belajar informal. Di Korea Selatan banyak orang bunuh diri karena stress karna tuntutan dalam pendidikan karna jika nilai jelek maka tidak bisa untuk masuk ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Sampai di bawah jembatan ada patroli guna menanggulangi bunuh diri yang tinggi.
Narasumber menyampaikan urgensi untuk semuanya.”J angan takut mengambil langkah untuk mengubah masa depan. Dan jangan melewatkan kesempatan.”
Dr. Naufal Kurniawan selaku Pembina Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK Official) mewakili Direktur APSK, tak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada narasumber, team, atas partisipasi tetap semangat dalam edukasi mencerdaskan bangsa. Dalam kesempatan yang berlangsung juga menyampaikan menyelenggarakan podcast tersebut adalah untuk meningkatkan minat kepada pemuda dengan adanya PPAN dalam hal mempelajari kultur budaya, dan perkembangan negara tersebut. Tutupnya Pembina APSK Official.
Penulis : Nugroho (Researcher’s – Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan)
Silahkan simak di @podcastaverrous


Kalimantan Tengah- Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK Offcial) menggelar Podcast Averrous dengan Tema “Menjadi Muslim Dengan Keberagaman Di Asia Tenggara” Minggu, 27 April 2025
Dengan Menghadirkan narasumber mahasiswa internasional yang berkuliah di Indonesia, narasumber berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, dengan 3 narasumber yaitu, Taufiq Muya, Marwan Maming, dan Burhan Yangoh yang berasal dari Thailand. Dengan host Fanisa Nuraziza dan co host Akrom Baneng (Researcher’s – Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan).
Banyak pertanyaan yang di utarakan oleh host dan co host. Narasumber Burhan Yangoh menjawab pertanyaan tersebut. “Di sana tradisi yang unik adalah makanan ketupat hari raya yang berbentuk seperti segi tiga, setelah itu apabila hari raya idul fitri, pada tanggal 1,2,3 dan 4 bulan syawal ada satu majlis di sebut dengan melayu raya. Di tanggal 3 syawal semua pemuda itu berkumpul di pantai teluban menggunakan baju adat melayu dan tanjak. Di 4 syawal adalah perhimpunan pemudi.”
Dan narasumber Burhan Yangoh menambahkan “bahwa disana mempunyai tradisi membuat pintu gerbang untuk menyambut hari raya, dan dibuat sebelum bulan ramadhan sampai selesai bulan ramadhan, disaat hari raya tiba mereka akan berfoto beramai-ramai. Dan pintu gerbang itu di lombakan, sebagai menunjukan sebagai seni dari setiap kampung tetapi setiap pintu gerbang terebut memiliki berbagai makna.
Narasumber menyampaikan bahwa “ mereka memutuskan kuliah di Indonesia karna mereka ingin menjalankan hukum-hukum syar’i untuk diterapkan di tempat mereka tinggal seperti tentang halal dan haramnya suatu makanan, pernikahan, dan lain-lain.
Dr. Naufal Kurniawan selaku Pembina Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK Official) tak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada narasumber, team, atas partisipasi tetap semangat dalam edukasi mencerdaskan bangsa. Dalam kesempatan yang berlangsung juga menyampaikan menyelenggarakan podcast tersebut selain silahturahhmi juga sebagai pengetahuan agar kita bisa mengetahui bagimana muslim dalam keberagaman yang berada di Asia Tenggara. Tutupnya Pembina APSK Official
Penulis : Nugroho (Researcher’s – Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan)
Silahkan simak di @podcastaverrous


Kalimantan Tengah – Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK Official) menggelar Averrous Podcast “Zero to Hero” dalam rangka Dalam Rangka Hari Kehutanan Sedunia (20 Maret 2025) dan Hari Women International /WIC (27 Maret 2025) Minggu, 16 Maret 2025.
Dengan menghadirkan narasumber, Dr.Ir. Siti Maimunah, S.Hut.,MP, IPU, ASEAN Eng. (Penerima Penghargaan Champion Asia Pacific Forest 2019 dari FAO, Sang Pelopor Hutan Pendidikan, Penerima Penghargaan Kategori Perintis Lingkungan ( TAHUN 2017) Penerima Penghargaan Kategori Pembina Lingkungan (TAHUN 2019) didampingi oleh Host M. Nafis dan Co-Host Fanisa Nur Azizah (Researcher’s – Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan).
Dr. Ir. Siti Maimunah, S.Hut.,MP, IPU, ASEAN Eng. Menyampaikan urgensinya keterlibatan anak muda dalam menjaga alam, dan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. jika alam tidak di jaga maka bencana akan silih berganti korbannya akan manusia itu sendiri
“Peran masyarakat dan pemuda sangat penting untuk melestarikan alam, jika alam tidak di jaga maka bencana akan silih berganti korbannya akan manusia itu sendiri. Serta Kalimantan sebagai paru-paru dunia menjadi penting perannya untuk tetap lestari berkelanjutan” ujar Dr.Ir. Siti Maimunah
Dr. Naufal Kurniawan selaku Pembina Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK Official) tak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada narasumber, team, atas partisipasi tetap semangat dalam edukasi mencerdaskan bangsa. Dalam kesempatan yang berlangsung juga menyampaikan pentingnya peran pentahelix dalam merawat dan menjaga alam semesta. Tutupnya Pembina APSK Official
Penulis : Nugroho (Researcher APSK Official)
Silahkan simak di @podcastaverrous
Podcast Averrous -Dr.Ir. Siti Maimunah, S.Hut.,MP, IPU, ASEAN Eng.(Champion Asia Pacific Forest2019)

Gerakan Transformasi Ekologis yang Menginspirasi
Oleh : Eman Sukmana, S.H.I., M.Han., M.Par., CHE. (Politeknik Negeri Samarinda)
Kesempatan emas dapat mengikuti sebuah forum yang menginspirasi kesadaran lingkungan, yaitu Shortcourse Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch 4 oleh Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK). Bagaimana tidak pertemuan pertama saja sudah diperkenalkan dengan sosok yang luar biasa, peraih penghargaan Kalpataru di level daerah dan nasional. Beliau adalah Pak Misman, seorang penggagas dan founder Sekolah Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Jauh di atas penghargaan yang beliau peroleh, ada kesadaran dan tanggung jawab yang direalisasikan menjadi gerakan restorisasi di sepanjang kawasan Sungai Karang Mumus yang awalnya hanya menjadi “comberan” limbah domestik masyarakat ibu kota provinsi yang terpilih menjadi daerah ibu kota negara yang baru. Di sepanjang tepian Sungai Karang Mumus yang dulu suram, kini terhampar pemandangan penuh harapan.
Di sepanjang menit diskusi, saya melihat Pak Misman selalu mencoba untuk menawarkan sebuah pendekatan untuk merestorasi sekaligus mengonservasi kawasan Sungai Karang Mumus, melalui kesadaran lingkungan sebagai inti kehidupan manusia, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan edukasi pelajar termasuk mahasiswa. Pendekatan ini terlihat seperti kolaborasi yang sedang dibangun untuk menemukan model keberlanjutan estafet gerakan ini agar tidak terlupakan oleh gaya hidup manusia yang abai terhadap lingkungan.
Pak Misman selalu menekan tentang perbedaan yang menonjol antara human centris dan environment centris yang akan menghasilkan dampak dan konsekuensi yang berbeda dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, memusatkan perhatian pada lingkungan sebagai inti kehidupan manusia akan memberikan peluang keberlanjutan ekosistem yang bermanfaat tanpa harus mengorbankan kebutuhan hidup manusia. Sebaliknya, jika manusia yang dijadikan sebagai pusat kehidupan, maka bisa jadi lingkungan dan ekosistem di sekitarnya akan dikorbankan. Karena keinginan akan lebih besar dari kebutuhan, sebagaimana menjamurnya fenomena tambang-tambang ilegal di Kalimantan Timur yang meninggalkan lubang kehancuran.
Beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Pak Misman, yaitu :
Di jantung Kalimantan Timur, Sungai Karang Mumus perlahan namun pasti bangkit dari keterpurukan, berkat pendekatan restorasi setidaknya tiga pilar yang menyatukan ekosistem, daur ulang, dan pemurnian air dalam satu tarikan napas yang digagas oleh Pak Misman dan Sekolah Sungainya. Pilar pertama, pemulihan ekosistem, bukan sekadar menanam pohon, melainkan menyulam kembali seluruh jaring kehidupan yang pernah terkoyak. Bayangkan ketika akar-akar pohon bungur yang kokoh merangkul tanah tepian sungai, mencegah erosi sambil menjadi rumah bagi mikroorganisme, kemudian daun-daun rengas yang rimbun menaungi permukaan air, mengatur suhu dan menjadi dapur bagi serangga air, serta ikan-ikan lokal yang mulai kembali, berenang di antara vegetasi air yang pulih, menyempurnakan siklus nutrisi yang sempat terputus. Setiap elemen dirancang saling mendukung, menciptakan simfoni ekologis dimana burung pemakan ikan, katak penjaga kualitas air, dan bakteri pengurai bekerja sama dalam keseimbangan yang rapih.
Pilar kedua menghadirkan solusi cerdas untuk masalah sampah melalui daur ulang, seperti ecobrick – sebuah alih wujud kreatif dari ancaman menjadi peluang. Plastik-plastik yang dulu mengotori sungai kini dijinakkan, dipadatkan, dan didaur ulang menjadi produk-produk yang ramah lingkungan. Pilar ketiga, pemurnian air, mengandalkan kecerdasan alam sendiri yang diperkuat dengan sentuhan teknologi tepat guna. Sistem penyaringan alami dibangun berlapis-lapis, mulai dari zona tanaman penyaring seperti eceng gondok yang menyerap logam berat, hingga bukit-bukit kecil dari batu vulkanik yang menjadi rumah bagi bakteri pengurai. Di titik tertentu, instalasi sederhana menggunakan arang aktif dan ijuk bekerja menyaring air sebelum kembali ke sungai.
Ketiga pilar ini saling bertaut seperti anyaman bambu yang semakin kuat karena saling mendukung. Upaya daur ulang akan mengurangi beban pencemaran, memberi ruang bagi ekosistem pulih, sehingga ekosistem yang sehat menyediakan lingkungan ideal bagi sistem pemurnian air bekerja optimal. Sementara air yang semakin bersih memungkinkan kehidupan akuatik berkembang, menyempurnakan rantai makanan. Ini bukan sekadar proyek lingkungan, melainkan revolusi cara pandang bahwa sungai bukan tempat pembuangan, tetapi pusat kehidupan yang layak dapat perhatian, kasih sayang, dan dedikasi dari seluruh elemen masyarakat.
Aktivitas ini bukan sekadar proyek lingkungan biasa. Ini adalah gerakan transformasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat – dari aktivis, akademisi, masyarakat, dan seharusnya juga pemerintah. Setiap tangan yang terlibat, setiap tetes keringat yang jatuh, dan setiap senyum yang mengembang, semuanya berkontribusi dalam menuliskan babak baru bagi Sungai Karang Mumus. Perlahan tapi pasti, sungai yang dulu sekarat ini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru, menjadi bukti nyata bahwa ketika manusia dan alam bekerja sama, keajaiban bisa terjadi tidak hanya di Sungai Karang Mumus, tapi pendekatan ini mungkin dapat diaplikasikan di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Seberapa Ideal Implementasi Sistem Instalasi Pengolahan Air Hujan
di Kabupaten Aceh Utara?
Oleh : Adhifatra Agussalim CIP, CIAPA, CASP, CPAM (Praktisi Internal Auditor dan media, aktif sebagai pemerhati lingkungan hidup)
Mukaddimah
Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sangat menarik materi yang disampaikan oleh Mbak Sri Wahyuningsih S.Ag dari Sekolah Air Hujan Banyu Bening Yogyakarta dengan judul paparan Air Hujan untuk Keberlangsungan Hidup pada kegiatan Short Course Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch 3 Dengan Tema Swasembada Energi dan Pangan Yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2024.
Sebelum masuk kepada pembahasan, ada baiknya kami sadur narasi mengenai isi makalah ini, seperti kita ketahui Bersama air merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan manusia. Namun, ketersediaan air bersih semakin menjadi tantangan akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya air yang tidak berkelanjutan. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mengimplementasikan sistem instalasi pengolahan air hujan (SIPAJAN). SIPAJAN ini dapat menyediakan sumber air alternatif yang berkelanjutan sekaligus membantu mengurangi dampak banjir di daerah perkotaan.
Kabupaten Aceh Utara, dengan karakteristik geografis yang beragam dan populasi yang terus bertumbuh, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya air. Permasalahan seperti keterbatasan akses air bersih, perubahan iklim, dan urbanisasi menjadi semakin nyata. Implementasi SIPAJAN menjadi salah satu solusi yang ideal dan fungsional untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, keberhasilan penerapan sistem ini perlu ditinjau dari aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Allahumma shalli alaa Muhammadin ‘abdika warasulika nabiyyil ummi wa’alaa aalihii wa sallim.
Kondisi di Kabupaten Aceh Utara
Aceh Utara memiliki curah hujan tahunan yang relatif tinggi, berkisar antara 1.500 hingga 3.000 mm per tahun. Kondisi ini memberikan potensi besar untuk memanfaatkan air hujan sebagai sumber air alternatif. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah perbukitan (Nisam, Nisam Antara), pesisir (Seunuddon, Samudera, Baktiya), dan perkotaan (Lhoksukon dan Panton Labu), yang masing-masing memiliki kebutuhan air berbeda. Di sisi lain, beberapa daerah di kabupaten ini masih kesulitan mendapatkan akses air bersih yang layak, terutama pada musim kemarau.
Prinsip Dasar Sistem Pengolahan Air Hujan
SIPAJAN bekerja dengan cara mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah air hujan agar dapat dimanfaatkan kembali. Tahapan utama dalam sistem ini, antara lain:
Pertama, harus adanya lokasi pengumpulan air hujan, air hujan dikumpulkan melalui atap bangunan atau permukaan lain yang memungkinkan. Saluran pipa diarahkan ke tangki penampungan yang dirancang untuk menampung air hujan secara efisien.
Tahap kedua, untuk penyaringan awal, sebelum masuk ke tangki utama, air hujan melewati penyaring awal untuk menghilangkan kotoran seperti dedaunan, pasir, dan partikel lainnya.
Pada tahap penyimpanan, air yang sudah disaring disimpan dalam tangki atau wadah khusus yang dilengkapi dengan sistem anti kontaminasi seperti penutup rapat dan pengaturan ventilasi.
Tahap terakhir, pengolahan lanjutan, untuk memastikan air hujan layak digunakan, pengolahan lanjutan diperlukan. Teknologi seperti penyaringan mikro, ultrafiltrasi, atau desinfeksi dengan sinar Ultraviolet (UV) atau klorin dapat diterapkan untuk memastikan kualitas air sesuai standar kesehatan.
Keidealan Implementasi Sistem Pengolahan Air Hujan
Idealnya untuk implementasi sistem ini, adanya ketersediaan sumber daya, disini tingginya curah hujan di Aceh Utara menjadikan SIPAJAN sebagai solusi yang realistis. Dengan sistem yang dirancang baik, air hujan dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik rumah tangga, irigasi, maupun industri kecil dan UMKM.
Kedua, adanya adaptasi terhadap perubahan iklim, notabenenya SIPAJAN ini berfungsi sebagai langkah adaptif dalam menghadapi dampak perubahan iklim, seperti penurunan debit sungai dan meningkatnya risiko banjir. Sistem ini membantu mengurangi limpasan air hujan yang dapat menyebabkan genangan di wilayah perkotaan.
Ketiga, sebagai pendukung infrastruktur air bersih, dalam konteks Kabupaten Aceh Utara, SIPAJAN ini dapat menjadi pelengkap bagi infrastruktur air bersih yang sudah ada. Misalnya, misalnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Pase dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kapasitas layanan mereka, untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Fungsionalitas dalam Konteks Aceh Utara
Aspek fungsionalitas juga sangat penting untuk dibahas, karena untuk pemanfaatan Rumah Tangga, air hujan yang diolah dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan menyiram tanaman. Ini sangat penting di daerah gampong (pedesaan) yang minim akses terhadap jaringan air bersih.
Selanjutnya penggunaan di bidang pertanian dan perikanan, sebagai daerah agraris, Aceh Utara sangat membutuhkan pasokan air untuk pertanian. SIPAJAN dapat menyediakan air tambahan untuk irigasi, terutama di musim kemarau, walaupun kondisi saat ini telah selesai dibangunnya waduk keuretoe.
Aspek terakhir, dukungan untuk industri local, Industri kecil dan menengah (IKM) di Aceh Utara, seperti pengolahan hasil laut dan makanan, dapat menggunakan air olahan untuk kegiatan produksi yang tidak memerlukan air dengan kualitas tinggi.
Manfaat Implementasi Sistem Pengolahan Air Hujan
SIPAJAN ini sendiri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber air tanah (sungai atau sumur bor), dengan pemanfaatan air hujan dapat mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Manfaat kedua, dapat mengatasi risiko kekurangan air bersih, SIPAJAN ini menyediakan sumber air alternatif, khususnya di daerah yang sering mengalami kekeringan atau minim akses ke air bersih.
Ketiga, manfaatnya dapat mengurangi risiko banjir seperti Kota Lhoksukon, dan Sebagian besar Kabupaten Aceh Utara wilayah tengah dan timur, dengan menangkap dan menyimpan air hujan, SIPAJAN ini membantu mengurangi limpasan air hujan yang dapat menyebabkan banjir di kawasan perkotaan. Manfaat lainya terjadinya efisiensi biaya, dalam jangka panjang, pemanfaatan air hujan dapat mengurangi biaya pembelian air bersih dari penyedia layanan publik.
Manfaat yang terakhir yang dapat kami rangkum adalah SIPAJAN ini sangat ramah lingkungan, sistem ini mendukung prinsip keberlanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.
Tantangan dan Solusi
Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi SIPAJAN ini , terutama biaya awal yang tinggi, biaya SIPAJAN bisa menjadi kendala, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Solusinya adalah melalui subsidi pemerintah atau program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) dari perusahaan-perusahaan serta diberikan insentif pemerintah, seperti subsidi atau pengurangan pajak bagi masyarakat atau perusahaan yang menerapkan SIPAJAN ini.
Kedua, adanya kualitas air yang tidak konsisten, hal ini dimungkinkan pemeliharaan yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan efisiensi sistem. Pemerintah Kabupaten atau lembaga terkait perlu menyediakan panduan teknis dan bantuan untuk memastikan keberlanjutan SIPAJAN ini. Solusinya yang dapat diterapkan dengan menggunakan teknologi pengolahan lanjutan untuk memastikan air memenuhi standar yang diperlukan.
Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat pengolahan air hujan dapat menghambat adopsi teknologi ini. Sosialisasi edukasi dan pelatihan teknis perlu dilakukan secara berkala tentang manfaat dan pentingnya SIPAJAN.
Kesimpulan
Implementasi SIPAJAN merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan air bersih di masa depan. Selain memberikan solusi atas tantangan ketersediaan air, sistem ini juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sistem ini dapat menjadi bagian penting dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Implementasi SIPAJAN di Kabupaten Aceh Utara merupakan langkah yang ideal dan fungsional untuk menjawab tantangan ketersediaan air bersih. Dengan dukungan curah hujan yang tinggi, kebutuhan masyarakat yang beragam, serta potensi dampak positif terhadap lingkungan dan ekonomi, sistem ini memiliki peluang besar untuk sukses. Namun, keberhasilannya memerlukan perencanaan matang, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta komitmen untuk menjaga keberlanjutan sistem. Sistem ini bukan hanya solusi untuk saat ini, tetapi juga investasi penting untuk masa depan yang lebih baik di Aceh Utara.
Tepat seperti biasa sebelum diakhiri, kami titip 2 pantun, semoga berguna bagi kita semua.
Hujan turun membasahi bumi
Air mengalir membawa berkah
Aceh Utara jaga harmoni
Air bersih milik Bersama menjadi amanah
Pohon rimbun tempat berteduh
Hujan reda langit cerah
Masyarakat bersatu dalam sejuk teduh
Air hujan jadi sumber berkah
Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq, billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Samudera Pase, Aceh Utara, 30 Desember 2024/ 29 Jumadil Akhir 1446 H

Sekolah Sungai Karang Mumus
Model Kolaborasi Konservasi
Penulis: Aprinalistria, S. Psi, S. Fil, M. Pd
(Dosen Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Kandidat Doktor dalam Ilmu Pendidikan)
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya merasa terhormat untuk berbagi pengalaman dan pemikiran terkait konservasi alam, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan kita. Dalam acara Shortcourse Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch 4 dengan tema “Peran Konservator Alam untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”, saya ingin menyampaikan pentingnya peran kita sebagai konservator alam dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh bumi ini.
Salah satu tokoh yang sangat menginspirasi dalam gerakan konservasi lingkungan adalah Bapak Misman, seorang aktivis lingkungan yang telah berjuang keras melalui Sekolah Sungai Karang Mumus di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekolah Sungai ini bertujuan untuk mengembalikan ekosistem yang rusak, khususnya di sekitar Sungai Karang Mumus yang tercemar oleh sampah dan limbah. Namun, perjuangan Bapak Misman tidak berhenti di situ; beliau juga memiliki pandangan yang sangat mendalam mengenai bagaimana manusia berinteraksi dengan alam dan bagaimana kita bisa mencapainya dengan cara yang berkelanjutan.
Sekolah Sungai Karang Mumus: Peran Masyarakat dan Mahasiswa dalam Konservasi Alam
Sekolah Sungai Karang Mumus bukan hanya menjadi inisiatif penting dalam konservasi lingkungan, tetapi juga tempat di mana masyarakat sekitar, termasuk para mahasiswa, terlibat langsung dalam upaya penyelamatan lingkungan. Bapak Misman menyadari bahwa keberhasilan gerakan konservasi sangat bergantung pada partisipasi aktif berbagai pihak, terutama masyarakat lokal yang sehari-hari bergantung pada alam.
Pada awalnya, Sekolah Sungai Karang Mumus berfokus pada pembersihan sampah di sepanjang sungai. Setiap sore, para relawan, yang sebagian besar adalah masyarakat sekitar, datang dengan semangat untuk membersihkan sampah yang mengambang di sungai. Mereka bekerja keras dengan keyakinan bahwa tindakan sederhana ini dapat memberi dampak besar dalam mengembalikan ekosistem yang sehat.
Namun, peran masyarakat tidak berhenti hanya pada pembersihan sampah. Bapak Misman juga melibatkan mereka dalam program penanaman pohon untuk restorasi lingkungan. Sejak didirikan pada tahun 2016, lebih dari 10.000 pohon telah ditanam, termasuk pohon buah produktif dan pohon endemik yang sangat penting bagi ekosistem sungai. Masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan ini. Mereka diajak untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana cara bertanggung jawab terhadap alam.
Peran Mahasiswa dalam Konservasi
Selain itu, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur turut berperan penting dalam keberhasilan Sekolah Sungai Karang Mumus. Bapak Misman selalu menyambut baik keterlibatan mereka dalam program ini, karena mahasiswa memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam riset dan edukasi. Banyak mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian tentang kualitas air, flora dan fauna di sekitar sungai, serta dampak dari kegiatan penanaman pohon yang telah dilakukan.
Lebih dari itu, mahasiswa juga berperan dalam menyebarkan pengetahuan tentang konservasi melalui kegiatan edukasi. Mereka berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk memberikan pelatihan tentang cara-cara menjaga kebersihan sungai, pentingnya daur ulang, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang ramah lingkungan.
Keterlibatan Bersama: Membentuk Masa Depan yang Berkelanjutan
Bapak Misman sangat menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, terutama generasi muda, dalam gerakan konservasi ini. Ia percaya bahwa masa depan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Oleh karena itu, setiap kontribusi—baik itu pembersihan sungai, penanaman pohon, ataupun riset—memiliki peran yang sangat vital dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga alam.
Selain itu, Bapak Misman selalu mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis mengenai bagaimana mereka dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari ke dalam solusi nyata yang dapat diterapkan di lapangan. Melalui riset dan keterlibatan langsung, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman berharga, tetapi juga turut andil dalam menciptakan perubahan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.
Sekolah Sungai Karang Mumus sebagai Model Kolaborasi Konservasi
Sekolah Sungai Karang Mumus merupakan contoh nyata bagaimana sebuah inisiatif konservasi dapat berkembang dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga akademisi. Gerakan ini mengajarkan kita bahwa menjaga alam bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolektif. Konservasi alam harus menjadi budaya yang melibatkan berbagai sektor, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan keberlanjutan bumi kita di masa depan.
Berikut adalah tujuh komentar Bapak Misman yang mencerminkan komitmennya yang kuat terhadap konservasi alam:
- “Setelah ditambang, area tambang mau jadi area produktif apa?”
Bapak Misman menekankan bahwa setelah proses penambangan, kita harus memikirkan bagaimana mengubah area yang sebelumnya rusak menjadi area yang produktif dan berguna bagi kehidupan masyarakat serta alam. - “Apakah tanpa menambang alam kita masih bisa hidup? Jika masih, tidak usah menambang karena efeknya berjuta tahun untuk konservasi.”
Beliau mengingatkan kita bahwa alam memiliki daya tahan jangka panjang yang harus kita jaga. Jika kita masih bisa hidup tanpa merusak alam, mengapa kita harus menambang? Efek dari penambangan dapat berlangsung selama berabad-abad, bahkan mempengaruhi generasi yang akan datang. - “Fokus pada tujuan hidup kita untuk memenuhi ‘kebutuhan’ masyarakat banyak, jangan pada ‘keinginan’ untuk bermewah-mewah saja.”
Bapak Misman mengajak kita untuk kembali ke dasar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia tanpa harus mengorbankan keberlanjutan alam demi keinginan semata. - “Konservasinya setelah menambang, jangan biarkan tanah jadi bolong-bolong, bekas tambang batu bara, tapi harus ditambal juga untuk setelahnya.”
Menurut Bapak Misman, setelah penambangan harus ada upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan ekosistem yang rusak. Jangan biarkan bekas tambang hanya meninggalkan lubang, tetapi harus ada rehabilitasi dan penanaman kembali agar alam bisa pulih. - “Semua tempat tambang itu ruang air, begitu struktur diubah maka mengganggu air, harusnya tidak sekadar kompensasi ekonomi tapi juga ekologi.”
Beliau juga mengingatkan kita bahwa tambang bukan hanya merusak tanah, tetapi juga merusak aliran air yang sangat penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dampak ekologis, bukan hanya keuntungan ekonomi yang sementara. - “Bencana akhirnya muncul karena kita zalim pada alam.”
Bapak Misman dengan tegas mengatakan bahwa bencana alam yang kita alami saat ini seringkali merupakan akibat dari kelalaian dan kekejaman kita terhadap alam. Ketidakhati-hatian kita dalam menjaga lingkungan akan berujung pada dampak yang merugikan kita semua. - “Jangan berpikir hanya untuk hari ini saja, tapi juga pikirkan generasi selanjutnya, anak cucu kita.”
Beliau menutup pesannya dengan mengingatkan kita untuk berpikir jauh ke depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi generasi mendatang, oleh karena itu penting untuk melestarikan alam demi masa depan yang lebih baik.
Dengan semangat yang besar untuk konservasi alam, Bapak Misman terus mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan, tidak hanya untuk kesejahteraan kita saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Pada acara ini, saya berharap kita semua dapat terinspirasi oleh semangat beliau dan menerapkan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan sehari-hari, agar bumi kita tetap lestari dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita dengan kondisi yang lebih baik.
Terima kasih kepada Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK) yang telah mengadakan acara ini dan kepada semua peserta yang telah hadir. Mari bersama-sama kita terus menjaga alam untuk masa depan yang berkelanjutan.
Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang terlibat, terutama kepada Pak Misman yang telah menginspirasi banyak pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Semoga acara ini dapat menambah wawasan dan mendorong lebih banyak orang untuk ikut serta dalam gerakan konservasi demi masa depan yang berkelanjutan.

Air Sumber Kehidupan
yang Tak Ternilai untuk Kesejahteraan Bersama
Oleh : Toriq Fatur Rohman, S.Kom., M.Kom. (Founder & CEO Etera Foundation)
Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih Founder Sekolah Air Hujan Bening, saya sedikit memberikan opini yang pernah saya bawakan pada saat saya diundang di acara World Water Forum 10th. Menurut pendapat saya, air sebagai sumber kehidupan, memiliki peran yang sangat krusial dalam menunjang kesejahteraan manusia. Mulai dari kebutuhan dasar seperti minum dan sanitasi hingga aktivitas ekonomi seperti pertanian dan industri, air menjadi faktor penentu kualitas hidup. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan iklim, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi tantangan global yang semakin mendesak.
– Sektor Kesehatan: Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kunci untuk mencegah berbagai penyakit menular. Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan tifus, terutama pada anak-anak.
– Sektor Pertanian: Sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air untuk irigasi. Ketersediaan air yang cukup akan menjamin produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
– Sektor Industri: Air digunakan dalam berbagai proses industri, mulai dari produksi barang konsumsi hingga pembangkit listrik. Ketersediaan air yang memadai akan mendukung pertumbuhan ekonomi.
– Sektor Ekosistem: Air adalah komponen penting dalam ekosistem. Kualitas air yang buruk dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam keanekaragaman hayati.
Tantangan dalam akses terhadap air bersih sebagai berikut.
– Kualitas Air: Pencemaran air oleh limbah industri, pertanian, dan domestik menjadi masalah serius.
– Kuantitas Air: Perubahan iklim, seperti peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan, dapat menyebabkan kekurangan air di beberapa daerah.
– Akses Air: Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan kumuh.
– Pengelolaan Air: Kurangnya pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan juga menjadi tantangan.
Air adalah sumber daya yang sangat berharga dan tak ternilai. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan hak dasar setiap manusia. Untuk menjamin kesejahteraan bersama, kita perlu bekerja sama dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Setiap individu, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan dan kualitas air untuk generasi mendatang. Dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa air tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menciptakan Kota Lebih Sejuk
Mengatasi Efek Pulau Panas Perkotaan (Urban Head Island)
Oleh: Tirta Yoga, SP., MP. (Dosen Agribisnis, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang)
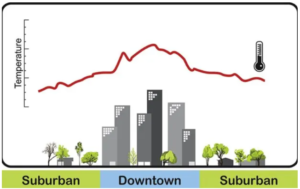
(Penentuan suhu permukaan lahan dan pulau panas perkotaan dari data geostasioner. Kredit: J. Silva dkk. Science Direct 2018)
Fenomena urbanisasi yang semakin masif membawa konsekuensi besar terhadap kondisi lingkungan perkotaan. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah terjadinya efek Pulau Panas Perkotaan atau Urban Heat Island (UHI). Istilah ini merujuk pada kondisi di mana suhu di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya sekadar isu termal, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, konsumsi energi, dan ekosistem perkotaan.
UHI disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain perubahan penutup lahan seperti beton, aspal, dan material bangunan lainnya yang menyerap dan menyimpan lebih banyak panas dibandingkan dengan vegetasi alami. Kurangnya vegetasi menghilangkan efek pendinginan alami yang diberikan oleh tanaman melalui proses evapotranspirasi. Selain itu, emisi panas antropogenik dari kendaraan, mesin industri, dan perangkat elektronik turut menyumbang peningkatan suhu lingkungan. Karakteristik geometris kota dengan bangunan tinggi dan jalan-jalan sempit juga meningkatkan penyimpanan panas, sekaligus mengurangi aliran udara yang berfungsi untuk melepaskan panas secara alami. Desain kota yang tidak mempertimbangkan prinsip keberlanjutan sering kali memperburuk masalah ini, seperti distribusi ruang hijau yang tidak merata dan kurangnya perhatian pada infrastruktur ramah lingkungan.
Lingkungan perkotaan di Eropa memberikan gambaran nyata tentang tekanan panas yang dapat terjadi akibat UHI. Sekitar tiga perempat populasi di Eropa tinggal di daerah perkotaan, dengan proporsi yang diperkirakan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Kondisi ini menyebabkan kota-kota di Eropa rentan terhadap suhu ekstrem, seperti yang terjadi selama musim panas 2020. Tanah beraspal yang menyerap panas, bangunan yang saling berdekatan, dan aktivitas manusia seperti kendaraan serta perangkat elektronik semakin memperparah efek UHI. Populasi lanjut usia di Eropa menjadi kelompok yang sangat terpapar risiko, dengan peningkatan angka kematian terkait panas yang signifikan. Flemish Institute of Technological Research (VITO) bersama mitra telah menggunakan data dari Copernicus Climate Change Service (C3S) untuk merancang model analisis tekanan panas di kota-kota Eropa. Model ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang UHI, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis dalam mitigasi dampak terhadap kesehatan masyarakat. Langkah ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara teknologi dan perencanaan kota untuk mengatasi tekanan panas akibat urbanisasi.
Efek UHI memiliki berbagai implikasi serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Suhu tinggi meningkatkan kebutuhan energi untuk pendinginan, seperti penggunaan AC, yang pada akhirnya memperburuk emisi gas rumah kaca. Gelombang panas yang diperparah oleh UHI meningkatkan risiko kesehatan, termasuk stroke panas, dehidrasi, dan penyakit pernapasan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Di sisi lain, suhu tinggi mempercepat reaksi kimia yang menghasilkan ozon troposfer, memperburuk kualitas udara perkotaan. Tidak hanya itu, peningkatan suhu juga berdampak pada infrastruktur, mempercepat kerusakan jalan, jembatan, dan gedung yang membutuhkan biaya pemeliharaan lebih tinggi. Bahkan, perubahan suhu memengaruhi perilaku fauna perkotaan serta mengganggu ekosistem lokal, termasuk kesehatan tanaman yang berperan sebagai penyaring alami polutan udara.
Mengurangi dampak UHI memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Salah satu langkah efektif adalah meningkatkan jumlah ruang hijau dengan menanam pohon, membangun taman kota, dan menciptakan atap hijau (green roofs). Inisiatif ini tidak hanya membantu menyerap panas tetapi juga meningkatkan evapotranspirasi yang berfungsi sebagai pendingin alami. Selain itu, penggunaan material reflektif untuk mengganti permukaan gelap dengan material yang memantulkan lebih banyak sinar matahari dapat mengurangi penyimpanan panas. Teknologi modern, seperti cat pemantul panas (cool paint) dan trotoar berbahan permeabel, juga dapat diterapkan untuk mengurangi suhu permukaan jalan. Perencanaan tata kota yang berkelanjutan perlu mengintegrasikan prinsip desain yang memungkinkan aliran udara yang optimal dan meminimalkan emisi panas, seperti orientasi bangunan yang strategis dan penciptaan koridor hijau. Edukasi publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang UHI dan langkah-langkah mitigasinya. Kampanye untuk mendorong perilaku ramah lingkungan, seperti menanam pohon di sekitar rumah, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendukung proyek hijau, dapat menciptakan perubahan positif dalam skala besar.

Perlunya Integrasi Konsep Pengelolaan Air Hujan
Dalam Kurikulum Pendidikan Menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri
Oleh: Adnan Iman Nurtjahjo Amir, S.M. - Ketua Komite Sekolah SD negeri Tegalrejo 1 Yogyakarta (Adiwiyata Tingkat Nasional)
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumberdaya air, pengelolaan air hujan menjadi salah satu solusi penting yang harus diimplementasikan secara sistematis. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan konsep pengelolaan air hujan ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah yang berorientasi pada program Adiwiyata Mandiri. Langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membentuk generasi muda yang sadar dan peduli terhadap kelestarian sumber daya alam.
Urgensi Pengelolaan Air Hujan di Sekolah
Sekolah Adiwiyata Mandiri memiliki visi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak sekolah adalah manajemen air, terutama dalam menghadapi intensitas hujan yang tidak menentu akibat perubahan iklim. Air hujan seringkali dianggap sebagai limbah, padahal jika dikelola dengan baik, air hujan bisa menjadi sumber daya yang bermanfaat. Misalnya, air hujan dapat ditampung dan dimanfaatkan untuk keperluan penyiraman tanaman, air minum, sarana terapi, hingga sebagai cadangan air bersih. Selain itu, pengelolaan air hujan juga dapat membantu mengurangi risiko banjir di area sekolah, meningkatkan resapan air tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan air hujan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga swasta, tetapi juga perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan.
Integrasi Dalam Kurikulum Pendidikan
Integrasi konsep pengelolaan air hujan dalam kurikulum dapat dilakukan melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan mata pelajaran seperti IPA, geografi, pendidikan lingkungan hidup, dan bahkan matematika. Integrasi yang dapat diterapkan melalui proyek praktik lapangan yaitu siswa dilibatkan dalam proyek nyata seperti merancang dan membangun sistem penampungan air hujan sederhana di lingkungan sekolah. Proyek ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga pengalaman praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, diberikan pembelajaran kontekstual mengenai siklus hidrologi dan pentingnya air dalam ekosistem dengan memberikan studi kasus tentang dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air. Dengan demikian, siswa dapat memahami pentingnya pengelolaan air hujan dalam konteks global dan lokal. Kaitannya dengan sekolah adiwiyata mandiri maka perlu dilakukan integrasi nilai adiwiyata tentang pengelolaan air hujan yang dapat dijadikan budaya sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, hingga tenaga kependidikan. Kegiatan seperti monitoring penggunaan air, evaluasi sistem resapan air, dan lomba desain sistem pengelolaan air hujan dapat menjadi cara efektif untuk memperkuat nilai Adiwiyata.
Manfaat Jangka Panjang
Integrasi pengelolaan air hujan dalam kurikulum tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi sekolah, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Siswa yang telah memahami pentingnya pengelolaan air hujan akan tumbuh menjadi individu yang memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Mereka tidak hanya menjadi pelaku perubahan di sekolah, tetapi juga di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, sekolah yang berhasil menerapkan konsep ini akan semakin mendekati tujuan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri, yaitu sekolah yang mampu menjadi teladan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Implementasi ini juga dapat meningkatkan citra sekolah sebagai institusi yang peduli terhadap masa depan lingkungan.
Pengelolaan air hujan seperti yang telah dilakukan Sekolah Air Hujan Banyu Bening di Kabupaten Sleman adalah salah satu langkah kecil namun berdampak besar dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya alam. Dengan mengintegrasikan konsep ini dalam kurikulum pendidikan, sekolah-sekolah formal tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang ramah lingkungan, tetapi juga membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan planet ini. Sekolah Adiwiyata Mandiri memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pelopor dalam inisiatif ini, sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi yang siap menghadapi tantangan lingkungan di masa depan. Mari bersama kita dorong pendidikan lingkungan yang lebih baik, demi masa depan yang lebih hijau. ***(Sleman: 28 Desember 2024).

Hujan, Harta Karun yang Tak Ternilai :
Saatnya Membranding Air Hujan
Oleh : Yuniana Cahyaningrum, S.Kom., M.Kom. (Institut Seni Indonesia Surakarta)
Preambule
Setiap tetes hujan adalah anugerah dari langit, sebuah siklus kehidupan yang tak pernah berhenti. Namun, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, kita seringkali melupakan betapa berharganya air hujan. Kita begitu sibuk mengejar materi dan teknologi, hingga tak sadar bahwa kita sedang mengabaikan salah satu sumber daya alam yang paling vital bagi keberlangsungan hidup. Air hujan, ibarat harta karun yang tersembunyi di langit. Ia menyuburkan tanah, mengisi sungai dan danau, serta menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Namun, saat ini, air hujan justru sering dianggap remeh dan bahkan menjadi ancaman. Perubahan iklim yang ekstrem menyebabkan pola hujan menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan silih berganti melanda berbagai wilayah.
Mengapa Kita Harus Membranding Air Hujan?
Branding air hujan bukan hanya sekadar memberi nama pada air yang jatuh dari langit, tetapi lebih dari itu, ini adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya air, khususnya air hujan, dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan branding, air hujan dapat diposisikan sebagai sumber daya yang berharga, bukan sekadar fenomena alam biasa. Ini akan mendorong masyarakat untuk:
- Lebih peduli : Masyarakat akan lebih peduli terhadap air hujan dan dampaknya terhadap lingkungan.
- Bijak dalam memanfaatkan : Masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan air hujan, misalnya dengan membangun tandon air hujan.
- Berpartisipasi dalam pelestarian : Masyarakat akan lebih aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti menanam pohon dan menjaga kebersihan sungai.
Konsep Branding Air Hujan yang Efektif
- Relevan : Branding harus relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- Inspiratif: Branding harus mampu menginspirasi masyarakat untuk bertindak.
- Berkelanjutan: Branding harus mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Implementasi Branding Air Hujan
Untuk mengimplementasikan branding air hujan, kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain:
- Kampanye edukasi : Melalui kampanye edukasi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya air hujan.
- Program komunitas : Membentuk komunitas peduli air hujan yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian.
- Kolaborasi dengan pemerintah : Bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pemanfaatan air hujan.
- Pemanfaatan media sosial : Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi.
Closing Statement
Air hujan adalah anugerah yang tak ternilai. Dengan membranding air hujan, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan air hujan sebagai simbol harapan dan keberlanjutan.

“Self-Love, Earth Love:
Cintailah Diri dan Bumi”
Oleh : Yuniana Cahyaningrum, S.Kom., M.Kom. (Institut Seni Indonesia Surakarta)
Prolog : Dalam era modern yang serba cepat, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang membuat kita melupakan hubungan mendalam kita dengan alam. Kita sibuk mengejar kesuksesan, kepuasan instan, dan materialisme, hingga mengabaikan bumi yang telah menjadi rumah kita. Padahal, kesehatan dan kesejahteraan kita sangat bergantung pada kesehatan planet ini.
Koneksi Antara Cinta Diri dan Cinta Bumi
Mencintai diri sendiri dan mencintai bumi bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya saling berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan lebih peduli terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Kita akan berusaha hidup sehat, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Semua hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada lingkungan sekitar kita. Sebaliknya, ketika kita mencintai bumi, kita akan lebih peduli terhadap keberlanjutan planet ini. Kita akan berusaha mengurangi jejak karbon, menghemat energi, dan membuang sampah pada tempatnya. Tindakan-tindakan kecil ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan kepuasan batin yang mendalam.
Mengapa Cinta Diri dan Cinta Bumi Penting?
- Kesehatan: Kesehatan fisik dan mental kita sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Udara bersih, air bersih, dan makanan sehat adalah hak dasar setiap manusia yang berasal dari alam.
- Kebahagiaan: Berada di alam memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Interaksi dengan alam dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup.
- Spiritualitas: Banyak orang menemukan kedamaian dan makna hidup melalui hubungan mereka dengan alam.
- Keadilan Sosial: Isu lingkungan seringkali terkait dengan isu sosial. Dengan merawat bumi, kita juga berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial.
Cara Menyatukan Cinta Diri dan Cinta Bumi
- Hidup Berkelanjutan: Mengurangi konsumsi, mendaur ulang, dan menggunakan energi terbarukan adalah cara sederhana untuk merawat bumi.
- Berinteraksi dengan Alam: Luangkan waktu untuk berada di alam, seperti berkemah, hiking, atau berkebun.
- Mendukung Organisasi Lingkungan: Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang peduli terhadap lingkungan.
- Menginspirasi Orang Lain: Jadilah contoh yang baik dengan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk peduli terhadap lingkungan.
Call To Action
Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri dan mencintai bumi, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Setiap tindakan kecil, sekecil apapun, dapat memberikan dampak yang besar.
“Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk bumi kita!”

Program Ketapang Kencana
Yang Menginspirasi
Oleh: Adnan Iman Nurtjahjo Amir, S.M. (Ketua Forum KIM Sembada Kabupaten Sleman, Jurnalis Media Center Sembada Kabupaten Sleman)
Di tengah tantangan global terkait ketahanan pangan, isu lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, program Ketahanan Pangan Keluarga Terencana (Ketapang Kencana) yang dikembangkan oleh Bapak Sri Widodo dan Ibu Nurul Fitri Hidayati melalui Yoso Farm Homestead patut menjadi contoh. Program ini tidak hanya memberikan solusi nyata untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup.
Ketapang Kencana mengedepankan gagasan bahwa setiap keluarga memiliki potensi untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan pendekatan berbasis komunitas, Owner Yoso Farm tersebut memberikan teladan tentang cara memanfaatkan lahan yang tersedia, di pekarangan kecil dengan mengintegrasikan berbagai Teknik pertanian yang ramah lingkungan demi mencapai ketahanan pangan skala keluarga. Hasilnya, keluarga Sri Widodo dapat menanam sayuran, buah-buahan, membuat pupuk untuk tanamannya hingga memelihara ayam dan ikan dengan memanfaatkan sumberdaya yang mudah, murah dan melimpah di sekitarnya. Selain memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, hasil panen yang berlebih juga dapat dijual untuk tambahan pendapatan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menciptakan ketahanan pangan di tingkat keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Kontribusi Pada Pelestarian Lingkungan
Selain berdampak pada ketahanan pangan, program Ketapang Kencana juga berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Melalui program mandiri pangan, mandiri pupuk, dan mandiri pakan, maka salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah melakukan daur ulang limbah organik rumah tangga menjadi pakan ternak berupa Magot maupun sampah organik berupa dedaunan yang kemudian difermentasi menjadi kompos dan digunakan sebagai pupuk alami. Dengan cara ini, limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat diolah menjadi sumberdaya yang bermanfaat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keberlanjutan, memastikan bahwa pertanian tidak hanya memberikan hasil optimal, tetapi juga melindungi ekosistem di sekitarnya.
Dampak Sosial dan Inspirasi Bagi Banyak Orang
Program ini tidak hanya terbatas pada keluarga yang terlibat langsung, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas. Melalui pelatihan dan pendampingan, Yoso Farm menginspirasi banyak orang untuk memulai kebun keluarga mereka sendiri. Program ini juga menciptakan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat, dengan menyediakan pangan organik bebas bahan kimia berbahaya.
Ketapang Kencana menjadi model pemberdayaan yang holistik. Selain menciptakan kemandirian pangan, program ini mendorong masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan dan meningkatkan solidaritas di antara warga masyarakat. Dalam skala yang lebih luas, inisiatif ini berpotensi menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di tingkat nasional.
Menghubungkan Lingkungan dan Kesejahteraan Manusia
Ketapang Kencana merupakan bukti bahwa menjaga lingkungan dan mensejahterakan manusia dapat berjalan seiring. Dengan mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan, pemberdayaan keluarga, dan pengelolaan sumberdaya yang bijak, Keluarga Sri Widodo dan Nurul Fitri Hidayati telah menciptakan ekosistem yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga menguntungkan. Program ini sebagai pengingat bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, bahkan dari sebuah keluarga. Jika lebih banyak keluarga dan komunitas mengadopsi model ini, Indonesia dapat memiliki ketahanan pangan yang kokoh sekaligus menjaga keindahan alamnya. Yoso Farm Homestead dan Ketapang Kencana adalah inspirasi nyata bahwa inovasi lokal dapat memberikan dampak global. Langkah kecil mereka untuk mengatasi krisis pangan dan lingkungan adalah harapan bagi masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. *** (Sleman: 21 Desember 2024)

Membangun Negeri
dari Halaman Rumah Sendiri
Oleh: Widia Anggia Vicky, S.T. - Community Director Mamaberclodi, Founder Waste Therapy, Eco-Content Creator, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Homestead adalah cara hidup yang berfokus pada keberlanjutan dan kemandirian, dimana penggunaan sumber daya lokal menjadi tujuan utamanya dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan produk industri. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan industri saat ini, menjalankan cara homestead tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama yang tinggal di area urban dan tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi masyarakat rural sendiri, kepemilikan lahan bisa jadi bukan masalah utama tetapi kebutuhan akan sumber daya manusia yang menjadi kendalanya.
Konsep homestead bisa jadi akan berbeda-beda penerapannya di setiap keluarga, sebab setiap keluarga unik dan memiliki kebutuhannya masing-masing. Secara umum, saat menerapkan cara homestead, keluarga akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dapur dari tanaman dan ternak yang dipelihara sendiri. Contohnya seperti yang dilakukan di rumah pak Widodo dan ibu Nurul yang membangun konsep Yoso Farm sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan keluarganya. Di Yoso Farm, halaman yang dimiliki dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dapur dengan menanam tanaman sayur, buah, serta karbohidrat. Selain itu juga ada kandang ayam yang diberi nama “kastari” atau kandang ayam lestari, dimana kandang ayam ini dibuat dengan sistem low maintenance. Sumber protein lain diperoleh dari memelihara ikan lele dan membudidayakan jamur dari bonggol jagung. Sebagai sumber makanan untuk ternak, Yoso Farm menggunakan maggot (larva lalat Black Soldier Fly) sebagai sumber pakai. Maggot ini juga yang berperan menjadi tentara yang mengelola sisa organik dari dapur.
Sistem yang dibangun di Yoso Farm memungkinkan untuk limbah yang dihasilkan di rumah tangga bisa dikelola secara mandiri dan masuk kembali ke rantai makanan melalui peranan maggot. Jika sistem seperti ini dapat diduplikasi oleh lebih banyak rumah tangga lainnya di Indonesia, impian untuk bisa mandiri pangan tentu bukan hal yang mustahil untuk dicapai. Meskipun dalam praktiknya tentu ada kendala yang akan dialami, tetapi dengan memahami urgensi untuk mandiri pangan dari halaman dan mengelola sisa konsumsi di lingkup rumah tangga, kendala yang ada akan bisa diatasi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing rumah.
Seperti yang disebutkan dalam hasil riset berjudul Climate Change and Sustainable Rural Livelihoods: Constraints and Adaptation Strategies oleh Dr. Shayan Javeed, masyarakat di wilayah pedesaan memang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim karena lebih banyak bergantung terhadap hasil alam untuk pemenuhan kebutuhannya. Sehingga kerja sama berbagai pihak untuk bisa meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat pedesaan terhadap krisis iklim perlu menjadi perhatian. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggalakkan cara hidup homestead yang akan mendorong masyarakat menjadi pelaku aktif dalam rantai pasok konsumsi, minimal untuk rumah tangganya masing-masing. Kebijakan dari pemerintah, hasil riset yang mumpuni dari akademisi, dan edukasi komprehensif ke masyarakat akan memudahkan terlaksananya sinergi untuk mendukung mandiri pangan dari halaman.

Pertanian Perkotaan
Solusi Jangka Panjang atau Masalah Di Depan Mata?
Adhifatra Agussalim, CIP, CIAPA, CASP, CPAM. (Praktisi Internal Auditor, aktif sebagai Sekretaris DPW Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Aceh)

“Pertobatan Ekologis”
sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Oleh: Yohanes Ada Lebang, SP., M.Si (Universitas Caritas Indonesia)
Pertobatan ekologis merupakan panggilan moral dan praksis yang mengarahkan manusia untuk merubah cara pandang dan perilaku terhadap alam. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hal ini menjadi kunci utama, terutama ketika kita dihadapkan pada tantangan degradasi lahan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan mendesak akan ketahanan pangan.
Program strategis nasional seperti food estate dirancang untuk meningkatkan produksi pangan demi mengatasi ancaman krisis pangan. Namun, realisasinya sering kali berbenturan dengan masalah ekologis, seperti pembukaan lahan secara masif yang merusak keanekaragaman hayati dan mengurangi kapasitas ekosistem dalam mendukung kehidupan jangka panjang. Di sisi lain, degradasi lahan sebagai akibat dari praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan juga mengancam keberlanjutan inisiatif ini.
Program strategis nasional seperti food estate merupakan salah satu upaya besar dalam mencapai ketahanan pangan. Namun, implementasinya tidak jarang memicu persoalan ekologis, terutama jika tidak dikelola secara holistik dan berbasis prinsip keberlanjutan. Pengembangan kawasan pertanian skala besar seringkali menuntut alih fungsi lahan yang mempercepat kerusakan ekosistem, memengaruhi kualitas tanah, keanekaragaman hayati, dan siklus hidrologi.
Di sisi lain, munculnya petani milenial memberikan optimisme. Generasi ini memiliki akses lebih baik terhadap teknologi, informasi, dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi pertanian. Namun, keberhasilan mereka bergantung pada pendekatan yang mengintegrasikan teknologi dengan kearifan lokal serta prinsip keberlanjutan. Tanpa kesadaran ekologis yang memadai, upaya mereka justru dapat memperparah eksploitasi sumber daya alam.
Generasi muda ini cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan teknologi modern yang dapat mendukung praktik pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Namun, potensi mereka hanya akan optimal jika didukung oleh pendidikan, kebijakan, dan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan.
Untuk menghadapi tantangan ini, pertobatan ekologis menjadi keharusan. Istilah ini mengacu pada perubahan paradigma dalam memandang alam sebagai mitra dalam pembangunan, bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi. Pendekatan ini melibatkan transformasi sistem pertanian menuju agroekologi, yang mengutamakan diversifikasi tanaman, konservasi tanah, dan pengurangan input kimia. Dengan demikian, ekosistem yang terdegradasi dapat dipulihkan secara bertahap, sambil tetap mendukung ketahanan pangan.
Konsep kembali ke alam dapat menjadi dasar dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan ini. Pertanian berkelanjutan berbasis agroekologi, misalnya, menawarkan solusi yang selaras dengan prinsip kembali ke alam. Pendekatan ini mengutamakan pengelolaan lahan yang menjaga kesuburan tanah, diversifikasi tanaman, dan praktik ramah lingkungan. Dengan ini, degradasi lahan dapat diminimalkan, sekaligus mendukung produksi pangan yang stabil.
Gagasan ini mengajak kita untuk mendekatkan hubungan manusia dengan ekosistem, menggunakan sumber daya secara bijak, dan melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang. Namun, dalam kenyataannya, kita dihadapkan pada tantangan serius seperti degradasi lahan, kebutuhan ketahanan pangan, dan keterbatasan sumber daya.
Pertobatan ekologis dalam konteks ini tidak hanya berarti menjaga lingkungan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung alam. Ini mencakup:
- Perubahan Kebijakan: Pemerintah harus memastikan bahwa program food estate tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga mematuhi prinsip keberlanjutan. Insentif bagi petani milenial untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik agroekologi harus diperluas.
- Penguatan Pendidikan dan Kesadaran: Petani dan masyarakat luas perlu dididik tentang pentingnya menjaga ekosistem untuk masa depan. Kampanye tentang keberlanjutan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
- Peningkatan Inovasi Berbasis Lingkungan: Teknologi seperti irigasi hemat air, pengelolaan limbah organik, dan pertanian presisi harus diperkenalkan dan diakses oleh petani, khususnya generasi milenial.
Dengan langkah-langkah ini, pertobatan ekologis dapat menjadi jalan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam keterbatasan sumber daya, manusia dituntut untuk bijak, bukan hanya mengejar kebutuhan sesaat, tetapi juga menjaga warisan ekologis bagi generasi mendatang. Membangun harmoni dengan alam adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang ada dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.
Dalam konteks ini, peran pemerintah dan masyarakat menjadi krusial. Kebijakan harus diarahkan untuk mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan, mendukung inovasi yang berbasis lingkungan, serta memberikan insentif kepada petani milenial untuk mengadopsi model bisnis yang ramah lingkungan. Selain itu, pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan perlu diperkuat, agar setiap individu memahami pentingnya harmoni antara kesejahteraan manusia dan kelestarian alam.
Hanya dengan komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung lingkungan, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia di tengah keterbatasan sumber daya.

Tradisi Futuristik Siklus Budaya Padi Ciptagelar
Merawat Kearifan Lokal untuk Ketahanan Pangan
Oleh: Adnan Iman Nurtjahjo Amir, S.M.
Ketua Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Sleman, Jurnalis Media Center Sembada Kabupaten Sleman
Kasepuhan Ciptagelar di Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi keberlanjutan dalam bidang pangan. Dipimpin oleh Kang Yoyo Gasmana sebagai Jambatan Kasepuhan atau juru komunikasi, masyarakat adat ini telah berhasil menciptakan sistem ketahanan pangan berbasis budaya yang mampu bertahan selama 640 tahun. Tradisi futuristik yang mereka jalankan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga membangun harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.
Siklus Budaya Padi: Warisan yang Berlanjut
Kunci utama keberhasilan ketahanan pangan di Ciptagelar adalah penerapan ngahuma atau sistem pertanian tradisional berbasis padi. Dalam tradisi ini, penanaman padi dilakukan dengan cara yang menghormati siklus alam. Tidak ada penggunaan pupuk kimia atau pestisida modern karena semua bergantung pada kearifan ekologis lokal. Pola tanam yang mereka anut juga tidak mengejar produksi massal, melainkan berfokus pada kualitas dan kesinambungan.
Kang Yoyo Gasmana, sebagai jembatan antara Kasepuhan Ciptagelar dan dunia luar, memiliki peran strategis dalam menyampaikan filosofi adat ini ke khalayak luas. Melalui perannya, ia mengomunikasikan pentingnya menjaga tradisi leluhur sebagai bentuk adaptasi budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi ini bukan hanya soal menanam padi, tetapi juga melibatkan serangkaian ritual adat seperti seren taun yang menjadi momentum untuk bersyukur kepada alam.
Ketahanan Pangan dan Filosofi “Tanpa Jual-Beli Padi”
Salah satu aspek paling unik dari Kasepuhan Ciptagelar adalah filosofi mereka untuk tidak menjual padi hasil panen. Padi yang ditanam hanya digunakan untuk kebutuhan masyarakat sendiri, sehingga menciptakan ketahanan pangan yang stabil. Gudang-gudang padi tradisional yang disebut leuit adalah simbol ketahanan ini. Setiap keluarga memiliki leuit sendiri, dan kelebihan padi disimpan sebagai cadangan dalam menghadapi situasi darurat.
Dalam konteks modern, filosofi ini sangat futuristik karena mendorong keberlanjutan tanpa bergantung pada pasar global. Ketika banyak komunitas menghadapi kerentanan akibat fluktuasi harga pangan dunia, Ciptagelar tetap berdiri kokoh dengan model otonomi pangan mereka. Kang Yoyo, melalui komunikasi yang efektif, telah membantu menyadarkan banyak pihak akan relevansi model ini sebagai solusi untuk mengatasi krisis pangan global.
Sinergi Tradisi dan Teknologi
Menariknya, meskipun sangat menghormati adat, Kasepuhan Ciptagelar tidak alergi terhadap teknologi modern. Dengan bimbingan Kang Yoyo, mereka memanfaatkan teknologi seperti listrik tenaga mikrohidro untuk mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari tanpa merusak lingkungan. Ini menunjukkan bahwa tradisi dan teknologi dapat berjalan beriringan, menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan.
Langkah ini juga memperkuat gagasan bahwa tradisi futuristik bukanlah sebuah kontradiksi. Justru, tradisi seperti di Ciptagelar membuktikan bahwa masa depan yang berkelanjutan hanya bisa tercapai dengan menghormati akar budaya dan ekosistem lokal.
Apa yang dilakukan oleh Kasepuhan Ciptagelar dan Kang Yoyo Gasmana adalah pelajaran berharga bagi dunia. Ketahanan pangan tidak hanya soal teknologi canggih atau modal besar, tetapi juga tentang menjaga hubungan manusia dengan alam. Dengan mempraktikkan nilai-nilai kearifan lokal, mereka telah menunjukkan bahwa tradisi yang berakar kuat mampu menghadapi tantangan globalisasi.
Kasepuhan Ciptagelar adalah bukti bahwa solusi masa depan dapat ditemukan dalam kebijaksanaan masa lalu. Tradisi futuristik ini layak menjadi model, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi komunitas global yang sedang mencari jalan keluar dari ancaman krisis pangan. Mari kita belajar dari Ciptagelar untuk merawat bumi dan melestarikan nilai-nilai luhur demi masa depan yang lebih baik.

Publik di buat Kagum:
Keserasian dalam Kehidupan Adat Kasepuhan Ciptagelar di Tengah Modernisasi
Oleh: Wisnu Setiadi
Islamic Community Development UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di mata dunia, Indonesia dikenal akan nuansa keberagaman budaya. Negara kepulauan ini memiliki 1.300 suku adat. Salah satu yang saat ini menjadi perhatian publik adalah kasepuhan Ciptagelar yang berada di Jawa Barat. Bagaimana tidak, perkampungan adat ini selain menjaga tatanan adat nenek moyangnya juga melek terhadap teknologi dan memiliki sistem tanam padi yang digadang-gadang akan menjadi contoh pembelajaran swasembada pangan nasional.
Masyarakat adat Ciptagelar menempatkan padi sebagai bagian kehidupan mereka. Sehingga wajar, terdapat beberapa treatment dalam pengolahan dari menanam hingga masa panen. Namun bukan hal itu yang menjadi topik tulisan ini.
Era moderenisasi dan industrialisasi menggiring umat manusia menjadi serba instan, peninggalan leluhur yang dilihat menghambat dalam percepatan pembangunan kian ditinggalkan. Perihal inilah yang membuat arus teknologi ditolak keras masuk ke desa adat yang masih mempertahankan nilai adatnya secara kuat. Meskipun demikian, masyarakat adat Ciptagelar mempunyai perspektif lain. Mereka masih menerima perkembangan teknologi modern tapi dengan batasan tertentu.
Hal di atas telah menunjukkan, konsep yang diyakini masyarakat adalah bagaimana di dalam kehidupan harus menciptakan keseimbangan. Filosofi ini diambil dari simbol dewi padi (Dewi Sri) sebuah keyakinan sebagai dewi kehidupan. Dewi Sri dimaknai sebagai “dwi” yang berarti “dua” dan “seri” yang berarti seimbang. Artinya, terdapat 2 hal yang saling seimbang, manusia dengan alam, tradisional dengan modern, dan lain sebagainya. Beberapa contoh yang diaplikasikan di kasepuhan Ciptagelar yaitu, pertama pohon padi tidak akan hidup tanpa ditanam manusia begitu pula manusia tidak akan hidup tanpa padi sebagai bahan pokok pangannya. Ini menggambarkan antara manusia dan alam saling membutuhkan dan merawat. Kedua, masyarakat kasepuhan tetap memelihara adat nenek moyangnya yang ketimuran sebagai counter nilai-nilai barat yang sudah menjamur di negeri ini. Ketiga, di tengah zaman Modern mereka menggunakan teknologi untuk membantu kehidupan mereka tapi dengan adanya batasan. Seperti listrik yang dikonsumsi sebagai penerangan maupun telekomunikasi berasal dari generator yang ditenagai arus sungai. Selanjutnya, penggunaan pupuk anorganik dari pabrik pula diaplikasikan pada tanaman padi namun hanya sekali di masa awal sepekan setelah penanaman padi untuk merangsang percepatan akar. Teruntuk pestisida, masyarakat menolak karena pada dasarnya sebagaimana poin pertama antara alam (termasuk makhluk hidup) dan manusia harus merawat.
Keselarasan inilah yang patut dijadikan percontohan masyarakat sekarang. Mengikuti arus globalisasi yang semakin modern tidak boleh melupakan nilai budaya lokal yang perlu di jaga kearifannya. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar telah membuktikan itu. Terimakasih salam penuh kerendahan hati dari Wisnu selaku penulis.

Aceh Seuramoe Mekkah:
Harmonisasi Tradisi Peradaban, Syariat, dan Lingkungan
Oleh : Adhifatra AS, CIP, CIAPA, CASP, CPAM
Praktisi Internal Auditor, aktif sebagai Sekretaris DPW Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Aceh, PT. Integra Sigma
Indonesia.
Mukaddimah
Bismillahhirrahmanirrahim, Alhamdulillah cukup menarik materi yang disampaikan oleh Kang Yoyogasmana dengan judul paparan Kasepuhan Ciptagelar – Menjalankan Titipan tradisi Leluhur sejak 1368 mengambil pendekatan Energi Air, Ketahanan Pangan Padi 640 Tahun dengan Swasembada Energi Mikro – Hidropower pada kegiatan Short Course Certified of Environmental Management Leadership (C.EML) Batch 3 Dengan Tema Swasembada Energi dan Pangan Yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024.
Setelah mengikuti kegiatan tersebut memicu penulis untuk bisa berkontribusi dalam mempersiapkan opini dibidang pemabahasan tersebut khususnya dari asal kami di Nanggroe Aceh Darussalam. Kami coba mengangkat esensi budaya serta lingkungan yang mempengaruhi semua lini kehidupan Masyarakat Aceh khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Budaya dan lingkungan merupakan dua elemen yang saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu sama lain sepanjang sejarah peradaban manusia. Budaya mencerminkan cara manusia hidup, berpikir, dan bertindak dalam lingkungan tertentu. Sebaliknya, lingkungan memberikan batasan, peluang, dan tantangan yang memengaruhi perkembangan budaya suatu masyarakat. Hubungan ini terus berkembang seiring kemajuan peradaban, menciptakan dinamika yang kompleks antara manusia, kebiasaan, dan alam. Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekah, memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam.
Budaya Aceh mencerminkan perpaduan unik antara tradisi lokal, nilai-nilai Islam, dan pengaruh sejarah dari berbagai peradaban yang pernah bersentuhan dengan wilayah ini. Dengan akar yang kuat dalam keislaman, budaya Aceh mencerminkan harmoni antara manusia, agama, dan lingkungan yang terus berkembang seiring waktu. Aceh juga memiliki sejarah panjang interaksi budaya dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh dinamika peradaban. Kekayaan budaya Aceh tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografisnya yang strategis, terletak di ujung barat Indonesia dan menghadap ke Selat Malaka. Lingkungan alam yang kaya, seperti laut, hutan, dan sungai, telah membentuk karakter masyarakat Aceh sekaligus menjadi fondasi bagi perkembangan budaya dan peradabannya. Allahumma shalli alaa Muhammadin ‘abdika warasulika nabiyyil ummi wa’alaa aalihii wa sallim.
Identitas Budaya Aceh yang Berlandaskan Islam
Islam menjadi elemen sentral dalam budaya Aceh. Nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga terintegrasi dalam berbagai aspek budaya, seperti adat istiadat, seni, dan hukum. Prinsip “adat bak po teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala” menggambarkan bagaimana adat istiadat Aceh berjalan berdampingan dengan syariat Islam, menciptakan sistem sosial yang harmonis.
Tradisi seperti peusijuek (ritual tepung tawar) mencerminkan penghormatan kepada Allah SWT dan permohonan keberkahan dalam setiap peristiwa penting, seperti pernikahan, pembangunan rumah, atau kelahiran. Dalam seni, kesenian seperti seudati, rapa’i, dan rateb meuseukat membawa pesan-pesan religius yang mengajarkan nilai-nilai keislaman melalui gerak dan lantunan syair.
Aceh terdiri dari berbagai suku, seperti Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, dan Simeulue, yang masing-masing memiliki tradisi khas. Keberagaman ini memperkaya budaya Aceh dengan warisan lokal yang unik. Masyarakat Gayo, misalnya, memiliki seni didong, yakni perpaduan puisi, lagu, dan tarian yang sering digunakan untuk menceritakan kisah atau menyampaikan pesan moral. Di Simeulue, tradisi smong (kearifan lokal tentang tsunami) diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk perlindungan terhadap bencana alam. Di gampong-gampong (sebutan untuk perdesaan), tradisi meuripee (gotong royong) menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong ini tidak hanya mencerminkan solidaritas sosial, tetapi juga memperkuat hubungan manusia dengan lingkungan.
Seni Kuliner dan Pakaian Tradisional
Budaya Aceh juga tercermin dalam seni kuliner dan pakaian tradisional. Kuliner Aceh terkenal dengan cita rasanya yang kaya rempah, seperti pada hidangan kari kambing, mie Aceh, dan kuah pliek u. Makanan-makanan ini tidak hanya mencerminkan kekayaan sumber daya alam Aceh, tetapi juga pengaruh sejarah perdagangan rempah-rempah dengan dunia luar. Dalam hal pakaian, baju adat Aceh seperti bajeu meukasah untuk pria dan bajeu kurung untuk wanita mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan keindahan. Pakaian ini sering dihiasi dengan sulaman emas dan motif tradisional yang memiliki makna simbolis.
Pengaruh Sejarah dan Globalisasi
Sejarah Aceh sebagai salah satu pusat peradaban di Asia Tenggara meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya masyarakatnya. Sebagai salah satu pintu masuk Islam di Nusantara, Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di wilayah ini. Hubungan dagang dengan bangsa Arab, Cina, Eropa dan Hindustan membawa pengaruh budaya yang memperkaya tradisi lokal Aceh. Namun, di era modern, globalisasi membawa tantangan baru bagi pelestarian budaya Aceh. Masuknya budaya asing melalui media dan teknologi mengancam beberapa tradisi lokal yang mulai terpinggirkan. Oleh karena itu, upaya revitalisasi budaya, seperti festival budaya Aceh dan pengajaran adat di dayah (pondok pesantren), madrasah (sekolah-sekolah), menjadi sangat penting untuk mempertahankan identitas Aceh.
Lingkungan Aceh sebagai Inspirasi Budaya
Sejak dahulu, masyarakat Aceh hidup berdampingan dengan alam dan menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya. Laut, misalnya, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat pesisir. Tradisi nelayan Aceh, seperti khanduri laoet (syukuran laut), adalah wujud penghormatan kepada laut sebagai sumber kehidupan. Khanduri ini juga mencerminkan harmoni antara manusia dan lingkungan, sekaligus mengajarkan nilai-nilai religius dan kebersamaan dalam masyarakat. Di pedalaman, hutan dan pegunungan menjadi penopang kehidupan masyarakat agraris Aceh. Sistem pertanian tradisional seperti tengku jahò (ladang berpindah) menunjukkan kearifan lokal masyarakat Aceh dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan air untuk sawah melalui sistem irigasi tradisional yang disebut keujreun blang juga mencerminkan bagaimana budaya Aceh menyesuaikan diri dengan kondisi geografisnya.
Pengaruh Peradaban terhadap Budaya dan Lingkungan Aceh
Sejarah panjang Aceh sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam membawa pengaruh besar terhadap hubungan budaya dan lingkungan. Pada masa Kesultanan Aceh, pelabuhan-pelabuhan seperti Banda Aceh dan Sabang menjadi simpul pertemuan berbagai budaya dari Arab, China, dan Eropa dan Hindustan. Perdagangan rempah-rempah seperti lada, yang tumbuh subur di lingkungan tropis Aceh, tidak hanya memperkaya ekonomi, tetapi juga membentuk budaya lokal yang menghargai kelimpahan alam.
Islam, yang menjadi identitas utama masyarakat Aceh, juga memengaruhi cara pandang mereka terhadap lingkungan. Nilai-nilai dalam ajaran Islam seperti menjaga keseimbangan (mizan) dan tidak berlebihan (israf) tercermin dalam praktik budaya masyarakat Aceh. Tradisi seperti peusijuek (tepung tawar) yang sering dilakukan dalam kegiatan penting menunjukkan bagaimana alam dan budaya saling mendukung dalam menciptakan harmoni. Namun, pengaruh peradaban modern membawa tantangan baru bagi hubungan ini. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi sumber daya alam seringkali mengabaikan kearifan lokal, mengancam keseimbangan lingkungan, dan mengikis budaya tradisional. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masif pasca-tsunami 2004 juga mengubah lanskap lingkungan Aceh, menuntut adaptasi budaya baru.
Interaksi Dinamis Budaya Aceh dan Lingkungan
Budaya Aceh selalu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan peradaban. Misalnya, bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 tidak hanya menghancurkan fisik wilayah ini tetapi juga memengaruhi budaya masyarakatnya. Dalam menghadapi trauma dan kerusakan lingkungan, masyarakat Aceh menghidupkan kembali nilai-nilai lokal seperti meuripee (gotong royong) dan memperkuat tradisi keagamaan sebagai cara bertahan dan bangkit.
Selain itu, perubahan iklim global mulai dirasakan di Aceh. Komunitas pesisir menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut, sementara petani di pedalaman harus beradaptasi dengan pola cuaca yang tidak menentu. Dalam konteks ini, revitalisasi budaya lokal yang ramah lingkungan menjadi semakin penting. Tradisi seperti Uteun Adat (Hutan Larangan Adat) dan pengelolaan sumber daya berbasis mukim menawarkan solusi lokal yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara budaya, lingkungan, dan peradaban.
Kearifan lokal masyarakat Aceh mencerminkan hubungan yang erat antara budaya dan lingkungan. Tradisi seperti khandurie laoet (syukuran laut) menunjukkan rasa syukur masyarakat pesisir kepada Allah SWT atas hasil laut yang melimpah. Selain itu, sistem adat seperti Uteun Adat (Hutan Larangan Adat) dan pengelolaan sawah berbasis komunitas melalui keujreun blang (Komunitas Tradisioanl Urusan Pertanian) menunjukkan bagaimana budaya Aceh menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pasca-tsunami 2004, masyarakat Aceh juga menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka dengan memadukan tradisi lokal dan bantuan global. Peristiwa ini memperkuat nilai gotong royong dan ketabahan yang menjadi ciri khas budaya Aceh.
Budaya sebagai Respons terhadap Lingkungan
Pada awal peradaban, manusia sangat bergantung pada lingkungan alam. Cara hidup nomaden masyarakat pemburu-pengumpul misalnya, terbentuk karena mereka harus berpindah-pindah untuk mencari sumber makanan. Ketika manusia mulai bercocok tanam, budaya agraris pun berkembang, menyesuaikan dengan kondisi tanah, iklim, dan ketersediaan air. Ritual-ritual seperti upacara meminta hujan atau syukuran panen mencerminkan bagaimana manusia menghormati alam sebagai sumber kehidupan mereka.
Keberadaan sungai besar di Aceh seperti Krueng (Sungai) Daroy di Banda Aceh cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam, Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara juga menjadi hilir sungai bagi Kesultanan Samudera Pase, Krueng Peureulak di Kabupaten Aceh Timur juga menjadi cikal bakal Kesultanan Peurerulak, mendorong lahirnya budaya peradaban besar yang mengandalkan irigasi. Pemanfaatan lingkungan secara terorganisasi melahirkan sistem sosial dan teknologi, seperti kalender untuk menentukan waktu tanam dan panen. Dengan demikian, budaya dapat dilihat sebagai adaptasi kreatif manusia terhadap lingkungan.
Pengaruh Peradaban terhadap Lingkungan
Seiring berkembangnya teknologi dan peradaban, hubungan antara budaya dan lingkungan mengalami pergeseran. Pada era Revolusi Industri, manusia mulai mengeksploitasi sumber daya alam secara masif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan. Budaya konsumtif yang lahir dari peradaban modern menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan perubahan iklim.
Namun, peradaban juga menciptakan budaya baru yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Gerakan pelestarian lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sampah berbasis daur ulang, menunjukkan bahwa peradaban modern mampu menciptakan budaya yang mendukung keseimbangan alam. Bahkan, budaya tradisional masyarakat adat yang mengutamakan harmoni dengan alam kini kembali menjadi inspirasi bagi solusi global terhadap krisis lingkungan.
Interaksi Dinamis antara Budaya, Lingkungan, dan Peradaban
Interaksi antara budaya, lingkungan, dan peradaban selalu bersifat dinamis. Di satu sisi, budaya manusia dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ekologi tempat mereka tinggal. Di sisi lain, manusia dengan peradabannya dapat mengubah atau bahkan menciptakan lingkungan baru. Contoh nyata adalah pembangunan kota-kota metropolitan yang mengubah bentang alam menjadi area urban. Hal ini menuntut manusia menciptakan budaya perkotaan yang mengatasi tantangan lingkungan baru, seperti polusi udara dan manajemen limbah.
Selain itu, perubahan iklim akibat ulah manusia juga mulai memengaruhi kembali budaya dan peradaban. Masyarakat pesisir, misalnya, harus mengubah cara hidup mereka akibat naiknya permukaan air laut. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan budaya dengan lingkungan tidak pernah berhenti berkembang dan terus saling memengaruhi.
Kesimpulan
Hubungan budaya Aceh dengan lingkungan menjadi cerminan dari kemampuan masyarakatnya untuk beradaptasi dengan tantangan alam dan peradaban. Lingkungan yang kaya memberikan inspirasi bagi budaya Aceh, sementara nilai-nilai Islam dan pengaruh peradaban modern membentuk cara masyarakatnya memandang dan memanfaatkan alam. Di tengah tantangan global, Aceh memiliki potensi besar untuk memadukan kearifan lokal dengan inovasi modern demi menciptakan harmoni antara budaya dan lingkungan. Hal ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan Aceh, tetapi juga menjadi kontribusi berharga bagi peradaban dunia.
Budaya dan lingkungan juga yang dipengaruhi oleh peradaban adalah cerminan dari perjalanan panjang manusia dalam memahami dan mengelola dunia tempat mereka hidup. Peradaban memberikan kemampuan bagi manusia untuk mengolah lingkungan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk melestarikannya. Dalam konteks global saat ini, upaya menciptakan budaya keberlanjutan adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara peradaban dan alam. Harmonisasi antara budaya, lingkungan, dan peradaban Islam tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga kunci bagi kelangsungan hidup generasi mendatang.
Budaya Aceh merupakan cerminan dari kekayaan sejarah, nilai-nilai Islam, dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi harmoni antara manusia, agama, dan alam. Di tengah arus modernisasi, budaya Aceh menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan dan lestari. Namun, dengan upaya pelestarian dan penguatan identitas budaya, Aceh dapat terus menjadi contoh bagaimana tradisi dan nilai religius mampu bertahan sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman. Budaya Aceh bukan hanya warisan, tetapi juga aset berharga bagi peradaban Indonesia dan dunia.
Sebelum kami tutup, ingin berbagi dua pantun, sebagai berikut :
Minum kopi di pagi hari,
Kopi Gayo harum mewangi.
Budaya Aceh kita jaga diri,
Warisan leluhur tetap lestari.
Bermain layang di kala senja,
Angin berbisik di pantai lancok bayu.
Aceh Serambi Mekkah yang indah berjasa,
Adat budaya dan syariat terpadu selalu.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq, billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Samudera Pase, Aceh Utara, 15 Desember 2024/ 14 Jumadil Akhir 1446 H

Harmoni antara Tradisi dan Modernitas
di Kasepuhan Ciptagelar
Oleh:Nur Muhammad Ghifari, S.Pt. (Universitas Indonesia)
Kasepuhan Ciptagelar merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat adat dapat berkontribusi dalam mencapai swasembada pangan dengan cara yang berkelanjutan. Dengan memiliki sekitar 8.000 lumbung padi, komunitas ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kuantitas produksi, tetapi juga pada kualitas hubungan antara manusia dan alam. Menariknya, dalam pandangan masyarakat adat ini, keberadaan hama seperti tikus dan burung bukanlah ancaman yang harus dimusnahkan, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang harus dihormati. Mereka memahami bahwa memaksakan panen tiga kali setahun, sesuai dengan standar pertanian modern, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berujung pada kegagalan panen.
Dalam konteks ini, penting untuk mencermati bagaimana pengetahuan ilmiah dan pengalaman tradisional dapat bersinergi. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar percaya bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan rasa memiliki nilai yang tinggi, bahkan lebih dari sekadar data empiris. Hal ini sejalan dengan pandangan filsafat pengetahuan yang menyatakan bahwa pemahaman mendalam tentang kehidupan sering kali berasal dari pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Ketika Kang Yoyo mengungkapkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami hal-hal batin, ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern dalam menghargai kearifan lokal yang telah ada sejak lama.
Dengan demikian, Kasepuhan Ciptagelar memberikan pelajaran penting tentang bagaimana menjaga tradisi sambil tetap membuka diri terhadap kemajuan sains. Keseimbangan antara pengetahuan saintifik dan kearifan lokal bukan hanya penting untuk keberlanjutan pertanian, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Di tengah arus modernisasi yang cepat, kita perlu belajar dari mereka yang telah berhasil menemukan harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

Desa Adat Ciptagelar :
Harmoni Tradisi dan Kemajuan Modern
Oleh : Muhammad Saddam Husein, S.Pi., CSCM. (IPB University)
Desa Adat Ciptagelar: Harmoni Tradisi dan Kemajuan Modern
Desa Adat Ciptagelar, yang terletak di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu perkampungan adat yang masih menjaga tradisi leluhur Sunda dengan ketat. Sebagai bagian dari komunitas Kasepuhan Banten Kidul, Ciptagelar memancarkan daya tarik unik berupa harmoni antara kebudayaan tradisional dengan tantangan modernitas.
Kehidupan yang Bersandar pada Tradisi
Desa Ciptagelar terkenal karena masyarakatnya yang masih setia menjalankan adat dan ritual yang diwariskan turun-temurun. Salah satu tradisi utama adalah Seren Taun, yaitu upacara panen padi sebagai wujud syukur kepada Dewi Sri, dewi kesuburan dalam kepercayaan Sunda. Dalam ritual ini, masyarakat tidak hanya mempersembahkan hasil bumi, tetapi juga memadukan seni tradisional seperti tarian dan musik gamelan dengan nilai-nilai spiritual.
Padi memiliki makna sakral bagi masyarakat Ciptagelar. Mereka masih mempraktikkan sistem pengelolaan pertanian tradisional, seperti penggunaan lumbung untuk menyimpan padi tanpa dijual ke pasar komersial. Sistem ini mencerminkan filosofi hidup mereka, yaitu hidup cukup, tidak serakah, dan menghormati alam.
Pemimpin Karismatik dan Struktur Sosial
Desa Ciptagelar dipimpin oleh seorang kasepuhan (tetua adat) yang dihormati sebagai simbol kebijaksanaan dan penjaga tradisi. Kasepuhan bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga tokoh yang menjaga kelangsungan adat dalam menghadapi arus perubahan. Kepemimpinan ini memainkan peran penting dalam memelihara keteraturan sosial sekaligus memberikan panduan dalam mengadopsi teknologi modern secara bijaksana.
Kemajuan Teknologi di Tengah Tradisi
Meskipun menjunjung tinggi adat istiadat, Ciptagelar tidak menolak kemajuan teknologi. Desa ini telah mengembangkan jaringan listrik tenaga mikrohidro secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengadopsi inovasi tanpa merusak nilai-nilai adat yang menjadi landasan hidup mereka.
Teknologi ini digunakan secara selektif, misalnya untuk penerangan, komunikasi, dan pendidikan, namun tidak mengubah cara hidup masyarakat yang bersandar pada nilai spiritual dan kearifan lokal.
Daya Tarik Wisata Budaya
Ciptagelar juga menjadi destinasi wisata budaya yang menarik bagi para pelancong yang ingin merasakan suasana hidup tradisional. Pengunjung dapat belajar tentang cara bercocok tanam, menyaksikan ritual adat, dan memahami filosofi hidup yang menghormati alam dan sesama.
Namun, kehadiran wisatawan juga menjadi tantangan. Desa ini harus menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap pengunjung dan perlindungan nilai-nilai adat. Pengelolaan wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan menjadi salah satu solusi agar Ciptagelar tetap lestari.
Pelajaran dari Ciptagelar
Desa Adat Ciptagelar adalah contoh nyata bagaimana tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan. Dengan memelihara adat, masyarakatnya mampu mempertahankan identitas budaya di tengah globalisasi. Di sisi lain, adopsi teknologi menunjukkan bahwa mereka tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, melainkan siap untuk menghadapi masa depan.
Desa Ciptagelar mengajarkan bahwa harmoni antara manusia, budaya, dan alam adalah kunci untuk hidup yang berkelanjutan. Dalam era yang penuh dengan eksploitasi dan kerusakan lingkungan, model hidup Ciptagelar dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk kembali menghormati alam dan menjaga warisan budaya leluhur.

Dewi Sri: Konsep Keseimbangan Hidup
sebagai Warisan Abadi Tradisi Leluhur di Era Modernitas dan Teknologi
Oleh : Yuniana Cahyaningrum, S.Kom., M.Kom. (Institut Seni Indonesia Surakarta)
Dewi Sri, dalam tradisi Nusantara, adalah simbol kesuburan, kemakmuran, dan keseimbangan hidup. Sosoknya tidak hanya dihormati sebagai dewi padi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Warisan leluhur yang diwariskan melalui mitos Dewi Sri sejatinya mengajarkan konsep keseimbangan yang relevan dengan kehidupan modern, khususnya di era modernitas dan perkembangan teknologi. Dalam tradisi agraris, Dewi Sri dipuja sebagai pemberi kehidupan. Ritual-ritual adat seperti Seren Taun di masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, atau tradisi Wiwitan sebelum panen, adalah wujud penghormatan kepada Dewi Sri. Upacara-upacara ini tidak hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga pengingat akan hubungan erat manusia dengan alam. Filosofi ini mengajarkan bahwa kehidupan yang seimbang hanya dapat tercapai jika manusia mampu menjaga alam dengan bijaksana.
Namun, era modernitas dan perkembangan teknologi membawa tantangan baru. Perubahan gaya hidup yang semakin berorientasi pada kemudahan dan efisiensi sering kali mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Teknologi canggih memang memberikan solusi praktis, tetapi di sisi lain, sering menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan dan mengurangi penghargaan terhadap tradisi. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang diusung Dewi Sri menjadi sangat relevan. Ketika manusia menghadapi krisis lingkungan, konsumerisme, dan ketimpangan sosial, warisan leluhur tentang keseimbangan hidup menjadi pedoman yang berharga. Dewi Sri mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati bukan hanya soal materi, tetapi juga harmoni dengan lingkungan dan hubungan yang baik dengan sesama.
Mengintegrasikan nilai-nilai Dewi Sri ke dalam kehidupan modern tidak berarti menolak perkembangan teknologi, tetapi menjadikannya alat untuk mendukung pelestarian keseimbangan. Misalnya, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertanian berkelanjutan, melestarikan tradisi melalui digitalisasi, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Sayangnya, nilai-nilai ini sering tergerus oleh arus modernitas. Tradisi penghormatan kepada Dewi Sri mulai terlupakan di beberapa wilayah. Padahal, esensi dari ajaran ini bukanlah sekadar ritual, tetapi filosofi kehidupan yang mampu menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal kembali warisan leluhur ini, tidak hanya sebagai bagian dari budaya, tetapi juga sebagai solusi atas tantangan global.
Melalui simbol Dewi Sri, kita diajak untuk merenungkan kembali makna keseimbangan dalam hidup. Menjaga tradisi bukan berarti menolak modernitas, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai luhur ke dalam kehidupan masa kini. Dengan memahami dan menerapkan filosofi Dewi Sri, kita dapat membangun kehidupan yang lebih selaras, baik dengan diri sendiri, alam, maupun sesama manusia.

Menjaga Tatanan Leluhur
dalam Perubahan Zaman Kesepuhan Cipta Gelar “Swasembada Energi dan Pangan Berkelanjutan”
Oleh: Tirta Yoga, SP., MP. (Agribisnis, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang CEO Bakultani)
Meneruskan titipan Leluhur dan Filosofi kehidupan di Kesepuhan Ciptagelar berlokasi di pedalaman Jawa Barat sejak tahun 1368 sampai tahun sebelumnya. Sebagai sebuah kesatuan yang erat dengan adat istiadat dan tradisi leluhur, masyarakat Ciptagelar memegang teguh nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Kehidupan di Kasepuhan Ciptagelar bukan hanya soal menjaga tradisi, tetapi lebih jauh lagi tentang menghidupkan kembali dan melestarikan prinsip-prinsip kehidupan yang sudah lama terkubur oleh arus modernisasi. Sebagai generasi penerus, mereka menjalani tugas suci untuk menjaga dan melanjutkan kehidupan yang pernah ditinggalkan oleh para leluhur mereka, sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan yang tak ternilai harganya.
Kesepuhan Ciptagelar menjadi saksi dari berbagai perubahan besar dari sejahrah Indonesia. Kese[uhan Cipta gelar menjalani kehidupan drngan berpijak pada nilai-nilai luhur yang diwarisikan oleh para leluhurnya, yang meliputi keseimbangan antara alam dan manusia. Sebuah wangsit pada tahun 1982, menjadi salah satu tonggal penting dalam perjalanan Kesepuhan Ciptagelar, sebuah petunjuk dari leluhur untuk turun memerintahkan untuk mengembalikan tatanan leluhur yang telah lama sembunyi. Wangsit ini menandakan sebuah panggilan untuk memperbaharui dan melanjutkan perjalanan hidup masyarakat Ciptagelar dalam keselarasan dengan nilai-nilai tradisional yang telah ada.
Tatanan leluhur ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan hidup, tetapi juga sebagai pemersatu masyarakat Ciptagelar dalam menghadapi era modern yang semakin mendominasi. Dalam pengertiannya, tatanan leluhur mengandung prinsip dasar yang berfokus pada keseimbangan hidup, baik dalam hubungan dengan alam, sesama manusia, maupun antara tradisi dan modernitas. Kasepuhan Ciptagelar berupaya untuk menghadirkan kembali keseimbangan yang telah lama hilang, yang dahulu menjadi ciri khas kehidupan bangsa Timur yang lebih mengutamakan nilai-nilai spiritual dan kolektivitas.
Simbolisme Dewi Sri: Keseimbangan dalam Kehidupan
Salah satu simbolisme yang kuat dalam Kasepuhan Ciptagelar adalah konsep Dewi Sri, yang melambangkan keseimbangan antara dua sisi kehidupan. Dewi Sri, yang dalam bahasa Sanskerta berarti “Dwi” (dua) dan “Sri” (seimbang), mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari alam dan tanah. Sebagai simbol dari kesuburan, Dewi Sri mengajarkan bahwa manusia hidup oleh padi, dan padi hidup oleh bumi yang dikelola dengan penuh perhatian dan penghormatan.
Dalam kehidupan Kesepuhan Ciptagelar, konsep keseimbangan ini diterapkan pada segala aspek kehidupan, dari cara berinteraksi dengan alam, hingga cara menjalani kehidupan sosial dan spiritual. Hidup tidak hanya tentang mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan baik jiwa dan raga, tradisi dan modernitas, serta alam dan manusia. Dengan prinsip ini, Kesepuhan Ciptagelar mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci untuk mencapai hidup yang harmonis dan berkelanjutan.
Proses Ngalalakon: Menjaga Tradisi dalam Perubahan Zaman
Salah satu aspek penting dalam kehidupan Kasepuhan Ciptagelar adalah proses yang dikenal sebagai ngalalakon, yaitu perjalanan spiritual dan fisik yang diambil oleh masyarakat untuk berpindah tempat sesuai dengan perintah leluhur. Proses ini adalah simbol dari perubahan zaman, di mana masyarakat harus berpindah dan beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, meskipun mengalami perubahan, prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh leluhur tetap dijaga dan dilestarikan.
Pada tahun 1982, Kesepuhan menjalani proses ngalalakon yang sangat penting, yaitu peralihan dari cara hidup analog ke digital. Hal ini mencerminkan transformasi besar dalam kehidupan, dimana berusaha untuk berusaha untuk mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai tradisional yang sudah ada sejak lama. Perubahan ini mengajarkan bahwa meskipun dunia terus berubah, esensi dari kehidupan yang dijalani harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang telah ada.
Laku Hidup dan Kearifan dalam Bertani
Kesepuhan Ciptagelar sangat bergantung pada prinsip-prinsip leluhur. Bertani setahun sekali dengan berpatokan pada pergerakan rasi bintang, yang menjadi petunjuk waktu untuk memulai menanam padi. Tidak ada konsep pertanian komersial yang dipaksakan, karena menganggap bahwa bumi sebagai ibu bumi dan bapak merupakan bapak langit. Seorang ibu hanya dapat melahirkan satu kali dalam setahun. Padi yang ditanam, adalah simbol dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga dengan penuh kesadaran. Dengan Bertani setahun sekali, Kesepuhan Ciptagelar mengajarkan pentingnya sabra dan bijaksana dalam mengelola sumber daya alam. Tanah tidak boleh dipaksakan untuk memberi hasil yang berlebihan dalam waktu singkat, melainkan harus diberi waktu untuk pulih dan menghasilkan kembali di musim berikutnya. Ini adalah filosofi yang mendalam tentang kelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dalam kehidupan modern yang seringkali mengejar hasil instan dan konsumsi berlebihan, prinsip ini menjadi pengingat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Merajut Kearifan Lokal, Ekonomi, dan Keberlanjutan Lingkungan
Menuju Ketahanan Pangan Nasional
Oleh : Eko Sutrisno, S.Si., M.Si (Universitas Islam Majapahit Mojokerto Jawa Timur)
Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan potensi alam dan sumber daya manusia yang besar. Sebagai sektor yang telah menjadi identitas bangsa, pertanian memiliki peran sentral dalam menyokong perekonomian nasional, menyediakan lapangan pekerjaan, serta memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan modernisasi teknologi, kearifan lokal dalam pertanian seharusnya menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Menyebut dirinya sebagai negara agraris, kondisi pertanian Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kompleks. Adanya upaya peningkatan produktivitas pertanian sering kali mengorbankan nilai-nilai lokal dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, kearifan lokal yang penuh makna syukur kepada Tuhan mulai tergerus oleh arus industrialisasi pertanian yang serba instan. Jika situasi ini terus berlanjut, tujuan besar mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional akan semakin sulit dicapai.
Kearifan Lokal sebagai pilar filosofis pertanian yang penuh syukur
Kearifan lokal dalam pertanian Indonesia bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga mencerminkan filosofi mendalam tentang hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Sejak dahulu, para petani di berbagai wilayah Indonesia memiliki pemahaman bahwa tanah, air, dan hasil panen adalah anugerah yang harus dihargai. Rasa syukur ini diwujudkan dalam berbagai ritual dan praktik pertanian tradisional yang berlandaskan pada harmoni dengan alam.
Di Bali, sistem Subak bukan hanya tentang distribusi air secara adil melalui saluran irigasi. Lebih dari itu, Subak adalah sebuah konsep yang melibatkan nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Para petani percaya bahwa menjaga keseimbangan antara manusia (pawongan), alam (palemahan), dan Tuhan (parahyangan) adalah kunci keberhasilan dalam bertani. Upacara tumpek bubuh, misalnya, dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Hyang Widhi atas berkah tanaman yang tumbuh subur. Beberapa wilayah di Jawa Timur, ada budaya Kawit dan wiwit, yaitu tradisi dalam pertanian padi di Jawa yang sarat makna religius, kearifan lokal, dan budaya. Kawit menandai awal musim tanam, sementara wiwit adalah ritual syukur saat panen pertama tiba. Dalam konteks keagamaan, tradisi ini mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan melalui padi, simbol kehidupan dan kesejahteraan. Secara budaya, wiwit menguatkan solidaritas sosial dengan melibatkan doa, sesajen, dan kenduri bersama. Kearifan lokal tercermin dalam harmoni antara manusia dan alam, memastikan kelestarian lingkungan serta menjaga siklus pertanian. Tradisi ini memperkaya nilai spiritual dan kebersamaan dalam kehidupan petani Jawa.
Selain Subak, wiwit dan kawit, praktik tumpangsari di berbagai daerah Indonesia juga mencerminkan kebijaksanaan lokal. Praktek menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, petani mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi risiko gagal panen, serta meningkatkan keanekaragaman pangan. Tradisi mapadendang di Sulawesi Selatan, yakni pesta pascapanen yang penuh suka cita, juga menggambarkan bagaimana rasa syukur menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan petani. Sayangnya, seiring dengan perkembangan zaman, banyak nilai kearifan lokal tersebut mulai ditinggalkan. Praktik pertanian modern yang mengandalkan pupuk kimia, pestisida sintetis, dan teknologi mekanisasi sering kali melupakan aspek keberlanjutan lingkungan. Selain itu, generasi muda semakin jauh dari dunia pertanian, karena menganggapnya sebagai profesi yang kurang menguntungkan dan tidak bergengsi.
Modernisasi Pertanian dan Tantangan Kerusakan Lingkungan
Modernisasi pertanian memang membawa dampak positif dalam meningkatkan produktivitas pangan. Introduksi teknologi mekanisasi, penggunaan pupuk kimia, serta pengembangan varietas unggul telah membantu Indonesia meningkatkan hasil panen dalam beberapa dekade terakhir. Namun, keberhasilan ini datang dengan harga yang mahal, yakni kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan telah menyebabkan penurunan kualitas tanah dan pencemaran sumber air. Sifat tanah yang semula subur dan kaya nutrisi kini semakin tandus dan bergantung pada input kimia. Hal ini menyebabkan biaya produksi petani semakin tinggi, sementara hasil yang didapat cenderung stagnan dalam jangka panjang.
Praktik monokultur, yang hanya menanam satu jenis tanaman dalam skala besar, telah menghilangkan keanekaragaman hayati di lahan pertanian. Monokultur memang efisien secara ekonomi dalam jangka pendek, tetapi rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, praktik ini menguras unsur hara tanah lebih cepat, sehingga memerlukan pemupukan yang lebih intensif. Tidak hanya itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perkotaan, atau properti juga menjadi tantangan serius. Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 90.000 hektare lahan pertanian produktif hilang akibat konversi lahan. Jika tren ini tidak diatasi, maka Indonesia berpotensi kehilangan sumber pangan lokal dan semakin bergantung pada impor pangan dari negara lain.
Di tengah kontribusi besar sektor pertanian bagi perekonomian nasional, kondisi ekonomi para petani kecil masih memprihatinkan. Petani, yang merupakan aktor utama dalam produksi pangan, sering kali berada dalam posisi yang rentan. Harga jual hasil panen yang tidak stabil, tingginya biaya produksi, serta minimnya akses terhadap teknologi dan pasar adalah beberapa permasalahan yang dihadapi. Rantai distribusi hasil pertanian dalam sistem pertanian konvensional cenderung panjang, sehingga keuntungan terbesar justru dinikmati oleh perantara atau pedagang besar. Petani sebagai produsen utama sering kali hanya menerima nilai ekonomi yang rendah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan yang berpihak pada petani kecil. Adanya reformasi dalam kebijakan pertanian perlu diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Petani harus mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan akses teknologi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Pemerintah juga perlu memastikan adanya stabilisasi harga hasil pertanian serta dukungan dalam bentuk subsidi dan kredit usaha tani.
Menuju Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Kearifan Lokal dan Keberlanjutan
Ketahanan pangan nasional adalah cita-cita besar yang hanya bisa dicapai jika seluruh komponen bangsa berkolaborasi. Dalam hal ini, pertanian berkelanjutan harus menjadi fondasi utama. Pertanian berkelanjutan adalah sistem yang memadukan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan kebutuhan pangan terpenuhi tanpa merusak sumber daya alam. Kearifan lokal dalam pertanian seharusnya diintegrasikan dengan teknologi modern yang ramah lingkungan. Contohnya, penggunaan pupuk organik dan teknologi precision farming dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Sistem irigasi hemat air, pengelolaan tanah berbasis agroekologi, serta praktik diversifikasi pangan juga harus didorong secara masif.
Pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merevitalisasi kearifan lokal yang mulai terpinggirkan. Kearifan lokal tidak boleh hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai solusi konkret untuk mengatasi tantangan pertanian modern. Generasi muda harus diberikan pemahaman bahwa bertani bukan sekadar profesi, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan dan kelestarian lingkungan.

Membangun Jurnalis Hijau
yang Progresif dan Profesional
Oleh: Adhifatra Agussalim
Praktisi Jurnalis, Pemimpin Redaksi Media Online, Associate member Institute of Compliance Professional Indonesia (ICOPI), Anggota Asosiasi Media Digital Indonesia (AMDI), Sekretaris DPW Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Aceh, member of Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), anggota dari Institute of Internal Auditor (IIA), UKW Wartawan Muda,
Mukaddimah
Bismillahirrahmanirrahim, Sangat Menarik paparan pertemuan pertama pada Short Course, Certified of Environmental Management Leadership Batch 3 dengan Tema Swasembada Energi dan Pangan Yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan, Pendekatan yang kami ambil mengenai potensi jurnalis hijau masuk dalam tatanan dan advokasi mewujudkan tema diatas. Dalam era yang semakin terfokus pada keberlanjutan dan kesadaran lingkungan, peran jurnalis hijau menjadi semakin penting. Jurnalis hijau merupakan mereka yang secara khusus meliput isu-isu lingkungan, iklim, keberlanjutan, dan dampak dari perubahan lingkungan terhadap masyarakat. Di tengah krisis iklim global, penggundulan hutan, polusi, dan degradasi lingkungan lainnya, kebutuhan akan liputan yang akurat, mendalam, dan berwawasan luas semakin mendesak. Oleh karena itu, membangun jurnalis hijau yang modern dan profesional adalah langkah penting dalam memperkuat peran media sebagai penjaga keberlanjutan planet. Allahumma shalli alaa Muhammadin ‘abdika warasulika nabiyyil ummi wa’alaa aalihii wa sallim.
Mengapa Jurnalis Hijau Penting?
Isu lingkungan dan keberlanjutan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kehidupan manusia, ekonomi, dan masa depan planet ini. Namun, isu-isu ini sering kali sulit dipahami oleh masyarakat luas karena kompleksitasnya. Jurnalis hijau memainkan peran vital dalam menerjemahkan data ilmiah yang rumit menjadi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Kedua, mampu menyuarakan suara komunitas lokal yang terdampak oleh perubahan lingkungan, seperti masyarakat adat atau petani yang terancam oleh perubahan iklim. Ketiga, mengawasi kebijakan pemerintah dan perusahaan, memastikan bahwa komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dijalankan dengan baik. Terakhir, mampu membangun kesadaran publik tentang isu-isu penting seperti pemanasan global, deforestasi, dan pencemaran air serta udara. Tanpa adanya liputan yang profesional dan mendalam dari jurnalis hijau, banyak isu lingkungan akan tenggelam di balik liputan berita lainnya, sehingga masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau memahami urgensi permasalahan tersebut.
Tantangan yang Dihadapi Jurnalis Hijau
Jurnalis hijau dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa tantangan utama yang mereka hadapi antara lain:
- Kompleksitas Isu Lingkungan, isu-isu lingkungan sering kali melibatkan data ilmiah yang kompleks dan terkadang sulit untuk dijelaskan kepada khalayak umum. Jurnalis hijau harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang lingkungan, sains, dan teknologi untuk menyampaikan informasi ini dengan cara yang dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
- Tekanan Ekonomi dan Politik, Jurnalis hijau sering kali harus melawan tekanan dari pemerintah atau perusahaan yang mungkin tidak ingin tindakan mereka terkait lingkungan diungkapkan. Liputan kritis tentang polusi, deforestasi, atau kegiatan perusahaan yang merusak lingkungan bisa menghadapi penolakan, sensor, atau ancaman hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- Minimnya Pelatihan Khusus, Banyak jurnalis hijau bekerja tanpa pelatihan formal yang cukup dalam bidang lingkungan atau keberlanjutan. Mereka mungkin kurang memahami metode penelitian ilmiah atau dampak jangka panjang dari isu-isu lingkungan yang sedang mereka liput, sehingga sulit untuk memberikan analisis yang mendalam.
Membangun Jurnalis Hijau yang Modern dan Profesional
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis untuk membangun jurnalis hijau yang modern, profesional, dan berdaya saing di era digital. Beberapa langkah penting yang dapat diambil antara lain:
- Diklat Berkelanjutan, salah satu cara utama untuk membangun jurnalis hijau yang profesional adalah melalui Diklat yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Pelatihan ini bisa mencakup, dasar-dasar ilmiah tentang perubahan iklim, polusi, dan konservasi alam sehingga jurnalis memiliki pemahaman yang kuat tentang topik yang mereka liput, selanjutnya adanya pelatihan metodologi penelitian untuk memastikan bahwa laporan mereka berdasarkan data yang akurat dan dapat diverifikasi dan juga pelatihan multimedia agar jurnalis dapat menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan dapat diakses di platform digital, termasuk melalui infografik, video, dan media sosial.
- Membangun Jaringan Jurnalis Hijau, Jurnalis hijau perlu memiliki jaringan kolaborasi yang kuat dengan sesama jurnalis, ilmuwan, dan organisasi lingkungan. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, mereka dapat memperkuat laporan mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, kolaborasi internasional juga penting, mengingat isu-isu lingkungan sering kali bersifat global.
Kerjasama dengan LSM lingkungan dapat memberikan akses kepada data dan wawasan yang lebih dalam. Jaringan jurnalis lintas negara dapat membantu dalam peliputan isu-isu lingkungan yang melintasi batas-batas geografis, seperti perubahan iklim atau pencemaran laut. c. Penguasaan Teknologi dan Inovasi Digital, Dalam era digital, jurnalis hijau harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan dan dampak liputan mereka. Teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan memvisualisasikan data terkait polusi udara, kualitas air, atau deforestasi melalui data journalism, menggunakan drone atau citra satelit untuk meliput kawasan kawasan yang sulit dijangkau secara fisik, seperti hutan tropis atau kawasan industri yang terlarang dan memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik dan membangun gerakan berbasis komunitas yang mendukung keberlanjutan.
- Etika Jurnalistik dan Transparansi, Seorang jurnalis hijau yang profesional harus mematuhi etika jurnalistik yang ketat, terutama dalam melaporkan isu-isu yang sensitif seperti dampak lingkungan dari proyek industri besar. Transparansi dalam sumber informasi dan metodologi yang digunakan juga penting untuk menjaga kepercayaan pembaca. Hindari sensationalism yang dapat menyesatkan atau memperkeruh pemahaman masyarakat tentang isu lingkungan. Laporan berbasis bukti harus menjadi landasan dalam setiap berita yang disampaikan, dengan mengandalkan penelitian yang sahih dan valid.
- Dukungan dari media dan institusi, untuk memajukan jurnalis hijau, dukungan dari media, lembaga pendidikan, dan institusi pemerintah sangat diperlukan. Media perlu memberikan ruang yang cukup untuk peliputan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Lembaga pendidikan harus menyediakan kurikulum yang fokus pada pelatihan jurnalisme hijau, sedangkan pemerintah dapat berkontribusi dengan menciptakan regulasi yang melindungi kebebasan pers terkait isu lingkungan.
Masa Depan Jurnalis Hijau
Seiring dengan semakin menguatnya isu-isu terkait lingkungan dan keberlanjutan, jurnalis hijau memiliki peran yang semakin signifikan dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan kebijakan. Dengan pelatihan yang memadai, jaringan yang kuat, dan pemanfaatan teknologi modern, jurnalis hijau akan menjadi agen perubahan yang mampu menyuarakan kepentingan planet dan masa depan yang lebih hijau. Di masa depan, jurnalis hijau tidak hanya akan berperan sebagai pelapor, tetapi juga sebagai pendidik, penggerak komunitas, dan influencer yang dapat mendorong masyarakat global untuk lebih peduli terhadap lingkungan.
Kesimpulan
Membangun jurnalis hijau yang modern dan profesional membutuhkan pendekatan yang holistik, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga penguatan etika jurnalistik. Di tengah tantangan yang kompleks, jurnalis hijau memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan bumi dan mendorong perubahan kebijakan serta perilaku masyarakat terkait lingkungan. Dengan melibatkan teknologi, memperkuat jaringan, dan terus berinovasi, jurnalis hijau dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju dunia yang lebih lestari.
Sebelum kami tutup, hendaknya berbagi pantun,
Bambu rimbun tumbuh di rawa, Mengalun angin lembut di sana. Jurnalis hijau menjaga dunia, Menulis kabar demi bumi tercinta.
Air mengalir jernih di hulu, Membawa kesejukan bagi yang butuh. Jurnalis hijau terus bersatu, Menyuarakan alam dengan hati yang utuh.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit-thariiq, billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat Samudera Pasai, Aceh Utara, 9 Desember 2024/8 Jumadil Akhir 1446 H

Spiritualitas Memasak
Sebuah Refleksi tentang Berkat untuk Tubuh, Sesama, dan Alam
Oleh: Joyce Heryanto (YMMI)
#SehatmuDimulaiDariDapurmu adalah tagar yang selalu saya gunakan ketika saya mengunggah foto-foto masakan saya di media sosial. Buat sebagian orang memasak sering kali dianggap sebagai aktivitas rutin dan biasa saja, hanya sekadar cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak bagi saya. Bagi saya memasak adalah pintu gerbang utama untuk menuju kesehatan keluarga saya. (Oya, saya tidak jago memasak, tetapi memasak tetap saya lakukan setiap harinya dengan alasan tersebut). Hari ini saya mendapatkan peneguhan dari Pak Iskandar Waworuntu tentang hal-hal terkait memasak yang sudah lama saya pikirkan.
Memasak menyimpan dimensi spiritual yang mendalam. Melalui memasak, kita tidak hanya meracik makanan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keberkahan, kesederhanaan, dan cinta kasih. Dalam Islam, konsep thayyib atau “baik” menjadi landasan untuk memilih makanan yang tidak hanya halal tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh dan jiwa, serta tidak berlebihan yang akhirnya meninggalkan sampah. Demikian pula, dalam tradisi Kristen, Doa Bapa Kami mengajarkan untuk meminta makanan “yang secukupnya,” dasar spiritualitas keseharian bagi kami sekeluarga.
Memasak dapat menjadi berkat bagi tubuh kita. Ketika kita memilih bahan makanan yang segar, alami, dan bermanfaat, kita sedang menghormati tubuh sebagai amanah dari Sang Pencipta. Makanan yang thayyib mencerminkan makanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendukung kesehatan secara menyeluruh. Dengan memasak sendiri, kita bisa memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi tidak terkontaminasi bahan-bahan yang merusak tubuh, seperti penyedap, pewarna buatan, pengawet, pemanis atau zat kimia berbahaya lainnya. Memasak adalah bentuk perhatian penuh pada tubuh untuk menjaga kesehatan dan keharmonisan hidup.
Memasak dapat menjadi berkat untuk sesama. Ketika kita memilih untuk membeli bahan makanan dari petani lokal atau pasar tradisional, kita berkontribusi pada perekonomian komunitas kecil, bukan pada korporasi besar yang kerap mendominasi pasar.
Memasak adalah wujud cinta kasih. Sebuah hidangan yang disiapkan dengan hati bisa menjadi ungkapan perhatian yang tulus kepada keluarga, teman, atau bahkan orang-orang yang membutuhkan. Dalam budaya lokal di Indonesia, berbagi makanan adalah salah satu cara untuk menciptakan koneksi manusiawi yang mendalam. Dalam buku Heaven All Around Us: God in Everyday Life yang ditulis oleh Simon Carey Holt 2, menggambarkan pengalaman religius yang mendalam ketika ia membuka buku resep milik ibunya. Holt menulis, “Ketika saya memegang resep-resep ibu saya, saya lebih memahami siapa diri saya, dari mana asal saya, saya menjadi makin kenal dengan ibu saya. Saya makin tahu bagaimana dia melayani dan memberi makan saya. Dalam makanannya, saya diberi makan, dipeluk, diampuni, dan dikasihi.”
Memasak juga mengajarkan kita untuk menjadi berkat bagi alam. Dengan memasak secukupnya, kita menghormati prinsip keberlanjutan dan menghindari pemborosan makanan. Dalam ajaran Doa Bapa Kami, permohonan untuk “makanan yang secukupnya” bukan hanya seruan untuk hidup sederhana, tetapi juga pengingat untuk tidak mengambil lebih dari yang kita butuhkan.
Memasak secara berkelanjutan juga berarti memilih bahan lokal yang sesuai musim, mengurangi limbah dapur, dan menghormati sumber daya alam yang terbatas.
Di balik setiap aktivitas memasak, ada kesempatan untuk merenung dan bersyukur. Memasak bisa menjadi bentuk meditasi, sebuah praktik kehadiran penuh yang mengundang kita untuk fokus pada proses—dari memotong bahan hingga menghidangkan makanan.
Pada akhirnya, bagi saya, memasak adalah sebuah praktik spiritualitas sehari-hari tentang kebermanfaatan, keberlanjutan dan kecukupan. Memasak menciptakan ruang bagi jiwa untuk bertumbuh dan makin mencintai Allah, sesama, dan bumi yang kita tinggali.
Selamat Memasak !

Permakultur Biogas
Dalam Perspektif Halalan Toyyiban
Oleh: Adnan Iman Nurtjahjo Amir, S.M. (FKIM Sembada Kabupaten Sleman )
Permakultur biogas merupakan salah satu solusi berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip permakultur dengan teknologi biogas untuk memanfaatkan limbah organik menjadi energi terbarukan. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan modern, seperti krisis energi dan polusi lingkungan. Dalam konteks masyarakat Muslim, penerapan permakultur biogas juga harus memperhatikan prinsip halalan toyyiban, yakni memastikan kehalalan dan keberkahan sumber daya serta hasilnya.
Selain itu, Permakultur adalah pendekatan desain yang bertujuan menciptakan sistem berkelanjutan dengan meniru ekosistem alami. Dalam konteks biogas, limbah organik seperti kotoran hewan dan sisa makanan digunakan untuk menghasilkan gas metana melalui proses fermentasi anaerobik. Gas ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, sementara sisa fermentasi dapat dijadikan pupuk organik yang memperbaiki kesuburan tanah.
Namun, bagaimana konsep halalan toyyiban diaplikasikan dalam permakultur biogas? Secara halal, bahan baku biogas tidak boleh berasal dari sumber yang haram, seperti limbah babi atau bahan najis lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan, baik energi maupun pupuk, tetap suci dan layak digunakan. Secara toyyib, sistem produksi harus ramah lingkungan, tidak mencemari, dan memberikan manfaat bagi manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai contoh, sistem biogas yang dirancang dengan baik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah pencemaran air tanah oleh limbah.
Lebih lanjut, penerapan permakultur biogas selaras dengan nilai-nilai Islami yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an (QS. Al-A’raf: 31), “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.” Sistem ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling efisien.
Di sisi lain, penerapan konsep ini membutuhkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Banyak yang masih memandang limbah sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Padahal, jika dikelola dengan benar, limbah dapat menjadi berkah yang berkelanjutan. Dengan pendekatan permakultur biogas, masyarakat dapat memperoleh energi bersih dan pupuk alami, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, permakultur biogas bukan hanya solusi teknologi, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Allah SWT dengan menjaga amanah-Nya berupa alam. Konsep ini menjembatani inovasi modern dengan nilai spiritual, menciptakan harmoni antara teknologi, ekologi, dan agama.

Muliakan Alam
Untuk Kehidupan Lebih Baik
Oleh: Guntur Subagja Mahardika
Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (INTANI). Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS)Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia
Bumi sedang mengalami ancaman berat. Kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana, areal hutan terus menciut, gunung-gunung terkikis, sungai dan laut tercemar. Dampaknya, adalah bencana besar bagi umat manusia. Perubahan iklim, pemanasan global, banjir, longsor, dan kekeringan, adalah akibat buruk dari kerusakan alam.
Data Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan konbsentrasi gas rumah kaca berada pada level tertinggi dalam kurun waktu 2 juta tahun. Dan emisi terus meningkat. Akibatnya bumi sekarang lebih hangat 1,1 derajat Celcius dibandingkan tahun 1.800-an. Periode 2011-2020 adalah rekor terpanas di bumi. (Indonesia.un.org/id)
Sepintas, perubahan iklim seakan-akan semata-mata hanya membuat suhu semakin hangat. Perubahan suhu hanya gejala awal dari ancaman bencana-bencana lainnya. Diantaranya, permukaan laut mengalami kenaikan, es di kutub mencair, banjir, kekeringan, kebakaran hebat, badai dahsyat, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
Laporan PBB tahun 2028, ribuan ilmuwan dan peninjau pemerintah sepakat bahwa membatasi kenaikan suhu global tidak lebih daari 1,5 derajat celcius akan membantu kita menghindari dampak iklim terburuk dan mempertahankan iklim yang layak huni,. Namun jalur emisi karbon dioksida saat ini dapat meningkatkan suhu global sebanyak 4,4% pada akhir abad ini.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan dana becnana alam pada 2024 mencapai 1.904 bencana. Sebanyak 957 bencana banjir, 405 bencana cuaca ekstrem, 118 tanah longsor, 336 kebakaran hutan, 54 kekeringan, 12 gelombang pasang dan abrasi, 17 gemba bumi, dan 5 erupsi gunung api. (gis.bnpb.go.id, data tanggal 9 Desember 2024)
Mengapa terjadi? Karena manusia yang hidup di muka bumi tidak memanfaatkan dan merawat alam dengan baik. Ekspoitasi berlebihan tanpa menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka pendek dengan motif keserakahan ekonomi, tanpa (atau) disadari telah merusak masa depan kehidupan manusia itu sendiri.
Industrialisasi menjadi pemicu utama yang mempercepat kerusakan alam. Tumbuhnya kapitalisme di belahan dunia dan perkembangan teknologi yang tidak ramah lingkungan, melahirkan beragam aktivitas ekonomi yang mengeksplotasi alam besar-besaran. Sumber daya alam di belahan bumi yang berlimpah dengan kearifannya masing-masing sudah sekian abad menjadi obyek kapitalisme dan keserakahan para penguasa kapital. Siapa yang menguasai sumber daya alam, itulah penguasa dunia saat ini.
Kita memahami penduduk bumi terus bertambah. Dengan jumlah warga dunia delapan miliar orang lebih saat ini, tentu kebutuhan akan hunian (pemukiman), makanan (food), dan lapangan pekerjaan (industri) besar. Lahan-lahan hutan dan pertanian terus tergerus karena kebutuhan pemukiman, industri, dan fasilitas lainnya untuk manusia. Produk-produk yang tidak ramah lingkungan memperparah kerusakan dan pencemaran udara, tanah, dan laut. Produk yang dari bahan-bahan kimia buatan itu tidak mudah terurai. Misalnya, plastik yang dibuang sebagai sampah, baru bisa terurai di tanah setelah ratusan tahun. Dengan realita ini, bencana makin besar mengancam bang-bangsa di dunia. Pola hidup tidak ramah lingkungan ini juga mengganggu kesehatan kita.
Apa yang harus kita lakukan? Langkah kecil individual akan menjadi solusi merawat alam. Mulai mengubah mindset (paradigma) dari diri kita sendiri. Mulai dengan bergaya hidup ramah lingkungan, bagun hunian ramah lingkungan, tidak membuang sampah yang mencemari dan melakukan daur ulang sampah, dan tanam pohon di lahan di halaman rumah kita.
Untuk konsumsi, saatnya makanan sehat alami bebas pestisida dan bahan kimia. Sumber makanannya dari pertanian alami. Sebagaimana yang disampaikan Iskandar Waroruntu, pemilik Bumi Langit Institute yang menjadi narasumber dalam Short Course Certified of Environmental Management Leadership (CEML) mengulas pertanian permaculture, yaitu pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan.
Langkah-langkah kecil ini dapat menjadi langkah kolektif yang menjadi bola salju menjadi gerakan gaya hidup ramah lingkungan yang semakin besar. Berkembang, dari individu ke komunitas, meluas ke bangsa dan negara, hingga menjadi gaya hidup warga dunia.
Mari kita muliakan alam untuk kehidupan lebih baik. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai hari ini! *

Menyemai Kearifan
Lokal di Era Modern Bersama Iskandar Waworuntu
Oleh: Dr. Eko Putra Boediman, MM., M.I.Kom (GTI )
Konsep keberlanjutan dan harmonisasi dengan alam sering kali terpinggirkan. Namun, sosok Iskandar Waworuntu hadir membawa oase segar melalui visi dan karyanya. Sebagai pemilik “Bumi Langit” di Yogyakarta, ia bukan hanya seorang pemimpin dalam praktik lingkungan berkelanjutan, tetapi juga seorang inspirator yang menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks modern.
Melalui pelatihan Certified Environmental Management Leadership (C.EML) yang saya ikuti, pemikiran dan pendekatan Iskandar begitu membekas. Dengan penuh keyakinan, ia mempresentasikan konsep Permakultur Biogas dan Halalan Thoyyiban sebagai solusi lingkungan yang tidak hanya ramah terhadap bumi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan ekologis dan spiritual.
Apa yang membuat Iskandar berbeda adalah kemampuannya memadukan tradisi dan inovasi. Ia tidak hanya berbicara tentang ide; ia mempraktikkannya secara nyata di “Bumi Langit”. Tempat ini bukan sekadar lokasi, tetapi sebuah manifestasi hidup dari nilai-nilai yang ia perjuangkan—menghargai alam, meminimalkan limbah, dan membangun keberlanjutan dengan melibatkan komunitas.
Dalam sesinya, Iskandar mampu menjadikan peserta seperti saya terinspirasi untuk berpikir lebih jauh tentang hubungan manusia dengan lingkungan. Ketulusan dan semangatnya terasa begitu nyata, menyentuh kesadaran bahwa solusi terhadap krisis ekologi tidak harus selalu berasal dari teknologi canggih, tetapi bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana dengan nilai yang mendalam.
Iskandar adalah contoh nyata dari seorang pemimpin transformasional. Ia tidak hanya memberikan teori, tetapi juga memberi teladan melalui tindakan. Ketika berbicara tentang halalan thoyyiban, ia tidak hanya menekankan pada kualitas pangan yang sehat, tetapi juga keberkahan dalam setiap proses produksi—sesuatu yang sering luput dari perhatian dunia modern.
Sosoknya layak menjadi inspirasi, tidak hanya untuk individu yang bergerak di bidang lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin menjadikan bumi ini lebih baik. Asosiasi Studi Kalimantan, sebagai forum intelektual dan akademis, dapat mengambil banyak pelajaran dari pemikiran Iskandar untuk diterapkan di wilayah yang kaya sumber daya alam ini.
Melalui pendekatan inovatif dan hati yang tulus, Iskandar Waworuntu mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas, tetapi juga panggilan untuk menghormati penciptaan dan kehidupan. Inilah wujud nyata kepemimpinan lingkungan yang sejati—memberi inspirasi sekaligus solusi bagi generasi mendatang.

Trash Talks:
Why Education Alone Fails to Solve the Waste Crisis
Oleh: Miftahol Arifin, ST.,MT. (Telkom University)
Dosen Teknik Logistik
Telkom University Kampus Purwokerto
Krisis sampah global telah menjadi tantangan lingkungan yang mendesak, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Di berbagai belahan dunia, negara-negara menghadapi peningkatan volume sampah, pencemaran air, dan penurunan kualitas udara akibat pengelolaan limbah yang buruk. Indonesia, dengan populasi besar dan wilayah kepulauan, adalah contoh nyata dari dampak buruk pengelolaan sampah yang tidak memadai. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan lebih dari 67 juta ton sampah setiap tahun, tetapi hanya sebagian kecil yang didaur ulang atau diolah dengan baik.
Berbagai kampanye pendidikan telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, tetapi perubahan perilaku nyata tetap sulit dicapai. Di tingkat global, banyak negara telah menginvestasikan dana besar dalam program edukasi untuk mengatasi krisis ini. Kampanye seperti ‘Reduce, Reuse, Recycle’ sudah lama diterapkan di sekolah, tempat kerja, dan ruang publik. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Namun, hasilnya seringkali jauh dari harapan. Studi menunjukkan bahwa meskipun banyak orang memahami dampak buruk sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, pemahaman ini jarang diterapkan dalam tindakan sehari-hari.
Penelusuran lebih mendalam mengungkapkan bahwa masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor sistemik. Ketimpangan sosial-ekonomi, kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah, norma budaya, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi hambatan utama. Bahkan ketika pendidikan berhasil meningkatkan kesadaran, dampaknya seringkali terbatas tanpa adanya sistem pendukung yang kuat. Kondisi ini menegaskan pentingnya mengevaluasi ulang strategi penanganan krisis sampah, dengan fokus pada cara menjembatani kesenjangan antara kesadaran dan tindakan nyata.
Saat Pendidikan Tak Berdaya Mengatasi Sampah
Pendidikan sering dianggap sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, tetapi dalam konteks pengelolaan limbah, keterbatasannya sangat terlihat. Banyak studi menunjukkan bahwa pengetahuan tentang masalah lingkungan tidak selalu mengarah pada perubahan perilaku. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Jakarta mengungkapkan bahwa meskipun 85% masyarakat memahami pentingnya memilah sampah, hanya 20% yang benar-benar melakukannya secara konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan saja, tanpa adanya perubahan sistemik yang mendukung, sulit menciptakan kebiasaan berkelanjutan.
Fenomena psikologis yang dikenal sebagai value-action gap membantu menjelaskan ketidaksesuaian ini. Meskipun seseorang mungkin menghargai pentingnya kebersihan dan pelestarian lingkungan, faktor eksternal seperti ketidakpraktisan, kurangnya manfaat langsung, dan pengaruh sosial sering menjadi hambatan untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan. Selain itu, pandangan budaya terhadap sampah, yang telah tertanam selama bertahun-tahun, menjadi tantangan tambahan. Di banyak komunitas, membuang sesuatu ke “tempat sampah” dianggap selesai, tanpa memikirkan ke mana “tempat sampah” itu sebenarnya.
Sayangnya, kampanye pendidikan sering kali mengabaikan kompleksitas ini. Banyak yang mengasumsikan bahwa memberikan informasi saja sudah cukup untuk mengubah perilaku, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor pendukung seperti infrastruktur, insentif, atau kebijakan. Pendekatan yang terlalu sempit ini membatasi efektivitas kampanye, sehingga diperlukan strategi tambahan untuk memperkuat dampaknya. Solusinya terletak pada menciptakan pendekatan terpadu yang menggabungkan pendidikan dengan dukungan praktis dan sistemik.
Untuk mencapai keberhasilan, diperlukan perubahan paradigma yang bergerak melampaui model pendidikan tradisional menuju solusi holistik yang berorientasi pada tindakan. Pendekatan ini mencakup integrasi antara pendidikan, insentif ekonomi, infrastruktur yang memadai, dan penegakan hukum. Dengan menyediakan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.
Contohnya bisa dilihat di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Program “waste-for-tickets” menjadi bukti nyata efektivitas pendekatan integratif ini. Dalam program ini, warga dapat menukar sampah yang dapat didaur ulang dengan tiket bus gratis, menghubungkan tanggung jawab lingkungan dengan keuntungan ekonomi. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memberikan penghargaan langsung, sehingga mendorong partisipasi yang berkelanjutan.
Inisiatif seperti ini menyoroti pentingnya menciptakan siklus positif, di mana masyarakat melihat dampak nyata dan langsung dari tindakan mereka. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga berfungsi sebagai katalis untuk menciptakan perubahan perilaku yang nyata. Integrasi pendidikan dengan dukungan sistemik seperti ini adalah kunci untuk mengatasi tantangan pengelolaan limbah secara efektif.
Dari Kebijakan ke Aksi Hijau
Dukungan kebijakan merupakan elemen penting dalam membangun ekosistem pengelolaan limbah yang efektif. Pendidikan saja tidak cukup; harus ada peraturan yang tegas yang memberikan insentif bagi kepatuhan dan sanksi bagi kelalaian. Negara-negara seperti Swedia dan Jerman, yang dikenal dengan sistem pengelolaan limbahnya yang maju, menunjukkan bahwa kombinasi pendidikan publik, undang-undang yang kuat, dan infrastruktur daur ulang yang canggih dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Misalnya, Green Dot System di Jerman mewajibkan produsen untuk membiayai pengelolaan limbah produk mereka, menanamkan pola pikir ekonomi sirkular dari tahap produksi hingga pembuangan.
Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam mendukung kebijakan ini. Sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi, seperti perangkat Internet of Things (IoT), memungkinkan pemantauan kebiasaan pembuangan sampah secara real-time dan memberikan penghargaan kepada rumah tangga yang aktif mendaur ulang. Selain itu, aplikasi seluler yang meng-gamifikasi proses pemisahan sampah dengan menawarkan poin yang bisa ditukar dengan diskon atau layanan tertentu telah mendapatkan popularitas di daerah perkotaan. Teknologi ini tidak hanya mempermudah pengelolaan limbah tetapi juga menarik perhatian generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.
Namun, keberhasilan kebijakan pengelolaan limbah juga membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya. Di pedesaan Indonesia, misalnya, kampanye lingkungan yang melibatkan pemimpin desa dan tokoh agama lebih efektif dibandingkan dengan program edukasi umum. Dengan mengintegrasikan pengelolaan limbah ke dalam nilai-nilai budaya setempat, masyarakat cenderung lebih menerima dan menerapkan kebiasaan ramah lingkungan.
Selain itu, peran sektor swasta tidak dapat diabaikan. Korporasi harus diberi insentif untuk mengadopsi solusi pengemasan berkelanjutan dan menetapkan program pengembalian untuk produk mereka. Model kolaboratif, di mana pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil bersama-sama menciptakan solusi pengelolaan limbah, dapat memperkuat dampak. Kerangka kerja tanggung jawab extended producer responsibility (EPR), di mana produsen bertanggung jawab atas dampak siklus hidup produk mereka, mencontohkan kolaborasi tersebut.
Akhirnya, mengukur dan mengomunikasikan dampak intervensi sangat penting untuk momentum yang berkelanjutan. Pelaporan kemajuan yang transparan tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga menginspirasi replikasi model yang sukses. Misalnya, mempublikasikan capaian program sampah untuk tiket Surabaya telah mendorong kota-kota lain di Indonesia untuk mengeksplorasi inisiatif serupa. Berbagi kisah sukses, didukung oleh data, membantu mengubah persepsi masyarakat tentang kelayakan dan manfaat pengelolaan sampah berkelanjutan.
Kesimpulan
Krisis sampah adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan solusi yang menyeluruh. Meskipun pendidikan tetap menjadi komponen penting, keberhasilannya sering terbatas jika tidak disertai dengan perubahan pada tingkat perilaku, infrastruktur, dan sistem. Solusi yang efektif terletak pada integrasi pendidikan dengan insentif nyata, kebijakan yang tegas, dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk menjembatani kesenjangan antara kesadaran dan tindakan, menciptakan perubahan yang bermakna menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Dengan cara ini, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi upaya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga langkah konkret untuk mendorong tindakan. Strategi ini mendefinisikan ulang narasi tentang pengelolaan limbah, menggeser fokus dari sekadar memahami menjadi benar-benar bertindak. Budaya tanggung jawab lingkungan yang terbangun melalui pendekatan terpadu ini dapat menjadi teladan untuk menyelesaikan tantangan lingkungan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa dengan kombinasi yang tepat antara pendidikan, tindakan nyata, dan dukungan sistemik, kebiasaan yang telah mengakar pun dapat diubah.

Gagasan atas Agenda
Pembangunan Manusia yang Lebih Beradab
Oleh: Lucitania Rizky, S.IP., M.A.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Teknologi Yogyakarta
Dalam era globalisasi yang bergerak begitu cepat dan instan, manusia dalam proses pembangunannya tidak banyak dihadapkan pada pilihan hidup yang mudah untuk mengamalkan nilai ‘Halalan Toyiban’. Halal sebagai bagian dari semangat ide sustainability yang terus berjalan dalam setiap proses hidup manusia. Namun, Halal menjadi ide utopis bagi sebagian kelompok, katakanlah para penganut neoliberalisme, karena semangat ‘Halalan Toyiban’ dianggap memberikan gagasan untuk memutus mata rantai industri dalam rangka memastikan apa yang dikonsumsi dan digunakan dalam hidup sesuai dengan nilai serta ajaran agama Islam. Sedangkan kelompok neoliberalisme menganggap bahwa manusia hanya akan mencapai titik kemakmuran jika masuk dan bersemang di rantai global industri. Pemikiran ini (neoliberalisme) sesuai dengan ide-ide antroposentrism yang terus digaungkan oleh sebagain besar kelompok barat sebagai suatu cara yang dianggap paling efektif untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa negara.
Sayangnya, gagasan pembangunan yang berpusat pada manusia tersebut (antroposentrism) telah berhasil menggadaikan bumi ini demi ketamakan para pemegang modal. Semangat neoliberalisme sebagai tawaran dari kelompok positivis ditentang oleh kelompok pandangan post positivis dengan gagasan: environmentalist dan social-justice, dimana suatu ‘barang’ seharusnya dapat diproduksi tanpa mengorbankan alam/ lingkungan dan kehidupan sosial. Tidak sedikit dari kita yang berfikir bahwa konsep barat atas pembangunan yang bersifat eksploitatif, berlebih, dan konsumtif lebih baik karna menuju kearah modernitas dan dianggap lebih berkelas. Namun, jika direnungkan kembali, antroposentrisme – modernism hanya menghadirkan suatu agenda pembangunan yang bersifat semu. Gagasan ini bertentangan dengan ajaran islam yang kita kenal sebagai ‘Zuhud’ yakni sikap merasa cukup terhadap kenikmatan dunia dan tidak bermewah – mewahan.
Nilai Zuhud dianggap dapat mengkontrol keinginan manusia untuk terus mengeksploitasi alam. Konsep ini juga diungkit kembali oleh Bapak Iskandar Waworontu, pendiri Bumi Langit Institute untuk merubah pola pikir, pola hidup, dan cara pandang manusia terhadap ‘gaya hidup’ agar menjadi lebih hemat dan sederhana dalam rangka upaya penyelematan lingkungan. Gaya hidup yang berlebih dan bergantung pada rantai produksi industri hanya menjadi bagian dari kesia-sian suatu kehidupan manusia. Zuhud dalam Islam sudah cukup jelas menjelaskan bahwa untuk menghadirkan suatu kondisi yang beradab atau civilize, kita perlu sadar bahwa dengan gaya hidup yang sederhana, maka alam juga akan jauh lebih menghargai keberadaan manusia di muka bumi. Alam akan dengan sendirinya membersamai agenda pembangunan manusia yang lebih beradab.

Perempuan sebagai Agen Perubahan
dan Perntingnya Berkesadaran Tentang Proses Belajar Sepanjang Hayat
Oleh : Samiati,S.Psi
Salam Rahayu…
Saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini kami…( saya bersama suami dan dibantu anak – anak ) bertani dan beternak dengan memanfaatkan lahan yang ada diseputaran rumah tinggal. Energi untuk mengikuti short course ini begitu besar hingga tiba saat pemaparan materi yang pertama oleh Beliau Bapak Iskandar Waworuntu . Begitu nano – nano sekali rasa dihati saya selama menyimak materi, materi yang sungguh sangat luarbiasa bagus sekali. Menariknya dari materi yang disampaikan seketika membuat saya merasa teramat sangat bersyukur bisa mengikuti kursus ini. Sebagai seorang perempuan sekaligus seorang ibu, menurut saya terdapat beberapa poin penting yang dapat diulas dari dua perspektif utama: perempuan sebagai agen perubahan dan proses belajar sepanjang hayat sebagai laku kehidupan.
1. Perempuan sebagai Agen Perubahan dan Jembatan Pengetahuan
Perempuan memiliki peran penting sebagai pembawa dan penyebar nilai-nilai transformatif. Dalam konteks ini, perempuan dapat menjadi katalisator utama untuk membangun kesadaran kolektif tentang isu-isu seperti keberlanjutan lingkungan, pendidikan anak, dan nilai-nilai hidup yang berbasis moralitas.
Materi mengenai konsep halalan thayibah yang menekankan prinsip keberkahan, kebaikan, dan keberlanjutan, secara implisit menempatkan perempuan dalam posisi penting. Sebagai pendidik pertama bagi generasi penerus, perempuan berperan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini. Mereka menjadi jembatan antara tradisi, agama, dan praktik kehidupan modern, memastikan bahwa generasi berikutnya memahami pentingnya keberlanjutan dan keharmonisan dengan alam.
Misalnya, perempuan yang aktif dalam komunitas seperti “Kelompok Wanita Tani (KWT)” yang ada dibasis – basis padukuhan , diharapkan mampu memperkenalkan metode seperti permakultur dan daur ulang. Dengan demikian, mereka tidak hanya mendidik tetapi juga menggerakkan perubahan yang konkret.
2. Proses Belajar Sepanjang Hayat
Seperti kata luhur dari para leluhur “Sinau sajroning Laku Urip” adalah benar bahwa belajar itu sepanjang hayat. Pembelajaran yang digambarkan dalam diskusi pada materi pertama kursus ini menunjukkan bahwa kehidupan adalah proses pembelajaran terus-menerus. Konsep ini selaras dengan life long learning, di mana manusia dituntut untuk terus mengevaluasi, merefleksikan, dan memperbaiki diri berdasarkan nilai-nilai fitrah.
Sebagai contoh, beliau Bapak Iskandar Waworuntu menekankan pentingnya memahami hubungan manusia dengan alam melalui pendekatan spiritual dan ilmiah. Hal ini menekankan bahwa proses belajar tidak hanya bersifat formal tetapi juga informal dan transformatif, melibatkan pengalaman hidup yang nyata.
Pendekatan ini sangat relevan bagi perempuan sebagai penjaga keluarga dan budaya. Proses pembelajaran sepanjang hayat memungkinkan mereka untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, seperti memahami dampak perubahan iklim atau pentingnya gaya hidup berkelanjutan.
Kesimpulan
Dalam materi pertama yang dibawakan oleh Beliau Bapak Iskandar Waworuntu memberikan refleksi mendalam tentang pentingnya prinsip-prinsip kehidupan berkelanjutan dan nilai spiritual dalam membentuk perilaku individu. Perempuan sebagai agen perubahan tidak hanya memiliki peran di tingkat keluarga tetapi juga dalam komunitas yang lebih luas, menjembatani pengetahuan untuk generasi penerus.
Proses belajar sepanjang hayat menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran diri dan kolektif untuk menghadapi tantangan zaman, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Keduanya berpadu untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya paham konsep keberlanjutan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga Semesta merestui dengan banyak bertumbuh kebaikan sinergisitas alam raya akan terjaga….
Salam Rahayu!!!

Berani Memulai Perbedaan Positif
Sebuah Insight dari Iskandar Waworuntu
Oleh : Asri Kusumastuti (Komunitas Belajar Minim Sampah)
Iskandar Waworuntu, founder Bumi Langit yang bermukim di wilayah Imogiri, Bantul, memulai perjuangannya sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Berusaha mewujudkan diri sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di bumi ini, yang berjuang mewujudkan lingkungan yang sesuai fitrah alam.
Lahan yang sangat luas, hidup harmoni dengan alam, permaculture, pendayagunaan alam sebagai sumber energi, pemenuhan kebutuhan sendiri dari alam, perawatan tanah sesuai daur alam, menjadi bagian dari hidup dan kehidupannya.
Menyadari bahwa setiap diri akan dimintai pertanggungjawaban di haðapan Allah dihari akhir nanti. Dan setiap manusia akan juga dimintai pertanggungjawaban mengenai tubuhnya. Bagaimana input makanan yang diberikan kepada tubuh, apakah halal, apakah tayyib? Karena betapa susah makan yang thayyib di era industri makanan yang serba praktis saat ini. Industri makanan telah merubah fitrah tubuh akan makanan alami menjadi makanan pabrikan yang penuh toksik dan menghilangkan kealamian tubuh.
Menjadikan tekad dan jalan hidupnya untuk mewujudkan makanan yang tidak cukup halal saja, tapi juga thayyib dari mulai proses penanaman hingga pengolahan menjadi makanan termasuk pengolahan residunya. Setiap langkah baru tidak akan pernah mudah. Meskipun dipandang terlalu idealis, dan menyusahkan diri sendiri di era modern ini, Iskandar bersama keluarga berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni dengan semesta.
Daun yang gugur pun bukan sebuah hal yang disia-siakan, karena secara zatnya akan berubah menjadi bahan organik untuk tanah. Kotoran ternak juga bukan hal yang sia-sia, karena akan menjadi sumber energi untuk memasak. Memilih bahan makanan terbaik yang masih alami dan berkualitas untuk diri, bukan semata-mata mengikuti industri..
Hidup dari alam dan untuk alam. Karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, dan sekecil bakti kita untuk alam akan dinilai sebagai amal sholih di hadapan sang Pencipta.
Mulai dari diri kita, kemudian keluarga dan masyarakat luas. Mengembalikan alam sesuai fitrahnya.. karena manusia dikaruniai akal bukan untuk merusak, tapi menjadi bagian dari sistem yang melestarikan alam semesta.
Sebuah inspirasi yang menggugah hati bahwa industri diciptakan agar alam lebih lestari sumber daya alamnya, bukan untuk mengeruk sepuasnya untuk kepentingan pribadi. Plastik ditemukan agar pohon tidak terforsir utk membuat kertas pembungkus, maka industri selayaknya menciptakan plastik yang awet, tahan banting, bukan semata-mata praktis tapi sekali pakai atau mudah rusak.
Karena jangan-jangan kita ikut menanggung dosa akibat plastik yang terurai puluhan juta tahun. Bagaimana agama juga menciptakan kesalehan dalam setiap profesi manusia.

Harmoni Alam dan Kehidupan
Inspirasi dari Bapak Iskandar Waworuntu
Oleh : I Putu Dicky Merta Pratama, S.H., M.H. (Praditama Nuswantara Initiative)
Ketika berbicara tentang keberlanjutan dan harmoni dengan alam, sosok Bapak Iskandar Waworuntu menjadi inspirasi yang patut diteladani. Di usia 70 tahun, beliau tetap bersemangat menjalankan prinsip halalan toyyiban yang ia gali dari Al-Qur’an selama lebih dari dua dekade. Dengan konsistensi yang luar biasa, beliau berhasil menunjukkan bahwa hidup yang selaras dengan alam bukan hanya idealisme, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan sosial yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai pendiri Bumi Langit Permaculture Institute di Yogyakarta, Bapak Iskandar merintis pendekatan yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Beliau memanfaatkan permakultur untuk menciptakan ruang hidup yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Apa yang ia lakukan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal nenek moyang kita yang, jika dilestarikan, dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mewujudkan kehidupan yang harmonis.
Ketika menyimak pemaparan dari Bapak Iskandar, saya melihat bahwa konsepnya memiliki keselarasan dengan filosofi Tri Hita Karana yang saya pahami dan yakini di Bali sebagai konsep kebahagiaan dan keharmonisan dalam ajaran Hindu Bali yang mengajarkan tiga hubungan utama: hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), hubungan manusia dengan sesama (pawongan), dan hubungan manusia dengan alam (palemahan). Melalui halalan toyyiban, beliau mengamalkan nilai-nilai yang mencerminkan keseimbangan ini: menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan, memelihara relasi sosial yang harmonis melalui komunitas yang ia bangun, dan merawat lingkungan melalui penerapan permakultur.
Konsep biogas yang dikembangkan oleh beliau, misalnya, tidak hanya memberikan solusi energi alternatif yang ramah lingkungan (palemahan), tetapi juga menciptakan peluang kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat lokal (pawongan). Pada saat yang sama, beliau menjaga prinsip keberlanjutan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta (parhyangan). Keselarasan ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip lokal seperti Tri Hita Karana maupun konsep halalan toyyiban memiliki relevansi universal dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Lebih dari sekadar praktisi, Bapak Iskandar juga seorang penginspirasi. Kehadirannya dalam film dokumenter Semes7a menjadi bukti nyata bahwa langkah kecil, jika dilakukan dengan niat tulus dan konsisten, dapat membawa perubahan besar. Beliau mengingatkan kita bahwa keberlanjutan bukan hanya soal teknologi atau teori, tetapi tentang kesadaran dan tanggung jawab moral kita sebagai makhluk sosial dan spiritual.
Dengan memahami dan mengintegrasikan konsep tersebut, saya belajar bahwa menjaga alam bukan hanya tugas ekologis, tetapi juga spiritual. Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Iskandar, harmoni dengan alam adalah cerminan dari harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Bagi saya sebagai generasi muda di era modern ini, meneladani semangat beliau adalah langkah kecil yang bisa kita ambil untuk memastikan bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi generasi mendatang.

Optimasi distribusi
penyebaran Tenaga Perawat di Kalimantan
Oleh : Devanda Faiqh Albyn (Palm Co)
Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang menghasilkan Sumber Daya Alam yang luar biasa sehingga banyak mengundang Investor atau Perusahaan – perusahaan besar membuat mega proyek di Kalimantan perusahaan dalam negri maupun luar negri, hal ini pernah di bahas dalam 4th Pontianak International Health Conference : Innovation and Health Resilience in Managing Non-Communicable Diseases (cancer, heart disease, stroke, Uronephrology), as well as Maternal and Child Health Towards a Healthy Generation. Dengan tema “PoV : Job Opportunities for Nurses as OHN and Paramedics in Mining Companies from a Welfare” Original Article dengan metode Qualitative Research, Exploratory Phenomenology oleh Devanda Faiqh Albyn, Elheart Budiman, Fredi Ardiansyah, Rizky Gilang Romadhon. Dalam event ini mereka menyampaikan aspek kesejahteraan dan peluang kerja sebagai perawat di perusahaan pertamabangan, terlebih bagi Elheart & Rizky Gilang yang merupakan putra daerah asal Kalimantan yang saat ini bekerja sebagai perawat di Perusahaan pertambangan ternama di Indonesia. Dengan pemberdayaan talenta local yang kompeten dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan daerah setempat terkait aspek CSR dan SDGs, menjadi bagian dari SDM K3 hanya saja masih sedikit kandidat yang belum memeuhi kualifikasinya dikarena kan karne tidak ada perkuliahan OHN saat dipendidikan keperawatan, sehingga mereka harus belajar secara otodidak baik dari senior, platform @ohnurseedu, dan kegiatan E-Learning dari APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia).
Gambar : 4th Pontianak International Health Conference, Poltekkes Pontianak 2024.
Perawat yang bekerja di Fasyankes sudah Overload, seperti kita ketahui bersama bahwa lulusan perawat setiap tahunnya di Indonesia sangat banyak tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan perawat di FASYANKES (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) seperti puskesmas, klinik, laboratorium dan Rumah Sakit bahkan belum tentu mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak kecuali yang sudah PNS dan PPPK sehingga Bekerja di industri/Perusahaan bisa menjadi second option selain bekerja di Luar Negri”. Aspek Kesehatan Kerja sangatlah penting dan menjadi urgensi saat ini guna menggapai Indonesia Emas tahun 2045 mengapa demikian? 1/3 dalam sehari waktu manusia dihabiskan di tempat kerja bahkan kejadian stunting pun bisa dicegah melalui tertibnya Implementasi K3 di tempat kerja terutama bagi pekerja muda dan usia produktif dalam hal ini perawat turut berperan besar. Setiap tahun ada sekitar 22 ribu sampai 40 ribu lulusan perawat harus menganggur, hanya sekitar 20% saja yang terserap di fasyankes (RS, Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium). Dari data Kemenkes 2023 Jumlah tenaga kesehatan terbanyak yakni perawat sebanyak 582 ribu orang, apakah sudah terdistribusi secara merata dan sudah sejahterakah kehidupan mereka? Karena Mengingat saat ini dimana Indonesia menuju tahun Industri Tangguh 2030 sehingga banyaknya Investor Asing dan Perusahaan Luar Negri yang membuat Operational Project / Join Operation di Indonesia selain Perusahaan BUMN dan BUMD. Profesi Perawat Perusahaan sangat bisa menjadi terobosan atau pengoptimalan terhadap distribusi SDM perawat di Indonesia sehingga akan terjadi pemerataan di berbagai sektor pelayanan kesehatan dan akan mengangkat citra perawat Indonesia, namun sampai sekarang acapkali masih jarang mengethui bahwasanya OH Nurse dan Paramedis merupakan bagian salah satu dari Profesi Tenaga Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan.

Belajar dari Komunikasi Alam
Oleh : Ir Ana Susanti Yusman M.Eng,C.STMI,C.DMA (UMSB)
Banjir Bandang di Bukittinggi sudah berlalu dan jalanan sudah kembali lancar. Ada beberapa learning lesson yang bisa diambil dari peristiwa ini. Banjir bandang yang melanda Kawasan Gunung Merapi juga melanda daerah sekitar yang mengakibatkan jalanan putus antara Bukittinggi – Padang. Bantaran Sungai Anai yang djadikan tempat pemandian bagi anak-anak terlihat hancur dilanda arus sungai yang kuat. Disamping itu ada juga café yang ikut terbawa arus. Pemandian dan café ini terletak di Kawasan Milik Sungai yang berarti sewaktu-waktu sungai akan mengambil kembali miliknya. Dengan kata lain bantaran sungai itu adalah daerah bebas yang tidak boleh diganggu gugat.Ini berarti tidak halal bagi manusia mengambil bagian yang sudah diperuntukkan Allah SWT bagi makluk lainnya. Ini adalah learning lesson yang pertama.
Learning lesson yang kedua, Kawasan daerah gunung Merapi sudah banyak yang gundul karena penebangan liar. Kalau ditelusuri lagi maka daur hidrologi sebagai sunatullah sudah terganggu, sehingga menimbulkan banyak bencana bagi kehidupan manusia. Seharusnya air di bumi dengan bantuan sinar matahari akan mengalami penguapan. Proses berikutnya adalah akan terbentuk uap air yang makin lama akan membentuk titik air. Dengan bantuan angin, titik air ini menjadi hujan. Hujan ini Sebagian akan diresap oleh tumbuhan dan sebagian lagi akan kembali menuju badan air/sungai/danau/laut. Kalau proses alamiah ini tidak terganggu maka kemungkinan banjir bandang tidak akan terjadi.Ini menyiratkan tidak halal bagi kita untuk menghabiskan hutan yang ditugaskan menjaga keseimbangan air yang ada di bumi.
Learning lesson ketiga, akibat pemanasan global saat sekarang terjadi fenomena alam yang tidak dapat dielakkan lagi.Sering ditemui iklim yang berubah cepat dan cuaca yang ekstrem. Akibatnya adalah sistem pertanian, hasil pertanian dan kesehatan manusia pun juga terganggu. Ini menggambarkan kemajuan industri harus dibarengi dengan kelestarian alam dan tidak halal bagi manusia untuk merusaknya.
Untuk itu, mari kita pelajari komunikasi alam agar mendapatkan kembali sesuatu yang paling baik dari alam untuk kehidupan kita.

Peranan Agama dan Lingkungan Hidup
Oleh : Dr. Sa'diyah El Adawiyah,M.Si. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Agama dan lingkungan tidak dapat dipisahkan meskipun seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman tersebut berkembang selama ini, sehingga agama cenderung tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan. Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Sehingga muncullah berbagai macam Gerakan untuk membangun etika lingkungan. Salah satunya muncul Gerakan model kultural dengan 3 hal dalam memahami lingkungan; 1) alam memiliki sumberdaya yang terbatas, 2) alam diciptakan dengan prinsip keseimbangan, satu sama lain salingbergantung, dan rentan intervensi manusia, 3) materialisme dan sedikit hubungan dengan alam hanya menjadikan manusia cendurung mendevaluasikan alam (Kemton, Boster, dan Hartley, 1995). Di kalangan ilmuwan sosial, misalnya menawarkan agar sosiologi beralih ke sosiologi agama. Stark (1999) misalnya menawarkan teori rational choice yang menawarkan pertimbangan evolusi keagamaan, di mana kekuatan supernatural yang dimaksud adalah Tuhan, dan manusia harus mengembangkan model interaksi dengan Tuhan, yaitu melalui agama.
Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui, dan menyadari arti penting menjaga lingkungan sehari-hari. Setiap kerusakan alam, akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri. Seperti yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41:
“Telah tampak kerusakan di bumi dan di laut karena tangan-tangan manusia yang akhirnya Allah rasakan kepada mereka ganjaran dari sebahagian yang mereka kerjakan, supaya mereka kembali” (ar-Rum, 41).
Upaya mewujudkan green ecology, membutuhkan perilaku etis. Perilaku yang terbentuk melalui pesan theologis dengan berbagai diskursusnya tentang kelestarian lingkungan, pengendalian dalam mengeksploitasi alam, pola relasi manusia dengan alam, harus mendapatkan perhatian. Namun ironisnya, pesan etis-theologis ini tidak sekuat pesan-pesan yang dikembangkan oleh pasar, padahal basic filosofi kehidupan yang berkembang saat ini adalah mekanisme pasar, dengan dikendalikan oleh mereka yang kaya (the rule of the rich). Mereka yang mengendalikan pasar, lebih tertarik pada pesan pesan antroposentrime sekular. Eksploitasi alam lebih dipercayakan kepada sains dan teknologi, dari pada dipercayakan kepada pesan-pesan ketuhanan. Hegemoni the rule of the rich yang bermain dengan hukum mekanisme pasar bebas itu telah banyak menyebarkan kecemasan, kemarahan, kekerasan dan radikalisasi. Sehingga, diskursus etika dan ketuhanan bisa dijadikan inspirasi untuk membangun kekuatan counter hegemony terhadap kekuatan mekanisme pasar bebas yang hegemonik itu, sembari mencoba membuka ruang lebih lebar untuk membangun green ecology.

Halalan Thayyibah:
Konsep Islam dalam Membangun Hubungan Harmonis dengan Alam
Oleh : Dini Anggraheni,M.Hum. (Universitas Semarang)
Dalam dunia modern saat ini, masalah kelestarian lingkungan semakin mendesak. Sebagai umat manusia, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga bumi dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ajaran Islam memberikan pedoman jelas tentang hubungan manusia dengan alam, mengajarkan kita untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga untuk menjaga dan merawatnya.
Tanggung Jawab Manusia dalam Islam
Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berarti kita bukanlah penguasa mutlak alam, tetapi pemimpin yang diberi amanah oleh Allah untuk merawat dan menjaga kelestarian bumi. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di laut, dan segala yang ada di bumi, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.” Ayat ini mengingatkan kita bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya.
Sebagai khalifah, kita dituntut untuk menjaga alam dan tidak merusaknya. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Jika seseorang menanam pohon atau biji-bijian, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, maka itu akan menjadi amal jariyah bagi orang yang menanamnya.” Hadis ini menggambarkan bahwa menjaga alam bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga dapat mendatangkan pahala yang terus mengalir.
Rahmatan Lil Alamin: Menjadi Berkah Bagi Alam
Konsep “rahmatan lil alamin” yang berarti “rahmat bagi seluruh alam semesta” adalah ajaran utama dalam Islam yang mengajarkan umat Muslim untuk menjadi berkah bagi seluruh ciptaan Allah. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berbuat baik kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap makhluk hidup lainnya dan alam semesta.
Prinsip rahmatan lil alamin ini mengajarkan kita untuk menjaga alam sebagai bagian dari ibadah. Sebagai umat Muslim, kita dituntut untuk menjaga alam agar tetap lestari, bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.
Halalan Thayyibah: Konsep Bersih dan Baik dalam Islam
Konsep “halalan thayyibah” yang berarti “halal dan baik” juga berhubungan erat dengan kelestarian lingkungan. Prinsip ini mengajarkan umat Muslim untuk memilih segala sesuatu yang halal dan baik, tidak hanya dalam hal makanan dan minuman, tetapi juga dalam cara kita berinteraksi dengan alam. Islam mendorong kita untuk tidak hanya menghindari hal-hal yang haram, tetapi juga untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam.
Sebagai contoh, memilih produk yang ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi plastik sekali pakai adalah cara untuk menerapkan prinsip halalan thayyibah. Prinsip ini juga mengajarkan kita untuk mengurangi pemborosan dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, seperti menghemat air dan energi.
Pengaruh Islam terhadap Praktik Lingkungan Hidup
Sejarah Islam menunjukkan bahwa umat Muslim telah lama memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga alam. Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan banyak petunjuk tentang cara menjaga lingkungan. Salah satunya adalah tentang menanam pohon. Nabi SAW bersabda, “Jika seseorang menanam pohon, maka setiap kali pohon itu menghasilkan buah, ia akan mendapatkan pahala.”
Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya pengelolaan air yang bijaksana. Dalam sebuah hadis, beliau berkata, “Janganlah kamu menyia-nyiakan air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir.” Ini mengajarkan kita bahwa air adalah sumber daya yang sangat berharga dan harus digunakan dengan bijaksana.
Konsep-konsep ini menunjukkan bahwa Islam sudah sejak lama mengajarkan umatnya untuk hidup selaras dengan alam. Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga untuk menjaga keseimbangannya agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
Penutup
Ajaran agama khusunya Islam tentang lingkungan telah mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga untuk menjaga alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah. Prinsip-prinsip seperti rahmatan lil alamin, halalan thayyibah, dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi mengajarkan kita untuk hidup harmonis dengan alam. Dengan mengikuti ajaran-ajaran ini, kita dapat menjaga kelestarian alam, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Menggali Kearifan Lokal
dan Konsep Halalan Toyyiban bersama Bapak Iskandar Woworontu
Oleh: Ahmad Rizqi Alima Fabri, S.Si.,M.Si. (Universitas Islam Malang)
Pada sesi pertama short course “Certified of Environmental Management Leadership” bertema “Swasembada Energi dan Pangan yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan”, peserta diperkenalkan pada sosok Bapak Iskandar Woworontu, seorang inisiator pergerakan permakultur, pengembangan biogas, dan pengusung konsep Halalan Toyyiban. Beliau adalah salah satu tokoh yang diangkat dalam film dokumenter “Semes7a,” yang menginspirasi masyarakat luas untuk kembali mengedepankan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam.
Dalam pandangan yang diangkat oleh Bapak Iskandar Woworontu, konsep Halalan Toyyiban bukan semata sebuah label kehalalan pangan, melainkan suatu prinsip mendasar yang mencakup keseluruhan proses dari hulu hingga hilir produksi, distribusi, dan konsumsi. Istilah “Halalan” bermakna bahwa sumber daya dan proses yang digunakan harus sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, termasuk nilai-nilai agama dan adat setempat, sehingga tidak melanggar prinsip moral dan hukum yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Sementara itu, “Toyyiban” memberikan pengertian secara umum yaitu unsur baik, sehat dan memiliki nilai guna baik terhadap manusia dan lingkungan.
Dalam Halalan Toyyiban menyiratkan pentingnya keadilan, serta dampak positif dalam jangka panjang. Selain itu kriteria yang menjadi penetapan bahwa pangan dan energi yang dihasilkan tidak hanya bebas bahan kimia berbahaya atau diperoleh secara resmi (legal), selain itu aspek Kesehatan, keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan juga harus dipertimbangkan. Prinsip ini menyeleksi bahan baku yang aman terhadap ekosistem, proses produksi yang efisien dan limbah yang sedikit, serta produk pengolahan yang mempertahankan kualitas nutrisi dan nilai gizi yang tinggi
Dengan penerapan Halalan Toyyiban, setiap aktor dalam rantai produksi—petani, pengrajin, pedagang, hingga konsumen akhir—terlibat dalam ekosistem yang saling menguntungkan. Petani, misalnya, didorong untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang mempertahankan kesuburan tanah, using pupuk organik, serta mengimplementasikan pengendalian hama yang ramah lingkungan. Secara bergantian, konsumen menerima product yang tidak hanya aman untuk dikonsumsi secara fisik, tetapi juga memiliki nilai etis dan spiritual, dengan kesadaran bahwa makanan atau energi yang mereka gunakan berasal dari proses yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Selamatkan Lingkungan, Selamatkan Hidup
Oleh : Dr. Iman Subasman, M.Si (Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon)
Lingkungan adalah rumah besar bagi kita semua. Bumi, dengan segala keindahan dan sumber dayanya, menjadi tempat kita bergantung untuk bertahan hidup. Namun, kenyataannya, banyak dari kita sering lupa bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keseimbangan ekosistem yang perlu dijaga. Polusi udara, sampah plastik yang menumpuk, hingga perubahan iklim yang semakin ekstrem menunjukkan bahwa lingkungan kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jika ini terus dibiarkan, generasi mendatang mungkin tidak lagi bisa menikmati udara bersih, air segar, atau keindahan alam yang kita miliki sekarang.
Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan saja. Kita semua punya peran. Mulai dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung gerakan-gerakan pelestarian alam. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama-sama, bisa membawa perubahan besar. Karena pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan planet ini, tapi juga menyelamatkan diri kita sendiri.
Menjaga lingkungan memiliki banyak manfaat yang langsung dirasakan oleh manusia. Udara yang bersih, misalnya, tidak hanya membuat kita merasa segar, tetapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit pernapasan. Begitu pula dengan hutan yang terjaga; mereka bukan hanya menjadi habitat bagi berbagai satwa, tetapi juga menjadi penyeimbang iklim dan sumber oksigen bagi manusia. Selain itu, menjaga lingkungan juga memastikan sumber daya alam seperti air bersih dan tanah subur tetap tersedia untuk generasi mendatang.
Namun, dampaknya tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik. Kehidupan sosial dan ekonomi juga dipengaruhi oleh keberlanjutan lingkungan. Ketika kita menjaga alam, kita juga menciptakan peluang baru, seperti sektor pariwisata berkelanjutan dan pengembangan teknologi hijau. Lebih jauh lagi, upaya ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama yang memperkuat solidaritas masyarakat dalam menjaga bumi sebagai tempat tinggal kita bersama.
Meski manfaat menjaga lingkungan sangat jelas, tantangan untuk mewujudkannya tidak bisa diabaikan. Salah satu kendala terbesar adalah biaya. Banyak teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan atau sistem pengelolaan limbah modern, dianggap mahal dan sulit diakses oleh negara-negara berkembang. Hal ini sering membuat pemerintah dan masyarakat ragu untuk berinvestasi dalam upaya pelestarian lingkungan karena dampaknya tidak selalu terasa secara instan.
Selain itu, konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan sering kali muncul. Banyak industri besar yang berkontribusi terhadap perekonomian, seperti pertambangan dan manufaktur, sering kali mengorbankan kelestarian alam. Di sisi lain, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan juga masih rendah. Tidak semua orang melihat urgensi dari perubahan gaya hidup untuk mendukung keberlanjutan. Tantangan-tantangan ini membuat upaya menjaga lingkungan terasa seperti perjuangan yang berat, meskipun pada akhirnya penting untuk keberlangsungan hidup kita semua.
Meski tantangan menjaga lingkungan cukup berat, bukan berarti upaya ini tidak bisa dilakukan. Salah satu cara untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah dengan memanfaatkan teknologi hijau sebagai investasi jangka panjang. Misalnya, energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga mampu menghemat biaya energi dalam jangka panjang. Selain itu, sektor ekonomi hijau, seperti pariwisata berbasis alam atau industri daur ulang, dapat menjadi peluang baru yang menguntungkan sekaligus mendukung kelestarian.
Pendidikan juga memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sejak usia dini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang lebih peduli terhadap alam. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal juga menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan yang realistis dan kolaboratif, menjaga lingkungan dapat dilakukan tanpa harus mengabaikan tantangan yang ada.
Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap individu, komunitas, dan pemerintah. Meskipun ada tantangan, langkah-langkah kecil yang konsisten dapat membawa perubahan besar. Memulai dari hal sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, hingga mendukung produk-produk ramah lingkungan, adalah bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan siapa saja. Di tingkat yang lebih besar, pemerintah dan perusahaan perlu terus mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan dan operasional mereka.
Pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya tentang melestarikan alam, tetapi juga melindungi masa depan kita bersama. Planet ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki, dan keseimbangan ekosistemnya adalah penentu keberlangsungan hidup manusia. Dengan komitmen yang kuat dan tindakan nyata, kita tidak hanya menyelamatkan bumi, tetapi juga memastikan generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang layak di planet yang sama. Jadi, mari bergerak bersama, mulai dari diri sendiri, untuk menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

"Jaga Bumi Jaga Lingkungan" Untuk Masa Kini dan Masa Depan
Oleh : Ovie Yanti, S.Sos., M.Pd., M.Si Dosen D-IV Manajemen Pemerintahan (Universitas Jambi)
Terinspirasi dari materi yang disampaikan pada Program Short Courses Certified Environmental Management Leadership Batch 3 mengenai Swasembada Energi dan Pangan Yang berkelanjutan serta Ramah Lingkungan, semakin menguatkan tekad untuk terus mengkampanyekan “Jaga Bumi Jaga Lingkungan” untuk masa kini dan masa depan. Slogan tersebut menjadi tongkat bagi kami untuk giat menjaga lingkungan baik secara langsung melalui kegiatan pembelajaran maupun secara tidak langsung melalui kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan kampus. Dari sudut pandang Islam, pengelolaan lingkungan bukan hanya merupakan tanggungjawab manusia terhadap alam, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan terhadap apa yang difirmankan Allah dalam kitab suci Al Quran. Dulu kebutuhan hidup manusia masih terbilang sedikit, karena memang jumlah penduduk belum terlalu banyak, sehingga tidak mengganggu keharmonisan lingkungan alamiah. Namun beberapa tahun terakhir, pesatnya pertambahan penduduk dan makin meningkatnya kebutuhan umat manusia yang didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Padahal Islam memandang bahwa agama tidak pernah bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ilmu tidak bersifat sekuler.
Bahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Maka Islam mendorong manusia untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara bijaksana dan berkelanjutan. Dalam konteks menjaga dan memelihara bumi secara berkesinambungan, manusia tidak boleh berlebihan (israf) memanfaatkan sumber daya alam hingga mengakibat kerusakan di muka bumi. Mengutip surat Al-Baqarah ayat 11 yang berarti : dan bila dikatakan kepada mereka “janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi” mereka menjawab “sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan”. Dalam menjaga bumi dan menjaga lingkungan sudah menjadi tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu merupakan sebuah fungsi yang diemban oleh manusia sesuai dengan amanat yang berikan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara bertanggungjawab serta mengelola sumber-sumber kehidupan dimuka bumi sebagaimana dalam surat Huud ayat 16 yang berbunyi : Dan Allah telah menciptakan kamu dari bumi (tanah), dan menugaskan kamu untuk memakmurkannya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan mengatasnamakan pembangunan, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan telah membuat mereka lupa diri, eksploitasi hutan, sungai, tanah, serta sumber daya lainnya dilakukan secara berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan dimana-mana. Ancaman Allah yang paling serius terhadap tindakan melakukan kerusakan adalah berdampak pada kebinasaan (Al- Baqarah, ayat 205). Bahkan Laporan hasil studi The Club Of Rome yang berjudul The Limits to Growth, (Prabha & Kumar, 2015) memprediksi bahwa sekitar tahun 2050 sistem kehidupan di muka bumi akan menghadapi ”total Collapse”, jika faktor pendukung kehidupan manusia(jumlah penduduk, pangan, hasil industri, sumber daya yang tak bisa pulih serta pencemaran) tetap secara eksponensial meningkat seperti saat ini. Na’uzubillah, semoga kita terhindah dari kebinasaan akibat ulah kita sendiri. Mari kita “Jaga Bumi Jaga Lingkungan” untuk masa kini dan masa depan. Wassalam.

Mendorong Kebijakan Lingkungan
yang Lebih Komprehensif untuk Menghadapi Perubahan Iklim
Oleh: Tirta Yoga, SP., MP (Dosen Agribisnis, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang CEO Bakultani)
(Ilustrasi Kekeringan/pexels/james frid)
Perubahan iklim kini bukan lagi sebuah isu yang bisa diabaikan. Dampaknya sudah mulai dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi namun juga rentan terhadap bencana alam. Dalam pembahasan ini melihat bagaimana kebijakan lingkungan di Indonesia perlu disesuaikan untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Tema ini sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara dengan banyak daerah rawan bencana yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global, seperti kenaikan suhu dan peningkatan intensitas curah hujan yang tidak menentu.
Kebijakan lingkungan saat ini di Indonesia masih jauh dari cukup untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim yang semakin akut. Data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Fakta ini memperjelas bahwa kita tidak hanya menghadapi ancaman dari sisi suhu yang meningkat, tetapi juga dari sisi bencana yang lebih sering terjadi akibat ketidakseimbangan alam. Indonesia harus lebih agresif dalam mengimplementasikan kebijakan adaptasi iklim yang berbasis pada data ilmiah dan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan berbasis data ilmiah sangat penting agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi aktual yang ada di lapangan, serta dapat memberikan solusi yang lebih nyata dan terukur.
Namun, meskipun ada dorongan kuat untuk memperbaiki kebijakan lingkungan, ada beberapa aspek yang belum cukup mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah masalah koordinasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Dalam banyak kasus, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sering kali mengalami kesulitan dalam implementasinya di tingkat daerah, terutama di daerah yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Sebagai contoh, proyek restorasi lahan gambut di Kalimantan yang dicanangkan pemerintah pusat sempat mengalami kendala besar karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak pemerintah daerah dengan masyarakat setempat. Data yang diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menunjukkan bahwa proyek-proyek serupa yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung cenderung gagal dalam jangka panjang.
Solusi yang ditawarkan tidak cukup jika hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat saja. Namun perlu melibatkan lebih banyak pihak, terutama masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi spesifik daerah mereka. Masyarakat lokal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian alam sekitar mereka, dan tanpa keterlibatan mereka, kebijakan lingkungan yang ada akan sulit untuk diterima dan dilaksanakan dengan efektif. Data menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kebijakan adaptasi iklim yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif, memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan lingkungan yang diambil.
Selain itu, kebijakan adaptasi perubahan iklim juga harus mencakup aspek pendidikan dan kesadaran lingkungan yang lebih luas. Tidak cukup hanya dengan membuat regulasi atau mengalokasikan dana untuk proyek restorasi, namun juga perlu ada upaya sistematis untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk menumbuhkan kesadaran akan perubahan iklim sejak dini, sehingga setiap individu dapat berperan aktif dalam menjaga bumi. Dalam hal ini, pendekatan berbasis data ilmiah dan pendidikan berbasis pengalaman yang diterima masyarakat akan sangat membantu dalam perubahan sikap masyarakat terhadap isu lingkungan.
Secara keseluruhan, perubahan iklim adalah masalah yang sangat kompleks dan memerlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan melibatkan semua pihak. Jika kita melihat negara-negara yang sudah lebih dulu menghadapi dampak perubahan iklim, mereka memiliki kebijakan yang tidak hanya berdasarkan sains dan teknologi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung. Indonesia, dengan segala potensi dan tantangannya, seharusnya dapat mengembangkan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dengan mengintegrasikan sains, teknologi, dan partisipasi masyarakat.

Dimas Anugerah
Change and Resistance: The Future of Kalimantan Studies
The first International Conference that led to the construction to the Genealogy of Kalimantan Studies

Kuala Lumpu Malaysia – Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan (APSK Official) menggelar International Conference on Kalimantan Studies (ICKS) 2024, di Hotel Grand Hotel International Asia Pasifik 12-13 Agustus 2024. Acara ini dibuka oleh Direktur Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan, Noorhidayah, S.H., M.A., C.EML. dengan openingnya menerangkan peran penting dekolonialisme arus balik berdikari dalam epistimologi Kalimantan Studies.
Dengan menghadirkan Opening Massage, Associate Prof. Dr. Thirunaukarasu A/L Subramaniam (Department of SouthEast Asian Studies, University of Malaya, Malaysia), Introduction of Guest Honor, Prof. Dr. Arndt Graff (Goethe University, Frankfurt, Germany) dan Dr. Syed Abdul Razak Bin Sayed Mahadi, University of Malaya, Malaysia di ikuti oleh berbagai kalangan mulai akademisi, anggota majelis adat, dosen, mahasiswa S1-S3, dan Umum.
Associate Prof. Dr. Thirunaukarasu A/L Subramaniam, Prof. Dr. Arndt Graff dan Dr. Syed Abdul Razak Bin Sayed mengapresiasi konferensi Internasional ini dengan menghadirkan presenter dan pemerhati kajian kalimantan studies yang akan mempresentasikan risetnya untuk bisa menjadi kajian akademik multidisiplin.
“International Conferensi ini adalah pertama di Asia bahkan bisa dikatakan yang pertama di Dunia dengan sangat spesifik mengusung tema Kajian Kalimantan Studies. Konfrensi ini adalah momentum yang bagus terlebih ketika Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Nusantara tentu riset tentang Kalimantan sebagai penunjang kemajuan sangat diperlukan.” ujar Associate Prof. Dr. Thirunaukarasu A/L Subramaniam
Associate Prof. Dr. Thirunaukarasu A/L Subramaniam memaparkan paper tentang Kalimantan Studies as an Emerging Discipline within Southeast Asian Studies narrative menjelaskan tentang main maping keilmuan Kalimantan Studies dan Pengembangannya untuk riset di Indonesia. Adapun Dr. Syed Abdul Razak Bin Sayed membawakan pemaparannya berjudul Pembinaan Ibu Kota Nusantara – Impak Migrasi & Pembangunan menerangkan akan mitigasi pemerataan pembangunan dengan melihat budaya sebagai Pembangunan berbasis daerah serta peran migrasi masyarakat yang rata. Selain itu, Prof. Dr. Arndt Graff memaparkan papernya tentang Prof. Dr. Arndt Graf, Goethe Universitat, Frankfurt Am Main, Germany – In Search of the emotional homeland in “Middle Indonesia”. a Case Study of the Pojok Comment in Arcaya, West Kalimantan tentang bagaimana sejarah kesejahteraan kalimantan dan peran media dalam pemahaman masyarakat.
Akhirnya, Dr. Naufal, S.Ag., M.Ag., C.I.P., C.EML. selaku Committee International Conference on Kalimantan Studies mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak dalam suksesi acara ini baik mulai kerjasama dengan Universiti Malaya Malaysia serta berbagai delegasi yang mempresentasikan paper terbaiknya. Setelah Conferensi Internasional dilanjutkan dengan visit Kampus Universiti Malaya, Museum Asia UM, Muzium Kraf Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Twin Tower KLCC serta Dataran Merdeka-Istana Negara.
ASOSIASI PENELITI STUDI KAWASAN KALIMANTAN
SEKERTARIAT:
JL. Diponegoro No. 2 RT. 01 RW.01, Kec. Pahandut Kel. Panarung, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 773111